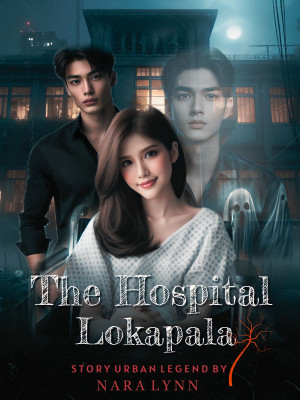Angin mengembus lembut, menerbangkan helai rambutmu yang terlepas dari ikatan. Sembari duduk di bawah pohon tanjung, tanganmu dengan lihai menggoreskan ujung pensil untuk mengabadikan pemandangan pegunungan di hadapanmu pada selembar kertas. Alunan lagu A Million Pieces yang dinyanyikan oleh Kyuhyun terdengar dari penyuara jemala yang terpasang di telinga—menemanimu yang tengah menikmati kedamaian menurut versimu. Dan menggambar ternyata masih menjadi obat paling mujarab bagimu.
Sudah sebulan ini kamu kembali menekuni dunia menggambar yang telah lama kamu tinggalkan karena seseorang berhasil mengembalikan keberanianmu menghadapi kesakitan masa lalu. Ayahmu adalah seorang pelukis dan beliau juga yang mengenalkanmu pada dunianya. Setiap akhir pekan, Ayah akan mengajakmu melukis bersama. Setelah itu, ibumu akan datang membawakan camilan untuk kalian. Banyak canda tawa di antara kalian dan itu merupakan kenangan indah nan hangat yang kamu miliki. Jadi, usai kejadian tragis itu, kamu takut kembali menyentuh peralatan menggambarmu. Kehilangan dan kesakitanmu sangat nyata dan mengingat memori orang tuamu akan membuatmu makin merindukan mereka.
Namun, seseorang ternyata menyadari satu hal kecil tentangmu yang bahkan tidak kamu sadari sebelumnya. Yakni kebiasaanmu mencoret kertas dan menghasilkan gambar secara tidak sadar setiap kali fokus memikirkan sesuatu. Dia juga yang mendengarkan ceritamu dengan saksama tentang kekhawatiranmu soal menggambar, kemudian memberikan dukungan yang memunculkan kembali keberanianmu. Seperti yang dia katakan, menggambar adalah obat bagimu dan menjadi satu-satunya hal yang dapat kembali menghubungkanmu dengan orang tuamu.
Saat sedang asyik dengan kegiatanmu itu, seseorang tiba-tiba datang dan mengagetkanmu hingga kamu menjerit dan nyaris terjungkal ke depan. Mendengar gelak tawa khas dari arah belakang, kamu lantas menoleh dan memberikan pelakunya tatapan tajam.
“Ian!” serumu kesal pada remaja laki-laki yang masih mengenakan seragam putih abu-abu sama sepertimu.
Tatapanmu kemudian tertuju pada kertas gambarmu. Di sana terdapat coretan panjang yang merusak hasil karyamu yang telah kamu kerjakan selama lebih dari tiga jam. Kamu menghela pun hanya dapat menghela napas panjang karenanya. Padahal hanya tinggal menambah detail saja gambarmu itu akan selesai.
“Ah! Maaf, Ke. Aku tidak tahu kamu sedang menggambar.”
Jika boleh jujur, sebenarnya kamu sedikit marah karena Adrian membuat hasil kerja kerasmu berakhir sia-sia. Akan tetapi, melihat laki-laki yang masih bertingkah seperti bocah itu meminta maaf dengan air muka penuh rasa bersalah setelah melihat gambarmu rusak membuatmu lagi-lagi hanya dapat menghela napas. Lagi pula semuanya juga sudah terjadi, begitu pikirmu.
Ketenanganmu kini terusik. Jadi, kamu segera menutup buku sketsa pemberian dari Mama—ibu Adrian, kemudian menyimpannya kembali ke dalam tas sekolahmu yang tergeletak di sisi kiri. Tanpa menatap ke arah Adrian, kamu kemudian bertanya, “Ada apa?”
Adrian mengambil duduk di depanmu. “Kamu marah, Ke?” tanyanya padamu dengan suara yang terdengar takut-takut.
Sudah hafal di luar kepala dengan tingkah seorang Adriansyah Mahendra, mau tidak mau kamu akhirnya memberikan respons yang lebih hangat. Otakmu masih panas sehabis mengerjakan soal-soal ulangan semester tadi, sehingga untuk saat ini lebih baik menghindari hal yang makin menguras energi—terlibat dalam drama yang dibuat Adrian misalnya. Kamu pun menatap laki-laki berkacamata itu sambil menarik kedua sudut bibir ke atas.
“Tidak, untuk apa aku marah?” ujarmu tenang.
Adrian mengerucutkan bibirnya. “Karena aku sudah mengagetkanmu dan merusak gambarmu.”
Tidak tahan lagi, kamu pun mengembuskan napas lelah dan menatap Adrian lurus. “Ian,” panggilmu tegas.
“Ya?”
“Kita sudah di penghujung masa SMA,” tuturmu.
Adrian tersenyum seperti orang bodoh, lalu menyahut, “Aku tahu. Kamu mau melanjutkan kuliah ke mana? Kamu akan ambil jurusan apa? Apa—”
“Mau sampai kapan kamu akan terus bertingkah kekanak-kanakan seperti ini?” sergahmu hingga membuat Adrian bungkam menatapmu. “Seperti yang kamu katakan, sebentar lagi kita akan memasuki masa perkuliahan. Kita bukan anak-anak lagi, Ian.”
“Aku kekanak-kanakan?” Adrian tersenyum masam.
“Ya,” kamu menjawabnya tegas.
“Di bagian mana?”
“Kamu terus merengek seperti anak-anak. Kamu juga ....” Suaramu dibiarkan menggantung di udara. Tidak ingin melanjutkan apa pun yang terlintas dalam benakmu saat ini karena itu akan melukai Adrian.
“Oh, jadi kamu sudah jengah dan lelah denganku, ya?” tutur Adrian dengan senyuman yang tampak sendu. “Apa karena itu juga kamu memilih kuliah di tempat yang jauh dan pergi dari rumah?”
“Dari mana—”
“Mama menceritakannya padaku.” Adrian menatapmu lurus. “Jika aku tidak bersikap kekanak-kanakan lagi, apa kamu masih tetap akan pergi?”
“Ian ....”
Merasa frustrasi, kamu pun membuang napas berat. Kamu yakin, Adrian tahu dan mengerti yang sebenarnya. Akan tetapi, sikap kekanak-kanakan seperti inilah yang membuatmu lelah menghadapi Adrian.
“Sudahlah. Lupakan saja. Aku juga tidak ingin menjadi penghalang masa depanmu,” ujar laki-laki itu sembari membenarkan letak kacamatanya, kemudian bangun. “Aku diminta Mama untuk menjemputmu pulang. Mama khawatir padamu.”
Setelah mengatakan itu, Adrian pergi meninggalkanmu lebih dahulu. Kamu termangu di tempat, menatap punggung laki-laki itu yang makin menjauh dari pandanganmu. Tumbuh bersama sejak anak-anak membuatmu mengerti dan memahami bagaimana seorang Adriansyah Mahendra. Kamu tahu, Adrian tengah bersedih setelah mendengar berita bahwa kamu akan berkuliah di Prancis karena mendapatkan beasiswa di sana. Laki-laki itu ternyata sama sedihnya denganmu ketika menyadari bahwa untuk pertama kalinya kalian tidak akan lagi bersama. Kehidupan yang berubah saat menuju dewasa sungguh menakutkan.
****
“Selamat datang di rumah, Kean.”
Selamat datang di rumah, Kean.
Setiap kali mendengar sambutan hangat itu dari Mama—ibu Adrian, ingatanmu selalu bercampur dengan kenangan ketika ibumu juga menyambut kepulanganmu ke rumah dengan kehangatan yang sama. Sudah hampir tiga tahun berlalu, tetapi waktu di sekitarmu seolah tidak pernah bergerak—terhenti tepat di hari ulang tahunmu yang ke-10. Bukan karena kamu tidak mengikhlaskan kepergian orang tuamu hari itu, melainkan kamu tidak pernah terbiasa dengan perubahan yang terjadi di hidupmu termasuk ketika keluarga Adrian mengadopsimu.
“Bagaimana sekolahmu hari ini, Ke?” tanya Mama yang datang dari arah dapur dengan senyuman lembut. Di badannya masih terpasang celemek merah muda kesayangannya. Mencium aroma kue membuatmu berpikir bahwa sepertinya Mama baru saja membuat eksperimen baru.
Kamu balas tersenyum, menyembunyikan sendu dari kerinduanmu terhadap Ibu. Namun belum sempat kamu menjawab, seruan dari arah belakang sudah terlebih dahulu menyerobot.
“Mama! Kok hanya Kean yang disambut! Aku juga anakmu lo, Ma!”
Mendengar seruan protes itu, kamu dan Mama saling bertukar pandang. Kemudian, Mama tampak menghela napas sebelum bertolak pinggang dan menatap putra semata wayangnya dengan garang.
“Ian! Tidak usah teriak-teriak seperti itu kalau pulang! Kamu itu ya ....”
Ibu dan anak itu kemudian saling bertengkar di hadapanmu. Tidak, dibanding bertengkar, kamu lebih menganggapnya sebagai interaksi antara seorang ibu dengan anaknya. Kamu tahu, Mama tidak benar-benar marah. Sebaliknya, beliau amat menyayangi Adrian. Melihat adegan di hadapanmu ini, membuatmu makin merindukan orang tuamu. Entah apa yang terjadi padamu, tetapi begitu Adrian melihatmu, bocah laki-laki yang kini mulai beranjak remaja sepertimu tampak kaget dan ... sendu.
“Kean ....”
Dia memanggil namamu. Kemudian, sebelum kamu sempat bereaksi, Adrian sudah terlebih dahulu memelukmu. Saat itulah kamu menyadari bahwa air mata telah menganak sungai di kedua pipimu. Lalu, ketika Mama juga bergabung dalam pelukan kalian, tangisanmu tumpah ruah.
Kamu belum baik-baik saja. Kamu masih terjebak dalam ingatan pilu hari itu. Kamu masih belum berdamai dengan kehilanganmu. Kamu ... sangat merindukan orang tuamu di surga sana.
****
Pagi ini hujan begitu deras mengguyur bumi. Mungkin langit tahu bahwa kesedihan yang tidak bisa kamu luapkan sudah tertampung begitu banyak, sehingga ia-lah yang menggantikanmu menangis. Matamu menatap ke luar jendela kaca yang berembun. Bukan untuk melihat dunia luar, melainkan untuk melihat ke dalam dirimu sendiri.
Bagi seorang bocah sepuluh tahun ... ah, tidak. Sebentar lagi usiamu akan menginjak angka belasan. Akan tetapi, apa yang berbeda dari itu? Kamu masihlah seorang bocah yang dipaksa takdir untuk kuat sendirian. Oh, ada satu perbedaan yang amat jelas dalam kehidupan bocahmu ini. Tidak ada lagi Ibu dan Ayah di sisimu. Kamu sendirian ....
“Kean!”
Atau tidak.
Mendengar pekikan menggelagar itu, kamu segera menoleh ke arah pintu. Tepat ketika itu, seorang bocah laki-laki dengan kaos berwarna merah bergambar salah satu karakter mobil yang dapat berubah menjadi robot muncul di sana dengan ekspresi bak anak anjing kehujanan. Belum sempat kamu memberikan reaksi, bocah laki-laki itu langsung berlari ke arahmu dan menyodorkan sebuah buku gambar yang kertasnya tampak lusuh karena bekas coretan pensil yang dihapus berulang kali.
“Bantu aku menyelesaikan tugas menggambar, ya?” pintanya memelas padamu. “Kamu kan pintar menggambar, he-he-he.”
Melihat bocah laki-laki itu masih saja cengar-cengir seperti orang bodoh, membuatmu sedikit iri. Adrian yang kamu kenal, ternyata masih tetap menjadi Adrian. Tidak hanya itu, keluarga Adrian juga tetap sebaik yang kamu kenal pertama kali. Mereka bahkan mengurusmu selama dirawat di rumah sakit dan begitu pulang, mereka membawamu ke rumahnya. Kini, kamu menyadari bahwa kamu telah menjadi bagian keluarga Adrian.
Ternyata tidak hanya satu hal yang berubah dari hidupmu, melainkan ada banyak. Satu peristiwa pilu itu ternyata telah memorak-porandakan kehidupan bocah sepuluh tahun sepertimu.
“Aku tidak bisa menggambar,” katamu tegas, setelah menatap buku gambar itu begitu lama.
“Ha? Kenapa tidak bisa menggambar? Oh! Apa tanganmu masih sakit? Kalau begitu aku saja yang pegang pensilnya dan kamu yang mengajariku. Bagaimana?”
Kini, kamu merasa kesal. “Aku tidak bisa menggambar,” katamu lagi dengan nada yang sedikit lebih tinggi.
Adrian menatapmu dengan mata yang menyedihkan. “Kok tidak bisa? Aku hanya minta tolong untuk—”
“Sudah kubilang, aku tidak bisa menggambar!” serumu seraya merebut buku gambar di tangan Adrian dan melemparkannya ke lantai.
Bukan hanya Adrian yang kaget dengan dirimu ini, kamu sendiri juga. Kamu tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kamu menjadi sangat marah dan kesal ketika Adrian mengatakan soal “menggambar”. Dadamu juga terasa sakit karenanya. Padahal, menggambar adalah kegiatan favoritmu. Adrian juga tidak salah mengatakan kalau kamu memang pintar menggambar berkat Ayah yang mengajarimu. Kamu ....
“Kenapa kamu marah, Ke! Aku kan hanya minta tolong untuk membantuku menyelesaikan tugas menggambar!” seru Adrian dengan mata berkaca-kaca yang menatapmu.
Sementara itu, kamu hanya terpaku bisu. Tidak tahu harus apa bahkan ketika akhirnya Adrian berlari pergi meninggalkanmu dengan uraian air mata. Namun, sebelum pergi, kamu mendengar bocah laki-laki itu berteriak padamu.
“Kamu jahat!”
Begitu katanya. Jadi, apakah saat ini kamu sudah berubah menjadi orang jahat? Kalau benar seperti itu, Ayah dan Ibu pasti akan marah dan membencimu. Ah! Mungkinkah karena selama ini kamu jahat, sehingga Ayah dan Ibu pergi meninggalkanmu sendirian?
Pantas saja ..., kamu membatin.
Tidak tahan lagi, akhirnya kamu luruh dan menangis keras. Di sela isak tangismu, kamu menyerukan janji untuk menjadi anak yang baik agar Ayah dan Ibu tidak marah dan membencimu. Kamu juga meminta mereka untuk kembali dan menjemputmu. Kamu tidak mau sendirian dan kamu ketakutan. Kemudian, kamu merasakan pelukan hangat yang begitu kamu rindukan. Namun, sebelum sempat membalas pelukan itu, kesadaranmu ikut hanyut bersama derasnya hujan.
Aku akan menjadi anak yang baik agar Ayah dan Ibu tidak marah dan benci.
Tapi, kenapa mereka tidak juga kembali? Apakah aku masih tidak cukup baik?
Ananda Kean Lavenia


 dita_xian
dita_xian