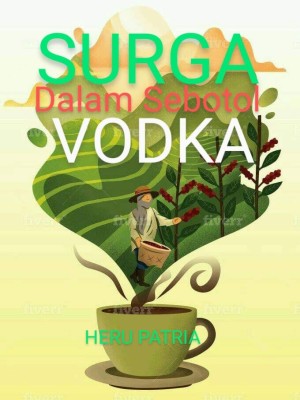“Kau bisa menggantikanku malam ini? Aku memiliki masalah yang urgent.”
Anthony menyerangku dengan kata-kata yang diucapkannya dengan begitu cepat, sesaat setelah aku mengangkat panggilan telepon darinya dan mengucapkan kata ‘halo’ dengan agak mengantuk.
“Maksudmu? Menggantikanmu bagaimana?” tanyaku yang masih belum sepenuhnya lepas dari alam mimpi. Maklum saja, ini baru pukul setengah enam pagi. Terlalu cepat bagi siapa pun untuk mengganggu ketenangan orang lain pada waktu seperti ini.
“Chandelier Hotel. Aku adalah satu dari sekian pianis solo yang bekerja di sana untuk mengiringi dinner pada malam akhir pekan. Dan malam ini adalah giliranku bermain. Tapi, aku tidak bisa berada di Chandelier nanti malam. Soalnya aku harus pergi ke Surabaya sekarang juga karena ada keluargaku yang sakit parah di sana. Kuharap kau bisa menggantikan aku, Viola.”
Nada bicara Anthony terdengar berat dan serius. Itu membuatku duduk dengan tegak di tempat tidurku, untuk berusaha mendengarkan setiap ujarannya dengan perhatian penuh.
“Kau hanya perlu memainkan beberapa lagu klasik dan pop ballad yang sudah kuaransemen untuk piano solo. Semua partiturnya yang sudah kuformat dalam bentuk file pdf akan kukirimkan kepadamu melalui WhatsApp. Pasti kau butuh berlatih dulu di rumah sebelum bermusik di sana.”
“Baiklah, Anthony, aku bisa menggantikanmu nanti malam. Dan aku turut menyesal soal keluargamu yang sakit parah itu. Kuharap dia cepat sembuh, ya.”
“Trims, Viola. Kau yang terbaik. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu.”
“Kapan pun itu, Anthony. Kau juga telah sangat banyak membantuku sejak dulu, kan?” balasku dengan senyum yang pastinya tidak akan mampu dia lihat dari tempatnya berada sekarang.
Sebelum percakapan kami usai, Anthony kembali menambahkan sesuatu padaku,
“Satu hal lagi, Viola. Honornya kauambil untukmu saja. Setelah ini akan kuhubungi orang yang mengurus soal itu. Dia yang akan berurusan denganmu malam ini. Oke?”
“Oke, Anthony. Selamat tinggal. Jaga dirimu baik-baik dalam perjalanan.”
“Pasti. Selamat tinggal, Viola,” sahut Anthony, lalu hubungan telepon kami resmi berakhir.
*
Kalau ada satu benda yang mampu menyelamatkan hidup seseorang, bagiku itu piano.
Sungguh, aku bisa bertahan hidup hingga detik ini karena menjadi pianis yang bermain dari satu event ke event lainnya. Aku juga pernah bermain sebagai pianis bersama Orkestra Simfoni Ibu Kota dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping itu, aku memiliki beberapa murid les privat piano di rumah—ada yang masih bertahan belajar denganku hingga sekarang, tapi ada pula yang pergi tiba-tiba karena alasan yang tidak kutahu pasti apa dan mengapa. Semua penghasilan itulah yang menghidupi aku, si gadis sebatang kara ini, di tengah teramat tingginya living cost[1] dalam ‘rimba’ sebesar Jakarta yang sudah penuh sesak oleh kepadatan manusia.
Malam ini, aku menunaikan janjiku untuk menggantikan Anthony sebagai pianis pengiring dinner di Chandelier Hotel. Aku sudah duduk di kursi piano yang sangat empuk dan nyaman. Di depanku, sebuah baby grand piano berwarna putih tampak berdiri anggun dengan elegan dan classy-nya.
Aku mengedarkan pandanganku ke sekeliling. Restoran yang berada di dalam hotel ini sangat luas dan mewah. Ceiling[2]-nya dibuat tinggi, dengan chandelier besar (yang sepertinya terbuat dari kristal) digantung menjuntai tepat di tengah-tengah ruangan sebagai pusat perhatian. Ruangan restoran ini menghadirkan nuansa warna merah marun yang hangat di setiap pasaknya. Itu menjadi seperti paradoks bila dibandingkan dengan udara dingin yang menyeruak dari air conditioner[3] mereka, yang terasa sejuk menyentuh kulitku. Aroma daging panggang dan bumbu-bumbu dapur nan segar menguar dengan nikmat terhidu sampai ke hidungku, dan membuatku harus menahan rasa lapar dengan susah payah karenanya.
Keberadaan aku dan baby grand piano yang keren ini tidak terlampau jauh dari kumpulan meja bundar dengan kursi-kursi bersandaran tinggi yang mengelilingi setiap meja—tempat di mana orang-orang kaya yang merupakan tamu di Chandelier Hotel ini akan menyantap makan malam mereka dengan khidmat, sambil diiringi alunan piano instrumental yang berasal dari jari-jemariku yang menari dengan lihai.
Sungguh sebuah pengalaman yang mengesankan bagiku untuk mengiringi makan malam dengan suasana yang begitu luar biasa. Menit demi menit berlalu, tidak terasa aku sudah memainkan puluhan bahkan mungkin ratusan ruas birama dari setiap lagu dalam partitur yang dikirimkan Anthony tadi pagi. Akhirnya, kini aku tiba di repertoar pamungkas untuk malam yang manis ini.
Jari-jemariku menarikan setiap not dari repertoar Le Cygne from “Le Carnaval Des Animaux” milik C. Saint-Saens dengan dinamika yang berubah-ubah, dari piano[4] ke mezzoforte[5], kemudian kembali ke piano lagi—persis mengikuti tanda dinamika yang Anthony bubuhkan dalam partiturnya yang kompleks.
Aku memejamkan mata ketika jari-jemariku menekan not terakhir dari repertoar yang indah itu. Sedetik kemudian, aku terkejut ketika mendengar tepukan tangan antusias dari seseorang entah siapa.
Aku menoleh ke kanan dan kudapati seorang anak berusia kira-kira 8 tahun sedang berdiri sambil memandangiku dengan binar senang dalam matanya.
“Kau luar biasa. Keren! Itu tadi bagus sekali, Kak!”
“Terima kasih, terima kasih,” sahutku sambil meletakkan sebelah tangan di dada dan membungkuk sedikit kepada anak baik hati ini.
“Aku ingin belajar,” ujarnya dengan semangat. “Ajari aku main piano. Kau datang ke rumahku saja, ya. Bagaimana? Bisa, kan?”
Aku tersenyum manis kepadanya. “Aku pasti dengan senang hati bersedia. Tapi, kau harus bilang dulu kepada orangtu—”
“Jason, aku mencarimu ke mana-mana! Jangan pernah pergi tanpa pamit lebih dulu kepadaku, mengerti?”
Kalimatku diinterupsi oleh kedatangan seorang lelaki tinggi yang mengenakan tuxedo hitam nan menawan. Aku berpikir dia adalah ayah dari anak kecil bernama Jason yang barusan mengobrol denganku itu.
Kemudian lelaki itu menatapku dengan matanya yang dingin, tajam, sekaligus sangat intens selama hampir enam detik. Aku sempat terenyak sekejap lantaran menerima tatapan sedingin es itu dari seorang lelaki tampan namun asing di sebuah restoran milik hotel berbintang lima ini.
“Unjo, aku ingin belajar main piano dengan Kakak ini. Bisakah kauundang dia ke rumah kita? Aku sangat ingin belajar dengannya, Unjo.”
Unjo? Nama macam apa itu? Jadi ayahnya Jason ini bernama Unjo? Maaf, Unjo. Kau memang tampan dan menawan, tapi namamu terdengar aneh di telingaku.
Mendengar permintaan putranya tadi, lelaki itu lalu memandang Jason dengan ekspresi yang tidak bisa aku terjemahkan artinya. Kemudian matanya tertumbuk ke arahku lagi, masih dengan ketajaman dan intensitas yang sama, lalu kembali lagi kepada Jason. Aku sendiri tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi semacam ini.
“Kita bicarakan itu nanti, Jason. Sekarang kita pulang,” tandas lelaki itu, lalu menggandeng Jason untuk hengkang dari hadapanku.
Jason masih sempat menoleh ke belakang dan memandangku dengan tatapan agak murung. Tapi kemudian, aku melambai kepadanya sembari tersenyum, dan dia membalas lambaianku dengan senyum yang ramah pula. Oh, sungguh anak lelaki kecil yang manis! Andai saja ayahnya tidak sedingin itu dan mau mengizinkannya untuk belajar piano denganku. Pasti akan sangat menyenangkan sekali, bukan?
Tak lama detik berselang, dua orang itu pun hilang ditelan oleh lautan manusia yang berlalu-lalang selepas makan malam usai.
Dan aku langsung teringat pada ucapan Anthony di WhatsApp pagi tadi. Bahwa aku harus menemui seseorang bernama Michael untuk mengurus perihal honorku sebagai pianis pengiring dinner di sini. Jadi, kuraih ponselku dan segera kuhubungi Michael yang nomor teleponnya sudah kudapatkan dari Anthony.[]
[1] Biaya hidup.
[2] Langit-langit/plafon.
[3] Pendingin udara/AC.
[4] Lembut.
[5] Agak kuat.


 rizkyel_kaendo
rizkyel_kaendo