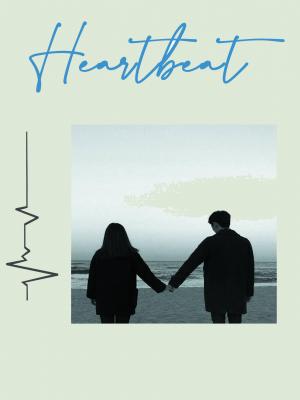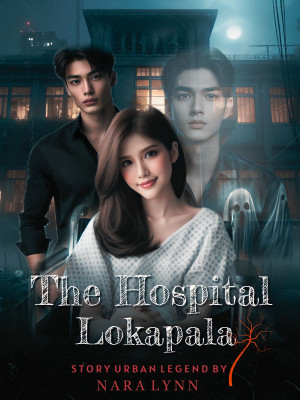Belaian angin menyapa dua insan manusia, aku dan Eoni, yang masih saja terduduk di tubir malam membiarkan waktu menyela begitu saja.
“Bila tiba titik menemui batas, apa sudah baik menyerah saja?” Ucapku lirih, sangat lirih, bahkan lebih lirik dari desau angin. Mungkin Eoni mendengar, mungkin juga tidak karena ia terlihat tidak bereaksi dengan pandangannya tetap lurus ke depan, entah memandang apa.
Sementara aku menunduk dalam-dalam tidak menyangka ada orang yang menyaksikanku dalam keadaan seburuk ini.
Dari dulu, aku selalu menyembunyikan segalanya dari permukaan, orang-orang hanya tahu aku yang bahagia, ceria, banyak bercanda dan selalu menjadi rata-rata air di mana pun aku berada.
Mereka tidak pernah paham bagaimana aku melewati hari-hari bingungku, masalah yang mendera dunia kerja, keterbatasan pengetahuan, tidak punya jalan pulang, semua itu aku alami dan nyata terjadi.
Belum lagi jika sudah kembali pada asumi bahwa abdiku untuk bekerja pada masa lalu, meneliti sejarah dan menemukan jejaknya, namun aku sendiri tidak bisa membuka masa laluku, mengerti muasalku, mengenal jejak ayah dan ibu kandungku. Semua yang ada hanya terasa bohong dan sia-sia. Entah sampai batas mana hal-hal ini akan terus terjadi.
Batinku berkecambuk mengalahkan kacaunya formasi rumput yang terseok-seok diganggu angin malam.
“Mengapa takut pada rasa sakit?” Tanya Eoni dengan tatap mata yang tidak berubah arahnya. Sekejap, tanya itu menyudahi jutaan tanya lain di kepalaku.
Aku diam, bukan karena tidak mau menjawab, melainkan karena tidak tahu jawabannya. Cukup lama suasana ini mengelilingi kami, nampaknya masing-masing pikiran tengah bekerja untuk tuanya dengan cara yang intens dan saksama.
Baru ketika iqamah dari surau-surau di kaki bukit membahana, saat itulah Eoni mengajakku turun. Sudah terlalu malam untuk udara yang dingin di pegunungan.
Dan kami pun turun. Mengambil langkah menuju peradaban desa yang lebih hangat oleh kepul asap dari tungku rumah belakang.
Di jalan turun aku sempat kebingungan, tadi, dari mana gadis ini berasal, namun nampaknya ia memang sudah ada sebelum aku ke sana dan ketika hari berganti malam, semua orang turun dari bukit, ia tetap di berada dan tidak meninggalkaku.
Namun ada satu kesalahan yang aku lewatkan, aku tidak sempat menyanyakan perihal perasaan, mengapa ia terus melakukan hal-hal yang berarti untukku, sementara yang aku tahu, hatinya mungkin tengah tertawan oleh hati lain.
Hingga kami tiba di beranda rumah aku tak juga punya keberanian untuk bisa menanyakannya.
“Oi, Bang Nadif dari mana saja kau. Kenapa baru pulang?” Guna menyambutku di depan kamar.
“Dari bukit Njahe, biasa, cari angin sepulang dari kota.” Jawabku meminta kemakluman dari Guna.
“Paling sengaja cari waktu dengan gadis sebelah. Kau pikir aku tidak lihat kau abis pergi dengan siapa?” Tentu saja gadis sebelah yang di maksud Guna adalah Eoni.
Aku menjawab cengengesan.
Di sana ada juga Bu Tinah, Yui dan Yua, Mbah Kakung serta Guna. El dan Sabang sama-sama sudah tidur, bedanya kalau El tidur di kamar Sabang, sementara Sabang di ruang tengah, di belakang tempat orang-orang berkumpul. Kata Mbah Kakung, mereka berdua kelelahan karena lintas alam seharian.
Cukup lama kami berbincang-bicang di menghadap alat penghangat ruangan tradisional bernama anglo. Bara apinya yang kemerahan sangat membantu menjaga suhu ruangan ini agar tetap manusiawi.
Pasalnya, di luar embun-embun mulai mengkristal dan hampir membeku karena kedinginan. Angin malam juga terlihat meniup-niup gorden di kaca jendela belakang, mungkin angin penasaran ingin bertemu udara hangat di dalam rumah.
Obrolan berakhir sebelum malam benar-benar larut, sambil menyantap ubi bakar yang habis dalam sekejap, satu per satu dari kami mulai meminta diri untuk beristirahat.
Bu Tinah bersama Yua dan Yui segera kembali ke basecamp putri, karena untuk sementara waktu, mereka memang tinggal di sana. Mbah Kakung juga mematikan anglo, dan pamit tidur. Hanya tinggal aku dan Guna, serta Sabang yang sudah hilang kesadarannya.
Aku masih betah membuka mata dan menghabiskan malam dengan tidak melakukan apa-apa, meskipun sekali-kali aku membaca buku untuk melihat catatan-catatan dan jurnal masa lalu.
Namun sepertinya Guna menyerah, dikalahkan rasa kantuk. Entah bagaimana mulanya, tiba-tiba renteten dengkuran segera menyergap telingaku tanpa permisi. Padahal kulihat Guna masih dalam posisi duduk, tidak bersandar, nampaknya ia adalah salah satu spesies manusia yang bisa tidur dalam keadaan apa saja.
Sedikit merasa tidak tega, takut-takut ia terjelungop ke belakang, kubangunkan dia dan kusuruh pindah di kasur.
Ketika aku sampai di kamar sendiri, El juga tidur dalam keadaan yang tidak lebih baik, kakinya dan seluruh tubuhnya melintang dari sisi ke sisi seolah-olah kasur itu adalah singgahsana mimpinya seorang.
Sudah kugoyang-goyangkan bahunya agak sedikit menyisakan ruang untukku tapi itu tidak ada artinya sama sekali.
El tidur seperti sedang simulasi meninggal, tidak bangun diperlakukan macam apapun. Mungkin ini efek kelelahan juga setelah seharian wira-wiri kesana kemari.
Tidak ada pilihan lain selain pindah. Nyatanya memang manusia sadar sepertiku dan mungkin siapa saja, pasti membutuhkan respon secara langsung ataupun tidak langsung, jika memang tidak ada sama sekali, pasti ia akan mencoba opsi lain salah satunya dengan; beralih.
Saat melihat Sabang yang tidur di ruang tengah, aku sudah mengambil posisi, tapi mengingat Eoni dan Maharani, rasa-rasanya cukup memuakkan juga manusia ini, alhasil aku pundah ke kamar Guna.
Meskipun dengkurannya membuat ketenangan jiwa menjadi gemetar, tapi ini adalah pilihan dan keputusan terbaik, setidaknya ada ruang untukku merebahkan badan dan pikiran.


 littlemagic
littlemagic