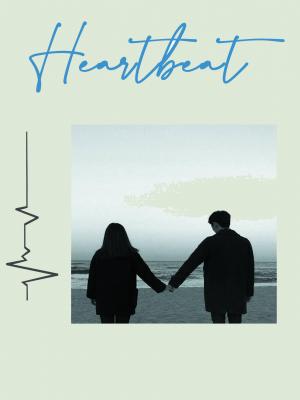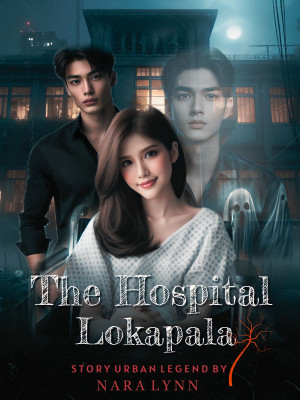Dan benar saja, cukup lama waktu berselang, setelah hujan mengguyur hingga sore sejak siang, suara derum mesin Jeep Willys terdengar merapat di sisi halaman rumah Pak Bah. Namun hanya ada satu orang yang turun dari sana dengan menenteng sebungkus Sobraine Black Russians, orang itu ialah Pak Leo.
Aku membuntuti Pak Bah yang segera menyapa kerabat lamanya itu. Meskipun usia Pak Bah terpantau cukup jauh dari Pak Leo dan Mr. Arief, tapi mereka terlihat seperti teman yang seimbang. Itulah salah satu keahlian Pak Bah, mampu menyatu dengan suasana dan hubungan macam apapun, netralisir yang bagus.
Tentu aku dan Pak Bah paham betul jika mobil yang di bawa Pak Leo ini adalah milik Mr. Arief, entah alasan apa yang membuat ia tidak jadi ikut serta.
“Pak Arief sedang ada urusan di kota dengan Mei, istrinya.” Ucap Pak Leo yang cukup menjawab pertanyaan kami, namun menimbulkan pertanyaan baru.
“Apa mereka baik-baik saja?” Pak Bah berterus terang, jarang sekali Mr. Arief melewatkan momen untuk bertemu dengan seorang yang telah ia anggap seperti abang atau mungkin keluarganya ini.
“Sepertinya, baik. Sejauh yang aku ketahui.”
Sejak dulu, Pak Bah selalu merasa ikut bertanggung jawab dengan urusan rumah tangga Mr. Arief dan Kak Mei, mungkin karena beliau lah yang mempertemukan dua sejoli itu. Masalah paling parah yang pernah menimpa mereka di masa lalu adalah percobaan bunuh diri Kak Mei tentang fitnah yang menyangkut orang ketiga.
Kak Mei selalu bilang pada Mr, Arief dan kami semua bahwa ia bisa mengkompromi berbagai kesalahan dan kekurangan dari Mr. Arief. Ia punya loyalitas dan pengertian yang besar mengenai sebuah hubungan, namun tidak dengan orang ketiga.
Namun, sebuah kesalahan dan kesalahpahaman tengah bekerja sama waktu itu. Sebuah surat palsu datang ke rumah Mr. Arief di siang hari yang sedang cerah-cerahnya. Sebuah surat kuasa tentang ahli waris yang jatuh pada perempuan yang tidak dikenal oleh Kak Mei.
Selidik punya selidik, Kak Mei mendengar berita bahwa nama yang tercantum di sana, yang dikatakan akan mendapat 1/19 aset perusahaan yang Mr. Arief pegang adalah manusia yang mendapat predikat orang ketiga itu.
Kak Mei kecewa, menerima kabar burung yang entah dari mana itu tanpa menyaring dan menanyakan pada suaminya terlebih dahulu. Hingga pada suatu siang, ia tergeletak di lantai kamar rumah dengan mulut berbusa dan mata mendelik karena meminum cairan yang mengandung soda api.
Beruntung, pembantu rumah tangga mereka segera menemukan dan pertolongan terbaik berhasil menyelamatkannya, meskipun sampai saat ini percernaan Kak Mei memiliki masalah yang cukup serius karena kejadian tersebut. Namun Tuhan masih berbaik hati agar dua manusia yang tengah terikat janji mulia itu memperbaiki segalanya.
Saat itu, cukup lama tidak ditemukan akar masalah dari segala carut marut yang melanda rumah tangga Mr. Arief yang baru seumur jagung. Namun kebenaran memang akan selalu menunjukkan wujudnya.
Pelakunya adalah tangan kanan dari Mr. Arief sendiri. Asisten beliau sebelum aku. Ia merasa tidak terima melihat surat berharga atas nama perempuan asing ~yang mana ia adalah saudara angkat Mr. Arief, yang tidak banyak orang tahu~ akan mendapat aset 1/19 dari perusahaan. Aset itu cukup besar dan lebih besar dari pendapatan yang setiap bulan ia terima sebagai tangan kanan Mr. Arief.
Merasa tidak terima, ia membuat segala macam strategi agar dunia setuju dengan ketidak-terimaan dirinya. Namun, bukan bunga yang ia dapat, melainkan kuncup yang membusuk. Tentu saja semesta percaya, bahwa kebohongan tidak akan menyelamatkan siapapun. Baik itu yang dibohongi maupun yang membuat kebohongan.
Tak sedikit pikiran, harta dan tenaga yang Mr. Arief keluarkan untuk menangani masalah pelik ini, Kak Mei pun tidak jauh lebih baik, ia menderita kelainan usus hingga saat ini. Dan mantan asistennya Mr. Arief itu pun kabarnya jauh dari kata baik.
Semesta tak mau bekerja sama dengan para pendusta, tentu saja.
Mereka adalah keluarga bahagia, Kak Mei sangat baik padaku dan pada kami semua. Di teras depan, aku, Pak Bah dan Pak Leo sempat diam beberapa saat sibuk dengan isi kepala sendiri. Manusia tiga generasi dengan perjuangannya masing-masing.
“Bagaimana dengan pekerjaan barumu, Dip?” Pak Leo membuka kata, membunuh sepi yang menghalangi hangatnya rumah Pak Bah.
“Semoga aku menyukainya. Minggu depan aku berangkat, Pak Leo.”
“Aku senang punya keponakan cerdas macam kau ini. Di mana dirimu ditempatkan?”
“Di sebuah desa bernama Sarang Panjang yang letaknya di kaki barisan Pegunungan Randu Dahyang. Ada beberapa situs temuan baru yang harus diteliti lebih lanjut. Tidak hanya satu tempat, kabarnya ada dua situs yang diindikasi adalah bangunan petirtaan kerajaan jaman dulu, sementara situs lain belum bisa diambil hipotesis atau semacamnya.”
“Tentu kau akan menyukai pekerjaanmu itu, Dip. Aku kerap memimpikanmu menjadi seseorang yang gagah, cerdas dan bekerja untuk masa lalu,” entah apa yang Pak Bah maksud kali ini, tapi aku selalu menyukai ucapan-ucapannya, “Kalau Pak Bah boleh tahu, bagaimana kau dan teman-temanmu bisa membedakan masing-masing dari temuan situs itu? Sependek yang aku tahu, temuan itu hanya berupa jajaran atau susunan batu bata yang sudah tertimbun oleh tanah. Bukankah mereka semua terlihat sama?”
“Memang betul apa yang Pak Bah ucapkan tadi. Untuk tahu apakah susunan bata itu adalah candi, atau makam, atau malah ternyata tidak berarti apa-apa, maksudnya tidak lebih dari tumpukan bata biasa, kami harus melakukan ekskavasi pada temuan-temuan tersebut, kami juga mencari acuan dan referensi pada kitab dan catatan sejarah, barangkali memang ada hubungannya dengan situs atau tempat yang akan kami teliti. Namun terkhusus pada petirtaan atau tempat pemandian kerajaan di masa lalu, ada sebuah mata air yang mengalir di antara batu bata merah tersebut. Walaupun tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Untuk batu batanya sendiri pun berbeda dengan batu bata merah jaman sekarang. Ukuran volumenya lebih besar dan metode pembuatannya pun tidak direkatkan dengan semen atau isian, melainkan digosok dengan terus dialiri air. Singkatnya begitu, Pak Bah.”
“Menarik sekali, yah. Aku jadi ingin ikut kau bekerja minggu depan.” Gurau Pak Bah dengan tawanya yang khas.
“Besok, kalau mau berangkat, telepon aku. Biar kuantar kau sampai stasiun.” Pak Leo selalu bersedia membantu kekuranganku tanpa aku meminta.
Aku mengangguk tersenyum dan mengucapkan terima kasih.
“Sepertinya kopi kami tinggal ampasnya saja, Dip. Boleh tolong buatkan segelas lagi? pakai cangkir yang kecil saja aku tak ingin insomnia nanti malam,” aku melakukan apa yang beliau katakan, “Ambil juga kripik pisang buatan ibumu yang tadi kau bawa di lemari atas. Mulutku dingin jika tidak mengunyah sesuatu.”
Walaupun sudah lama tidak masuk ke rumah Pak Bah, aku tidak lupa tempat beliau menaruh sesuatu mulai dari gula, garam, kopi, teh, susu, mie instan dan makanan ringan yang biasa Pak Bah jadikan cemilan. Tentu saja aku tidak akan lupa karena letak barang dan tempatnya sama sekali tidak berubah. Kadang, hal-hal yang semacam ini lah yang membuatku merasa kembali ke rumah. Ketika aku kembali, tempat-tempat yang kutinggalkan tidak melupakanku atapun membuatku lupa.
Entah apa yang tengah bapak-bapak itu bicarakan di teras depan. Suara tawanya terdengar jelas bahkan hingga ke dapur tempatku meracik kopi.
Kopi ini buatan ibuku. Kami orang Nara terbiasa membuat kopi hitam sendiri, dari kebun sendiri. Mulai dari memetik, menjemur, menumbuk dan menyangrainya kami lakukan sendiri, kecuali saat menggilingnya. Aku sudah bertetangga dengan pohon kopi sejak kecil, ia ditanam sekali dan berbunga sepanjang tahun.
Kopi yang sudah merah akan segera dipetik sebelum rontok dan busuk di tanah. Aku cukup ahli dalam memanjat pohon dan meraih tangkai yang tinggi-tinggi, aku dan ibu sering meminta tolong tetangga yang luang waktunya untuk turut memanen kopi sebelum didahului tupai atau codot. Kopi merah yang masih mentah sangat hits di kalangan hewan mamalia karena rasanya yang manis, kadang aku iseng mencicipinya.
Dulu, saat ayah masih ada, kami bisa memanen kopi hingga tiga karung, baru kemudian dijemur dan dipisahkan dari kulitnya. Saat yang paling aku suka adalah ketika biji-biji kopi kering itu disangrai, wanginya benar-benar membuat nyeri di kepalaku sedikit terangkat. Setelah disangrai, barulah biji kopi yang sudah hitam mirip arang tadi kemudian digiling ke tempat penggilingan.
Dulu almarhum ayah punya mesin gilingan sendiri, dan kami pun menerima jasa giling kopi. Sekali giling biasanya diongkosi lima sampai sepuluh ribu. Tapi, menurut yang aku dengar dari ibu, sebelum orang Nara menggunakan mesin penggiling, mereka bisa menumbuk biji kopi itu dengan tenaga sendiri menggunakan lumpang dan alu.
Alu adalah kayu lurus, panjang, dan mengkilap dengan kedua ujung yang tumpul untuk menumbuk kopi, sementara lumpang adalah tatakannya, tempat kopi ditumbuk. Dari proses yang sederhana itu, tercipta cita rasa kopi yang tidak pernah sama dengan buatan pabrik, aku berani bertaruh.


 littlemagic
littlemagic