Hati yang kurang hati-hati bisa jadi petaka bagi siapa saja. Seminggu ini aku benar-benar mencoba bertahan dengan diriku sendiri.
Menerima sisa-sisa kesabaran dalam sebuah penerimaan yang utuh.
Aku mencoba bersyukur atas apa pun yang terjadi pada diriku meski dipandang hanya seujung kuku, aku hanya tidak pandai melihat yang lebih luas lagi.
Entah tenung apa yang membuatku dipecat berkali-kali. Mungkin aku terlalu sibuk berusaha hingga lupa diri.
Lupa bahwa akan selalu ada faktor-faktor dalam kehidupan ini yang tidak kita mengerti, yang turut andil dan mengambil peran untuk menggiring kita kepada takdir yang telah ditentukan.
"Kau hanya harus percaya kalau apa pun yang menimpamu adalah baik, mungkin akan sulit menyadarinya sekarang. Tapi jawaban tidak harus datang sekarang, mungkin nanti, mungkin juga besok. Tidak ada yang tahu. Tidak usah terburu-buru memaksakan takdir untuk menceritakan rencananya. Kita hanya tidak boleh berhenti percaya."
Setelah hari-hari yang menyedihkan, Ibu sudah bisa dikatakan lebih baik saat ini.
Ia mulai bisa duduk dan berdiri tanpa harus merasa pusing atau mual yang berlebihan.
Ia juga sudah tidak dianjurkan lagi untuk minum obat pereda nyeri lambung setiap hari.
Lihat aku kini, pengangguran dan bekerja serabutan, tidak punya kejelasan tentang masa depan, belum mapan dan tidak punya pasangan.
Predikat mana lagi yang lebih menyedihkan dariku?
Tapi lihatlah gadis yang kini tengah bersamaku, menemaniku, membantuku merawat Ibu.
Rela meluangkan waktu di antara segala kesibukan yang ia punya. Aku sungguh tidak memintanya, aku bahkan menyuruhnya pulang, barangkali ia punya hajat yang lebih penting.
Namun ia menolak, entah untuk alasan apa ia tetap menemaniku.
"Bang, Mba Laila minta dijemput di perempatan pasar. Katanya belanjaannya banyak, motornya tidak cukup untuk membawanya sendiri." Sena memberikan kunci motor milik ayahnya padaku.
"Tapi aku tak bisa pergi, bagaimana dengan Ibu?"
"Ibu sedang istirahat, nanti kalau tiba-tiba terjaga masih ada aku. Abang juga perginya kan tidak lama," ucapnya dengan menepuk punggungku.
Aku belum pernah memastikan perasaan padanya, aku juga tidak tahu apakah orang sepertiku pantas untuknya yang begitu berkilau dan ramah kepada siapa pun.
Aku takut tidak cukup mampu untuk membuatnya bahagia jika ia bersamaku. Sebenarnya aku benci pikiran semacam ini.
Karena seberapa pun aku mencoba, bayang Zahwa selalu menyertai.
Seolah aku selalu menyama-nyamakan sosok Sena dengan Zahwa.
Padahal aku tahu itu tidak boleh dan aku tidak berhak menilai siapa pun. Aku juga tidak pantas.
Tapi semakin ke sini, aku semakin dewasa dan memaksaku berpikir realistis.
Memangnya apa yang memastikan Zahwa akan kembali padaku? Apa yang membuatnya bertahan padaku sementara aku tidak pernah memberinya pegangan?
Apa alasan yang membuatnya tidak bisa menerima orang baru dengan keadaannya yang sekarang?
Kini ia telah lebih cantik, lebih berpendidikan dan lebih berpengalaman, sementara aku masih begini-begini saja.
Jangan-jangan pikiranku tentang Zahwa yang mengharapkan punya perasaan yang sama denganku, hanyalah angan-angan belaka yang aku ciptakan sendiri.
Jangan-jangan diriku lah yang membesar-besarkan asumsi tentang dirinya secara berlebihan. Tapi apa yang bisa aku lakukan?
Sepulang membawa belanjaan, Sena membantu menurunkan barang-barang.
Ia terlihat akrab dengan Lail, meskipun pada awalnya Lail bilang tidak terlalu menyukainya karena rambut Sena yang ganti-ganti warna, tapi kini ia terlihat terbiasa dengan itu.
Aku sering menemukan mereka tertawa bersama, entah tengah membahas apa.
Ibu juga, saat bersamaku, Ibu tak lagi menanyakan tentang Zahwa. Ibu juga mulai bertanya jika Sena tidak datang ke rumah.
Benar yang Pak Bah ucapkan dahulu, pertemuan yang tidak sengaja, kebanyakan memang mengubah rencana.
Entah dengan cara yang bagaimana tiba-tiba Sena menyelusup masuk ke dalam kehidupan keluargaku.
Sangat lincah, apik, dan mulus, kini ia tengah jadi penyusun cerita ceria di bawah atap rumahku, meskipun ia belum menjadi siapa-siapaku.


 littlemagic
littlemagic








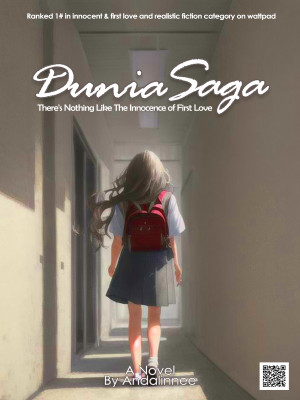



I wish I can meet Nadif & Pak Bah in real life :'
Comment on chapter Epilog