Semburat sinar remang-remang menerobos dinding rumahku yang masih terbuat dari anyaman bambu.
Mataku mengerjap-erjap menatap langit-langit kamar yang bersih tak ada satu pun sarang laba-laba. Hari baru, usaha baru, rezeki baru.
Sudah seminggu aku tidak bertemu Zahwa, harusnya lumrah saja jika kejadian di jembatan itu tidak terjadi. Aku merasa dia seperti menjauh, entah benar atau hanya perasaanku saja.
Kutunggu ia di rumah, tapi tidak datang. Setiap hari aku pura-pura membeli barang-barang di tokonya yang sebenarnya tidak terlalu aku butuhkan, hanya agar bisa bertemu, tapi ia tidak ada.
“Bu, Zahwa sekarang tidak pernah kemari ya?” Masakan Ibu kali ini spesial, sup jamur kesukaanku. Kemarin Ibu menemukan jamur tiram ini di kebun dekat mata air.
“Ada apa, Nang? Bukankah kamu yang tiap hari ibu lihat datang ke tokonya, harusnya kamu yang lebih tahu.”
Aku hampir tersedak, diam-diam Ibu tahu kebiasaan anehku. “Nadif tidak bertemu dengannya, Bu.”
Ibu menyendok sambal bawang dan menaruhnya di piring yang tengah aku pegang.
“Atau Zahwa sedang pergi? Ibu dikabari atau tidak? Atau Zahwa sedang ikut Pak Akbar ke luar kota?”
Ibu menggeleng, “Ibu tidak tahu, Nang. Hal yang seperti itu harusnya kau tanyakan sendiri padanya, bukan pada ibu atau orang lain, bukan juga pada diri sendiri. Satu-satunya orang yang tahu jawaban pastinya adalah orang itu sendiri.”
Aku diam lagi sambil mengunyah makanan dan sibuk dengan isi kepala.
“Jangan mengira yang tidak-tidak,” kata Ibu, “kalian sedang bertengkar?”
Aku diam sejenak, “Tidak tahu, Bu.”
Sarapanku sudah selesai, kugendong sling bag hitam andalanku dan mencium tangan Ibu, siap-siap berangkat ke toko.
“Nadif berangkat kerja dulu, Bu. Assalamualaikum.”
Di ambang pintu, Ibu membalas salam dan berkata. “Nang, jika kau menyukai seseorang kau harus mendoakan kebaikan baginya.”
Aku mengangguk, sejak Ayah masih ada, Ibu selalu mengatakan hal itu padaku.
Sebelum sampai di persimpangan, kuulangi lagi kebiasaan baruku yang sudah aku lakukan selama seminggu ini, yaitu membeli barang tidak penting ke toko Bu Widi dengan harapan bisa melihat Zahwa.
Pagi ini barang yang kupilih untuk dibeli adalah korek bensol.
Sempat terpikir ingin membeli solasi bening saja yang lebih murah, tapi benda itu sudah kubeli di hari ketiga atau tepatnya empat hari yang lalu.
Mungkin jika barang-barang remah seperti ini sudah semua aku beli, bisa jadi beras seperempat kilo atau minyak goreng kemasan kecil akan ikut dalam usaha terselubungku ini.
Entah akan sampai hari ke berapa.
Sepanjang jalan aku merenung, kerjaku di toko tidak maksimal. Aku lima kali dimarahi pelanggan dan baru saja sehari yang lalu aku berkelahi dengan Jupri.
Tidak hantam-hantaman, melainkan hanya adu mulut. Hal itu malah lebih berbahaya karena yang terluka bukanlah fisik tapi langsung ke hati. Lisan adalah benda tajam bagi perasaan.
Apa mungkin hal ini ada hubungannya dengan Zahwa? Apa mungkin suasana hatiku yang kurang baik ini berpengaruh sampai ke kehidupan nyataku?
Jika iya, mengapa aku jadi tidak profesional sekali.
Di tengah jalan aku bertemu dengan Dilan, kakak Zahwa satu-satunya. “Dip, mau sekalian bareng tidak? Aku mau ke Koperasi.” Ia mengendarai motor matic yang biasa dibawa Zahwa.
“Boleh, Bang.”
“Tumben, jalan kaki. Biasanya sama Laila, atau sama Nurdin.”
“Sedang ingin jalan, Bang. Sambil olah raga.” Aku tertawa kecil. Aku ingin bertanya tentang Zahwa tapi untuk menyebut namanya secara terus terang rasanya tenggorokanku tidak sanggup. “Kemarin keluarga pergi ke mana, Bang?”
“Kemarin, tidak pergi-pergi, Dip.”
“Maksudnya seminggu yang lalu.”
Lawan bicaraku diam sebentar terlihat sedang mengingat-ingat. “Oh itu, kami ke kota kabupaten, Dip. Mengantar Ayah berobat.”
“Satu keluarga?”
“Iya, darah tinggi Ayah tiba-tiba kumat. Aku yang menyetir, Ibu dan Zahwa menjaga Ayah di belakang.”
Satu pertanyaanku telah terjawab.
Kuucapkan terima kasih dan Dilan meneruskan laju kendaraannya sampai ke Koperasi.
Di toko, Jupri masih mendiamkanku gara-gara aku menghilangkan desain undangan pernikahan milik pelanggan yang harus dicetak hari itu juga.
Sudah kubilang aku tidak sengaja dan meminta maaf, tapi malah Jupri mengungkit-ungkit kinerjaku yang payah selama seminggu ini.
Aku yang tidak terima, dengan pikiran dan fisik yang lelah, meledak-ledak karenanya. Rasa saling maklum yang kurang antar pegawai tak jarang jadi sumbu perpecahan di dalam pekerjaan, seharusnya hal seperti itu wajar.
Tapi kesadaran untuk saling mewajarkan belum menelusup masuk ke otak dan hati kami berdua yang masih bebal.


 littlemagic
littlemagic







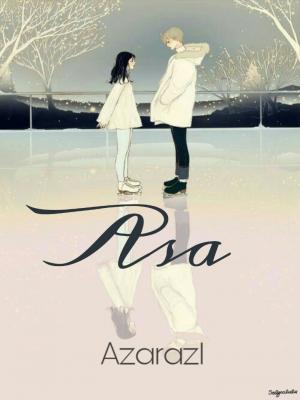




I wish I can meet Nadif & Pak Bah in real life :'
Comment on chapter Epilog