Sorenya aku pulang dengan Nurdin, dia mengajakku mampir ke warung ronde. Aroma jahenya yang kuat dan hangat membuat minuman ini sangat cocok dengan kami yang tinggal di pegunungan.
“Aku titip satu ya, buat Laila.” Nurdin menyodorkan satu plastik berisi wedang ronde.
“Buatku mana?”
“Besok, Dip. Aku sedang tipis.” Maksudnya dompetnya.
“Pajak, Din. Atau plastik ini tidak sampai ke kakakku.” Aku pura-pura mengancam.
Nurdin mengeluh. “Tolonglah, Dip. Kamu kan kawanku yang paling baik.”
Aku berdecih malas disogok dengan kata-kata. Nurdin dan aku bertetangga tapi tak dekat, rumahnya di puncak sementara aku di kaki bukit.
Beberapa kali terdengar gosip dari anak-anak sepantaranku tentang Nurdin yang sedang mencoba mendekati kakak perempuanku yaitu Laila. Salah satu caranya adalah dengan mendekatiku.
Sebenarnya aku dan Nurdin sudah berteman sejak lama, tapi memang akhir-akhir ini Nurdin lebih sering mengajak pergi atau silaturahmi ke rumahku.
Aku sebenarnya tidak terlalu setuju jika kelak Nurdin jadi kakak iparku, tapi biarkan saja.
Laila juga kelihatannya tidak tertarik, terakhir yang aku tahu Laila tengah naksir dengan karyawan bank syariah yang dekat dengan rumah sakit tempatnya bekerja.
Ingin kukatakan hal itu pada Nurdin, tapi aku tak sampai hati.
Lagi pula Nurdin tak pernah terang-terangan mengatakan padaku jika ia menyukai kakakku, yang ada hanya ia menanyakan kabar, menitipkan buah tangan, meminta tolong padaku untuk melakukan ini itu.
Aku mau-mau saja, karena yang ia minta pun tidak merepotkanku, malah menguntungkan. Misal nanti ronde ini tidak Laila makan, tentu saja aku yang habiskan.
Pernah pada suatu saat Nurdin menitipkan dua batang coklat, yang satu besar yang satu kecil. Dia bilang yang besar untuk Laila dan yang kecil untukku. “Tolong jangan dulu bilang kalau ini dari aku, Dip,” tambahnya. Aku iya-iya saja.
Dua hari setelahnya Laila memarahiku karena coklat yang ia makan ada kacangnya. Tiga jerawat berkunjung di pipi, alis, dan dagunya.
Aku sempat berdebat dengannya jika yang membuatnya berjerawat bukan kacang, melainkan coklatnya. Laila bisa menolaknya sejak awal. Tapi ia tak mau tahu, pokoknya aku harus tanggung jawab.
Ingin sekali kukatakan pada Laila jika coklat itu pemberian Nurdin, jadi mengapa harus aku yang tanggung jawab. Namun urung, aku sudah berjanji untuk tidak mengatakannya.
Kusampaikan kabar itu pada Nurdin. “Laila marah besar?” tanyanya.
Aku mengangguk, kukatakan jika Laila marah mirip sekali dengan ayam betina yang kehilangan telurnya.
Tak kusangka, Nurdin langsung menunduk dalam penuh penyesalan seolah kekeliruan besar yang menyangkut kedamaian dunia telah ia lakukan secara tidak sadar.
Aku mencoba membesarkan hatinya bahwa belum tentu jerawat itu ia yang sebabkan, bisa saja memang siklus bulanan Laila hampir tiba, aku dengar-dengar itu bisa menyebabkan datangnya jerawat.
Tapi Nurdin mengelak dan menunduk tambah dalam. “Tidak, Dip! Akulah penyebabnya, aku yang menyuruhmu memberikannya coklat hingga muncul jerawat yang tidak Laila sukai di wajahnya. Aku yang salah, Dip. Aku!” Sambil menepuk dadanya, masih dengan penuh penyesalan.
Aku keheranan menatap pria berbadan besar di depanku, mengapa Nurdin menjadi lembek begini.
Padahal urusan jerawat ini sangat sederhana dan wajar, tapi Nurdin bertindak seperti jerawat adalah alasan mengapa ia akan ditolak saat melamar Laila kelak. Sangat tidak logis.
Lama kelamaan menatap Nurdin, sejujurnya aku ingin tertawa tapi juga prihatin. Ia masih menunduk, saat ia mendongakkan kepala, aku buru-buru memasang wajah normal seolah tidak terjadi apa-apa.
Tidak lama ia pamit pulang dengan badan lesu dan langkah yang gontai karena mendengar kabar dariku.
Aku jadi ikut merasa bersalah, tapi aku juga tidak tahu jika Nurdin akan menanggapi perkara jerawat hingga seperti itu.
Kulihat Nurdin melangkah lemas menaiki jalan berundak menuju rumahnya, tidak kusangka lelaki sekuat Nurdin yang sanggup menguliti kambing hanya dengan satu kepalan tangan di tempatnya bekerja, menjadi sangat loyo ketika berhubungan dengan perasaan.
Kulitnya yang coklat matang, berubah menjadi pucat.
Perasaan bagaimana yang kini tengah merundungnya? Lalu ke mana logikanya pergi?
Belum selesai sampai di situ, malam harinya Nurdin kembali ke rumah dengan membawa sebuah salep kecil katanya itu obat jerawat.
Aku manggut-manggut saja diminta untuk memberikannya pada Laila.
Dengan tambahan, ”Tolong jangan dulu bilang kalau ini dari aku, Dip.” Aku mengacungkan jempol seperti biasa dan Nurdin segera pamit pergi, bilang sudah terlalu malam.
Setelah aku berikan salep itu pada Laila, ia tak terlihat keberatan dan mengucapkan terima kasih. Semua terasa aman, sementara.
Paginya, kamarku didobrak Laila saat masih subuh buta. Ayam di kandang berkokok terkejut seperti melihat jin.
Ia mengomel lebih mengerikan dari sebelumnya. Aku bersembunyi di atas lemari panjang yang tidak bisa ia jangkau.
Omelannya tak berhenti hingga Ibu datang menengahi dan bertanya ada apa.
Laila menjelaskan, ternyata salep yang semalam kuberikan bukan salep jerawat melainkan salep untuk bisul. Sambil terus bersembunyi aku menghela napas dan membatin, “Astaghfirullah, Nurdin...”.


 littlemagic
littlemagic




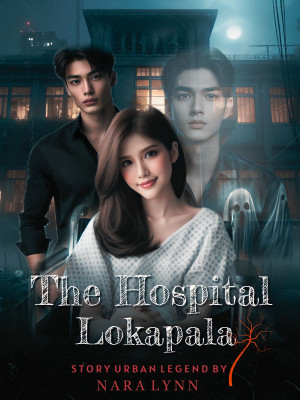







I wish I can meet Nadif & Pak Bah in real life :'
Comment on chapter Epilog