Aku menunggu pagi meminta maaf kepadaku. Ayam baru selesai berkokok tapi mejaku sudah penuh dengan tumpukan kertas yang belum dijilid.
Anak-anak SMA rewel bukan main minta makalahnya diselesaikan paling dulu.
Mulut mereka seperti ada seribu, riuh berisik memenuhi jagad Toko Berdikari. Tak ada yang tidak berebut, alasannya klise, sudah ditunggu gurunya di kantor.
Beberapa dari mereka merengek, merasa sudah akrab denganku. Alih-alih kasihan, aku muntab dan mereka kubentak sekalian.
“Lain kali kalau bikin tugas jauh-jauh deadline! Jangan satu jam ditagih baru ingat ada tugas,” ucapku sambil mengacung-acungkan lakban dan stapler ke hidung mereka.
Aku sudah persis emak-emak yang emosi karena hutangnya tak kunjung dilunasi.
“Maaf lah, Bang. Kalau belum mepet deadline otaknya belum bisa disuruh mikir,” jawab salah satu dari mereka, kalau tidak salah namanya Gopal.
“Kalau begitu, pepet saja otakmu sendiri, jangan otakku juga kamu pepet suruh cepat-cepat menjilid makalahmu ini.” Aku mengomel seperti belum pernah jadi anak SMA saja.
Padahal zaman SMA-ku lebih parah dari ini. Dahulu, aku bahkan pernah beberapa kali meminta kawan lain untuk mengerjakan tugasku saking banyaknya tugas yang aku tumpuk. Tunda, tunda, dan tunda adalah hobiku dahulu.
Derum motor yang suara mesinnya masih halus merapat ke parkiran toko. Pengendaranya turun dan mencantolkan helm bogo bermotif jam dinding berwarna coklat di atas spion kanannya.
“Bang Nadif, sudah nge-print CV-ku yang semalam? Sudah aku kirim via e-mail.” Suara itu ibarat lagu merdu di tengah hiruk pikuk Toko Fotokopi Berdikari yang dipenuhi anak sekolah.
“Eh, Zahwa.” Aku salah tingkah, berharap ia tadi tak melihatku mengomel seperti emak-emak. “Belum sempat aku print. Toko sudah ramai bahkan sejak kami belum buka. Anak-anak inilah penyebabnya.” Aku melirik kesal ke arah pasukan putih abu-abu, yang dilirik, balas memelototiku.
Zahwa tertawa, “Aku perlu CV itu sekarang, Bang. Mau aku scan buat tes masuk PTN sama daftar beasiswa yang kemarin aku cerita itu, pendaftarannya ditutup nanti malam, sepuluh jam lagi. Masih banyak berkas yang harus aku lengkapi.”
“Waduh, kalau begitu biar aku print-kan sekarang.” Pasukan anak SMA protes tidak terima, mereka sudah menunggu sejak jam enam pagi dengan harap-harap cemas tidak diomeli Ibu guru di sekolah karena telat mengumpulkan makalah.
Dari selidik-selidik yang kerap mereka ceritakan, guru bahasa yang bernama Bu Sumi itu memang mengerikan bukan main. Aku membayangkan beliau tidak lain seperti Profesor Dolores Umbridge di Film Harry Potter. Bedanya beliau tidak bisa sihir.
“Makalah kami dulu, Bang. Mbak ini kan baru saja datang.” Sorak-sorai membuntut di belakangnya, setuju.
“Hust! Mbak ini sudah kirim e-mailnya sejak semalam. Berarti dia duluan, lagi pula keperluannya lebih penting. Dia mau daftar sekolah universitas di kota besar sana. Kalian kalau lulus nanti mau juga kan?”
Mereka mengangguk.
“Nah, ya sudah. Biar aku melayani Mbak ini dulu,” kata mbak ini membuatku sedikit geli, tidak pernah sekalipun aku memanggilnya demikian.
“Baaaang, jangan begitu. Bu Sumi sudah pasang tanduk, kami ndak boleh telat lebih lama lagi,” protes mereka lagi.
Zahwa tertawa, “Aku print sendiri saja boleh tidak, Bang? Biar Bang Nadif selesaikan makalah anak-anak.”
Pasukan anak SMA berteriak setuju. Setelah berpikir sejenak, aku mengangguk. Sepakat. Cukup adil. Mau bagaimana lagi.
Tangan Zahwa segera lincah mengotak-atik tikus elektronik yang tersambung dengan CPU. Mata sayunya menatap tajam pada layar monitor mencari pesan singkat yang katanya sudah ia kirim semalam.
Salah satu anak SMA berbisik padaku. “Abang suka sama perempuan itu ya?” Sambil tertawa cekikikan.
“Mana ada! Tidak. Kami hanya tetangga.”
“Oooooo,” jawab mereka meledek, sambil tertawa-tawa.
“Sungguh!” Aku merasa mereka tak percaya dengan perkataanku tadi.
“Kalau cuma tetangga, kenapa dari tadi Abang tidak berhenti melirik-lirik?”
“Kata siapa aku melirik? Aku hanya memastikan tombol yang ia klik di komputer benar.” Aku melotot, sebenarnya jelas aku berbohong, aku memang ingin melihatnya, tapi mana mungkin aku bisa terus terang dengan hal bodoh ini di depan anak-anak SMA yang senang sekali membuat emosiku naik turun. “Kalau kalian tidak diam, aku buang semua kertas ini, bila perlu aku sobek-sobek.”
“Ampun, Bang. Kenapa jadi sensi sekali.”
Aku diam, sambil sesekali melirik Zahwa dan kembali fokus pada lakban dan stapler. Anak-anak SMA masih berkerumun di depan etalase toko menunggu giliran.
Semakin siang toko bertambah ramai, mereka menyerbu toko membuat kewalahan para pegawainya.
“Sudah, Bang. Semuanya dua lembar. Harganya berapa?” Zahwa mengemas kertasnya untuk dimasukkan ke dalam tas.
“Eh cepat sekali. Sudah gratis saja.”
“Jangan begitu, Bang. Aku jadi tidak enak.”
“Cuma dua lembar, di-print sendiri. Tidak apa. Berdikari tidak akan rugi hanya karena itu,” jawabku sambil tersenyum.
“Tidak mau.” Zahwa meninggalkan dua lembar uang seribuan di etalase toko. “Terima kasih banyak, Bang Nadif.” Sambil berlari ke sepeda motornya, takut uangnya kukembalikan.
Aku tersenyum menatapnya yang tersenyum padaku. Dia memang menggemaskan sekali, membuat siangku jadi tidak terlalu penat, lumayan bisa untuk refreshing dari seharian meneriaki anak-anak SMA.
Zahwa melambaikan tangannya padaku dan mengangguk berpamitan. Aku balas mengangguk, tentu saja dengan memasang senyum terbaik yang aku punya, meskipun tetap jelek.
“Bang, aku gratis juga ya?” celetuk Gopal si anak SMA. Ingin sekali aku piting kepalanya.


 littlemagic
littlemagic


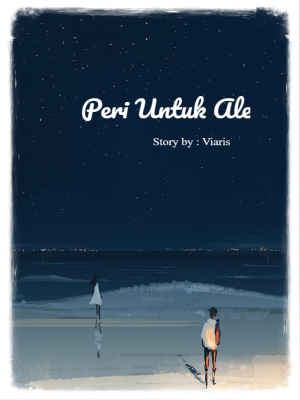









I wish I can meet Nadif & Pak Bah in real life :'
Comment on chapter Epilog