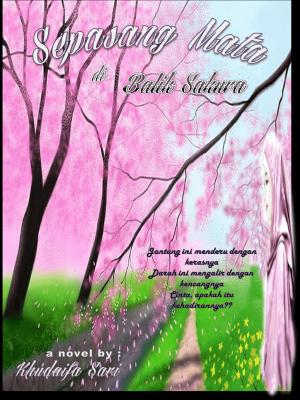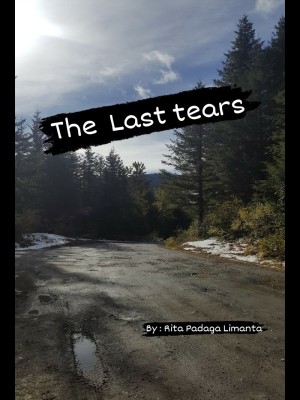“Oh ... marah,” cicit Dienka. Mendadak pikirannya terarah ke segala arah.
“Lo samperin dia, ya, Ka. Gue percaya sama lo.”
Dienka mengangguk cepat, merasa seberkas semangat menyinari hatinya. “Lo tahu dia di mana?”
“Belakang sekolah.” Candra mengembangkan senyuman tipis yang terpaksa. Mempercayakan segalanya pada Dienka.
Dienka mematung, menjadi canggung. Suasana apa ini? Marah?
“Ya udah, gue pergi dulu. Lo nggak perlu mikirin Lana. Gue janji anter dia balik ke kelas.”
Candra mengangguk setuju. Membiarkan Dienka beranjak seorang diri ke belakang sekolah.
Lapangan dan kawasan sekolah lainnya mulai lengang lantaran bel pertanda usainya istirahat akan segera berbunyi. Tanpa berniat untuk menyerah ataupun lelah, Dienka terus menyusuri belakang sekolah yang luas. Dengan lengan yang menggaruk tendasnya frustrasi, ia berhenti di satu titik—tak mengerti di mana tepatnya harus mencari Lana. Besarnya belakang sekolah membuatnya sedikit kewalahan.
Namun, seolah mendapat pencerahan dari Tuhan, telinga kecilnya itu menangkap suara sedu sedan lirih yang entah bagaimana terasa nyata. Lantas tanpa keraguan, Dienka mendekati suara itu dengan harapan suara Lana-lah yang di dengarnya, bukannya lelembut.
Harapannya terkabul. Itu sungguh Lana. Terduduk, menyembunyikan paras di balik paha yang tertutup jaket merah berbahan katun. Gadis itu tampak menyedihkan.
Meski berupaya meredam suara tangisannya, Lana gagal. Seakan tak bisa mengontrol diri, ia meneruskan tangisannya dengan yang terdengar pilu. Hal itu jadi kali pertama dan langka bagi Dienka untuk melihat sisi melankolis Lana.
“Lan.”
Lana menaikkan hulunya terkesiap, segera menghapus sisa air mata saat menemukan Dienka terduduk di sandingnya.
“Eh? Kok berhenti nangis? Nangis aja. Gak baik ditahan. Pura-pura bahagia dan kuat itu sakit, ‘kan?”
Tanpa diperintah kedua kali, tirta bening itu sudah kembali mengalir deras. Tangisan yang tadinya merepotkan, kini menjadi melegakan.
“Ucucuu ... sini, sini.” Dienka menarik lembut tubuh Lana dan mendekapnya. Gadis itu tak sampai hati membiarkan sahabatnya menangis seorang diri.
Isak Lana makin menjadi, malar-malar tangannya mencengkeram lengan bebas Dienka sebagai luapan kemarahan. Dienka tersenyum, membiarkan Lana menyelesaikan acara tersedan-sedannya agar kelak dapat bercerita dengan jelas dan benar.
[🌻]
Dengan surai yang masih basah kuyup, Lana berlari ke lapangan basket. Tempat di mana dia biasa menemukan Candra. Tempat di mana mereka bertiga—Lana-Irena-Candra—biasa menghabiskan waktu bersama. Namun, semua tinggal kenangan. Keadaan telah berubah, dan mereka dipisahkan oleh kesalahpahaman.
Bukannya mendapati Candra, Dienka, lebih-lebih Varen; Lana justru menjumpai Irena yang mematung. Menahan tangisan dengan pandangan pada lapangan. Pemandangan itu turut membuat Lana mematung di tempat. Sampai ketika Irena menyapu pandangan dan menyadari ekstensi Lana, gadis bersurai hitam pekat itu buru-buru berlalu menghindarinya.
“Ren! Tunggu!” Dengan sigap Lana mencekal erat lengan Irena. Dia sudah benar-benar siaga ketika akan didorong kembali. “Lo bener-bener mutusin persahabatan kita? "
Irena tak menjawab. Namun tak tercipta berontak seperti sebelum-sebelumnya.
"Udah berhari-hari sejak kita pisah dan—gue nggak bisa, Ren. Lo berarti bagi gue! Mau bagaimanapun lo sahabat gue. Jangan biarin satu masalah merusak hubungan kita gitu aja, Ren. Tolong b—”
Irena menepis tangan Lana, tak sekasar sebelumnya. “Apa? 'Berarti'? Duit gue?” sarkasnya.
“Lo nggak mau coba percaya sama gue?” lirih Lana dengan ain berkaca-kaca.
“Gue pernah percaya sama lo! Tapi apa? Gara-gara lo Varen jadi benci gue. Itu semua karena insiden kepala lo yang bocor!” Irena menggeleng cepat, “Varen lupain beribu-ribu kebaikan gue karna kejadian itu. Dia lupain semua kenangan yang udah kita lalui. Dia abai sama gue.”
“Gue—“
“Kalau lo nggak mau terluka lagi, lebih baik lo pergi.” Setelahnya Irena berlalu, meninggalkannya.
Seolah menyerah, Lana hanya memandangi punggung Irena yang makin menjauh. Menyerahkan semuanya pada sang sangkala dan Tuhan yang pastinya menghendaki terbaik pada tiap umatNya.
“Lo bodoh, Lan!” Lana membalikkan badannya, tergemap lantaran sekonyong-konyong Candra memakinya begitu saja. “Lo kenapa sih jadi sok lemah gini? Lo kenapa biarin diri sendiri ditindas?”
“Gue gak akan jauh berbeda dari mereka kalau gue reaktif juga.”
Sembari terus mengegah mendekati Lana, Candra menggeleng. “Nggak, Lan. Lo di cap takut sama mereka. Di cap pengecut!” desis Candra, terlihat gemas dengan tingkah Lana itu. “Lihat seragam lo. Lo nggak capek setiap pulang sekolah yang sore banget itu langsung cuci baju, gantung, setrika? Waktu belajar lo habis, Lan! Lo lawan mereka, dong!”
Lana kehabisan kata-kata. Gusar dan resah untuk menimpali ucapan Candra beberapa saat lalu.
“Lo juga kenapa minta maaf sama cewek egois itu, sih—Irena?!” Candra kian meninggikan suaranya.
“Dia sahabat kita, Can,” cicit Lana.
“Sahabat? Mana mungkin sahabat lebih percaya sama orang lain banding sahabatnya sendiri?” Lana membeliakkan matanya. Terkejut akan suara Candra yang terus meninggi. “Gue paham kalian sahabatan sejak lama. Tapi apa adil lo digituin?!”
“Can ... gue juga gak mau keadaannya kayak gini.”
“Kalau gitu lo lawan mereka! Serang mereka balik! Jangan jadi lemah!” sentak Candra penuh penekanan. Menolak menimpali, Lana hanya membisu. “Apa bener rumor lo tentang Varen? Oh ... lo bener suka sama dia?”
Lana menggelengkan tendasnya secepat mungkin.
“Terus kenapa lo gak jelasin ke mereka?! Lo harus berani untuk jelasin! Gue nggak suka liat lo menderita, nangis tiap kali!”
“Apa mereka bakal percaya sama gue?!” Lana menahan isakannya, “Irena yang sahabat gue sendiri aja nggak percaya! Apalagi mereka!"
“Lo bahkan nggak pernah coba!” Candra menghentikan ucapannya sesaat, menatap Lana tajam-tajam. “Lo mau pertahanin gelar penikung lo itu, hah? Justru lo seakan membenarkan rumor itu! Lama-lama gue juga jijik sama lo kalau lo lemah kayak gini! Gue capek ngelindungin lo yang nggak bergeming ngerespons mereka!” tekan Candra di setiap katanya.
Lana merunduk, menyembunyikan paras seraya membenarkan posisi kacamatanya. Baru kali ini ia mendapat sentakan setinggi itu oleh Candra. Atau lebih tepatnya, ini kali pertamanya dibentak oleh lelaki itu. Kenyataan tersebut berhasil membuka luka di hatinya, mengikis pertahanannya.
Dengan lengan terkepal, Lana memberanikan diri untuk menentang Candra yang masih menghadap padanya. Memberanikan diri untuk balik menyentaknya.
“Gue juga nggak suruh lo lindungin gue, kok! Silahkan jijik sama gue!” Terdorong oleh rasa sakitnya, Lana memilih berlalu dengan terburu-buru. Menahan sedu.
Sadar peringatannya kelewatan, sadar ia melampiaskan keresahannya pada Lana membuat Candra meraup wajahnya kasar. Beralih gusar pada diri sendiri. 'Kenapa gue jadi bentak Lana sekeras itu?,' sesalnya.
“Gue minta maaf, Lan. Gue cuma mau lo bangkit. Gue benci lihat lo sedih ....” monolognya.
[🌻]
“Eumh ... Candra gak sekejem itu, kok. Dia tau apa yang terbaik buat lo. Gue juga. Gue bakal suruh lo bangkit ngelawan mereka. Mungkin suasana hati dia lagi buruk habis eskul basket,” urai Dienka, berusaha membuat Lana mengerti.
Seraya mengangguk, Lana berujar, “Gue tahu. Gue nggak bakal bisa marah sama Candra, Ka. Candra itu segalanya selain lo di sekolah ini bagi gue.”
Dienka meresponsnya dengan senyuman tipis.
“Eh, tadi lo bilang apa? Basket? Candra nggak menang?” berondong Lana, suasana hatinya sudah sangat membaik berkat Dienka dan lawakannya.
“Lomba aja enggak.”
“Hah?!”
Dienka membenarkan posisi silanya, bersandar pada tembok hitam di belakangnya. “Candra gak dipilih coach Didit buat lomba. Varen yang dipilih,” terang Dienka.
Lana manggut-manggut, mulutnya melangah, “Oh ... pantes tadi pagi nggak liat Varen,” gumamnya lirih
.
“Kenapa? Kangen?” goda Dienka sembari tertawa.
“Dih?! Kesimpulan dari mana?” pekik Lana kesal. Namun Dienka meneruskan tawanya.
“Eh ngomong-ngomong ... kok gak masuk akal, ya? Anak-anak yang lain kan mainnya lebih payah daripada Candra!” seru Lana tak terima.
“Bukan gitu, Lan. Coach Didit sengaja majuin anak-anak yang belum begitu mahir buat ikut lomba. Buat pengalaman belajar, buat acuan juga. Coba kalau dipilih yang mahir trus? Yang pemula kan lama-lama kesel juga minder, keburu nggak bergairah. Kalau emang begitu, berarti pihak sekolah yang egois. Mereka nggak mau lihat potensi tiap-tiap murid. Ya, ‘kan? Entar banyak yang gak semangat, asal-asalan—semakin kecil kemungkinan mereka mahir, dong.”
Lana mengangga sesaat, tetapi tetap manggut-manggut.
“Paham?”
“K-kayaknya, hehe.”
Dienka terkekeh samar, sementara Lana hanya menggaruk tengkuknya. “Sana balik ke kelas. Kalau entar masuk BK, bisa brabe gue. Bakal digeprek Mama!” gerutu Dienka.
“Okey! Thanks, ya, udah balikin mood gue.” Setelah mengatakan itu, Lana langsung bangkit dari posisinya.
“Always Lana cantiik! Habis pulang kita nge-mie ayam, yuk? It's on me.”
“Serius? Gue sih mau, sekalian baikan sama Candra.”
“Di mana?”
“Soal tempat, urusan gue.”
“Sip.”
“Okei! Lo emang the best, Ka!” serunya.


 aneylarevaa_
aneylarevaa_