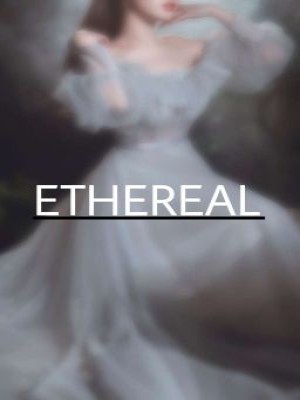“Lan, kamu bawa baju cadangan lagi?”
Lana menghentikan gerakannya, menoleh ke arah Olena yang menatapnya bingung. Sedikit menelisik tingkah Lana yang mencurigakan.
“Iya, Ma.”
“Ada acara outbond?”
“Ehm, iya semacam,” kilah Lana. Kembali memasukkan kemeja putih cadangannya dari kelas X, just in a case.
“Emang ada event apa, Lan?”
Lana tersenyum tipis, fokus dengan kegiatannya. “Kurang tahu, Mah.”
Olena memperdalam kerutan di glabelanya, kian memandang anak bungsunya dalam-dalam. “Kamu kalau ada apa-apa terbuka, lho, ya!”
“Iya Mama.”
“Bisa janji?”
Lana mengedikkan bahunya, “Mungkin.”
Gadis itu meraih tas punggungnya, mengangkatnya dan berjalan mendekati Olena. Semakin dekat jaraknya dengan Olena, makin hancur sanubarinya. Ia telah membohongi Mamanya berulang kali. Ia telah biasa berdusta kini.
“Mau langsung berangkat? Udah pesen ojek?”
Lana menyengguk hingga sang Ibunda menyodorkan lengannya, rutinitas Lana sebelum berangkat. Lantas, bukannya mencium telapak tangan Olena, Lana justru memeluk tubuh mungil itu. Mengeratkannya, berusaha untuk menutup luka di hatinya yang telah menganga lebar. Lara rasanya. Biasanya, Mamanya berhasil menyembuhkan segala penyakit dengan mudahnya. Dan kali ini, semoga hasilnya tetap sama.
“Udah sana berangkat. Udah jam setengah enam.”
“Mama baik-baik, ya, di rumah,” ingat Lana.
“Iyaa ....”
“Lana duluan ya, Mah.”
Olena manggut-manggut, masih tak memalingkan atensi dari sang buah hati. Karena apa pun yang sedang terjadi, Olena yakin itu anaknya telah berdusta jauh-jauh hari.
🌻
Lagi-lagi Lana berakhir di bilik toilet lainnya. Membunuh sangkala untuk menyendiri, meratapi banyak hal. Rasa bersalahnya makin menguat, mengental. Sebab selain telah tertutup dari Mamanya, ia telah membohongi dan menolak untuk berterus terang. Ini tak mudah baginya. Itu terlalu pahit.
“Ada sampah masyarakat, guys! Harus diguyur dan dibasmi!!” jerit Iris, bersamaan dengan tumpahnya dua ember yang penuh dengan air keran secara bersamaan. Dari kanan, maupun kiri biliknya.
Lana membuka lebar mulutnya. Meraup oksigen sebanyak mungkin. Karena tertimpa air dengan volume yang tidak sedikit, ia sempat tidak bisa berasimilasi. Dara itu memejamkan kedua matanya rapat-rapat, berusaha sabar dan menganggapnya balasan dari Tuhan akibat telah membohongi Olena—Mamanya.
Lana gegas berdiri, menyorong pintu bilik dan menyembulkan diri. Lengannya menggenggam jaket Dienka yang masih ada padanya di depan dada. Sedikit menunduk dan membenarkan posisi kacamata, ia berlagak seakan tak terjadi apa pun sebelumnya. Kenyataan itu menciptakan geraman kesal dari para perundung. Niat utama mereka untuk membuatnya gusar sekali lagi gagal. Rupanya itu lebih sukar dari kelihatannya—untuk melantarkannya berangsang.
Lana melangkah keluar dengan menjatuhkan pandangan pada Iris yang termakan amarahnya sendiri. Kala Iris hendak melangkah maju, menampar atau mungkin melakukan hal khas merundung lainnya—satu tangan menahannya. Memutarnya dan membuat Iris meringis kesakitan. Sosok itu mengunci gerakannya hanya dengan satu lengan.
“Lo bener-bener lupa atau ngelupain perjanjian kita?!”
Iris tergemap. Melirik Varen yang membelalang padanya. “Gue bakal bikin lo nyesel, Ris!” ancam Varen tajam.
Iris mendengkus seraya melempar lengan Varen sekuat tenaga. Lantas dengan tergopoh-gopoh ia beranjak pergi diikuti anak-anak lainnya. Meninggalkan Varen dan Lana yang saling pandang.
Varen merasa sangat bersalah, sungguh. Andai saja dia bisa melakukan banyak hal untuk gadisnya—Lana. Namun untuk sementara ini, ia berjanji untuk selalu ada di sisi Lana. Ia harus melindunginya hingga sesuai dengan kehendak sang Ibunda—Vena.
🌻
“Lo nggak perlu ikutin gue.”
“Berarti lo bolehin gue ada di sisi lo?”
“Lo harus belajar pahami kata-kata manusia.”
Varen tersenyum. Ia selalu rindu menghabiskan waktu untuk berdebat dengan Lana yang tidak ada habisnya. Ia suka saat membuatnya kesal, tetapi ia benci ketika dirinya-lah alasan utama Lana menderita.
“Gue minta maaf.”
“Nggak bakal gue terima sampai gue balikan sama Irena.” Lana mendesah lirih, merasa sukar untuk menemukan Irena kapanpun itu. Irena lebih memilih untuk absen atau izin, mencari hiburan. Namun tampaknya, dara kelahiran Kanada itu sudah kembali dari Singapura.
“Lo mau terima Irena balik?”
Lana melirik, memasang durja masamnya. Terlihat gamblang tak menyukai ucapan Varen barusan. “Kenapa? Ada yang salah?” Lana mengulum bibirnya sesaat, menahan rasa dingin yang ia rasa. “Lo harus ekstra belajar buat mikir, bukan nyerocos. Nyebelin,” maki Lana tajam.
“Aneh kalau lo minta maaf sama dia. Gue bahkan nggak mau untuk maafin dia.”
Lana berdecak, memalingkan wajah. Niatnya, ia tak ingin merespons satu pun ucapan dari Varen, tetapi rupanya dia penasaran juga. “Irena punya salah sama lo?” tanyanya dingin.
“Ternyata lo nggak bisa mikir juga. Lagian ngapain gue marah kalau dia nggak salah?”
Lana memutar bola matanya, berniat segera berlalu entah ke mana. Yang utama, dia tak boleh berlama-lama dengan Varen di koridor lantai dua ini. “Apa alasan lo nggak mau maafin Irena?” tanyanya lagi.
“Dia udah bikin orang tersayang gue terluka—dan gue gak rela.”
Lana tergelak sesaat, membuat Varen yang tak beranjak menautkan kedua alisnya. Setelah membenarkan posisi kacamatanya Lana berujar lagi, “Lo aneh.”
“Aneh?”
“Orang Irena gak sengaja,” balas Lana, penuh kepercayaan diri.
“Jangan kepedean, orang yang gue maksud bukan lo,” tukas Varen dengan senyuman tengilnya. Memasang ekspresi yang halal untuk dijadikan samsak.
“Gue nggak membenarkan kalau itu gue!” seru Lana tak terima. Memecah tawa Varen yang akhir-akhir ini bahkan jarang tersenyum.
“Gue harus ke kelas. Gue pinta ini dengan sopan, untuk: jangan deketin gue sementara waktu. Kesepakatan ini bakal berguna, ‘kan?”
“Hm ... ati-ati,” balas Varen setengah hati. Masih menatap gadis yang dicintanya sampai menghilang di balik tembok yang jadi saksi bisu interaksi keduanya.
🌻
“Ada yang lihat Lana, nggak?!” seru Dienka belingsatan pada anak-anak di koridor kelas X, keadaannya lumayan riuh rendah.
Kebanyakan murid yang sibuk bergunjing berjamaah sedikit terganggu dengan seruan barusan. Mendorong salah satu murid untuk menatap Dienka sinis, “Ngapain lo nyariin Si Penikung? Mau caper gara-gara dia lagi jadi buah bibir sekolah?” cibirnya.
“Woi, gue nanya bukan ngajak berantem! Sumpah lama-lama gue tampar pipi lo sampe jadi ungu!" kesal Dienka seraya mengangkat tangan kanannya, berlagak hendak menampar anak IPS barusan.
Karena tak kunjung mendapatkan jawaban, Dienka kembali berjalan menyusuri semua kawasan sekolah. Melacak Lana yang belum dilihatnya sampai istirahat kedua saat ini. Hingga kemudian, tanpa sengaja netranya menangkap Candra yang berada tak jauh darinya.
Menyaksikan Candra yang berasak bersila di lapangan basket, Dienka makin melebarkan senyumnya. Namun, sesegera mungkin ia membuyarkan lamunannya yang melanglang-buana. Ini bukan saatnya untuk itu! Ini menyangkut Lana dan ia harus menemukannya di dua puluh menit ke depan.
“Can!” jerit Dienka dengan napas tersengal.
Mendengarnya, Candra menengok cekatan—kentara nanap, “Kenapa, Ka? Lo nggak apa-apa?”
Dienka melanjutkan lariannya, mendatangi Candra yang beringsut berdiri. “Lo lihat Lana, nggak?” tanyanya balik.
Candra menggeleng dengan mimik yang tahu-tahu saja berubah.
“Dari pagi sampai istirahat kedua ini gue gak lihat dia, loh! Lo beneran gak tahu?” seru Dienka panik.
“Dia ngantin.”
Dienka melotot seketika, “Lo nggak temenin?”
Candra menghela napas arkian menggeleng, “Nggak.”
Dienka menghela napas, sedikit gemas. “Kenapa nggak?”
“Sekali dia gak mau ditemenin, ya ... enggak.”
Dienka berdecak cepat, tak terima. “Bercanda lo, mah! Kok lo tinggal gitu?! Lo tahu sendiri, 'kan gimana kacaunya keadaan sekarang! Lo juga tahu—”
“Dia lagi marah sama gue.”
Dienka yang hendak melayangkan seruan lain—menyayangkan kebodohan Candra—segera mengurungkan niatnya. Perlahan mulutnya terkatup dengan sendirinya.
“Ooh ... marah,” cicit Dienka. Mendadak pikirannya terarah ke segala arah.


 aneylarevaa_
aneylarevaa_