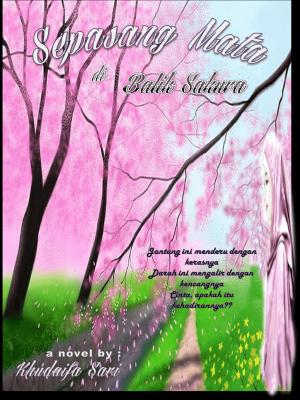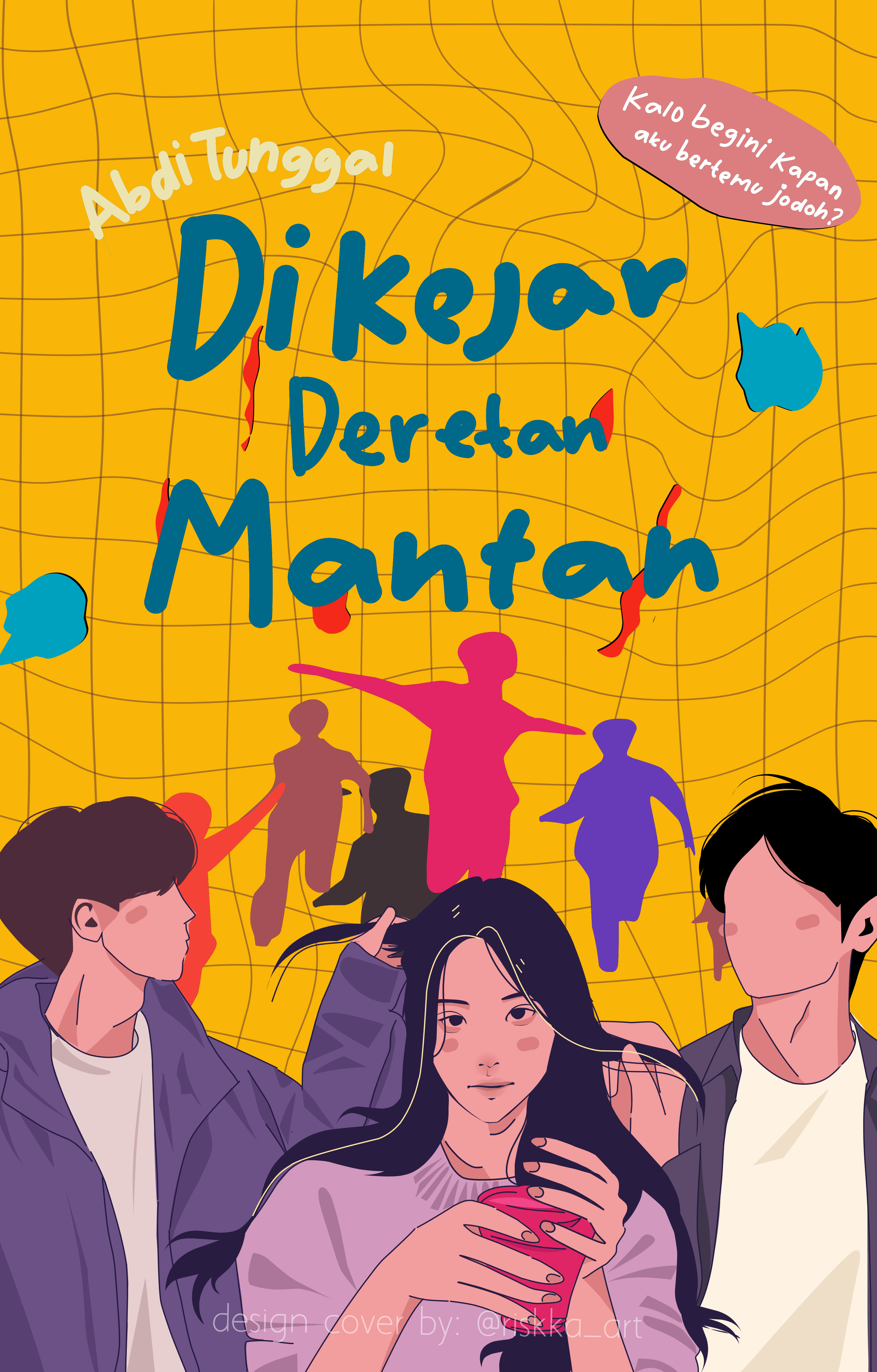“Mah ... Varen ke restoran, ya!” seru Varen pada Mama tercintanya yang tengah terduduk di ruang tengah, iseng menonton salah satu FTV akibat sungguh-sungguh jenuh.
Varen lalu berlari ke kamarnya. Mengemas seragam, buku-buku pelajaran, dan peralatan sekolah lainnya secepat mungkin sebelum hari kian menggelap.
“Ngapain? Nanti malam aja sama Mama.” Mamanya mematikan televisi dengan cepat. Menoleh pada Varen yang sukses berlalu ke kamarnya. Jaraknya hanya beberapa langkah dari ruang tengah yang memang diatur sedemikian rupa untuk Varen.
“Vareeeen?” seru wanita itu cepat. Tampak tak suka karena Varen tak menyahuti perkataannya. Prinsip keluarga mereka yaitu: tak boleh ada satu pun yang lebih fokus kepada hal lain tatkala sedang berbicara satu sama lain. Saling menghargai, intinya.
“Sekarang udah mau malem, 'kan? Varen mau tidur di sana, Mah,” sahut Varen. Namun masih sibuk dengan kegiatannya.
Mama Varen, Vena, yang telah berdiri di depan kamar anak semata wayangnya tersebut bergeming sesaat. Menatap anaknya lekat-lekat yang masih asyik sendiri. Setelah terdiam cukup lama, Vena menghela napas kecil. Mungkin sudah waktunya bagi ia untuk melepas dan membebaskan anak yang sangat dicintainya itu.
“Hmm ... terserah kamu. Yang pasti tetep hati-hati.”
Varen melepas cekamannya pada tas ransel birunya. Dengan penuh senyuman yang menampakkan sebagian giginya, ia berpusing di mana Vena menatapnya lembut. “Mama emang terbaik!” serunya cepat. “Brangkat dulu, Maa!”
Setelah tergopoh-gopoh menenteng tasnya, Varen melompat ke Triumph Rocket 3 GT miliknya. Melajukan motor besarnya tadi ke restorannya sendiri. Melesat cepat dengan kewaspadaan penuh. Namun, setelah lamanya perjalanan yang ia tempuh, Varen malah membelokkan motornya—tepat sebelum tanjakkan tinggi yang sedikit curam. Ia berhenti di sana.
Varen melepas helmnya. Memandangi rumah bercat jingga cerah yang senada dengan suasana hatinya. Ia terkekeh kecil tidak jelas, “Gue ngapain di sini coba ....” gumamnya sembari terus menyengir.
Varen menatap rumah sederhana di hadapannya. Terus membayangkan kehadiran Lana di depannya. Ia belum cukup berani untuk memanggil gadis unik itu. Lagi pula, bisa-bisa dia di cap gila karena mendatangi seorang perempuan yang baru dikenalnya selama beberapa jam.
Lelaki tersebut masih tersenyum, sesekali terkekeh entah karena apa. Dia sibuk dengan imajinasi gilanya, membuatnya tampak menyedihkan.
“Lo ngapain?”
Varen melompat kecil dengan teriakan nyaringnya. Laki-laki itu menaikkan kedua lengannya tinggi-tinggi, memandangi Lana dengan kedua mata yang melotot tajam. Lana ikut membelalang, ia menjadi merasa bersalah telah mengejutkan laki-laki tersebut.
“Sorry .... gak maksud kagetin.”
Varen memandang Lana yang menatapnya heran juga. Tanpa membalas permintaan maaf Lana, Varen segera berujar, “Lo habis dari mana?”
Masa iya Lana teleportasi?!
Tentu Varen kalang kabut. Ia tak akan nekat memarkirkan motor di depan rumah gadis itu jika melihat Lana atau siapa pun itu di sana. Perasaan tadi tidak ada siapapun.
Lana menaikkan kedua bahunya samar, tak masalah kalau Varen mengacanginya barusan. “Gue bersihin daun di got. Kotor,” terang Lana lalu melanjutkan kegiatannya kembali.
Varen melonggokkan kepala, mengintip. Pantas saja, tinggi got tersebut mencapai lutut orang dewasa. Mereka atau siapapun itu bisa bersembunyi tanpa terlihat di sana—dari tukang kredit mungkin.
Lana mengabaikan Varen dan meneruskan kegiatan bersih-bersihnya. Memungut satu-persatu daun kering dari permukaan got yang tergenang air sampai mata kaki.
Varen meringis cepat, “Ih kotor!” serunya.
Lana terkekeh maklum. Varen bukan satu-satunya yang keheranan atau bergidik ngeri dengan kebiasaan Lana setiap sore. Padahal harusnya secara logika, berhubung dia misofobia—ia tak akan sudi masuk ke selokan tersebut.
“Enggak, dong. Kalau dibiarin baru kotor,” papar Lana seraya menoleh sejenak ke Varen yang belum mengubah ekspresinya.
Lana melanjutkan aktivitasnya, sedang Varen semakin memperdalam ringisannya. Kendati paritnya tidak berbau ataupun sejorok itu, bagi Varen got tetap menjijikkan. Walau tak kotor lah—berairlah. Ia akan sekala menganggapnya menggelikan.
“Lo ... gak merasa itu jorok?”
“Lebih jorok kalau gak dibersihin, sih.”
“Tapi pas kotor, kan ... tetep jorok!”
Lana kembali mengedikkan bahu, “Gue menikmati prosesnya. Dari kotor banget, ke bersih, dan bersiih banget.”
Varen menggeleng prihatin. Sudahlah. Lagian niatnya kemari bukan untuk menyuruh Lana menghentikan acara bersih-bersihnya.
“Ehm ... gue mau nanya sesuatu.” Gadis itu menceletuk. Menegakkan tubuhnya. Merapikan helai daun-daun itu menjadi seperti barisan kartu remi.
“Iya! Apa?” tanya Varen antusias.
“Ada obat yang ketinggalan, nggak?” Lana sukses berdiri keluar dari got. Tampaklah seluruh tubuhnya yang mengenakan jas hujan tebal, sarung tangan kuning, dan sepatu bot. Entah apa maksudnya mengenakan itu. Pastinya terlihat lucu sebab kala itu tidak turun hujan.
“Enggak. Obat apa, ya?” Varen membodohi gadis itu. Ia tak akan jujur karena telah memiliki rencana yang harus terlaksana besok. “Enghh ... nanti gue cari. Gak usah dipikirin banget," sambungnya cepat-cepat.
Lagi-lagi gadis itu mengedikkan bahunya. Kembali melanjutkan aktivitasnya dan tak acuh pada Varen yang terus memandanginya.
Akhirnya, setelah cukup lama Varen menyuarakan keheranannya, “Lan ... lo ngapain pake jas hujan dan segala macem segala?” Varen penasaran. Terlebih ketika melihat Lana, gadis itu terlihat nyaman saja dengan outfit uniknya.
“Jaga-jaga kalau hujan.”
Mendengar itu Varen tertawa lepas, “Hujan? Gak mungkin, Lan! Ini kan cerah!”
Dalam sekali kedipan mata, hujan datang lalu berubah menjadi sangat deras. Seakan Lana lah yang mengendalikannya lewat tatapan saja—benar-benar selepas Varen menertawakan pernyataannya.
“Astaga tas gue! Akhh! Ini ada seragam sama buku-buku sekolah gueee! Semuanyaaaa!" jerit Varen panik.
Lana memasukkan paksa sekumpulan daun tadi pada kantong keresek yang digantungnya pada pagar taman. Mencopot sarung tangan kotornya, dan mendekati Varen kembali dengan raut wajah yang sukar digambarkan.
“Gak keberatan, 'kan, neduh di rumah gue yang sederhana?” desisnya.
“Gak! Sama sekalii gak!” serobot Varen.
Laki-laki itu berharap Lana lebih cekatan untuk menarik tangannya dan menyeretnya ke kediaman asri itu. Dan benar saja. Setelah gadis bersurai coklat tua itu menarik napas panjang, tangan lembutnya menarik lengan Varen yang mulai mendingin. Keduanya berlari dengan suasana hati yang sama-sama ... menghangat?
🌻
Syukurlah hujan berubah menjadi rintik-rintik kecil sekarang. Satu-satunya fakta yang berhasil membuat Lana tersenyum setelah kedatangan Varen—terlebih ketika mengetahui tak ada satu pun daun yang mengotori pekarangannya. Ajaib.
Lelaki itu—Varen— masih termangu di kamar tamu dengan kaos sederhana yang dipinjamnya dari kakak Lana serta secangkir teh pada tangannya. Wajar saja, Varen alergi dengan yang namanya kopi. Jadi ia lebih memilih minuman yang berhasil menghangatkan tubuhnya tersebut.
Karena menerima tamu, Lana ikut bergeming di sebelahnya. Tak ada pembicaraan apa pun. Ruangan sederhana tetapi super rapi itu sebatas dihiasi oleh suara menggigil dan gemertak gigi dari Varen.
“Lebay banget,” gumam Lana lantas tergelak lumayan keras.
“Kenapa ketawa?” Varen jelas terkejut melihat Lana yang mendadak saja tertawa. Lebih lagi sepertinya tak ada hal yang bisa ditertawakan.
“Nggak apa-apa.” Lana beralih menoleh ke jendela dengan senyuman simpul. “Tuh udah gak deres. Sana pulang,” ia gegas mengusirnya karena merasa kurang nyaman.
“Tapi masih hujan,” rengek Varen. Ia tak ingin membasahi tasnya kedua kali meskipun seluruh barang di dalamnya masih kering kering. Tentu hal tersebut lantaran ia memeluk tasnya, melindunginya dari hujan.
“Sana pulang~” usir Lana lagi dengan suara yang lebih lembut. Memaksakan satu senyuman yang membuat Varen mencebik—sok memelas.
“Hush, Lana. Kamu main usir aja sih?” timpal Mama Lana yang tahu-tahu saja ada di tengah-tengah mereka. Membuat Lana menghela napas samar. Ia selalu tak suka situasi ini.
“Ma ... udah malem. Nanti kalau Varen dicariin gimana?”
“Eh, Tante!” Varen antusias berdiri dan menunduk sopan. Mencium tangan Mama Lana yang terkekeh manis. Perempuan itu dibuatnya tersipu karena sikapnya yang santun. Sedang Lana—anak bungsunya hanya mencibir.
“Ish, udah, duduk aja! Nih, dimakan ya!”
Olena, Mama Lana meletakkan bubur ayam hangat dari tangannya ke atas meja yang ada di depan mereka. Bau sedap menyeruak, membuat perut Varen bergejolak. Tak bisa dipungkiri, Lana pun tergiur akannya. Melongo dan menpertanyakan, sejak kapan Mamanya memasak ini?
“Butuh apa lagi, Ren? Ehm ... selama masih mungkin bisa Tante siapin,” ujar Olena lembut begitu sadar sekaya apa Varen ini.
“Astaga Tante ... nggak perlu, Tan. Ngerepotin!”
“Enggak dong, Ren. Ehmm ... sering-sering main sini, ya?" Lana dibuatnya menyalang tidak setuju, tetapi Olena abai padanya. “Ini dimakan! Harus dihabisin kalau gak, gak boleh pulang,” titah Olena masih sama lembutnya.
“Siaap, Tante!”
Varen gegas mengganyang bubur ayam made in Mama Lana yang masih suam itu dengan semangat empat lima. Mengelih begitu lahapnya lelaki itu, Olena berlalu meninggalkan kamar tamu. Lana—masih di tempatnya—memutar bola netra, Mamanya selalu saja begitu saat ada anak laki-laki main di rumahnya. Energik dan kadang berlebihan. Untunglah Varen bisa menerimanya—atau malah memang mengharapkannya.
“Pacar kamu, ya?” bisik Olena saat Varen sukses menghilang dengan motor gagahnya. Netra Lana membola sempurna, sudut bibir atasnya naik—tidak terima.
“Apa sih Mama? Ngaco, ih. Bukan tipe Lana. Lana kagum aja.” Lana memang sukar jatuh cinta. Dia belum pernah benar-benar menyukai seseorang seumur hidupnya.
Mendengar penuturan anaknya sendiri, Olena berseru tidak terima. Keheranan akan kebodohan anaknya itu, “Orang kayak gitu bukan tipe kamu? Orang sesempurna Varen bukan tipe kamu?!” Olena menggebu-gebu, “Trus tipe kamu gimana? Gembel?”
Mata dara itu menyipit tidak terima, tetapi memutuskan tak menimpali kemarahan Ibundanya.
“Oohh, Candra nih jangan-jangan?” goda Olena.
“Ck, apaan sih, Ma?” Lana terlihat tersipu—meski amat samar.
Olena menghembuskan napasnya, mulai lelah untuk mendorong anak gadisnya agar lekas memiliki kekasih hati. “Mama tuh heran sama kamu, loh. Mama kan tipe orang tua yang bolehin anaknya pacaran ... tapi kok kamu malah gak pacaran? Apalagi di era gila kayak gini. Anak-anak zaman sekarang kan sukanya pamer pacar mereka!” seru Olena menggebu-gebu.
“Ya Tuhan, Maaah. Baru aja SMA, belum lulus juga. Masak Mama ngebet Lana pacaran? Belum mau, Mah. Nanti ganggu belajar.” Lana berlalu dan masuk ke kamarnya dengan langkah terseok-seok.
“Kok ganggu?! Pacaran malah bikin semangat belajar tauuu! Ya ampun Lanaa ... Mama gak habis pikir sama prinsip kamu.”
“Kata siapa? Mama, ih jangan sok tau. Udaah! Lana mau belajar. Gak usah bahas ini! Lana masih punya banyak waktu buat cari yang terbaik!” Lana lantas menutup pintu kamarnya. Membalikkan badan dan melempar tubuhnya ke kursi putar hitamnya. Merebahkan kepala dan termenung cukup lama. Pikirannya melanglang-buana.
Dia pikir-pikir sejurus ... pelik juga Varen mendatanginya tanpa ada maksud tertentu. Pada mulanya, Lana berharap Varen membawakan obatnya yang hilang itu, tetapi yang ada lelaki itu dengan tangan kosong datang begitu saja. Tanpa tujuan tertentu dan malah merepotkannya.
Lebih-lebih ia harus mengepel lantai sebab kamar tamunya basah. Pastinya, akibat tubuh Varen yang basah kuyup itu. Menambah kotoran piring dan gelas; ditambah juga Lana pasti akan dimarahi kakaknya setelah meminjamkan bajunya ke sembarang orang.
Huhhh!
Lana menghela napas kasar. Dongkol akan kedatangan Varen barusan. Namun, gadis itu tetap berusaha berpikir positif.
Bisa aja Varen pengen ke restorannya, tapi cari angin sejenak, 'kan? Bisa dong.
Lana menggelengkan tendas. Memutus lamunan arkian berupaya memusatkan atensi ke buku Sejarahnya, bukan anak baru yang bukan siapa-siapanya itu. Semoga saja ia bisa mendapatkan obatnya kembali.


 aneylarevaa_
aneylarevaa_