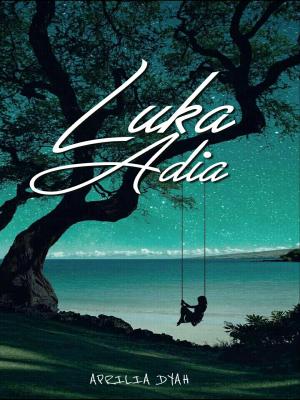Untuk beberapa saat Adelia terbuai dengan perasaan nyaman itu, tapi saat pipinya mulai memanas dan dia sadar bahwa itu memalukan, Adelia menjauhkan kepalanya. Dia mengerucutkan bibir, kemudian mengalihkan wajah. “A-apa yang kau lakukan? Aku bukan anak kecil lagi!”
Ilay menarik tangannya, dia mengulum senyum. “Ya, ya, kau sudah dewasa sekarang. Jadi, bagaimana kalau kita berkencan saja?”
Es tebu yang berada di genggaman Adelia terjatuh begitu saja. Gadis itu terbelalak dengan kedua mata yang membulat. Sementara Ilay menatapnya dengan senyum tipis dan tatapan yang lembut. Pada akhirnya, Adelia menghela napas, dia mengambil sisa rujak buahnya dan beranjak. “Berhentilah bicara omong kosong, Ilay. Aku mau pulang. Kau juga kembalilah, kau sedang kerja ‘kan.”
Adelia berjalan dengan langkah cepat, napasnya terlihat naik turun, wajah paniknya memutari kepala Ilay yang kecil. Lelaki itu hanya bisa melihat punggung Adelia yang menjauh. Matanya kini berubah sayu, bahkan hingga Adelia sudah sangat jauh, Ilay masih menatapnya tanpa berkedip. Dia menghela napas, “padahal aku serius.”
Langkah kaki Adelia menyepat seiring debar jantungnya. Sedari tadi, ia hanya memegang bungkusan rujak, menentengnya ke mana langkahnya pergi. Dia hendak pulang, melewati jalan yang sama yang ia lewati saat pergi. Ilay keterlaluan, laki-laki itu selalu membuatnya jengkel. Pada awalnya, Adelia duduk di taman itu bukan semata-mata hanya untuk meminum es tebu atau pun memakan rujak buah, melainkan untuk menenangkan pikiran sejenak. Sebagai seorang anak yang kemungkinan besar di buang oleh orang tua sendiri, Adelia kerap merasa marah. Ayah dan Ibu yang pembohong besar, berkata bahwa mereka akan kembali merupakan dusta yang menyakitkan. Namun, Adelia tetap mendamba mereka datang, entah suatu hari nanti, walau hanya untuk mendekap tubuh lemah gadis itu.
Panti itu tempat yang paling menyakitkan, bukan karena anak-anak atau pengurus panti yang buruk, melainkan sebagai bukti bahwa Adelia pernah di buang oleh orang tuanya. Tanpa sadar Adelia menangis, dia masih berjalan cukup cepat, entah ke mana arah dan tujuannya. Saat menengadah ke langit, awan bak kapas itu terlihat berjalan pelan, bergerak ke depan mau pun ke arah sebaliknya. Adelia menghela napas kasar, melihat langit membuatnya sadar bahwa dia harus bersyukur.
Zeelay Mirza, anak laki-laki yang ceria dan mempunyai sebuah senyum yang menawan, datang pada Adelia sambil mengulurkan tangan. Semua anak-anak bahkan Ibu pengurus panti memanggilnya Ilay. Dia sudah berada di panti itu sejak bayi, ibunya meninggal saat melahirkannya, dan sang ayah pun meninggal beberapa hari setelah menitipkannya di panti. Kala itu, Adelia kecil sedang menangis tersedu seorang diri di teras panti. Adelia menatap ke depan dengan air mata yang berlinangan. Gadis kecil itu terlihat sok kuat, padahal di dalam hatinya dia rapuh, itulah yang mungkin saja Ilay pikirkan.
Sejak saat itu, Ilay selalu mendekati Adelia, mereka semakin akrab, bahkan di saat Adelia sedih, Ilay selalu ada untuk menghibur gadis itu.
“Jangan menangis, orang tuamu pasti akan ke sini lagi untuk menjemputmu.”
“Jangan berbohong padaku! Mereka membuangku! Mereka tak akan menemuiku lagi!”
Bukannya marah karena di bentak, Ilay malah tersenyum. “Kau tidak di buang, mereka mungkin ingin kau hidup lebih baik tanpa mereka. Mereka sangat menyayangimu, maka dari itu kau di titipkan di sini. Jika nanti mereka tak kunjung datang, jangan terlalu kecewa. Kau anak yang baik dan cantik, ada banyak orang yang mendambakanmu. Saat salah seorang itu datang dan mendapatkanmu, kau harus berjanji untuk tidak menangis lagi. Kau harus bahagia, Hanna.” Ilay tersenyum sembari mengusap kepala Adelia dengan pelan.
Adelia berhenti, dia sudah terlalu jauh berjalan. Keringat mengucur memenuhi dahi dan lehernya, napasnya tersengal. Dia terkejut lantaran ponselnya bergetar, sebuah panggilan dari ibunya itu membuat pikirannya buyar. Beberapa saat dia menatap ponsel itu, matanya mulai berkaca-kaca lagi. Namun, kali ini dia tak membiarkan tangisnya pecah. Adelia menggeser tombol hijau pada layar ponselnya. “Halo, ah ibu, iya aku sedang dalam perjalanan pulang sekarang.”
***
Pukul sepuluh lewat sepuluh, Kanaya memandangi kalender yang terpajang di pintu kamarnya. Sudah masuk pertengahan bulan, dan dua minggu lagi dia harus kembali membayar bunga pinjaman pada rentenir. Wajahnya menekuk hingga membuatnya terlihat menakutkan. Kepalanya mulai pusing, bahkan saat dia hanya melihat kalender. Bunga pinjaman, cicilan yang menunggak, biaya makan, biaya sewa rumah, semuanya membuat kepala Kanaya ingin meledak. Ditambah, gajinya akan di potong kas bon yang uangnya telah raib di makan penipu. “Semoga kalian sengsara seumur hidup,” umpat Kanaya dengan nada kesal. Lagi-lagi Kanaya merasa frustrasi.
Beberapa menit yang lalu, dia baru saja menelepon ibunya. Dia rindu. Namun, dia belum bisa pulang karena tidak mempunyai uang lebih. Setidaknya Kanaya bisa bernapas lega karena rentenir itu menepati janjinya untuk tak mendatangi sang Ibu saat menagih utang. Sebagai gantinya, mereka selalu mengganggu Kanaya dengan mengajukan pertanyaan yang menakutkan, yaitu “kapan kau akan membayar utang?”
Kanaya menghela napas. Alih-alih memikirkan semuanya, perutnya tiba-tiba bergetar karena lapar. Satu-satunya makanan yang ada hanyalah mi instan, makanan tiga menit jadi yang selalu Kanaya stok di indekos.
Dalam keheningan, Kanaya menyantap makan malamnya. Mi goreng instan tanpa telur, karena Kanaya lupa membelinya sewaktu pulang kerja. Tidak apa-apa, Kanaya masih bisa menikmati makanan itu karena perutnya lapar.
Setelah makan pun pikiran Kanaya belum juga membaik, dia masih gelisah, memikirkan gaji yang kemungkinan tak ada sisa nantinya. Jika saja dia tak tergiur dengan pinjaman online, mungkin tagihannya tidak membludak seperti ini. Kanaya merasa mampu saat meminjamnya, tanpa berpikir panjang, pada akhirnya dia terjebak. Tubuh dengan pikiran yang berat itu dia lemparkan begitu saja di atas ranjang. Merentangkan tangan sambil menatap langit-langit kamar. Kehidupan sangat berat, untuknya yang belum genap berusia dua puluh tiga tahun.
Kanaya meraba-raba ponsel di samping tubuhnya. Dia frustrasi, dan entah kenapa dia ingin sekali mendengar suara Vincent saat ini. Tanpa berpikir lama, dia membuang semua ego dan rasa malunya. Kanaya menekan nomor Vincent, kemudian meneleponnya tanpa ragu.
“Halo.”
Kanaya mengulum senyum, “halo, Vin, kau belum tidur?”
Terdengar Vincent menghela napas dari seberang sana. “Aku menjawab teleponmu, itu berarti aku belum tidur.”
Gadis yang sudah duduk di ujung ranjang sambil memilin daster tidurnya itu pun tersenyum malu, padahal dia tidak sedang di goda. “Oke, oke, kau sedang apa? Aku tidak mengganggu ‘kan?”
“Jika kubilang kau menggangguku, apa kau akan menutup teleponnya?”
“Ya ampun, kenapa kau selalu seperti itu padaku? Aku ini sedang frustrasi, makanya aku meneleponmu.”
“Kalau kau sedang frustrasi, harusnya kau ke psikolog, kenapa kau malah meneleponku malam-malam begini.”
“Hahaha.” Kanaya tertawa pelan, dia takut seluruh penghuni indekos akan terganggu kalau dia mengeraskan tawanya. “Aku tidak butuh psikolog. Kau tahu, suaramu sudah lebih dari cukup mengobati rasa frustrasiku.”
Vincent tak menjawab, kemudian panggilan telepon itu pun terputus. Kanaya tertawa geli, dia kembali berbaring, kali ini dengan senyum yang mengembang. “Mungkin dia malu,” ujar gadis itu memeluk bantal gulingnya erat. “Ah, aku jadi tak sabar untuk besok. Aku akan mengirimkannya pesan, agar dia tidak terlambat.”


 megazulma
megazulma