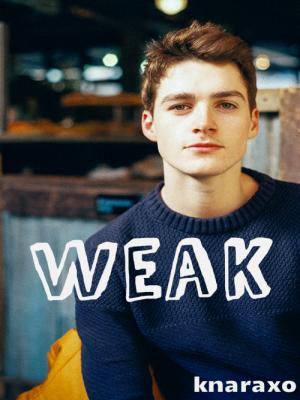http://www.sebelasdesember.blog.com
[Latest post]
“Catatan Sebelas Desember”
Posted by Bunga Kupu-Kupu on December 11th. 00:38 a.m
Pernah memikirkan tentang kematian?
Aku sering.
Belakangan ini aku sering memikirkannya.
Bunga kupu-kupu, hari ini ulangtahunmu, kenapa kamu justru memikirkannya? Tentang kematian? Membayangkan bahwa ... kamu tidak pernah ada, di dunia. Tidak pernah terlahir. Atau jika tidak mungkin memutar ulang waktu, kenapa tidak menghapusnya saja?
Malam ini, tepat di hari ulang tahunku yang ketujuh belas, yang terasa amat menyedihkan, aku memikirkannya, lagi.
Kenapa hidupku yang tidak berguna ini tidak dihapus saja?
Kenapa jika aku di sini hanya untuk menjadi bunga kupu-kupu yang terus diabaikan, kenapa hidupku tidak dihentikan saja?
Dunia sudah memiliki dia, mawar, dan itu cukup. Aku tidak diperlukan.
Dan jika harus memilih mawar atau bunga kupu-kupu yang harus disingkirkan dari taman ini ... kupilih bunga kupu-kupu saja. Kupilih diriku saja.
Aku ingin pergi.
───
1 views. 0 likes. 0 comments.
***
Rabu, 16 Desember, 13.02 WITA (Sehari Sebelumnya)
“Nawala,” sapaku begitu berada di luar ruangan.
Aku memilih satu sudut di pojok lorong yang buntu, memandangi taman belakang rumah sakit dari pembatas balkon setinggi perut orang dewasa, ponsel di telinga.
“Jambu,” sapanya balik dari ujung sambungan. Sapaan itu, setelah hari-hari yang membuat semua orang seperti mayat hidup, hari ini secara ajaib terdengar hangat, bersahabat. Aku nyaris tersenyum mendengarnya.
“Kamu apa kabar?” tanyanya lagi, mendahuluiku membuka topik. Seperti yang hampir selalu dia lakukan.
“Baik.”
“Bohong.”
Aku berdecak. “Emangnya apa yang kamu harapkan? Tapi ... Laura sudah bangun. Things finally get better... get back to its place. Ah, ya. Kalian belum ketemu lagi. Nggak mau ketemu Rara?”
“I want to see you,” katanya. Aku mengerutkan kening.
Dan seperti mengerti kebingunganku, Nawala kembali bicara. “Besok... terakhir ujian semester. Aku akan ke sana.”
“Nggak usah buru-buru. Fokus aja ujiannya.”
Aku tahu tidak mudah untuk datang ke sini. Kampus Nawala dan rumah sakit ini berada di kota yang berbeda. Ia harus berkendara nyaris dua jam, dan untuk ukuran mahasiswa yang sedang menghadapi padatnya ujian, pasti sulit baginya membagi waktu.
“Terakhir kali aku enggak terburu-buru, hasilnya nggak menggembirakan,” kekehnya di ujung sana.
Aku tidak mengerti.
“Kamu sudah makan?”
Pertanyaan sederhana itu membuatku menggigit bibir. Membuatku merasa sedikit ... lebih hangat. Di saat seperti ini, saat semuanya tengah menanggung sakit, siapa yang peduli padaku yang segar bugar ini apakah aku sudah makan atau belum.
Sebagai jawaban, aku memilih untuk jujur. “Belum.”
“Mau makan apa? Nanti aku pesankan.”
“Eh, nggak usah! Papa udah beli... tinggal makan.”
“Kalau gitu cepat makan. Gimana kepala kamu? Masih pusing?”
Sedikit. Tapi dia tidak perlu tahu. “Enggak.”
“Bagus deh. Jangan lupa makan. Jangan sampai pingsan lagi kayak waktu itu.”
Aku mengangguk.
“Besok. Aku ke sana besok. Tunggu aku.”
Aku kembali mengangguk.
Di akhir panggilan, tanpa kusadari senyumku mengembang. Ada hangat yang menetap di ujung jemari ketika aku memasukkan kembali ponsel ke saku. Mungkin ..., aku masih begitu menyukai kehadirannya di sisiku.
Perasaan yang seharusnya tidak kumiliki. Perasaan yang menamparku begitu kembali ke ruangan dan bertemu Laura, saudari kembarku. Kepada siapa, seluruh cinta dicurahkan.
Sekarang, aku bahkan tidak keberatan. Dia pantas mendapatkannya.
***
Keesokan paginya, aku menemukan bangun adalah hal yang sulit, amat sulit.
Kesadaranku ditarik kembali ke tubuh pada dini hari menjelang subuh. Tiba-tiba saja, aku terbangun oleh rasa sakit yang seakan menjambakku kuat-kuat. Rasanya duniaku berputar seketika, membungkamku dari coba berteriak meminta pertolongan.
Padahal aku punya banyak rencana untuk hari ini. Aku berjanji untuk memandikan Laura, meski hanya mengelap tubuhnya dengan air hangat. Aku berencana meminta Papa untuk membelikan Donat DO’Nut, untuk dimakan bersama, meski hanya aku yang akan makan. Aku berniat membantu Mama keramas, dia mengeluh rambutnya mulai lepek dan berbau, setelah semua kejadian ini, dia baru saja mulai peduli dengan dirinya sendiri.
Lalu, aku juga berjanji akan bertemu Ghea. Dan Nawala. Nawala menyuruhku menunggunya. Dia akan datang.
Aku meremas selimut tipis yang menjadi alas tidurku malam ini sambil merasakan jantungku berdegup cepat. Kepalaku terasa dicengkeram kuat, perutku bergejolak, dan rasanya seakan beban berat menindih dadaku, membuatku kesulitan bernapas. Tubuhku ... aku tidak dapat merasakannya. Kelebat memori mulai berputar di kepalaku, bersatu dengan besi ranjang tempat tidur Laura, bersama ketakutan yang teramat sangat.
Aku masih punya janji-janji yang belum kutepati. Sebentar lagi. Sebentar lagi ... aku ingin diberi waktu sebentar lagi...
“Na? Nana?”
Lalu, aku terbangun untuk kali kedua ketika Mama mengguncang pundakku. Aku masih meringkuk di tempat yang sama. Bedanya, ruangan itu terang benderang sekarang, oleh cahaya matahari yang menembus jendela dan lampu ruangan itu sendiri. Aku membawa tubuhku untuk bangkit duduk. Berhasil.
“Jam ... berapa sekarang?”
“Udah hampir jam delapan. Kamu tidurnya nyenyak banget,” kata Mama, tersenyum.
Aku balik tersenyum. Lantas mendongak sedikit demi melihat Laura yang duduk di atas ranjang, di atasku. Lekas-lekas, aku melipat kembali selimutku dan berdiri.
“Rara sudah mandi?”
Mama menggeleng. “Belum. Katanya mau nungguin kamu.”
Kemudian, aku menemukan diriku dan Laura bertukar pandang, lalu bertukar senyum berkomplot seperti yang biasa kami lakukan saat kecil. Aku pun meraih baskom aluminium itu dari tangan Mama. “Ya udah, biar aku yang mandiin. Mama istirahat.”
“Oke.” Mama turut memberikan handuk kecilnya. “Air panasnya sudah dicampur.”
Aku mengangguk.
Sebelum Mama berlalu untuk mengerjakan hal lain, aku memanggilnya. “Ma?”
Mama menoleh. “Ya?”
Aku ingin check up ulang. Perawat yang membantuku ketika pertama tiba di rumah sakit ini tidak pernah benar-benar memeriksaku. Kepalaku sakit dan aku rasanya mau mati. Ketakutan menguasaiku dan melihat matahari pagi membuatku ingin menangis. Tetapi begitu melihat kantung mata Mama, dengan keriput yang rasanya bertambah dalam semalam karena kecemasannya, semua kalimat tertinggal di ujung lidah, tidak sanggup kuucapkan.
Aku tidak ingin menjadi dramatis. Jadi aku menggeleng.
“Nggak jadi.”
Yang harus kulakukan hanyalah meminum obat yang kubeli di warung beberapa waktu lalu, kemudian semuanya selesai. Ketakutan ini sama sekali tidak berasalan.
Pagi itu kuhabiskan dengan mengelap tubuh Laura dan mengobrol banyak dengannya. Hari ini, Laura terlihat jauh lebih baik dari kemarin. Dia mampu menghabiskan makanannya lebih cepat. Dia mampu bicara lebih banyak, lebih jelas. Warna, meski sedikit, mulai kembali ke wajahnya. Dia juga ... tersenyum lebih banyak.
Rasanya, segalanya mulai membaik sekarang. Luka-luka itu ... yang terlihat maupun tidak, perlahan mulai menutup, mulai tersembuhkan.
***
Dingin. Kesemutan di ujung-ujung jemari dan kaki yang sempat kurasakan semenjak tadi tiba-tiba saja semakin parah. Aku mengibas-ngibaskan tangan dan mulai melangkah lebih cepat. Tidak berhasil. Rasanya aneh. Rasanya seperti darahku berhenti mengalir hingga semua yang kurasakan dingin. Tubuhku mulai terasa kaku. Dan tidak hanya itu. Sakit kepala itu kembali. Berkali lipat lebih parahnya, menghantamku. Seiring rasa mual yang sulit ditahan.
Aku menggapai-gapai, menemukan pegangan tangga dan berpegangan erat padanya. Aku tidak lagi bisa merasakan tanganku, kakiku, mereka kaku. Apa yang semula kupikir hanya kesemutan mulai merongrongku seperti kawanan lebah, mengisi paru-paruku dan membuatku sesak. Aku kesulitan menarik napas.
Sedikit lagi, pikirku.
Aku harus berjalan sedikit lagi, menemukan bantuan untuk diriku sendiri. Dan meski sulit, aku pun melakukannya, meski selalu oleng, meski berkali terjatuh.
“Jambu!”
Aku mendengar Nawala, melihat siluetnya berjalan ke arahku, meski buram. Senyumku mengembang sedikit, ia menemukanku, ia akan menolongku. Aku juga ingin berjalan lebih cepat ke arahnya, Tetapi tubuhku tidak mengizinkan, tetapi aku tidak bisa melakukan apa-apa.
Ada sesuatu yang terasa basah, yang jatuh di dekat kakiku. Aku menunduk dan melihat ... darah. Ketika aku menyeka hidung, aku tahu darah itu berasal dariku. Lalu, dunia mulai berputar di sekitarku. Aku terayun-ayun. Pandanganku semakin buram dan buram.
“Jambu?!” Ia memanggil lagi, kali ini terdengar khawatir. “Nana?! Na?!”
Namun aku tidak bisa merespons panggilannya. Sesaat, aku merasakan tubuhku jatuh melorot dan kedua lengannya menyokongku. Tetapi hanya itu. Aku tidak bisa merasakan tanganku, kakiku, dan seluruh tubuhku seakan mati rasa dengan sesak yang menghimpit dada, dengan sakit yang seakan ingin merobek kepala. Ketika aku coba membuka mata untuk melihatnya, aku bahkan hampir tidak dapat melihat apa-apa lagi.
Tiba-tiba saja ... aku ketakutan. Amat sangat ketakutan.
Tiba-tiba saja ... semuanya gelap.
***
Pernah memikirkan tentang kematian?
Aku sering.
Aku sering memikirkan bagaimana halaman terakhirku. Bagaimana buku kehidupanku akan berakhir. Apakah indah? Apakah amat menyakitkan? Apakah malaikat maut akan menemuiku ketika sedang tergolek di atas aspal, bersimbah darah? Atau saat aku tidur dengan nyaman di bawah selimut? Atau saat aku tua, tidak sanggup berbuat apa-apa dan sudah menunggu waktuku untuk masa yang lama.
Ataukah ... sekarang? Ketika umurku masih tujuh belas.
Kupikir ... aku sekarang sedang berjalan, sejengkal demi sejengkal, mendekat ke arahnya. Melangkah di jalan yang sama seperti Ulfi dan Kama. Menuju kematian.
Kelebat demi kelebat terus berputar. Kadang aku mendengar suara. Kadang aku melihat secercah cahaya. Kadang ... semuanya kosong.
“Na? Nana?! Bangun, Na!”
Aku mendengar suara Laura. Nada cemas begitu kental. Bercampur isak tangis. Ia sedang menangis ... karenaku? Untukku?
“Nana... please.”
Namun aku tidak mampu meresponsnya.
Aku dapat merasakan genggam tangan Nawala pada tanganku. Sekilas, aku dapat melihat bayangan wajahnya di benakku. Senyumnya yang menenangkan, yang hangat seperti matahari. Dan semua itu cukup untuk membuatku percaya sekarang.
Surat itu untukku.
Aku juga mendengar Mama, Papa, merasakan mereka. Aku berharap mereka baik-baik saja. Aku berharap Laura mampu membuat mereka baik-baik saja, membuat mereka kembali tertawa. Segera. Mereka semua memanggilku. Mereka semua ingin aku kembali.
Namun aku ... sudah melangkah terlalu jauh. Namun ini sudah waktuku.
Dan aku bahagia. Aku bahagia bahwa aku sempat merasakan perasaan ini, sempat mengetahui kenyataan ini. Bahwa bunga kupu-kupu yang bersembunyi di sudut taman ... juga dicintai. Bahwa aku juga dicintai. Dengan sepenuh hati.
Aku bisa pergi dengan damai.
Namaku Launa. 11 Desember kemarin, umurku genap 17 tahun. Harapanku ... aku ingin ... semua orang bahagia. Dengan atau tanpaku.


 rainaya
rainaya