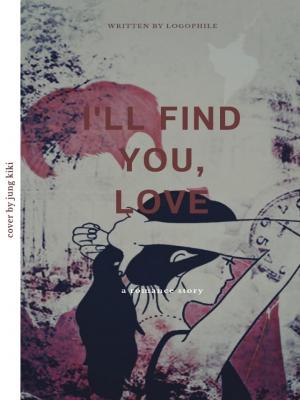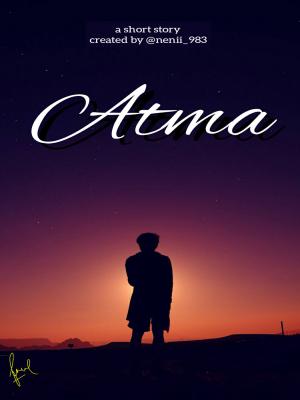Selasa, 15 Desember. 18.21 WITA
Sejujurnya, Laura tidak pernah terlihat jelek, atau menyedihkan. Matanya selalu bersinar indah, cerdas, penuh dengan tawa. Rambut lembut dan terawat, selalu ditata. Bibirnya secara alami berwarna merah muda, yang seringnya disapukan lipgloss warna senada yang membuatnya lebih segar. Lebih ... menawan.
Tidak pernah kulihat Laura sekacau ini.
“Aku bawain kamu donat.Agak basah, soalnya tadi kehujanan,” ujarku, menyapukan jemari pada kotak yang menjadi lemah dan nyaris hancur karena terkena air. “Tapi donatnya masih bagus, kok. Liat, ada enam rasa.”
Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kuucapkan. Yang kulakukan ... hanyalah meracau, hanyalah mengeluarkan seluruh isi kepalaku yang berhamburan.
“Itu .. donat kesukaan kamu,” bisikku. Sekeras mungkin berusaha menahan suaraku agar tidak bergetar, atau mataku yang memanas untuk tidak menumpahkan isinya sekarang. “Kamu masih suka, kan? Beberapa hari lalu kamu pengin makan itu dan ... kamu nggak bisa makan. Sekarang kamu bangun, ya? Sebelum donatnya dingin dan jadi keras... Ah, ada rasa stroberi. Kamu paling suka itu, kan?”
Tidak ada reaksi apapun. Tentu saja. Memangnya apa yang bisa kuharapkan?
Kutaruh donat itu di atas meja nakas di samping tempat tidur. Lalu kedua tanganku menggenggam tangannya. Jemari kami satu ukuran, sehingga ketika aku menautkannya, rasanya begitu pas. Rasanya ... seperti aku tidak akan melepaskan. Tidak ingin.
“Papa dan Mama nungguin kamu setiap hari,” ujarku lagi. Kali ini aku menyadari suaraku mulai parau. “Papa yang nggak pernah absen kerja itu ... aku dengar dia marah-marah di telepon karena bosnya nanyain kapan dia masuk kerja. Dia bilang dia ingin berhenti. Dia bilang dia nggak peduli sama pekerjaannya. Dia hanya peduli sama kamu...”
Aku sudah berusaha menahannya. Tetapi sulit. Satu bulir air mata jatuh begitu saja di pipiku.
“Aku nggak tahu kapan terakhir kali Mama tidur. Atau ... apakah dia pernah tidur. Mama bahkan lupa untuk marah-marah, Ra. Dia cuma nangis dan di sini setiap hari nungguin kamu...” Airmata lain mengaliri pipiku dengan cepat. Menderas. “Bangun, Ra... jangan takut. Mama nggak akan marah. Mama nggak akan marah meski kamu terlambat pulang... Mama nggak marah, jadi tolong bangun, Rara...”
“Kasian mama,” isakku. “Jangan takut. Kalaupun dia marah, aku yang lindungin. Kamu boleh salahin aku aja, oke? Biar dia marahin aku aja nggak papa!”
Kuremas tangannya. Sekarang, air mataku bahkan berjatuhan ke tangan kami yang bertautan. Aku tidak bisa lagi menahan diri.
“Semua orang sayang kamu, Laura. Ghea di sini juga nungguin kamu. Plis, plis jangan pergi kayak Ulfi dan Kama. Cukup Ulfi dan Kama, Ra. Kamu jangan ... siapa... siapa yang akan nemenin aku dan Ghea nanti? Rei...”
Aku gelagapan. Lantas dengan satu tangan yang bebas berusaha mencari-carinya di tasku. Benda itu. Surat itu. Aku menemukannya sesaat kemudian, lusuh, penuh perekat, setengah basah terkena hujan. Sebagian tulisannya telah luntur. Tetapi ... aku masih ingat isinya. Aku hafal isinya di luar kepala.
“Ini dari Rei...,” kataku dalam isakan yang coba kureda. Aku menghapus airmataku dengan kasar, dengan lengan yang sama basahnya. Hanya coba menghambat agar tidak lebih banyak airmata mengalir. Agar suaraku tidak terus-terusan terhambat isakan. Dan itu cukup berhasil.
Aku menarik napas panjang demi menenangkan diri. Sementara di tanganku yang gemetar, surat itu telah kugelar. Surat yang kurobek di malam ulang tahun kami. Surat yang kemudian kurekatkan kembali dengan hati-hati di malam yang sama. Surat itu ... lebih tepat jika aku menyebutnya sebuah puisi.
Dan tebak siapa yang mengajari Nawala membuat puisi?
“Jambu, sibuk?” tanyanya waktu itu. Hanya dua minggu sebelum ulang tahun kami.
“Kenapa? Mau ganggu?” jawabku, dengan nada ketus yang dibercandakan. Nawala tahu itu, bahwa aku hanya senang memasang wajah dan nada jutek itu. Katanya, kalau tidak ketus, bukan Nana namanya.
“Iya,” sahutnya enteng. “Kamu suka bikin puisi kan?”
Aku yang amat keheranan mendengar pertanyaannya itu, bertanya balik alasannya. Hanya untuk mendapatkan jawaban yang lebih membuatku tercengang lagi.
“Ajarin bikin puisi.”
“Buat apa? Kamu nggak mendadak panas, kan?”
Cowok itu tertawa. Aku bahkan masih dapat mengingat tawa renyahnya. Tawa yang dulu kusukai setengah mati.
“Ada, deh. Nanti kamu juga tahu.”
Dia benar. Aku sekarang sudah tahu. Puisi ini untuk Laura. Dan sebanyak apapun aku membencinya, Laura berhak tahu. Laura berhak mendengarnya.
Karena itu, dengan suara setenang yang kubisa, aku mulai membacakannya.
...
Kamu tahu apa yang lebih indah dari setangkai mawar?
Seikat bunga kupu-kupu, terselimut embun, mengintip malu pada pagi.
Kamu tahu apa yang lebih indah dari pagi?
Embun pagi yang bias, tersiram cahaya hangat matahari.
Kamu tahu apa yang lebih indah dari keduanya?
Dari seluruh dunia dan isinya?
Dari galaksi dan seluruh jagad raya?
Kamu. Senyummu. Caramu bercerita. Caramu memandang dunia.
.
Kamu tahu apa yag lebih berantakan dari puisi ini?
Aku. Saat memikirkan kamu.
Yang lebih parah dari itu?
Jantungku. Semua sistemku ketika memandangimu.
Ini semua salahmu. Semua tentangmu.
Kamu. Sinar matamu. Caramu bicara. Segala yang ada dalam dirimu.
.
Selamat ulang tahun. Tetaplah jadi matahari. Dan aku akan jadi bunga kupu-kupu, yang memandangimu dari kejauhan.
...
Usai menyelesaikan puisi itu, aku merasakan perasaan yang tidak kurasakan sebelumnya. Yang tertutup cemburu pada awalnya. Yaitu keindahan. Aku suka bagaimana Nawala tidak menggambarkan kecantikan fisik Laura yang kerap membuat cowok manapun mengejarnya. Aku suka Nawala yang mencoba mengenal Laura dengan semua apa yang ia punya. Aku suka ... caranya menatap dengan cara berbeda.
Setidaknya aku tahu, ada seseorang yang mengagumi saudariku setulus itu. Menyukainya tidak untuk luarnya saja.
“Kamu denger?” tanyaku, menghapus air mata. “Kamu ... seberharga itu, Ra. Sesayang itu Rei sama kamu.”
Air mata kembali jatuh di wajahku. Namun kali ini aku tidak menghapusnya. Itu bukan lagi air mata yang sama yang kutumpahkan di malam sebelum Sebelas Desember. Itu adalah air mata kelegaan, kerelaan, dan permohonan.
Aku mengeratkan tautanku di tangan Laura, membawa hangat tangan itu ke pipi.
“Jadi kumohon bangunlah... Demi Mama, Papa, Ghea, demi Rei ... dan demi aku, Ra. Demi aku yang sudah bersama kamu sejak hari pertama kita di rahim Mama. Demi aku yang selalu hidup berdua dan tidak akan sanggup melanjutkannya sendirian saja. Kumohon...”
Kemudian, bunyi pada monitor perekam detak jantung mulai berubah. Aku menoleh, memastikan dengan mata kepalaku sendiri bahwa yang kudengar tidaklah salah. Dan memang tidak salah. Degup jantung Laura ... sedikit demi sedikit beranjak lebih cepat.
Aku tidak tahu artinya. Dan aku panik setengah mati. Tetapi, telapak tangan hangat di genggamanku seakan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahwa Laura akan baik-baik saja.
Lalu, aku merasakan jemarinya bergerak.


 rainaya
rainaya