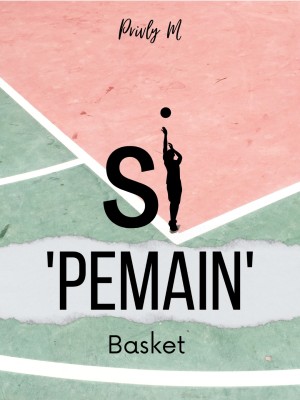Kamis, 10 Desember. 19.35 WITA
Makan malam bersama tidak selalu terjadi di keluarga kami. Kedua orangtuaku bekerja, Papa kadang lembur, Mama bekerja shift di sebuah klinik bersalin. Kadang, makan malam hanya terdiri dari aku dan Laura. Atau hanya aku, karena Laura akan sibuk di luar bersama teman-temannya yang lain, atau cowok-cowok yang berusaha mendekatinya.
Malam ini menjadi salah satu dari malam-malam yang jarang terjadi itu. Kami berempat berkumpul bersama, mengelilingi meja persegi panjang dengan sepiring cumi asam manis yang dibeli di perjalanan pulang, dua potong ayam goreng tepung, serta semangkuk besar mi instan kuah rasa Soto Banjar Limau Kuit yang kumasak dengan ditambah telur.
“Hari ini masih latihan?” Papa bertanya di sela kunyahannya, pertanyaan yang tentu bukan dialamatkan padaku.
Aku meneruskan menyantap cumi di piringku sementara Laura harus meneguk makanannya sebelum menjawab pertanyaan itu. “Iya, dong, Pa. Latihan terus sampai dua hari sebelum hari H. Habis itu gladi resik.”
Laura tergabung dalam kelompok paduan suara yang akan tampil untuk acara HUT sekolah minggu depan. Papa dan Mama berjanji akan datang untuk melihat penampilannya, mereka terlihat gembira.
Sementara aku? Bukan apa-apa.
Aku pandai dalam pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, tetapi nilai matematikaku biasa saja dan ranking dua atau tiga di kelas bukan sesuatu yang bisa dibangga-banggakan amat. Laura sebaliknya, rapornya tidak lebih baik bagitu. Tetapi ia selalu bisa tetap berada di sepuluh besar sementara dirinya juga aktif di luar pelajaran. Ia ikut OSIS an mendapat banyak teman di sana. Ia juga sempat menjadi anggota paskibra yang mengibarkan bendera sekabupaten, ikut paduan suara mewakili sekolah, serta memenangkan lomba debat. Piala-piala yang berhasil ia raih bersusun rapi di lemari di ruang tamu.
Milikku? Tidak ada.
Aku hanya mendengarkan obrolan mereka sambil menekankan kepada diri sendiri bahwa ... tidak apa-apa menjadi diriku sendiri dan bukannya seperti Laura.
“Bagus itu,” Mama berkomentar. “Kamu juga harus ikut-ikut ekskul begitu kayak Rara, Na. Kamu kan kebanyakan di rumah. Banyak-banyakin temen juga, kayak Rara.”
“Banyak temen juga buat apa,” aku menyuap nasi ke mulut hingga penuh. Setidaknya membuatku punya alasan untuk tidak menjawab selama beberapa menit ke depan.
“Biar kamu punya keahlian, koneksi, bukan cuma belajar aja.”
Kediaman terjadi di meja itu kemudian. Aku mengunyah nasiku dengan lambat demi mengulur waktu. Meski sebenarya, perutku tiba-tiba terasa penuh dan aku tidak lagi mengenali rasa lapar.
Hanya Papa, yang kemudian memecah keheningan singkat itu.
“Eh iya, besok ulang tahun kalian, mau hadiah apa?”
Aku belum memikirkannya. Sebenarnya, aku bahkan lupa tentang hari itu, atau apakah hari itu penting. Bukan aku yang meminta dilahirkan ke dunia, jadi kenapa harus dirayakan?
“Aku mau sepatu baruuu,” rengek Laura seketika. “Boleh nggak, Pa?”
Papa mengernyit sebentar. “Loh, sepatu kamu kan banyak.”
“Sepatu sekolah. Aku maunya sepatu buat jalan, yang warna pink! Aku liat koleksi terbaru Polla Polly bagus deh, Pa! Mau yang Raya Pink.”
Tanganku terhenti di udara, aku menaruh sendok kembali ke piring tanpa suara, tanpa disadari siapapun. Merk itu ... aku mengenalinya. Amat mengenalinya.
“Mahal?” tanya Papa sembari mengunyah dan menyipitkan mata. Mungkin dia sudah tahu, kebiasaan Laura yang jika terus dituruti, akan menguras isi dompet.
“Nggak juga, Pa. Cuma 800 ribuan kok. Worth it, lah karena emang cantik bentuknya! Boleh, ya? Boleh, ya?”
“Mahal banget sepatu doang. Kalau dibeliin sendal jepit bisa buat kios sendal.”
“Ya beda dong, Pa. Sepatu segitu nggak terlalu mahal kok. Boleh, ya? Boleh, ya?” rengeknya lagi. Aku bahkan melihat matanya seakan nyaris berair ketika ia memohon. Dan ketika jurusnya tidak terlalu berhasil, Laura mulai membujuk Mama. “Boleh ya, Ma? Kan ulang tahun Rara, lagian udah lama banget nggak beli sepatu. Ya? Ya? Ya ya ya?”
“Iya,” kata Papa, luluh setelah dua menit. “Tapi kamu harus sukes penampilannya sama ranking semester ini harus masuk lima besar.”
Seketika, Laura memeluk lengan Papa, matanya berbinar-binar. “Yay! Makasih, Pa. Papa memang yang terbaik!”
Lalu kembaranku itu terus menceritakan seperti apa sepatu yang diinginkannya. Salah satu koleksi Polla Polly dengan warna pink lembut yang mendekati peach, ada bunga-bunga kecil berwarna serupa di kedua sisinya, tidak menyolok. Itu bukan gaya Laura. Gaya Laura adalah Balenciaga dan Adidas, atau sepatu dengan heels dan kerlap-kerlip yang cocok untuk ke pesta. Gaya Laura adalah warna-warni, penampilan yang membuatnya menjadi pusat perhatian. Apa yang membuat dia tiba-tiba menginginkan sepatu itu?
Sementara, koleksi itu ... aku menginginkannya. Aku menyimpan fotonya di ponselku. Aku mengatakan pada Laura, aku sedang menabung untuk membeli sepatu itu. Tabunganku hampir cukup sekarang.
Apakah dia menginginkannya hanya karena aku menginginkannya? Apa dia terobsesi dengan apa-apa yang kusukai?
“Kalau gitu Nana nanti nyusul ya,” kata Papa setelah beberapa saat. “Uang Papa cuma cukup buat beli sepasang sepatu.”
Tidak ada pilihan lain bagiku selain mengangguk dalam diam. Aku menahan diri untuk mengikuti makan malam hingga akhir, meski mempercepatnya dengan buru-buru menghabiskan makanannku, tanpa menyentuh salad buah yang juga dibeli mama sepulang kerja
Tidak ada lagi yang ingat untuk menanyakan apa yang kuinginkan untuk ulang tahun, atau apa yang sebenarnya kuinginkan. Di meja itu, meskipun dikelilingi orang-orang terdekat, meskipun bersama keluarga sendiri, aku merasa ... kesepian.
***
“Mama punya hadiah buat kalian. Tadaaa~”
Kenangan pertamaku, anehnya adalah tentang gaun. Dua buah gaun putri yang cantik, identik. Hadiah untuk ulang tahun kami yang ke-5. Satunya berwarna merah jambu dan satunya kuning. Aku dan Laura, sama-sama menyerbu yang merah jambu.
“Punyaku!”
“Punya Lala! Lala mau yang pink!”
“Kamu udah punya banyak yang pink!”
“Nggak mau! Pokoknya yang pink!”
Lalu, sebelum gaun itu robek, Mama telah memisahkan kami. Ia membiarkan Laura gaun yang merah jambu, lalu berjongkok padaku, mengusap rambutku.
“Nana,” ujar Mama, lembut. Aku bersungut-sungut. “Nana pake baju yang kuning, ya? Kan baju Nana biasanya warna kuning.”
“Tapi Nana mau yang pink!”
“Yaudah, lain kali, Nana yang pink, ya.”
Aku tahu tidak akan ada lain kali. Mama selalu bilang begitu, nanti, nanti. Dan nanti pula, Laura akan merebutnya dariku.
“Kenapa Nana nggak boleh pake yang pink?!”
“Karena punya Lala kan warna pink. Kalau sama, nanti ketuker. Nana nggak mau ketuker, kan?”
Selalu menjadi pertanyaanku, kenapa anak kembar harus selalu memakai baju yang sama dengan warna berbeda? Setiap kali Mama mendandani kami, Laura dengan pita pink di rmabutnya dan aku dengan warna kuning, lalu memamerkannya pada kerabat atau tetangga, aku tidak pernah menyukainya.
Orang-orang itu lebih menyukai Laura. Aku tidak buruk, sungguh. Pada pertemuan pertama, orang-orang akan mengatakan aku cantik. Tetapi setiap melihat Laura, semua orang selalu teralih ke arahnya. Dia punya bulu mata yang lebih panjang, mata yang lebih cerah, dan rambut ikal seperti boneka. Rambutku lurus dan tebal, seperti sapu ijuk. Dia memakai baju pink dan aku tidak.
Dan bahkan, hingga sekarang, baju berwarna pink itu tidak pernah menjadi milikku.
Dan aku ... selalu suka warna pink.
***
Kamis, 10 Desember. 23.48 WITA
Aku tidak tidur usai salat isya. Setelah melipat mukena dan mengembalikannya ke tempatnya─pada rak kecil di dekat lemari pakaian, aku menarik kursi di meja belajar dan membiarkan keheningan memerangkapku.
Pada jam sepuluh, rumah ini sudah sepi seperti biasa. Lampu-lampu dimatikan dan kebisingan tidak lagi diizinkan. Semua orang pergi tidur. Aku biasanya tidak. Malam ini pun tidak. Aku suka kedamaian yang hanya kudapatkan di saat-saat seperti ini. aku suka berteman dengan diri sendiri.
Setidaknya untuk sebentar, aku hanya tidak ingin memikirkan tentang Mama yang jelas-jelas lebih mencintai Laura, Papa yang terlalu sibuk dan tidak peduli, dan ... aku juga tidak ingin memikirkan tentang keberadaan Laura yang tengah tertidur sekarang. Aku tidak ingin pergi tidur lalu berbagi tempat tidur yang sama dengannya. Jadi aku membuka buku tebal terjemahan Wuthering Heights milikku, salah satu yang paling kusukai dan salah satu yang paling tidak tersentuh. Buku-buku ini, bayi-bayiku ini, selalu menakuti orang-orang dengan ketebalannya, atau dengan kalimat-kalimat yang rumit. Terkadang aku merasa seakan kita senasib. Aku juga, selalu mendorong orang lain menjauh karena isi pikiranku yang berbeda dengan mereka, atau hanya karena menampilanku. Aku terlihat seperti aku tidak ingin bicara dengan siapapun, meski sebenarnya aku memang tidak ingin bicara dengan siapapun.
Dengan lampu yang hampir semuanya dimatikan, tersisa redup dari lampu tidur berbentuk pohon dengan bohlam-bohlam kecil di setiap rantingnya di sudut meja yang menjadi peneranganku satu-satunya. Aku membuka buku di tanganku. Bukan untuk membacanya, kali ini. Tetapi untuk menemukan apa-apa yang terselip di beberapa halaman. Carik-carik kertas dengan tulisan-tulisan pendek. Juga, beberapa kelopak kering bunga kupu-kupu. Aku memungutnya, merasakan teksturnya di bawah ujung jemariku. Dan kenangan tentangnya pun hadir tanpa diundang.
Kenangan itu melibatkan Nawala, matahari pukul sembilan pagi, senyumnya yang seratus kali lipat lebih baik dari matahari itu sendiri, serta keringat di dahi.
Hari itu Minggu, dan aku sedang berkebun. Dulu, ketika menanam bunga dan tanaman-tanaman hias sedang trend, Mama mendapatkan beberapa tanaman hias dari rekan kerjanya. Lalu ia membeli beberapa lagi beserta pot-pot besar dan kecil untuk tanaman-tanaman itu. Tetapi karena kesibukan, tanaman-tanaman itu mulai terlantar, akan terlantar seandainya tanggung jawab tidak segera ia jatuhkan ke pundakku. Aku dan Laura, tepatnya. Tetapi Laura terlalu sibuk untuk berkebun, dan dia tidak pernah suka bersentuhan dengan tanah dan pupuk atau semacamnya. Jadi bisa dibilang, kebun itu sekarang milikku, tanggung jawabku.
Aku pribadi menganggap diriku biasa-biasa saja. Memiliki wajah biasa-biasa saja dan penampilan biasa-biasa saja. Tetapi hari itu, dengan kaus lusuh dan overall biru kusam yang bagian celananya menggantung tanggung di atas mata kaki─baju lamaku waktu SMP, tanpa sentuhan make up apapun selain debu dan tanah, juga keringat yang sebesar biji jagung di kening, aku tahu penampilanku saat itu adalah yang terburuk.
Lalu, Nawala datang, menyapaku.
Ketika aku mendongak untuk menatapnya, aku bersumpah aku seakan memasuki dunia yang seperti digambarkan novel-novel romansa. Nawala berdiri di antara aku dan matahari, membuat silau. Badannya wangi, wajahnya bersih dan tampan. Lalu dia tersenyum dan segala menjadi lebih baik lagi. Tetapi bukan itu yang paling menarik dalam kenanganku.
Dia berjongkok di sisiku, tanpa ragu menggulung lengan panjang bajunya hingga siku, lalu meraih sekop kecil dari tanganku.
“Butuh bantuan?” tanyanya. Terlambat, dia sudah menceburkan diri sebelum bertanya, sehingga aku tidak dapat menolak.
Ia membantu mengambil alih lebih dari separuh pekerjaanku, menyekop tanah, menambahkan pupuk, memindahkan rumpun-rumpun tanaman ke dalam potnya yang baru, lalu menyirami mereka.
Kami hampir selesai. Aku sedang memindahkan satu pot sedang mawar ke bagian halaman yang terkena sinar matahari ketika Nawala memanggil.
“Ini dijemur juga?”
Aku menoleh, melihatnya membawa pot gantung berisi bunga kupu-kupu dalam dekapan. Buru-buru, aku menggeleng. Lalu setengah berlari ke arahnya dengan pot mawar dalam dekapan, lupa untuk diletakkan. “Enggak! Di situ aja. Dia nggak perlu kena sinar matahari.”
Wajah yang selalu menyenangkan untuk dilihat itu sekarang mengerut. “Kok?”
Aku terkekeh. “Itu bunga kupu-kupu,” kataku, tanganku terulur untuk menyentuh daun-daunnya yang berwarna ungu gelap, yang jika diperhatikan, berbentuk menyerupai kupu-kupu. “Dia nggak butuh sinar matahari langsung. Dia baik-baik saja ... berada di bawah bayangan.”
Kami menggantung bunga itu di sudut teras, teduh berlindung di balik pohon jambu air yang menjatuhkan bayang-bayang panjangnya setiap pagi ke arah sana. Lalu bersama-sama, kami menjemur mawar di ujung teras lainnya dimana sinar matahari mengintip. Mawar itu sedang berbunga, tengah mekar dengan kelopak merah muda lembut. Selama beberapa saat, aku melihat Nawala memandanginya.
“Cantik banget, ya,” tegurku.
Ia menatapku, lalu terkekeh. “Cantik itu katanya relatif, tapi kayaknya nggak ada orang yang nggak setuju kalau bunga mawar memang cantik.”
Aku mengangguk. Memang, mawar selalu cantik. Kecantikan yang universal.... Seperti Laura, dia cantik dengan cara seperti itu.
“Kalau kamu?” Pertanyaan dari Nawala membuyarkan lamunanku. Saat aku menatapnya, dia tengah menatapku. Dan perlu usaha keras dariku untuk mengendalikan jantungku agar berdetak dengan normal karenanya. “Mana yang paling cantik menurut kamu?”
Kududukkan diri di pagar teras, pagar itu setinggi paha, terbuat dari kayu ulin dengan satu papan di atasnya untuk menjejerkan pot-pot tanaman berukuran sedang dan kecil. Aku mengambil tempat yang kosong, di sisi mawah dan di bawah bunga kupu-kupu. Kepada Nawala, aku tidak segera menjawab melainkan mengetuk-ngetukkan jari pada dagu sembari bersedekap, berpikir.
“Kalau yang paling cantik, aku akan jawab mawar itu. Tapi kalau yang paling kusuka,” jariku menunjuk pot di atasku. “Aku pilih bunga kupu-kupu.”
“Kenapa?” tanyanya.
Satu pertanyaan itu mendatangkan banyak jawaban dalam kepalaku. Karena bunga itu adalah aku, bersembunyi malu setiap kali, tidak berani menghadapi sinar matahari, hanya dapat menatap dari kejauhan. Karena matahari itu adalah Nawala dan Laura adalah mawar. Karena aku juga ingin ... sedikit saja, dicintai selayaknya mawar.
“Karena hampir semua orang menyukai mawar,” jawabku. “Bunga kupu-kupu juga butuh disukai.”
Lalu, Nawala mengangguk. “Setuju.”
Sekarang, matahari telah merangkap seperempatnya dari kubah langit dan jam tangan cowok itu menunjukkan pukul sembilan lewat sedikit. Nawala yang sekarang berbeda dengan Nawala yang tadi menyapa. Dia tidak lagi sewangi tadi, dia sekarang memiliki noda tanah di pakaian dan wajahnya. Dan biji-biji peluh terbentuk di kening, sebelum mengalir di pelipis.
Tetapi, ketika melihatku, ia kembali tersenyum. Dan sekarang, setelah semua yang kami bagi, setelah kalimat sederhana yang dia ucapkan, semuanya menjadi lebih berharga. Senyumnya menjadi seribu kali lebih baik dari apapun. Itu adalah momen yang membekas di kepalaku. Itu adalah momen jatuh cintaku untuk kali ke sekian. Pada orang yang sama.
Dan seakan tahu bahwa aku tengah merindukannya teramat sangat, ponselku bergetar, menampilkan nama dan senyumnya tampak sampingnya di layar. Foto yang kuambil secara diam-diam.
“Belum tidur?” Cowok itu terdengar terkejut dengan kecepatanku menjawab, yang sedikit kusesali. Seharusnya aku menunggu sedikit, tidak bereaksi secepat ini.
“Belum,” jawabku seadanya seraya melirik jam dinding. Hampir pukul dua belas malam. Rasa penasaran segera membuatku bertanya. “Ada apa nelpon malem-malem?”
“Kenapa? Ganggu?” Terdengar kekeh di seberang sana. Aku tersenyum. “Enggak sih. Surat yang tadi sore ..., kamu belum buka, kan?”
Aku menggeleng. Lalu, sadar bahwa Nawala tidak bisa melihatnya, aku terburu-buru menjawab. “Belum. Boleh buka sekarang?”
“Hmm. Pas jam dua belas, ya,” katanya lagi, setengah berbisik.
Dan ... bohong jika kubilang aku baik-baik saja. Jantungku seketika menggila, membuatku cemas dia dapat mendengarnya dari seberang sana. Terutama, ketika kemudian Nawala seakan membisikkannya di telingaku.
“Selamat ulang tahun, Nana.”
Aku memejamkan mata. Perlakuan sederhana ini membuat wajahku memanas, jantungku menolak berfungsi, dan aku ... merasakan seakan kupu-kupu beterbangan di sekitar, tidak hanya di perutku. Saat ini, detik ini, aku merasa bahagia.
Setidaknya satu orang juga menyukai bunga kupu-kupu yang malu.
“Sekarang buka isi koran itu, oke? Ada dua surat. Yang pita biru untuk kamu. Yang pink, tolong sampaikan ke Rara, ya.”
“Oke.”
Telepon kututup setelahnya. Butuh beberapa menit bagiku untuk menenangkan diri, untuk menyiapkan mental pada apapun itu yang bersembunyi di dalam kertas, terurai oleh tinta. Selembar surat yang membuatku membayangkan Nawala ketika menuliskannya.
Aku meraih gulungan surat yang diikat dengan pita biru muda, merasakan tekstur lembutnya sebelum menarik pita tersebut. Surat yang Nawala tulis tidaklah panjang. Lebih mirip surat-surat yang selalu ia selipkan di dalam koran pada pertukaran-pertukaran surat kami yang biasa. Hal ini membuatku tidak bisa menahan senyum.
Surat itu berbunyi:
Untuk, Jambu.
Hei, ingat pertama kali kita ketemu? Lewat koran, yang masih sering kita tukar sampai sekarang. Meeting you is one of the best things happened, honestly. Kamu itu ajaib, kayak pikiran-pikiran kamu. Manis, kayak jambu air depan rumah kamu. Cantik, seperti bunga kupu-kupu.
Dan, aku sangat berterima kasih atas persahabatan kita.
Jambu, terima kasih atas surat-suratnya. Terima kasih atas puisi yang kamu buatkan. Terima kasih sudah hadir dan terlahir.
Selamat ulang tahun. Have a sweet seventeen, Jambu.
Selama lima menit penuh, aku tersenyum tanpa bisa menghentikannya. Selama lima menit penuh, aku merasa amat bahagia. Dan seharusnya, kebahagiaan itu bisa bertahan lebih lama, atau selamanya. Seandainya, rasa penasaran tidak menuntunku untuk meraih surat dengan pita merah muda.
Surat kedua itu untuk Laura, bukan untukku. Tetapi entah bagaimana, aku menarik pitanya, mengulur suratnya.
Aku membacanya. Surat itu.
Lalu, aku merobeknya.
***
Jumat, 11 Desember. 00.23 WITA
Sudah lewat tengah malam. Jarum panjang dan pendek yang saling bertolak belakang menunjukkan sekarang hampir pukul setengah satu pagi. Artinya, sudah tiga jam berlalu sejak Laura menutup telepon dari seseorang dengan berbisik-bisik. Tetapi aku dapat mendengarnya, itu suara Rei. Sudah tiga jam sejak kembaranku itu menarik selimut dan menenggelamkan diri di alam mimpi. Dan ... sudah lebih dari setengah jam sejak kedua mataku mulai mengalirkan air terjun yang tidak dapat kuhentikan.
Aku masih di sini, terduduk di lantai yang dingin dengan punggung bersandar pada sisi lain tempat tidur. Surat itu berhamburan di sekitarku, robek dan sudah tidak berbentuk. Ada juga novel Wuthering Heights yang terbuka, lusuh, dan mungkin mendapat beberapa bekas airmata di halaman tengahnya.
Aku tidak beranjak untuk memeriksa. Aku tidak bisa. Aku sedang dalam upaya keras menahan diriku sendiri untuk tidak kembali menangis. Enam belas, hampir tujuh belas tahun hidupku, aku berusaha menahannya, selalu. Seolah jika aku menahannya, atau berpura-pura mereka tidak pernah ada, perasaan itu akan lenyap. Nyatanya aku hanya sedang membodohi diri sendiri.
Sementara Laura telah tertidur dengan nyenyaknya, aku di sini, kesulitan menahan isak, kesulitan meredakan dada yang sesak. Orangtua selalu punya pilihan apakah mereka menginginkan anaknya atau tidak. Tetapi anak? Tidak bisa memilih oleh siapa ia dilahirkan, atau apakah ia ingin dilahirkan sama sekali. Atau dengan siapa, ia harus dilahirkan. Orang yang jatuh cinta tidak bisa memilih dengan siapa dia jatuh cinta. Tetapi ia dapat memilih untuk bertahan atau berjuang. Namun tidak ada yang dapat memilih oleh siapa dia dicintai.
Poinku adalah bahwa ... Dunia itu... tidak pernah adil. Tidak akan pernah.
Aku tidak punya pilihan apapun di sini. Aku merasa amat tidak berdaya. Aku ingin dunia adil meski sekali saja.
Lalu, keresek di pintu serta gumaman-gumaman yang samar terdengar menyentakku. Aku menoleh tepat ketika mendengar suara Mama yang lantang, diringi ketukan tangan.
“Raaa! Naaa! Buka pintunya, Nak.”
Cepat-cepat aku membereskan buku dan kertas-kertas yang berantakan dan menyusut airmata dengan lengan baju, meninggalkan kelopak bunga kupu-kupu kering di lantai. Ada apa Mama mengetuk tengah malam begini? Jam di bawah lampu meja itu mengonfirmasi bahwa sekarang baru pukul dua belas lewat dua puluh tiga menit.
Aku menunggu beberapa saat sebelum membuka pintu. Mengacak rambut, berpura-pura tertidur dan mengambil waktu untuk membangunkan diri.
“Launaaa! Lauraaa! Bangun, Nak!”
Suara Mama disertai gedoran pintu yang kembali terdengar memaksaku untuk bangkit duduk lalu berjalan menuju pintu kamar, sembari menerka-nerka apa yang kiranya diinginkan Mama. Memang, dia dan Papa kadang bekerja lembur dan pulang sampai larut malam. Papa adalah pegawai di sebuah perusahaan swasta, pabrik mi, sementara Mama dinas di rumah sakit sebagai seorang perawat. Kadang, mereka belum pulang ketika kami tidur. Tetapi hari ini keduanya pulang sore, kami bahkan makan malam bersama. Juga, jarang sekali, hampir tidak pernah beliau mengetuk tengah malam begini. Hal penting apa, memangnya─
Aku membuka pintu dengan malas-malasan yang pura-pura, dengan mata setengah terpejam. Tetapi teriakan Mama, tepuk tangan Papa serta silau cahaya lilin di depanku berhasil serta-merta mengusir rasa kantuk.
“Happy birthday, Nanaaa! Rara mana?”
Mama memelukku sebentar dengan sebelah tangan, sementara tangan lainnya dengan teguh memegangi kue tart dengan lilin di atasnya. Ia kemudian segera beralih mendekati tempat tidur, pada saudari kembarku yang terduduk sampai mengucek mata. Keberisikan tadi rupanya telah membangunkan Laura.
“Raraaa~ Happy sweet seventeen, Sayang.”
“Ma, ini jam berapa coba? Ngantuk~” Rara, seperti biasa, justru mendorong Mama pelan di pundak. Tetapi ia tersenyum dan merapikan rambut. “Sok-sok ngasih kejutan. Habis liat di Tiktok, ya?”
Mama berdecak, tetapi tidak menyanggah. Ia menarikku mendekat, mendudukkanku di samping Laura.
“Selamat ulang tahun anak-anak Mama yang cantik. Sekarang, berdoa dan tiup lilinnya.”
Aku memejamkan mata.
Ada banyak yang kuinginkan di dunia ini. Aku ingin menjalani kelas dua dengan penuh prestasi, lulus dengan baik, lalu diterima di universitas bergengsi nantinya. Aku ingin menjadi penulis besar, seperti idolaku Nicholas Sparks atau Suzanne Collins. Aku ingin membangun rumah impianku dan melewatkan masa tua dengan kursi goyang di terasnya. Aku ingin Nawala, satu-satunya sosok manusia yang kuinginkan, sangat kuinginkan. Aku ingin bahagia.
Namun, yang berputar di kepalaku saat itu hanyalah satu hal. Hanya satu doa.
Namaku Launa. Hari ini, sebelas Desember, umurku genap 17 tahun. Keinginanku? Hanya satu. Aku ingin saudari kembarku menghilang.


 rainaya
rainaya