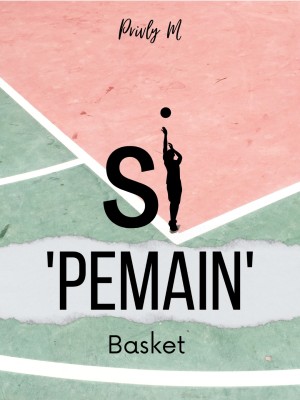Jessi yang ada di sana hanya bisa ternganga melihat peristiwa
spektakuler di hadapannya, membekap mulut dengan kedua tangan. Matanya melebar
tidak percaya dengan apa yang ia saksikan. Bahkan semua orang di kantin ikut
tercengang, kemudian melihat ke arah Vanta dengan tatapan iba.
Kenyataan itu membuat Vanta kalap, hampir lepas kendali. Ia
terpaku karena apa yang dilakukan Alvin. Cowok itu menggunting rambutnya!
Rambut panjangnya yang selalu menjuntai melewati bahu. Walaupun pernah berpikir
untuk mengubah gaya rambutnya jadi sedikit lebih pendek, tapi bukan begini
caranya. Bukan tangan itu yang Vanta harapkan untuk melakukannya.
Keheningan massal di kantin membuat suasana menegang. Seakan hanya
ada dua musuh besar itu di sana. Nyatanya, semua mata masih memandang Vanta dan
Alvin dengan beragam reaksi. Di tempatnya berpijak, Vanta mati-matian berusaha
menahan gejolak emosi yang sudah meluap-luap dengan mengepalkan telapak tangan.
Dia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata erat-erat selama sepersekian
detik, kemudian menatap Alvin tajam. Setajam sebilah pedang.
”Lo udah gila,” desis Vanta lirih, nyaris seperti bisikan. Dadanya
bergerak naik turun menahan marah. Vanta berharap tatapannya mampu
mencabik-cabik Alvin saat itu juga.
”Lo bener-bener gila! Kenapa sih, lo segitu nggak sukanya sama
gue?!” Kali ini suara Vanta meninggi. “Nggak cukup perbuatan lo
kemarin-kemarin? Cuma karena gue udah numpahin lemonade, lantas lo terus-terusan siksa gue begini?” Air mata yang
sejak tadi ditahannya menyebabkan wajah dan matanya memerah.
”Lo tuh udah keterlaluan tau, nggak?! Sampe kapan lo mau bales gue
karena masalah itu?! Sampe kapan lo bakal berhenti??” jerit Vanta geram sambil
menahan isaknya. Dia tidak peduli pada penampilannya sekarang. Rambut yang
berantakan dan panjang tak beraturan. Yang dirasakannya hanya kemarahan dan
kesedihan.
Alvin maju selangkah, menatap tepat pada manik matanya. ”Sampe gue
merasa itu cukup.”
“Gue, benci banget sama lo!” Terdapat penekanan pada setiap kata
yang diucapkan Vanta.
Sementara itu Jessi masih terpaku di tempat. Sampai Vanta berbalik
dan berlari meninggkalkan kantin, dia baru tersadar dan mengejar sahabatnya.
Vanta masuk dan menutup pintu toilet perempuan. Kedua tangannya
bertopang pada wastafel. Ditatapnya pantulan dirinya yang kacau di cermin.
Sudut-sudut matanya telah basah. Penglihatannya terhalang oleh kabut di pelupuk
mata. Perlahan titik demi titik air mengalir turun, membasahi pipinya. Ia terus
mengusap dengan kasar setiap tetes air mata yang luruh. Lelah memendam
semuanya, kini tangisnya pecah.
Jessi berhasil mengejar Vanta sampai ke toilet. Namun, ia terlambat
untuk ikut masuk. Gadis itu telah mengunci toilet dari dalam. Diketuknya pintu
toilet beberapa kali.
“Ta, buka dong.” Satu kali Jessi memanggil.
“....”
“Ta, lo nggak aneh-aneh kan?” Panggilan kedua, Vanta tetap tidak
mengeluarkan suara.
“Ta?” Setelah yang ketiga kalinya, samar-samar Jessi mendengar
isak tangis Vanta. Hatinya seperti ikut terluka mendengar temannya menangis.
Rasa sakit yang dirasakan Vanta seolah dapat ia rasakan. Akhirnya Jessi memutuskan
untuk membiarkan Vanta menenangkan diri beberapa waktu. Ia menunggu di depan
pintu toilet dengan sabar sampai suara tangisan Vanta berhenti.
“Tata, gue boleh masuk?” tanya Jessi hati-hati dari luar toilet.
Namun tetap tidak ada jawaban. Jessi menghela napas. “Lagi nggak ada orang kok,
di depan sini.”
Setelah kalimat terakhirnya, Jessi mendengar suara dari dalam
toilet. Dan kemudian pintu itu terbuka. Keadaan Vanta membuat Jessi tersengat.
Gadis di depannya─yang tadi pagi muncul dengan keadaan rapi─tampak berantakan, begitu kusut,
begitu kacau. Matanya sembab dan merah. Segera Jessi memeluk Vanta, mengelus
kepala gadis yang lebih tinggi darinya.
“Jangan nangis lagi ya, Ta.”
Tubuh Vanta kaku dalam pelukan. Sadar dengan situasi yang ada,
Jessi menarik Vanta masuk lagi ke toilet. Dikeluarkannya tisu dari dalam tas
untuk menghapus air mata di pipi Vanta. Selama beberapa saat tidak ada satu pun
dari mereka yang bicara. Jessi hanya terus mengelus Vanta, menyalurkan
ketenangan pada gadis itu.
“Jes ...,” panggil Vanta dengan suara sengau.
“Ya? Kenapa?”
“Gue mau minta tolong.” Vanta yang semula menyandarkan kepala di
bahu Jessi menegakkan badan. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Mata
Jessi langsung terbelalak begitu Vanta menyerahkan benda itu. “Potong habis
aja, Jes.”
***
“Bangsat. Lo dapet ilham dari mana, sih? Pake acara
gunting-guntingan segala?” Di tempat lain, tanpa Vanta ketahui, ada orang yang
marah untuknya. Ada orang yang berdiri di garda depan untuk membelanya.
“Apa, sih? Cuma rambut, nanti juga tumbuh lagi. Gue bukan ngebunuh
anak orang, kali. Lagian kenapa lo yang marah?”
Toto yang merasa ulah Alvin keterlaluan kali ini langsung
menyeretnya bicara empat mata. Sebelumnya, ia hanya diam dengan ulah-ulah iseng
Alvin karena memahami apa yang terjadi pada sahabatnya. Toto tetap berada di
sampingnya, membiarkannya dan tidak menegurnya karena dia tahu hanya itulah satu-satunya pelampiasan Alvin. Tapi
melihat masalah yang dibuat Alvin kali ini, dia tidak bisa tutup mata. “Lo
emang nggak bunuh dia secara fisik, tapi lo bunuh mentalnya!”
Alvin cukup kaget mendengar kalimat Toto. Cowok itu tidak
merespons.
“Dia bisa aja trauma gara-gara lo,” tukas Toto lagi. Dia membuang
napas keras, tidak habis pikir. Sebetulnya, kenapa Alvin masih terus mengincar
Vanta?
Soal lemonade itu perkara
yang tidak seberapa. Toto dan Alvin saling kenal sejak SMP. Walaupun saat itu mereka
belum terlalu akrab, sepenglihatan Toto, biasanya Alvin hanya akan mengabaikan
seorang cewek yang berulah.
Dalam kasus yang sekarang mungkin berbeda. Vanta bukan berulah
untuk menarik perhatian Alvin, apalagi merayunya. Cewek itu murni sebal dengan Alvin.
Dan harusnya Alvin cukup mengabaikan satu cewek lagi seperti biasa.
“Lo udah berkali-kali balas dia, harusnya itu udah impas. Lo cuma perlu
cuekin dia kalo ketemu. Anggap aja nggak ada atau nggak kenal, sama kayak biasa
lo ke cewek-cewek. Sadar nggak sih, ini kayak bukan lo banget.”
Alvin menyugar rambutnya dan bergumam, “Kalo bisa juga udah gue
lakuin.”
“Terserah lo, deh. Yang pasti kalo lo bertingkah lebih dari ini,
gue nggak bisa tinggal diam. Gue bakal berpihak ke tuh cewek.” Toto
mengatakannya dengan wajah tenang, namun nadanya menusuk. Pemuda itu kemudian
menepuk pundak Alvin dan berjalan melewatinya.
Alvin diam di tempat. Tak berbalik sedikit pun melihat kepergian
Toto. Rahangnya terkatup rapat. Kedua tangannya mengepal erat. Satu tinju lalu melayang
ke tembok terdekat.
***
Vanta baru keluar dari kamar saat hari sudah gelap. Perutnya
lapar. Seharian ini menangis membuat energinya terkuras. Ia mengendap-endap di
dapur. Barangkali ada sesuatu yang bisa dimakan di sana. Sejak pulang ke rumah,
Vanta belum bicara dengan mamanya. Mama sudah ada di rumah ketika Vanta pulang
tadi. Dia hanya menyapa singkat dan langsung masuk ke kamar. Mama yang melihat
penampilan Vanta saat itu langsung terkejut. Mama pasti khawatir. Tapi Vanta benar-benar
tidak ingin bertatap muka dengan siapa pun. Perasaannya masih kacau balau.
“Ta?” Lampu dapur menyala bersamaan panggilan itu. Vanta terhenyak
dan menoleh. “Kamu mau makan?” tanya Mama.
“Mmm, iya Ma.” Vanta menarik salah satu kursi di meja makan dan
duduk di sana, sementara Mama membuka tudung saji di atas meja. Ada udang
goreng mentega dan angsio tahu kesukaan Vanta.
Mama mengambilkan peralatan makan dan mengisi piring dengan lauk
dan nasi. Setelah itu memilih duduk di seberang Vanta. “Kok potong rambut?”
Pertanyaan yang tak bisa lagi dihindari oleh Vanta.
“Biar nggak ribet aja, Ma, kalo nugas.”
“Tumben nggak bilang-bilang? Biasa soal rambut, mau potong dua
senti aja pasti kamu udah heboh galau-galauan di rumah.”
Biasanya, Vanta selalu meminta pendapat Mama untuk hal sekecil apa
pun. Meski sudah punya jawaban sendiri, gadis itu tetap cerita lebih dulu untuk
sekadar memberi info. Vanta suka mengobrol banyak hal dengan mamanya. Bagi
Vanta, Mama adalah orang tua yang sangat pengertian dan selalu mendukungnya.
Vanta menyayangi Mama sebesar kasih sayang yang didapatnya. Oleh karena itu,
Vanta tidak ingin memuat Mama khawatir dengan menceritakan tentang
pertikaiannya dengan Alvin.
Naluri keibuan Mama bekerja. Melihat putri bungsunya diam, pasti
ada yang tidak beres. “Ata capek kuliah sambil kerja?”
Vanta segera menggeleng cepat. “Nggak, Ma. Ata sanggup, kok.”
“Kamu tau kan, Mama masih mampu biayain kuliah kamu. Ada Kak Oka
juga. Kamu udah berjuang dapat beasiswa, itu lebih dari cukup, Ta. Bukan
kewajiban kamu buat kerja. Sekarang, tugas kamu belajar untuk raih cita-cita
kamu.”
“Ata yang mau kerja, Ma. Lagian aku bosen kalau lagi nggak ada
Mama di rumah. Mama tau sendiri, anak Mama ini nggak bisa diem.”
Mama tersenyum mengusap punggung tangan Vanta sekilas. “Jadi, apa
yang bikin kamu potong rambut?”
Bukan apa, melainkan siapa.
Vanta menghela napas, menimbang-nimbang untuk bercerita. “Ada satu
orang yang bikin Ata kesel di kampus.” Akhirnya Vanta buka suara. “Awalnya
memang aku yang salah, sih, numpahin minuman ke dia. Terus dia nggak terima, sejak
itu jadi suka ngerjain Ata. Sampe tadi ... dia nempelin permen karet di bangku
yang aku dudukin.”
Mama tampak tenang mendengarkan. Menyimak setiap kata yang keluar
dari mulut Vanta dengan penuh perhatian. “Kamu nggak sengaja numpahin minumnya?”
Ditanya begitu, Vanta tak berani langsung menjawab.
“Sengaja ya?” tanya Mama tersenyum. “Apa alasan kamu numpahin
minum ke dia? Anak Mama nggak mungkin marah tanpa alasan.”
“Ata lihat dia ganggu mahasiswa lain di kampus. Dia semena-mena
gitu sama temennya, Ata jadi kesal lihat cowok sok bossy. Jadi, refleks Ata ...” Vanta menggantung kalimatnya dan
mengendikkan bahu.
Ternyata anak
laki-laki, pikir Mama. “Setelah itu kamu
udah minta maaf sama dia?”
Kening Vanta berkerut bingung. Jika permintaan maaf pura-puranya
di kantin dapat dihitung, berarti dia sudah minta maaf. Tapi maksud permintaan
maaf yang ditanyakan Mama pasti bukan yang seperti itu. Permintaan maaf yang sungguh-sungguh
dan tulus. Namun tiba-tiba Vanta bergidik membayangkan dirinya meminta maaf
pada seorang Alvin. Cowok tengil yang kadar menyebalkannya selangit.
“Kamu tau nggak,” Mama melanjutkan karena Vanta tidak menjawab. “Orang
yang pemarah itu sesungguhnya orang yang butuh perhatian dan kurang kasih
sayang di rumahnya. Dia memberontak demi mendapat apa yang dia mau. Menurut
kamu, orang yang kesepian itu kasihan nggak?”
Vanta menatap Mama selama sepersekian detik, lalu mengangguk.
“Nggak semua orang hidup penuh cinta meski keluarganya lengkap.
Nggak semua orang baik-baik aja meski terlihat punya segalanya.”
“Jadi Ata harus gimana, Ma?” tanyanya sambil menatap Mama memelas
dengan sepasang mata bulatnya yang hitam.
“Permusuhan kalian nggak akan selesai kalau salah satu dari kalian
nggak mencoba berlapang dada dan mengalah. Mama yakin kamu pasti bisa lebih
bijak menyikapinya.”
Vanta menunduk menatap piringnya. Rasa marahnya pada Alvin menguap
entah ke mana karena terlalu sibuk mencari jawaban. Lebih bijak ya, batinnya dalam hati. Kalau begitu apa yang
dilakukannya guna mengakhiri perang mereka?


 lunetha_lu
lunetha_lu