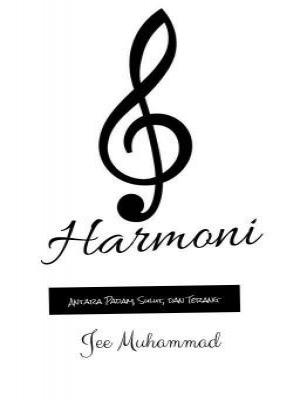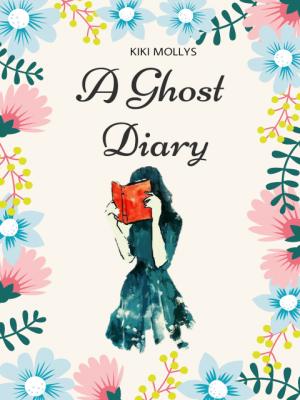[Ivy’s pov]
February 5th, 2008
Sudah lama sekali aku tidak berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Begitu Dorothea mengatakan akan tampil di pembukaan dan penutupan di ujian menari dari sanggar tempatnya mengajar, aku langsung mempersiapkan celana kain dan cropped blazer untuk dipadupadankan dengan tank top putih polos keesokannya.
“Kita ngapain sih di sini?!” gerutu seorang anak perempuan SD yang membuntutiku dari belakang. Namanya Gaby, ia adalah keponakanku yang baru saja pindah sekolah dan rumah karena ayahnya dimutasi. Sementara itu, orangtuanya--adik sepupu perempuanku, Veni dan Arthe, sang suami—sudah berjalan lebih dulu di depan menikmati sinar matahari yang tidak begitu terik karena langit dipenuhi awan.
Aku langsung merebut ponsel dari kedua tangan Gaby yang protes dengan suara melengking. Setelah menerima ponselnya, Veni memarahi putri semata wayangya, “Gaby! Jangan bikin malu ah! Sana ikut Aunty!”
Melihat orangtuanya yang duduk bermesraan di salah satu pendopo yang memang boleh ditempati. Kubiarkan anak kecil itu mengikuti arahku berjalan menuju panggung penampilan para peserta ujian dengan sikap kekanaknnya yang menghentak-hentakkan kaki ke tanah.
Begitu turut duduk sepertiku di salah satu kursi penonton, ekspresi kesal Gaby perlahan memudar dengan tatapan penasaran bercampur kagum. Aku telah gagal menonton Selat Segara sebagai tarian pembuka, tetapi tidak akan melewati Dorothea menutup acara dengan Oleg Tamulilingan. Semalam aku sempat melakukan sedikit riset tentang tari penutup itu sekaligus mempersiapkan diri melihat Dorothea menari berpasangan dengan orang lain.
Usai para peserta dengan nomor urut tiga puluh enam hingga empat puluh satu selesai membawakan Tari Cendrawasih, sang MC menjelaskan tentang burung-burung jantan maupun betina yang bermain gembira secara berpasangan sebagai latar belakang cerita tarian itu.
“Setiap Tari Bali punya cerita ya?” tanya Gaby di tengah riuh tepuk tangan para penonton setelah MC mempersembahkan tarian berikutnya, Panji Semirang.
Aku hanya menjawab dengan bergumam tidak jelas sampai seseorang menepuk pundak dan berjongkok tepat di samping kursi yang kududuki. “Dori?” Dorothea yang masih lengkap dengan make up tebal khas penari—eyeshadow tiga warna di kelopak matanya--melambaikan tangan dan melempar senyum manis pada Gaby sebelum berujar senang, “Kupikir kamu tidak datang!”
Di saat aku meminta maaf pada Dorothea karena bangun kesiangan hingga terlambat, Gaby sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan menatap Dorothea tanpa berkedip. Begitu melihat gerak mata Dorothea yang kembali pada Gaby, aku pun turut memandang keponakanku itu. “Kakak juga ujian, ya?” tanya Gaby polos.
“Aku guru, tapi memang selalu ikut menari setiap ada ujian,” jawab Dorothea. Perempuan itu menambahkan, “Karena disuruh pemilik sanggarnya juga, sih!”
“Kenapa? Kamu juga ingin belajar tari?” tanyaku. Bukannya menjawab Gaby membuang muka ke arah dimana orangtuanya menonton ujian tari dari samping satu barisan penonton.
“Nanti kalau adik sudah lahir, tidak ada yang jaga--” Kini aku paham kemana kekhawatiran anak kecil ini. Tepatnya ke perut sang Ibu yang membesar karena mengandung selama tujuh bulan.
“Mama kamu kan bisa sewa babysitter atau titip ke penitipan anak yang setiap sore orangtua jemput, memangnya kamu yang minta adik dari Papa dan Mama?” Gaby menggeleng sebagai jawaban pertanyaanku di akhir kalimat. Setelah mengatakan pada Gaby kalau melakukan kegiatan non-akademik itu juga bagus untuk tingkat konsentrasi saat belajar—satu-satunya yang ia suka—maupun bermain game, aku kembali beralih pada Dorothea yang sejak tadi asik memperhatikan interaksi seorang Bibi dan keponakannya. “Kucarikan kursi--”
“Tidak perlu!” Dorothea menahan lenganku yang hendak berdiri. “Aku sudah harus pakai kostum untuk tarian terakhir, dan Gaby!” Dorothea memanggil si anak perempuan bermata kelabu itu dan kembali berkata ramah, “Kutunggu di Sanggar ya! Nanti kita belajar bersama!”
Kuperhatikan arah netra Gaby yang terus mengikuti kemana Dorothea pergi. Begitu sosok sahabat SMAku itu menghilang di balik pintu gedung kecil tempat berganti pakaian, Gaby beralih menyodok pinggangku dengan telunjuknya.
“Ada apa sih?”
“Nanti temani aku bilang sama Mama ya ... tentang les menari,” bisiknya.
“Hanya bicara tentang itu saja pakai ditemani segala!”
“Aunty!” rajuk Gaby sambil menggoyang-goyangkan tangan kananku.
“Kenapa kamu tiba-tiba langsung ingin belajat tari?”
Gaby kembali menatap lurus ke arah panggung dan berucap, “Biar aku tidak disuruh belajar terus.” Sedetik setelah mendengar alasan itu aku terbahak sambil menggodanya yang pernah bilang ke Veni kalau ia sangat suka membaca buku pelajaran dan tidak akan pernah bosan dengan kegiatan itu. Hal itu sedikit mengingatkanku pada masa lalu dimana aku gemar merajut wol untuk boneka pemberian Ayah, dan berjanji akan menjadi seorang desainer. Nyatanya baru setahun belajar di Sekolah Dasar, tekadku mulai goyah karena mulai menyukai basket.
Setelah menahan api cemburu saat berlangsungnya penampilan Oleg Tamulilingan oleh Dorothea dan penari pria, aku mengambil foto dengan memfokuskan kameran pada sosok perempuan yang kusuka sejak lulus sekolah. Mulutku berdecak tanpa sadar saat salah satu foto terdapat penari pria itu yang berjabat tangan dengan Dorothea. “Kalau dipotong kan nanti gambarnya jadi blur,” komentar Gaby sembari mengintip layar ponselku.
“Ah, cerewet!” ujarku sinis yang kemudian mendapat hadiah cubitan di paha yang hanya tertutup tipisnya kain bahan celanaku. Seakan tidak puas telah mencubitku, Gaby berseru riang pada Dorothea bahwa aku ingin berfoto dengan perempuan yang masih lengkap memakai kostum tarinya.
“Ayo!” Dorothea menyambar ponselku dan meminta tolong Gaby mengambil foto kami. Aku memprotes keras karena hari ini hanya memakai bedak dan lipstick seadanya saja.
Gaby yang sepertinya masih marah kupanggil ‘cerewet’ berkata santai dengan kedua tangan yang sudah siap membidik, “Tidak usah dandan sudah jelek kok, Aunty.”
“Apa?” omelku tidak terima. Akhirnya aku pasrah dan berpose bersama Dorothea sesuai hitungan Gaby mengambil foto.
Saat Gaby dan aku berpamitan untuk menemui Veni dan Artha yang lebih dulu menunggu di mobil, Dorothea mengingatkanku untuk mengirim foto kami berdua. “Akan kujadikan wallpaper ponselku!” ucapnya sebelum bergabung dengan para penari lain.
February 14th, 2008
“Kukira grand openingnya hari ini,” ucapku menggaruk tengkuk salah tingkah pada kedua asisten kepercayaannya—Jovi, pria berkacamata dengan rambut ikal menutupi leher, dan Ezra, perempuan dengan poni yang hampir mengenai matanya serta berkulit putih pucat seperti porselen. Kami bertiga berkumpul di satu meja dari ruangan underground dengan temaram lamupu kuning yang menerangi laptop Jovi dan Oreo-Crumbs milkshake pesananku. Ezra membenarkan bahwa pembukaan resmi bisnis coffee shop milik Dorothea yang diwariskan dari Este jatuh pada tanggal 24 Februari, lengkap dengan jam tutupnya. Jadi bisnis coffee shop akan berjalan bersama toko roti yang sudah dirintis Este sejak dulu.
Ketika Jovi pergi ke dapur—setelah berkata ‘Khusus untuk hari ini saja kubuatkan milkshake!’--untuk melanjutkan wawancara pada dua calon barista yang akan bekerja yang terpotong jam makan siang, kecanggungan hadir di antaraku dan Ezra. Perempuan itu terus menatapku tajam tanpa berkedip. Terlihat jelas ia ingin memarahiku, tetapi karena Dorothea adalah atasannya sekaligus sahabatku, maka pemilik sepasang mata bulat dan terang layaknya boneka itu hanya bungkam. “Ada yang ingin kamu katakan?” tanyaku setelah menelan remah biskuit dengan susah payah.
“Siapa sebenarnya yang kamu suka? Mendiang Kak Este atau Kak Dorothea?”
“Este sudah kuanggap seperti adik perempuan sendiri!” bantahku. Jika Este masih di sini ia pasti akan tertawa keras di depan wajahku.
“Jadi Kak Dorothea?” Ezra lanjut memastikan tanpa ekspresi di wajahnya. Berbanding jauh denganku yang sudah tidak tahu harus melihat ke arah mana. Tidak ada pembeli lain selain diriku, lagipula kenapa aku bisa memilih underground sebagai pilihan tempat untuk berkunjung. “Kamu pasti sangat menyukai Kak Dorothea.”
Perkataan Ezra barusan membuatku terdiam dan mengerjapkan mata seperti orang linglung. Sampai perempuan itu menunjuk lukisan sketsa Dorothea yang dipajang tepat di meja yang kami tempati. Aku langsung tersedak remahan biskuit Oreo yang tiba-tiba tersangkut di tenggorokan. Seolah tidak cukup mengeksposku, Ezra kembali berujar, “Sepertinya foto remaja Kak Dorothea di ponselmu itu tidak cukup ya.”
“Berhenti bicara.” Kuangkat satu tangan di depan wajah datar Ezra yang jelas menghiraukan bendera putih yang kukibarkan untuk setiap tebakannya yang tepat sasaran. “Kalau memang serius sama Kak Dorothea, tolong tunjukkan. Jangan hanya sekadar omogan dari mulut.”
Aku dibuat tercengang dengan kalimat terakhir Ezra yang kemudian berdiri dari kursi dan menaiki tangga meninggalkan ruang underground. ‘Astaga, tahu apa dia? Aku bukan lagi orang yang bermulut besar seperti Louis, Este saksinya.’
Suara Rie Fu menyanyikan Life is Like A Boat memenuhi seisi toko roti rangkap coffee shop itu. Lupa tanggal pembukaan resmi hanyalah alasan belaka. Sejujurnya aku sengaja datang mejelang sore karena Dorothea bilang setiap malam ia akan mampir dan mentraktir kedua asistennya itu makan di restoran ramen seberang.
...Nobody knows who I really am
I never felt this empty before
And if I ever need someone to come along
Who's gonna comfort me and keep me strong...
“Ivy! Kenapa menunggu sendirian di sini?”
Begitu aku menengadahkan wajah, tampak Dorothea datang dengan fur cardigan cokelat yang kubelikan untuknya sehari setelah ia tampil di ujian menari. Ia meletakkan vanilla milkshakenya berhadapan dengan milikku dan tersenyum gugup sembari sesekali melirik asbak di sudut meja yang sudah terisi puntung sisa rokok milikku dan Jovi. “Aku tidak merokok setiap hari, tidak usah khawatir.”
“Aku lebih suka kamu mengunyah lolipop setiap sedang memikirkan banyak hal.” Jawaban Dorothea membuatku membenturkan pelan kepala saat menyandarkan tubuhku ke lukisan sketsa wanita di hadapanku.
“Dan ... aku lebih suka melihatmu sendiri tanpa Joshua,” candaku. Namun, langsung kuhentikan karena Dorothea kelihatan murung setelah aku menyebut nama kekasihnya. “Maaf, aku tidak bermaksud mendoakan--”
“Itu rencanaku,” sela Dorothea sambil menyeruput minumannya tanpa melepas kontak mata kami. Melihatku yang terlihat bingung dan terkejut secara bersamaan, Dorothea kembali berkata, “Aku akan menjalani hidup tanpa Joshua dan persepsi konyol keluarganya. Maksudku, memangnya kalau aku suka pakai jins setiap hari membuatku tidak secantik saat memakai rok atau gaun? Huh! Mereka sangat seksisme.”
Aku mempertanyakan apakah benar alasan Dorothea memutuskan masa berkencan dengan Joshua selama hampir tiga tahun karena keluarga pria itu?
Dorothea berhenti menegak minumannya dan mengatakan ia ingin Joshua mengejar Marjorie setelah tidak berhasil mengungkapkan perasaannya pada wanita itu sejak SMA, “Kamu tahu darimana?”
Dorothea mengangkat kedua bahunya, “Setiap menerima telepon dari Marjorie, Joshua tersenyum seperti orang bodoh, begitu juga saat wanita itu dan Louis bermesraan tepat di depannya. Lihat saja, keluarganya akan sangat malu putra kebanggaan mereka mencintai pembunuh dan perebut suami orang lain seperti Majorie.”
Kupendam dalam-dalam perasaan bahagiaku mendengar kabar putusnya Dorothea dan Joshua, lalu bertanya dengan wajah yang kuusahakan terlihat cemas, “Bukankah Marjorie akan semakin menderita jika kamu akhirnya menikahi Joshua?”
Dorothea bertopang dagu dengan salah satu tangannya dan menatapku intens, “Begitukah?”
“Ya ... entahlah, Marjorie seperti juga menyukai Joshua, tidak dengan Louis. Menurutku, Marjorie hanya senang karena bisa membuat Louis tunduk, dan siapa tahu ia juga sengaja medekati Louis agar Joshua cemburu?”
“Sudahlah!” Dorothea mengibaskan tangan tidak ingin mengungkit kehidupan orang-orang yang membuat Este tersakiti. “Bagaimana jika kita membicarakan dirimu saja?”
Aku tertawa gugup karena Dorothea berpindah duduk tepat di sebelahku. Kukatakan padanya tidak ada yang menarik dalam kehidupanku. Namun, Dorothea berujar bahwa aku adalah orang misterius paling menyenangkan yang pernah ia temui. “Kamu pendengar cerita yang sangat baik, tetapi tidak pernah sekali pun kamu mengekspos beban hidupmu.”
“Hal yang sudah berlalu tidak perlu diungkit,” sambarku sambil meminum tandas sisa milkshake dari gelas yang kupegang.
“Termasuk hubunganmu bersama AJ?”
“Apa?!” tanyaku shock. Bagaimana ia bisa tahu?
“Apa itu alasanmu belum mau kembali ke Michigan? Karena AJ akan menikah dengan Betty?”
“Aku hanya jatuh pada pesona luar James, Dori,” Telunjukku mengusap pipi Dorothea yang masih membalas tatapanku tanpa berkedip. “Dia tidak akan pernah bisa menggantikan keberanianmu di kedai es krim waktu itu, dan...,” Aku mengganti posisi tubuh hingga berhadapan lurus dengan Dorothea yang mulai meneteskan air mata sembari menahan isakannya dengan menggigit bibir bawah. “Permintaan maafku tidak akan bisa membayar kesedihanmu karena aku pergi tanpa berkata apa-apa, aku dan James memang sepasang pengecut yang bodoh!”
Kubiarkan hidung kami saling bersentuhan, dan isak tangis Dorothea mereda seiring menatap sayu kedua belah bibirku. “Apakah aku masih memiliki tempat dihatimu?”
“Kamu memenuhi setiap ruang di hatiku ... selalu....” Dorothea memejamkan kedua kelopak matanya, menarik tengkukku dan menyatukan bibir kami. Kedua tangannya turun bersandar nyaman di kedua bahuku, sedangkan lenganku memeluk erat pinggangnya hingga debar jantung kami saling berlomba menyuarakan perasaan cinta yang sangat berbahaya untuk dikatakan.
“Aku akan menjadi berani sepertimu, Dori.”
I want you to know who I really am
I never thought I'd feel this way towards you
And if you ever need someone to come along
I will follow you, and keep you strong
Akan tetapi, kenapa aku harus memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang perasaan yang nyata ini? Dorothea masih mencintaiku. Ia masih memilihku, dan kali ini aku tidak akan lari.
And every time I see your face
The oceans heave up to my heart
You make me wanna strain at the oars
And soon I can see the shore


 urmr9teen
urmr9teen