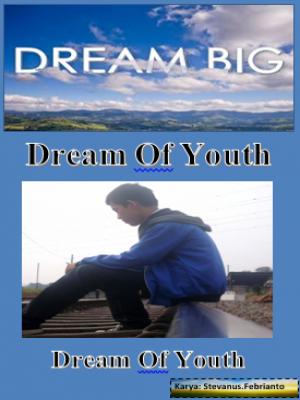Hei, bagaimana kabarmu?
Kau menoleh dari layar laptopmu dengan dahi berkerut ketika mendengar suara notifikasi posnselmu. Siapa yang menghubungimu soal pekerjaan malam-malam begini?
Kau meraih ponselmu dengan malas, sepertinya berharap itu bukan pekerjaan yang harus menguras pikiranmu di tengah malam seperti ini. Kerutan di dahimu semakin dalam ketika mengetahui bahwa itu bukan notifikasi tentang pekerjaan, tetapi notifikasi pesan instan dari akun sosial mediamu. Mungkin tidak biasanya kau mendapatkan pesan instan.
Kau membuka pesan itu, tetapi dahimu tidak berhenti berkerut selama membacanya.
“Hei, bagaimana kabarmu?
Sudah lama aku tidak bertemu denganmu.
Aku ingin melihatmu.
Aku sangat merindukanmu.”
*
Kau menghentikan langkah kakimu di depan sebuah bangunan abu-abu dengan pintu dan jendela kaca bertuliskan Echo Coffee selama beberapa detik sebelum akhirnya benar-benar melangkah masuk ke dalam. Aroma kopi yang hangat segera menyambut indra penciumanmu begitu kau membuka pintu, membuat salah satu sudut bibirmu terangkat sedikit.
“Selamat datang di kedai kopi kami.”
Kau mengangguk seraya tersenyum tipis, kemudian mengedarkan pandanganmu ke sekeliling. Kedai kopi mungil ini masih tetap bergaya minimalis tanpa banyak aksen, dengan sentuhan kayu dan warna putih di mana-mana. Satu-satunya perbedaan yang sepertinya berhasil menarik perhatianmu hanyalah koleksi buku yang semakin beragam di rak buku di sudut kedai. Ah, sepertinya kedai kopi ini tidak banyak berubah sejak terakhir kali kau datang—bersama laki-laki itu.
“Anda ingin pesan apa?” sapa pelayan ramah seraya menyodorkan buku menu begitu kau duduk di kursi. Setelah menyebutkan kopi pesananmu, kau melirik jam tangan yang melilit pergelangan tanganmu.
Sebentar lagi.
Kau mengerjapkan matamu beberapa kali. Entah apa yang kaupikirkan. Apakah mungkin kau tidak sabar? Atau mungkin kau mulai merasa ragu dengan keputusanmu untuk datang ke sini? Entahlah.
Pesananmu datang lima belas menit kemudian, menghentikan laju roda pikiranmu secara paksa. Kau menatap cangkir kopi yang masih mengepulkan uap panas itu lekat-lekat, menggenggam cangkirnya dan membiarkan kehangatannya menjalar ke seluruh tubuhmu, kemudian menyesapnya perlahan. Ah, rasa kopinya pun bahkan masih sama.
“Hei, kopi bisa merusak lidahmu.”
Kau menoleh dari cangkirmu, menatap laki-laki bertubuh tinggi besar yang berdiri dan tersenyum di hadapanmu entah sejak kapan. Tanpa banyak bicara, laki-laki itu segera menggeser kursi yang ada di depanmu dan duduk di sana, kemudian mulai memesan minuman.
Kau menatapnya tanpa berkedip. Ah, ia masih sama saja.
Sebut saja namanya Brian.
Ia cinta pertamamu yang tidak terbalas.
Kau meletakkan cangkirmu di meja, masih sambil menatapnya tanpa berkedip. Ah, ia masih sama saja. Kulit putih bersihnya masih sama. Rambutnya yang tertata rapi masih sama. Lesung pipi yang muncul dan pipinya yang sedikit mengembang saat tersenyum pun masih sama. Caranya menatapmu masih sama—sorot matanya bersinar-sinar hangat dan begitu polos, persis seperti anak kecil.
Sepertinya ia makan dengan baik.
“Bagaimana kabarmu?” tanyanya.
Kau mengangkat bahu acuh tak acuh. “Seperti yang terlihat.”
Ia menatap cangkir kopimu, kemudian berujar, “Kau masih sama saja.”
“Ada apa tiba-tiba ingin menemuiku?” Kau menatapnya lurus-lurus. “Apa aku muncul di mimpimu semalam?”
Mendengar itu, Brian menatapmu dengan mata melebar. “Mungkin?” ujarnya sambil tertawa kecil.
Kau kembali menyesap kopimu, sementara keheningan yang sepertinya terasa canggung mulai menyelinap di antara kalian selama dua menit. Hanya ada suara grinder yang sejak tadi terus-menerus bernyanyi melayani pelanggan yang datang dan pergi.
Kau baru saja akan menyesap kopimu lagi ketika tiba-tiba ia buka suara, memecah gelembung keheningan yang sepertinya terasa sangat lama dan menyesakkan. “Aku merindukanmu.”
Kau mengerjapkan mata beberapa kali. Sepertinya kau ingin mengatakan sesuatu, tetapi, entah mengapa, pada akhirnya kau tidak mengatakan apa pun.
“Aku sangat merindukanmu,” ulang lelaki itu lagi, kali ini dengan sedikit penekanan dalam suaranya. “Aku sangat merindukanmu.”
“Ah,” gumammu. “Kau bertemu denganku untuk mengatakan ini?”
Brian mengangguk.
“Kau sudah mengatakannya di pesan instan.”
Pembicaraan kalian terhenti sejenak karena minuman yang dipesan Brian sudah datang. Lelaki itu tidak segera meminumnya. Brian hanya mengangguk lagi. “Aku tahu. Namun, aku hanya ingin mengatakannya sekali lagi—langsung padamu.”
Melihatmu yang hanya diam, Brian pun melanjutkan, “Aku tahu, mungkin kau merasa tidak nyaman. Namun, aku ingin mengatakannya langsung. Aku harap, dengan begitu perasaanku untukmu bisa tersampaikan dengan lebih baik.”
“Terima kasih sudah merindukanku, tetapi kurasa kau tidak mengenalku dengan cukup baik,” sahutmu setelah berhasil menemukan suaramu kembali dengan susah payah.
Brian mengangguk lagi, tampaknya setuju dengan perkataanmu barusan. “Kau benar, aku tidak mengenalmu sebaik yang kukira.” Ia terdiam sejenak, lalu tertawa pelan, seolah sedang menertawakan dirinya sendiri. “Aku hanya mengenal sosokmu yang ada di sosial media. Aku tidak pernah, tidak ingin, tahu apa yang kausukai, apa yang tidak kausukai, bagaimana perasaanmu, apa mimpi dan harapanmu. Aku hanya mengenal dirimu yang ingin kulihat, bukan dirimu yang sebenarnya.”
“Kau juga mengabaikanku,” tukasmu seraya menyesap kopimu yang kini tinggal seperempat penuh.
Brian kembali mengangguk dan tertawa pelan, seakan baru saja menyadari sesuatu yang penting tetapi terlupakan. Ah, bahkan matanya yang tinggal segaris ketika tertawa itu pun masih sama. “Ah, ya, kau benar. Dan aku menyesal.”
Kau menatap laki-laki itu tepat di mata. Laki-laki yang sudah tak kautemui selama sepuluh tahun. Laki-laki yang diam-diam kausukai selama sepuluh tahun. Sepertinya ada banyak hal yang ingin kaukatakan padanya, tetapi kau hanya berucap pelan, “Kau tidak melakukan kesalahan apa pun.”
Brian hanya tersenyum kecil sebagai jawaban, meskipun sepertinya kau tidak terlalu yakin apakah ia benar-benar mendengar apa yang kaukatakan atau tidak. “Katanya, teknologi membuat orang yang jauh menjadi dekat, dan orang yang dekat menjadi jauh. Kurasa itu ada benarnya.”
Ia terdiam sejenak, tampak berpikir-pikir, kemudian melanjutkan, “Akhir-akhir ini aku banyak berpikir, pekerjaanku yang banyak melibatkan teknologi mungkin memang bisa membuatku terhubung dengan banyak orang, bahkan orang dari jauh. Namun, semakin lama aku melakukannya, aku merasa lelah. Aku pikir aku sudah mengenal semua orang dengan baik, tetapi ternyata tidak. Jauh di dalam hatiku, rupanya aku tetap lebih menyukai interaksi langsung—ketika aku bisa menatap matamu, mendengar suaramu, mengamati ekspresi dan reaksimu akan sesuatu, misalnya.” Brian mulai meneguk minumannya yang tak tersentuh sejak tadi, kemudian menatapmu tepat di mata tanpa berkedip.
Kau kembali terdiam, dahimu mulai berkerut, mungkin sedang berusaha mencerna apa saja yang baru saja ia katakan. Melihat itu, Brian tersenyum lagi, lalu berujar, “Aku ingin mengenalmu lebih dalam dengan benar.”
Kau menghela napas panjang, kemudian mengembuskannya perlahan. Kau baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Brian bicara lagi, “Aku tahu, aku pernah mengabaikan perasaanmu. Maafkan aku. Aku ingin memperbaikinya, tentu jika kau tidak keberatan.”
“Bagaimana jika aku keberatan?” tanyamu.
“Aku tidak akan memaksamu.” Seulas senyum lagi-lagi mengembang di wajah Brian. “Asal kau bahagia, aku sudah puas.”
Kau berusaha tersenyum sebagai jawaban.
Ah, ia masih sama.
“Jadi … bolehkah aku menyukaimu?”


 amandajgby
amandajgby