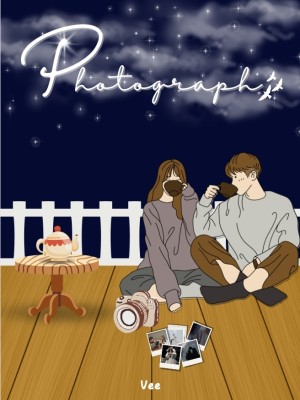“Mengapa kau begitu suka menulis?”
“Karena itu menyenangkan,” kataku sambil tersenyum menatap langit biru yang cerah.
“Bahkan ketika kau menulis akhir yang menyedihkan?” Kali ini laki-laki itu menoleh, menatapku lurus-lurus. “Apa enaknya menulis sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang jahat? Itu hanya akan membuat orang sakit hati. Mengapa kau lebih memilih menulis tentang kematian, kematian, dan kematian? Kurasa akhir yang bahagia jauh lebih baik,” lanjutnya lagi. Ekspresinya sangat serius, yang entah mengapa membuatku ingin tertawa.
“Kematian jauh lebih baik dan lebih seru.”
“Kau gila,” ejeknya. “Pembaca lebih senang akhir yang bahagia, kau tahu?”
“Dan aku menyukai akhir yang kejam.” Aku tertawa, setengah mendengus. Aku menatap langit biru, seolah meminta persetujuan pada langit yang seakan sedang tersenyum cerah padaku.
Laki-laki itu menatapku dengan tatapan tidak setuju. “Aku jadi ingin menantangmu.” Ia tersenyum misterius. Matanya berkilat-kilat, entah kilat apa itu.
Mau tak mau, aku menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jarang-jarang seorang penulis terkenal sepertiku ditantang oleh seorang dancer yang sama sekali tak mau tahu tentang novel, cerpen, dan segala tetek-bengeknya. Benar-benar menarik.
“Apa?” tanyaku dengan mata melebar ingin tahu.
Ia menyipitkan mata, senyum misterius masih tersungging di bibirnya yang kemerahan. Ia menyodorkan selembar kertas berukuran sedang padaku dan berkata, “Tulis sebuah cerita di kertas ini.” Ia melirikku sekilas sebelum akhirnya melanjutkan, “Cerita itu harus bisa diselesaikan dalam selembar kertas. Maksudku, kau harus bisa menuliskan semuanya—mulai dari awal sampai akhir—hanya dalam selembar kertas ini. Tidak lebih dan tidak kurang, harus selembar,” jelasnya. Laki-laki itu kemudian menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi taman, menyilangkan kedua tangannya di depan dada, dan menatapku. Seulas senyum menantang tersungging di bibirnya, dan matanya berkilat-kilat jenaka. “Kau setuju?”
Aku mengernyitkan dahi, memikirkan kira-kira apa keuntungan dan konsekuensi yang akan kuterima jika aku menyanggupi tantangan ini. Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, laki-laki itu menambahkan, “Ah ya, dan satu lagi, cerita itu harus berakhir bahagia. Tidak berakhir dengan kesedihan, kematian, ataupun akhir yang menggantung,” ujarnya. “Bagaimana?”
*
Aku memandang kertas berwarna putih bersih itu dengan tatapan kosong. Ya, aku memutuskan untuk menyanggupi tantangan laki-laki itu. Tak ada salahnya, bukan? Lagi pula, tantangan itu kelihatannya cukup mudah. Kau hanya perlu menuliskan sebuah cerita—dari awal hingga akhirnya—di selembar kertas ini. Sama sekali tidak sulit bagi penulis terkenal sepertiku.
Atau hanya untuk awalnya, kurasa.
Tantangan itu memang terlihat mudah, tapi nyatanya kini aku masih saja duduk diam di depan meja sambil memutar-mutar pulpenku, dengan kertas yang masih kosong sejak satu setengah jam yang lalu.
Aku menggaruk-garuk kepalaku yang sebenarnya sama sekali tidak gatal, kemudian mengembuskan napas gusar. Rupanya tantangan ini tidak semudah kelihatannya. Ide-ide yang sebelumnya memenuhi otakku kini justru menguap entah kemana. Akibatnya, kini aku hanya diam saja tanpa melakukan apa pun. Aku berusaha melakukan brainstorming untuk menghasilkan ide baru, tapi ide baru pun tak kunjung terlintas di pikiranku.
Aku menggerutu kesal dalam hati. Kenapa aku harus mengalami writers block di saat-saat penting seperti ini? Well, mungkin ini berlebihan, tapi bagiku ini sangat penting. Aku harus bisa membuktikan pada laki-laki itu kalau aku bisa membuat akhir yang bahagia, meskipun sebenarnya aku tak begitu menyukainya. Kau tahu, bagiku akhir yang bahagia tidak lebih dari sebuah akhir yang membosankan. Tidak bervariasi dan sangat mudah ditebak. Kau bertemu dengan seseorang, menyukainya, lalu kalian saling jatuh cinta, kemudian kalian memulai suatu hubungan, dan diakhiri dengan pernikahan yang membentuk keluarga bahagia. Pilihan lainnya adalah kau hidup sendiri dengan segala kesuksesanmu, menemukan orang yang kaurasa tepat untukmu, dan selanjutnya akan berjalan persis seperti alur pertama.
Benar-benar membosankan, bukan?
Aku mengusap-usap wajahku frustrasi dengan tangan dan memejamkan mata. Merasa tak ada gunanya jika hanya duduk di sini, aku memilih bangkit dari kursiku dan menuju tempat tidur. Mungkin berbaring sebentar bisa menjernihkan pikiranku, sehingga aku bisa mendapat ide baru.
Aku membaringkan tubuhku dengan santai, mencoba rileks dan memejamkan mataku.
Dan berharap inspirasi hebat dari inspiratorku segera menghampiri otakku.
*
“Kau sudah selesai?”
Aku mengangguk semangat dan tersenyum.
“Cepat sekali.”
“Hei, kau belum tahu kalau aku ini sangat hebat, hm?” aku mengangkat salah satu alisku dan tersenyum, sedikit menyombongkan diri. Kusodorkan kertas itu padanya. “Hanya selembar, bukan?”
“Mari kita lihat apakah kau melakukannya dengan baik,” ujarnya sambil membolak-balik kertas yang kini sudah penuh dengan tulisan tanganku. Tidak terlihat rasa ingin tahu sedikit pun di wajahnya. Datar. Tanpa ekspresi.
Ia menoleh dari kertas itu dan menatapku datar. “Duduklah,” katanya sambil menepuk-nepuk pelan bangku taman yang didudukinya, lalu kembali menatap kertas itu dengan serius tanpa menunggu jawabanku.
Aku pun duduk di sampingnya. Aku memejamkan mataku sejenak dan membukanya perlahan. Menikmati semilir angin yang kini sedang mencoba menggelitik wajahku di siang hari yang cerah ini. Aku menoleh ke kiri, dan kulihat sosok laki-laki itu masih duduk dengan tenang di sampingku. Matanya masih terus bergerak-gerak, membaca setiap kata, kalimat, dan paragraf yang kutuliskan, tanpa ekspresi.
Bagaimana? Bagaimana pendapatnya? Aku tidak bisa membacanya. Sama sekali tidak. Aku bersahabat dengannya selama tiga tahun, tapi tetap saja, aku masih tak mampu membaca ekspresi wajahnya yang selalu datar itu. Yang bisa kulihat hanyalah wajah datar dan tatapan mata yang tajam dan dingin. Aku tak pernah melihat ekspresi lain di wajahnya, di matanya. Tak pernah ada binar senang di matanya, raut kesedihan di wajahnya, ataupun kemarahan yang mampu membuat rahang mengertak dan otot-otot leher menegang.
Tak ada apapun.
Namun, aku senang melihatnya. Melihat ekspresi wajah datarnya. Menikmati setiap detik yang kuhabiskan bersamanya.
Aku jatuh cinta padanya.
Aku meremas-remas tanganku perlahan dan menundukkan kepala. Lagi-lagi kurasakan tatapan yang dingin dan tajam itu, serasa menusukku.
“Angkat kepalamu.”
Aku mengangkat kepalaku perlahan, dan kudapati ia menatapku dengan tatapannya itu. Wajahnya sangat dekat dengan wajahku. Bahkan aku bisa merasakan embusan napasnya yang hangat merasuk ke dalam pori-pori kulitku. Aku segera mundur, mencoba memberi jarak antara wajahku dan wajahnya, namun ia justru semakin mendekatkan wajahnya padaku, hingga akhirnya punggungku menyentuh sandaran bangku.
Sial. Aku tidak bisa melarikan diri.
Aku menggigit bibir bawahku gugup. Sialan. Sudah berapa kali aku merutuk hari ini?
“Buka matamu, bodoh.”
Aku membuka mataku perlahan. Wajah laki-laki itu sudah menjauh dari wajahku, namun ia masih menatapku dingin, tanpa berkedip dengan selembar kertas di tangan kanannya.
“Apa matamu tidak kering?” tanyaku, memecah keheningan yang hinggap di antara kami. Bodoh.
Bukannya menjawab pertanyaanku, laki-laki itu justru mengangkat kertas itu di depan wajahku dan bertanya dengan alis terangkat. “Apa ini?”
*
Sudah satu minggu berlalu sejak aku memberikan selembar kertas tantangan itu padanya. Tidak ada yang terjadi. Kami mengobrol seperti biasa, makan bersama seperti biasa, dan melakukan hal-hal lain yang biasa kami lakukan. Semuanya sama saja. Tak ada apa pun yang terjadi.
Ia bersikap seperti tak ada yang terjadi. Seolah-olah tantangan itu tak pernah ada. Padahal, jelas-jelas ia membaca tulisanku hingga selesai minggu lalu.
“Hei,” panggilku. “Menurutmu, bagaimana tulisanku?”
“Tulisanmu?” Laki-laki itu terdiam sejenak, sepertinya berusaha mengingat-ingat. “Ah, tantangan itu?”
Aku mengangguk. “Kau belum memberitahuku bagaimana pendapatmu.”
“Begitukah?” Ia menatapku dengan mata melebar dan berujar, “Tulisanmu bagus.”
“’Tulisanmu bagus,’” ulangku sambil mengernyitkan dahi. “Kau bilang tulisanku bagus, padahal minggu lalu wajahmu tanpa ekspresi, seolah-olah tulisanku merupakan tulisan terburuk di dunia.” Aku menatapnya tanpa berkedip. “Katakan padaku, apakah tulisanku seburuk itu sampai-sampai kau tidak berekspresi seperti itu?”
“Itulah ekspresiku saat menemukan sesuatu yang bagus.”
“Apa?” Lagi-lagi aku menatapnya dengan mata melebar. “’Itulah ekspresiku’ katamu? Yang benar saja,” dengusku.
“Terserah kau saja jika tak percaya,” sahut laki-laki itu lagi, kemudian beralih ke ponselnya karena ada notifikasi pesan masuk.
“Aku hanya ingin tahu bagaimana pendapatmu,” kataku, mulai sedikit gusar.
Ia hanya menggeleng seraya berkata, “Jangan terlalu penasaran, nanti kecewa.” Ia menyodorkan sebuah amplop berwarna biru pastel padaku.
“Apa ini?” tanyaku seraya membolak-balik amplop itu dengan rasa ingin tahu.
“Buka di rumah,” ujarnya singkat.
“Apa ini?” tanyaku sekali lagi. “Apakah ini berisi uang sogokan? Uang saku?”
“Pulanglah ke rumah untuk mengetahuinya.”
*
Begitu sampai di rumah, aku segera menuju ke kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Aku begitu bersemangat. Aku penasaran.
Sepanjang perjalanan pulang tadi, aku berusaha menebak-nebak apa isi amplop darinya. Aku sempat tergoda untuk membuka isinya di perjalanan, tetapi kemudian aku mengurungkan niatku ketika tatapan matanya yang tajam dan dingin itu terbayang di pelupuk mataku. Entah mengapa, aku merasa dihantui, jadi akhirnya aku berusaha keras menahan rasa ingin tahuku hingga sampai di rumah.
Kini, aku telah sampai di rumah, di dalam kamarku. Aku duduk di pinggir tempat tidur, mengamati amplop itu lekat-lekat sebelum membukanya. Kubuka amplop itu dengan sangat berhati-hati, seolah-olah isinya akan rusak jika amplopnya robek sedikit saja.
Apa ini? Apakah ini uang merah?
Apa ini?
Seseorang baru saja mengirim surat cinta untukku.
Ini semua berawal dari tantangan yang kuberikan pada seseorang. Ia menyanggupinya dan menyelesaikannya dalam waktu tiga hari. Menurutku, itu hebat. Maka, aku segera membacanya.
Seseorang baru saja mengirim surat cinta untukku. Tak banyak yang ia tuliskan dalam suratnya. Katanya, ia jatuh hati padaku. Katanya, ia senang karena ia jatuh hati padaku. Katanya, ia senang bisa menyimpan rasa diam-diam di dalam hatinya untukku.
Aku telah mengenalnya selama tiga tahun. Hingga sekarang, kami sering bersama. Aku tak pernah menduga bahwa ia akan jatuh hati padaku, bahwa seseorang sepertiku akan membuat seorang gadis jatuh hati.
Seseorang baru saja mengirim surat cinta untukku. Sebenarnya, aku tak tahu apakah tulisannya pantas disebut sebagai surat cinta. Namun, bagiku itu merupakan surat cinta termanis yang pernah kudapatkan selama hidupku. Aku akan menyimpan surat ini selamanya.
Seseorang baru saja mengirim surat cinta untukku. Sebenarnya, tak perlu ada balasan untuk suratnya. Namun, aku ingin membalasnya. Maka, aku segera mengambil secarik kertas dan menuliskan balasan ini. Aku bukan orang yang pandai merangkai kata seperti dirinya, tetapi aku ingin membalas suratnya dan mengungkapkan apa yang kupikirkan tentangnya.
Aku ingin mengungkapkan bahwa aku juga jatuh hati kepadanya. Aku ingin berterima kasih kepadanya karena telah bersedia jatuh hati kepadaku.
Terima kasih telah jatuh hati. Terima kasih.
Mr. S
Aku mengerjapkan mata beberapa kali dengan tak percaya. Aku membacanya sekali lagi. Sekali lagi. Dan sekali lagi.
Ia benar-benar menuliskan ini? Laki-laki tanpa ekspresi itu?
Benarkah?
Siapa yang akan menduga bahwa ia bisa menulis hal-hal seperti ini?
Aku membacanya lagi, dan kemudian aku tersenyum. Aku mengamati setiap goresan tangannya, caranya menuliskan kata demi kata hingga selesai. Aku mengamati caranya mengungkapkan isi hatinya.
Kurasa, ia telah berekspresi begitu banyak melalui tulisannya.
*
Seseorang memberiku sebuah tantangan kecil. Ia ingin aku menuliskan sebuah cerita di selembar kertas ini, dari awal hingga akhirnya.
Awalnya, kukira ini mudah. Aku hanya perlu memikirkan alur yang bagus dan menyusunnya hingga selesai dalam selembar kertas ini. Namun, ternyata tidak semudah itu. Ia tidak memberikan batasan waktu, tetapi tetap saja aku merasa kesulitan. Lagi pula, aku tetap ingin menyelesaikannya sebagai wujud pembuktian diri.
Pada akhirnya, aku tidak menulis cerita fiksi. Aku hanya akan menuliskan sesuatu yang sederhana. Kuharap, ia tak menganggapku curang, meski sebenarnya memang curang.
Seseorang berhasil membuatku jatuh hati. Kami telah bersama selama tiga tahun dan melakukan banyak hal. Aku jatuh hati padanya dan menyimpan perasaanku selama tiga tahun. Ia bukan lelaki tampan layaknya tokoh-tokoh dalam novel, tetapi bagiku ia lelaki tertampan yang pernah kutahu. Ia tak pernah berekspresi dan sering kali memendam semuanya sendiri. Aku jatuh hati padanya dan aku ingin menjadi teman dalam kesepiannya.
Namun, sepertinya ia tak pernah memikirkan hal-hal semacam ini. Ia hanya memikirkan apa yang menurutnya penting. Dan kurasa percintaan bukanlah sesuatu yang penting baginya, jadi kurasa ia tidak merasakan apa yang kurasakan.
Namun, itu semua baik-baik saja. Jatuh hati sendirian sudah lebih dari cukup. Menemaninya sudah lebih dari cukup.
Aku tak ingin ia mengetahuinya.
Namun, karena ini merupakan tantangan, maka ia akan mengetahuinya.
Hei, aku sedang jatuh hati kepadanya, dan aku bahagia.


 amandajgby
amandajgby