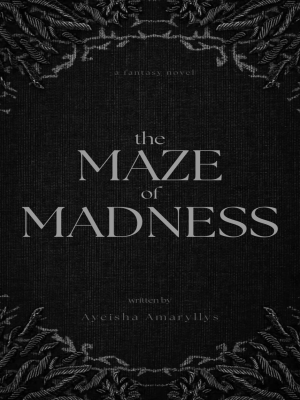Pada kasus-kasus yang biasa aku tangani, pasien akan bertindak tidak terkendali saat ia mendengar satu kata ganti peran yang menimbulkan banyak euforia di dalam halusiansi romantisme. Satu kata ganti peran yang membuat orang bisa menangis dan tertawa di saat yang sama, seolah di dalam kata ganti peran tersebut, tersimpan banyak kenangan manis yang justru menimbulkan luka besar dan dapat mengancam kejiwaan manusia. Kata ganti peran tersebut ialah kekasih atau belahan jiwa.
Tabu rasanya jika menyebut kata berbau cinta dan kekasih di depan orang-orang yang sudah berlari melewati batas kewarasannya. Umumnya saat mendengar kata tersebut mereka akan merespon dengan berteriak histeris, menangis teragis, bahkan tertawa histeria. Namun, ada juga satu pasien yang malah menyisir rambutnya rapih, memulas bedak dengan piawai dan memoles lipstiknya dengan anggun. Seolah setiap harinya ia akan berjumpa dengan orang yang begitu istimewa. Nama pasien itu ialah Sima. Entah ia berpura-pura atau tidak, anehnya rekam medis selalu menunjukkan jika kondisi kejiwaannya normal.
Kalau boleh jujur, penampilan Sima berhasil menghipnotis semua perawat dan pegawai di rumah sakit, rasa-rasanya seperti menegak segelas jus jeruk dingin di tengah musim kemarau saat melihat Sima bertindak wajar diantara teman-temannya. Sikapnya yang begitu kasmaran kadang membuat perawat gatal untuk menahan pertanyaan, siapa yang tengah ia tunggu, dan kalau sudah begitu, Sima akan menjawab dengan senyum manisnya. “kekasihku,”
“Kak,“ panggilannya yang tiba-tiba membuatku buyar terhadap lamunan. Tanganku yang sedang memegang pompa tensi terasa kaku lantaran ketahuan tengah melamun.
“Ya?” Jawabku berusaha terlihat wajar.
“Tinggal lah di sini, sebentar saja. Aku ingin menunjukkan betapa bahagiannya menunggu kekasihku datang.” Mendengar ucapan Sima membuatku tertegun. Aku mengerjapkan mataku sesaat. Apakah aku terlihat tengah patah hati, sehingga Sima menawarkan hal ini padaku?
Jujur, hubunganku dengan Edo (calon suamiku) sedang kacau-kacaunya saat ini. Namun, aku berusaha tetap bersikap profesional di hadapan pasienku yang tidak akan membantu jika tahu bahwa aku tengah patah hati. Belum sempat aku menjawab tawaran dari Sima, ponselku bergetar. Kutatap layar yang menampilkan wajah Edo, ragu-ragu kuangkat telepon, dan kata-kata pertama dari seberang telepon membuatku buru-buru berlari dari area rumah sakit, memasuki mobilku dan pergi mencarinya.
***
Jam digital di pergelangan tanganku berpedar lemah, diantara gelapnya lorong rumah sakit. Sayup-sayup gemuruh hujan berderai dengan nyaring, menciptakan resonasi yang begitu menenengkan, juga begitu sendu dan putus asa. Barangkali, hanya aku saja yang berpikir demikian. Bagi ribuan pasangan di belahan dunia ini, hujan adalah saat yang tepat untuk saling berpelukan erat, bercumbu di tengah gelapnya malam, sambil bersyukur bahwa keduanya telah dipertemukan di antara ketidak pastian dunia yang begitu kejam. Tidak seperti nasibku yang begitu hancur tak tertolong.
Hujan membuatku teringat akan banyak peristiwa yang telah aku lalui bersama Edo. Bagaimana dengan romantisnya kami berbagi payung di bawah rinai hujan, sambil tersipu malu. Bagaimana kami memesan satu cup mie instant sambil membahas masa depan, cita, angan-angan, dan tidak pernah kuduga, bahwa pembahasan terakhir kami ialah kenyataan yang selama ini Edo tutup erat dariku.
Beberapa jam yang lalu, setelah aku menerima telepon darinya, telepon yang tanpa tedeng aling-aling langsung dimulai dengan kalimat ‘Dea, ayo kita putus,’. Setelah aku langsung mengunjunginya, menanyakan alasan ia memintaku putus, dengan wajah datar tanpa merasa bersalah ia menjawab : “Aku diminta Ayahku untuk menjadi pacarmu dengan tujuan balas dendam. Perusahaan Ayahmu telah membuat bangkrut perusahaan Ayahku. Awal rencananya ialah aku menghamilimu dan mencampakkanmu, tetapi aku tidak bisa. Aku tidak tega, lebih baik kita akhiri saja hubungan kita.” Tanpa tersadar, mengingatnya membuatku menangis kembali.
Bagiku, Edo adalah segalanya. Masa depanku, harapanku, kepastian. Namun dalam hitungan beberapa menit, segala persepsi itu dapat ia putar balikkan tanpa ia hiraukan perasaanku. Sekarang aku dapat mengerti mengapa Laras menjadi gila saat ia dicampakkan oleh suaminya di masa hamil tua. Mengapa Ruminah menjadi gila karena ditinggal Bang Toyib yang tak pulang-pulang, sehingga ia harus dikejar penagih hutang. Diantara segala empati yang sedang aku resapi, aku terenyak saat teringat Sima dengan wajah jumawanya saat ia tengah membicarakan kekasihnya. Kekasih yang selama lima tahun masa rawatnya, tidak pernah terlihat.
Langkah gontaiku terhenti di depan sebuah pintu yang sangat aku kenali, kemudian kuputar kunci dan kunyalakan lampu kamar dengan lemah. Sima perlahan bangkit dari posisi tidurnya. Kuamati ia mengucek lembut matanya dengan wajah setengah mengantuk, tetapi begitu ia melihatku ia tersenyum lebar. Seolah senyumnya dapat menjadi sumber cahaya saat lampu tengah padam.
“Aku tahu, kamu akan menunggu bersamaku,” ucapnya begitu saja.
Air mata yang tadinya sudah susah payah aku hapus, kini kembali mengalir. Aku tidak bisa menahan mulutku untuk tidak mengucapkan sebuah pertanyaan besar yang selalu mengusikku. “Kekasihmu itu, seberapa kerennya ia? Ia telah membuatmu menunggu selama lima tahun, loh.” Di tempat seperti ini. Imbuhku di dalam hati.
Sima tersenyum kecil, sambil menatapku iba. Diraihnya selimut, dan dibebatnya tubuhku yang basah. “Kekasihku sangat baik. Ia membiarkan semua orang mencintainya dan ia cintai semua orang, bahkan yang tidak mengenalinya sama sekali.”
Aku tersenyum kecil. Di dalam hati malah menertawai diriku sendiri. Sebenarnya, jawaban apa yang kuharapkan dari Sima? Kupandangi dengan lekat pipinya yang merona, sementara matanya mulai berbinar. Seolah ia sungguh-sungguh tengah kasmaran dan mengaggumi kekasihnya.
“Lantas, mengapa kamu di sini? Bukankah cinta dari kekasihmu menyaktikan sampai-sampai kamu berdiam di tempat ini?” Pertanyaanku berhasil membuat cahaya di matanya perlahan meredup. Sima menelan ludahnya, mimik wajahnya terlihat getir.
“Aku pernah membulatkan tekadku, menggunakan gaun putih, bersumpah di depan altar, untuk terus mencintai dan setia padanya. Meskipun konsekuensinya aku tidak boleh menikmati banyak hal. Namun, begitu mendengar rencanaku, kedua orang tuaku menentangnya dengan keras. Mereka menyeretku kembali ke rumah. Aku terus memberontak dan bersikeras, sehingga mereka mengganggapku gila. Yah, di sinilah aku sekarang.” Seperti tersambar gledeg di tengah malam, aku melotot terkejut. Sima waras?
“Sima?” panggilku ragu, tanpa sadar kugigit lidahku. Aku bingung harus berekspresi seperti apa. Mendadak aku lupa akan segala sakit hatiku.
“Iya, saya waras,” jawabnya dengan tenang, seolah informasi yang barusan ia ucapkan adalah hal yang seharusnya wajar aku dengar. Memang benar demikian, jika aku tidak tengah menemuinya di sebuah gedung rumah sakit jiwa, di dalam kamar serba putih berukuran tiga kali tiga meter persegi.
Kuamati gerak-geriknya yang perlahan merogoh bawah bantal. Kemudian ia mengeluarkan sebuah kalung dengan banyak manik-manik. Kalung yang biasa aku ketahui sebagai rosario.“ Setiap malam aku berdoa menanti kedatanganNya. Setiap hari terasa begitu indah, karena aku tahu Ia akan datang. Ia tidak akan pernah ingkar janji.”
Kusisir rambutku yang basah menggunakan jemari. Segala informasi terbaru yang kudapat dari Sima membuatku kebingungan. Aku harus segera membawnaya keluar dari tempat ini. Ia tidak sepantasnya menetap disini. Namun bagaimana caranya? Orang tua Sima selalu berkata bahwa putrinya tidak waras, sehingga pihak rumah sakit yang semula kebingungan akhirnya memilih diam saja karena menerima uang yang cukup besar. Pihak atasan juga tutup mulut dan membiarkan Sima menetap di sini.
Sima menepuk lembut bahuku dan tersenyum. “Saya percaya, sebentar lagi kekasihku akan datang.”
“Sima,” aku menggigit bibir bawahku, kebingungan menanggapi ucapannya. Kalau memang Sima benar-benar waras, bisa jadi kekasih yang dibicarakan olehnya dan hendak ia nikahi di depan altar ialah Tuhan. Kepalaku rasanya ingin pecah memikirkan semua kemungkinan ini. Bagaimana bisa Tuhan datang, kalau Sima tidak mati?
“Tidak percaya, ya?” Aku menatap matanya, tanpa sadar aku menggeleng takut.
“Aku sudah melihat tandanya, kekasihku telah mengirim kamu untuk menemui saya malam ini. Saya percaya, kamu akan membantu saya keluar dari sini. Terimakasih,” Sima memelukku erat, air matanya tercurah deras, penuh suka cita, barang kali harapan. Sementara aku hanya bergeming kaku dengan segala rasa gentar dan bingung.
***
Jika memang mencintai akan seindah Sima yang menunggu lima tahun kebebasannya untuk menjadi seorang biarawati, barang kali semua orang akan hidup dengan penuh sukacita. Tidak akan ada lagi orang yang gila, karena tidak siap dicampakkan kekasihnya. Begitu juga tidak akan ada orang yang dianggap gila, karena terlalu mencintai Tuhan.
Aku ingat peristiwa beberapa tahun lalu, saat aku berusaha mengeluarkan Sima dari rumah sakit jiwa. Menentang dan mendebat habis-habisan kedua orang tuanya, kemudian membawa Sima ke sebuah tempat perkumpulan para biarawati. Setelah itu, kuhabiskan bertahun-tahun hidupku untuk berusaha berpikir jernih dan membandingkannya dengan Sima. Kami sama-sama patah hati, hanya saja Sima selalu bersuka cita, sementara aku sebaliknya. Pada akhirnya, aku paham perbedaan antara kisah cinta Sima dengan kisah cintaku, Laras, atau Ruminah.
Kami sama-sama jatuh cinta dan menyerahkan segalanya. Tanpa syarat. Namun yang Sima cintai sudah pasti setia dan tidak pernah meninggalkan, sementara yang aku, Laras, atau Ruminah cintai bisa jadi tidak setia dan punya kebebasan untuk meninggalkan kami. Bukankah Tuhan sudah berkali-kali bersabda bahwa Ia tidak pernah ingkar janji? Sekalipun ibu meninggalkan anaknya, Ia tidak akan pernah meninggalkan umatNya. Ia hanya meminta agar kita mampu mengikuti kehendakNya, seperti mencintaiNya dengan segenap jiwa, akal budi, dan hati.
Awalnya aku meragu, tetapi akhirnya aku memilih untuk meniru Sima. Meniru ia begitu mencintai Tuhan tanpa syarat dan menantikannya seperti seorang mempelai wanita menanti mempelai prianya. Beberapa tahun yang lalu, aku merasa begitu terpuruk kehilangan Edo. Aku merasa begitu hancur, porak poranda, sehingga takut untuk mencoba berhubungan kembali. Takut mencoba menjalani kisah cinta yang baru. Saat aku membayangkan Sima yang begitu tegar selama lima tahun hidupnya, membuatku tanpa sadar terinspirasi olehnya. Aku ingin setegar Sima.
Kembali ke saat ini, setelah berlama-lama bernostalgia sambil berdoa di depan salib, aku perlahan berdiri dari posisi berlututku. Tiba-tiba saja, seorang wanita dengan jubah putih, khas biarawati melangkah ke arahku dan tersenyum manis. Mataku terbelalak, tidak kusangka biarawati itu ialah Sima. Ia tersenyum dengan air mata mengenang dan memelukku erat.
“Semalam, saya berdoa pada kekasih saya. Saya ingin sekali berjumpa denganmu, karena saya begitu rindu. Ternyata Ia mengabulkan doa saya.” Kubalas erat pelukannya dengan mata berkaca. “Aku juga,” balasku dengan suara serak.
Buru-buru Sima melepas pelukannya dan tersenyum lebar, “Terima kasih,” ucapku.
“Untuk?” Sima menatapku heran dan bingung.
“Mengajarkan padaku, bagaiman menjadi orang kasmaran yang benar. Mengajarkanku betapa indahnya menanti kedatangan Tuhan, seperti seorang wanita menunggu mempelainya,” wajah Sima berlipat-lipat mendengar ucapanku, perlahan wajahnya menjadi cerah begitu melihat seorang anak kecil berlari dan memeluk kakiku erat. Seorang pria di kejauhan berjalan dengan napas terengah-engah seolah ia telah berlari mengitari segala tempat demi mengejar anak kecil tadi.
“Ah,” Sima tersenyum, “Ia selalu hadir, bahkan dalam jodoh, pekerjaan, dan keluarga. Aku bersyukur kamu sudah berhasil dengan sabar menanti kedatanganNya di dalam hidupmu, dan memberikan tahta ter-indah untukNya.” Sima menaikkan kedua alisnya sebelum menambahkan, “di hatimu,”.
Seolah peramal, ia tengah membaca jelas segala yang terjadi dalam hidupku. Saat mengingat peristiwa malam aku bertemu dengan Sima, aku selalu bersyukur. Barangkali, bukan aku yang Tuhan kirim untuk menolong Sima, tetapi Sima-lah yang Ia kirim untuk menolongku.
TAMAT


 CalseRatna
CalseRatna