***)
Seusai mengajar, Nasya memilih pulang. Teryata Abi di rumah, begitu juga dengan ummi. Tak biasanya. Matahari saja belum bergeser jauh dari ufuk timur. Ia mengintip jam karet yang melingkari pergelangan tangan. Masih pukul sepuluh pagi. Ragu rasanya hendak masuk, karena sepertinya tak hanya abi dan ummi yang ada di ruang tamu itu.
Pintu rumah yang sengaja dibuka lebar, membuat ia yang memang berdiri di depan deret jendela --tertutup kelambu, dapat mendengar obrolan dari dalam. Kedengarannya serius. Terselip namanya, dan itu suskses memukul dirinya sampai tersentak mundur.
Setelah mencuri dengar beberapa saat, Nasya mendapati kenyataan baru. Gerangan orang yang tengah berbicara dengan abi dan ummi, tak lain dan tak bukan adalah Azan. Suara lembut pemuda itu berulang kali membait namanya. Nasya dibuat penasaran, tapi tak tepat juga jika masuk sekarang. Sebentar lagi, ia perlu menunggu sampai waktunya pas.
"Seluruh keputusan ada pada, Nasya."
Keputusan apa? Nasya menajamkan pendengaran. Tahu-tahu jantungnya berdesir hebat. Pembahasan macam apa yang tengah mereka gelarkan, dan itu menyangkut dirinya serta Azan.
"Saya berusaha menghindari zina, Kiai. Saya bersyukur jika Kiai mempunyai pemikiran sama."
Sinyal darurat menggedor-gedor kesadaran. Apalagi yang bisa dibahas oleh orang tua, terhadap putri dengan laki-laki yang bukan mahromnya.
"Perjodohan!" pekik Nasya. Bulat matanya menyala tak terima.
Alasan macam apa yang membuat abi membelenggunya pada sebuah perjodohan? Di era modern seperti sekarang ini, kisah Siti Nurbaya agaknya tak lagi relevan. Perkara hati sudah saatnya diputuskan sendiri. Tanpa campur tangan orang lain, termasuk orang tua.
Nasya melepas sepatu flat hitam, lantas terbirit masuk ke dalam rumah.
"Assalamualaikum," salamnya.
Nasya mendapati wajah-wajah terkejut itu. Ya, mungkin saja mereka tak menyangka ia datang, karena kehadirannya tentu mengganggu perjodohan yang tengah mereka siasatkan.
"Waalaikumussalam, kebetulan. Duduk, Nak ... Abi ingin bicara," pinta Kiai Jamal, sembari menepuk ruang kosong di sampingnya.
Kiai Jamal tak duduk di singgasananya, membiarkannya kosong. Nasya pun jadi tahu, abi tidak sedang menempatkan dirinya sebagai junjungan, tapi lebih pada seorang keluarga.
"Ya, Abi."
Gadis berpakaian batik biru itu duduk. Sempat melirik ke arah Azan yang duduk di hadapannya, dia berulang kali mencuri pandang. Tak lama, karena setelanya, Azan menunduk sembari memainkan jemari tangan.
"Nak, Abi butuh persetujuan darimu."
Sebuah Perjodohan? Telak Nasya dalam hati. Tapi, perjodohan macam apa yang butuh persetujuan? Setahunya, perjodohan itu sepihak, tanpa perlu mendengar kesediaan salah satu kubu. Apakah pembahasan ini lebih dari sekadar perjodohan? Nasya dibuat susah menelan salivanya.
"Nduk, kamu ingat amplop yang kamu berikan pada Abi semalam?"
Tentu ... bagaimana bisa lupa? Berhubungan kah, amplop itu dengan kondisi tak nyaman ini?
"Amplop itu berisi pengajuan lamaran dari Ustad Azan untukmu?"
Tahu rasanya tersambar petir, sesak napas, dan merasa tak suka pada orang lain tanpa alasan? Itu yang kini membanjiri hatinya. Rasa simpati pada Azan yang sebelumnya tumbuh subur, seketika mengering. Harusnya dia tak memberanikan diri datang dengan membawa pinangan. Tak tahukah, kabar ini mengoyak harapan pada cinta yang sebenarnya ingin ia rengkuh. Cinta salah satu makhluk yang selalu terpintal di ujung doanya.
Nasya terjebak sekarang. Tak mungkin menolak lamaran yang datang. Tak mungkin meneliti sosok sempurna seperti Azan untuk mencari tabiat terburuknya. Cepat atau lambat kabar ini akan tersiar ke seluruh pesantren, sebelum kemudian terembus ke kuping Amir, dan menutup rapat pintu harapan akan cintanya.
"Bagaimana, Nasya?" Ummi menyentak Nasya dari alam bawah sadarnya.
Seutas senyum masygul ia kembangkan. Tak mungkin terang-terangan menolak. Harus ada alasan kuat agar lamaran ini batal dengan sendirinya.
"Biarkan Nasya berpikir dulu, ya?" putusnya.
Azan yang malu-malu, berubah sedih. Mungkin ia dapat membaca penolakan dari gesture serta sorot mata Nasya. Bu nyai yang sebelumnya antusias, melempar tatapan marah. Salah apabila menganggap ini sebagai penolakan. Nasya hanya butuh waktu untuk menerima semua. Menyakini, jika jalan hidupnya tak seperti yang ia dambakan. Melepas jerat pada cinta dan membiarkannya pergi, tak sehari dua hari, bukan?
"Kasih waktu untuk Nasya berpikir. Cukup satu minggu. Setelah itu, Ustad Azan akan tahu jawabannya."
Azan pun mengangguk paham.
"Biarkan kabar baik itu saya dengar dari, Pak Kiai," harapnya, lalu bangkit dari duduk.
Kiai Jamal mengikuti selanjutnya. Membiarkan Azan mencium punggung tangannya, sebelum kemudian pamit undur diri.
Setelahnya, menjadi hening. Nasya tak bergeser dari duduknya. Begitu juga bu nyai. Kecuali Kiai Jamal, yang telah menduduki kursi kebesarannya. Kini, sang abi memposisikan dirinya sebagai Kiai Jamal yang mesti dipatuhi.
Nasya terkurung pandangan dua orang penyambung hidupnya. Meski begitu, ia tak gentar. Keputusannya sudah bulat. Menyangkut hidup tak boleh asal dan gegabah.
"Satu minggu," paksa Nasya. Mau tak mau orang tuanya mesti menerima.
Sembari menunggu persetujuan, biji mata Nasya menyasar dinding bercat biru terang dengan beberapa frame foto ukuran sedang menempel berjajar--tepat dihadapannya. Deru napasnya berat. Deret potret dirinya dan Kamila ketika masih ingusan. Foto terbaru pun hanya saat Kamila lulus MAN. Pantaslah, mind-set mereka masih menganggap kedua putrinya anak kecil --yang setiap keputusan dalam hidupnya perlu dimonopoli.
Seharusnya udara tak sesesak ini. Di luar, angin semilir menerbangkan dedaunan. Sayangnya, di dalam sini, asupan udara seperti terputus. Ia terhimpit sampai tak mampu menghirup gas oksigen yang seliweran di depan cuping hidung.
"Satu minggu. Setelah itu, Nasya harus menerima pinangan Ustad Azan," putus Kiai Jamal.
Nasya membelalak tak percaya. Oh, perlu dinego lagi rupanya.
"Abi, bagaimana dengan kuliah S-2 Nasya di Australia?"
"Belum pasti juga. Jika kamu benar-benar lolos, Ummi dan Abi tidak perlu khawatir melepasmu saat kamu sudah menikah." Bu nyai pun tak ingin kehilangan peran dalam pembahasan penting itu.
Desahan itu memadamkan harapannya. Jika manusia tak bisa dibujuk, maka Allah jalan satu-satunya tempat meminta pertolongan. Bukan menampik jodoh yang datang, tapi tak ada salahnya mendamba kebahagiaan.
***
Nasya menjeda murajaahnya, ketika derit pintu terdengar keras. Kamila masuk dengan tegesah. Sedikit mengerutkan alis saat mendapati putri terakhir rumah ini masih terbalut mukena di jam santainya. Biasanya, Kamila akan mendapati Nasya telungkup di atas ranjang, dengan dada terganjal bantal dan membaca novel roman.
"Sya, tukang pijatnya datang. Cepat turun."
"Nggak, deh, Mbak. Nasya udah enakan, kok."
Kamila mendekat. Nasya menutup mushaf dan melepas mukena, lalu melipatnya kecil.
"Jangan gitu, kasihan. Tukang pijatnya sudah jauh-jauh datang ke mari."
Nasya mengalah. Membawa mukena yang terbungkus sajadah ke depan ranjang, kemudian meletakkannya di sana.
"Ada apa, Sya. Mbak lihat kamu murung terus dari siang. Padahal sejak habis isya tadi Mbak tunggu, loh. Katanya mau ikut sidak ke kamar santri putri."
Nasya menggeleng. "Lain kali aja, Mbak."
Dengan langkah diseret-seret ia melewati Kamila keluar kamar.
"Karena lamaran Ustad Azan?"
Nasya tersentak, langsung membalikkan badan.
"Dari mana Mbak tahu?"
"Abi yang cerita."
Langkah kaki mereka terhenti di anak tangga ketiga.
"Nasya nggak mau nikah sama Ustad Azan, Mbak."
Sejujurnya perasaan itu sudah menjadi gondok yang kian membesar. Ia tak bisa memberitahu siapa pun terkait ketidak sediaannya kecuali pada Kamila.
"Kenapa, Sya. Apa kurangnya Ustad Azan?"
"Mbak, ini perkara hat--"
Ucapan Nasya terputus. Suara gaduh dari arah luar menyetaknya.
"Assalamualaikum, Pak Kiai!"
Salam itu terlantun dari suara peralihan usia. Lebih dari satu. Mereka saling sahut menyahuti.
"Ada apa, ya, Sya. Malam-malam begini? Apa mereka nggak tahu toto kromo," rutuk Kamila.
"Ya, mana aku tahu, Mbak."
Nasya dan Kamila bergegas turun. Mendapati beberapa santri putra dan dua santri putri, berikut para penjaga asrama serta seksi kedisiplinan, berkumpul di ruang tamu. Berdiri di depan Kiai Jamal yang menyambut mereka ramah. Anehnya, air muka mereka seperti bersiap akan perang.
"Nah, itu Neng Nasya, kita tanya langsung saja," celetuk salah satu santri yang bertugas menjadi seksi kedisiplinan.
"Tunggu, dulu Rasyid. Jangan ngawur kamu." Azan memberi peringatan. Ia menjadi tameng keluarga ndalem.
"Ini sudah melanggar tatib pesantren, Ustad. Dosa, ini ... dosa."
"Syid, sabar dulu. Jangan nggak sopan. Ini ndalem, hormati Pak Kiai." Rasdi menarik mundur tubuh Rasyid yang terus saja merangsek hendak melewati blokade yang Azan buat.
"Aku kecewa. Bagaimana, seorang putri Kiai bisa mengajarkan hal yang nggak baik begitu?!"
"Jangan gegabah. Mana mungkin Neng Nasya mengajarkan perbuatan yang jelas-jelas dilarang agama," bela Ustad Rahmad.
Nasya yang berdiri sedikit jauh di belakang Kiai Jamal hanya mampu mengerutkan dahi. Sampai detik ini ia belum paham dengan apa yang terjadi. Namanya tersangkut. Kesalahan seperti apa yang sudah ia perbuat, ketika ia sendiri tak mengingatnya.
"Ustad Rahmad kalau nggak percaya tanya mereka berdua." Rasyid menunjuk dua santri putra di belakangnya. "Tanya, apakah mereka mendapatkan surat cinta berbahasa inggris itu atau tidak?"
"Benar, le?" Kiai Jamal sendiri yang menanyakannya.
Dua santri itu tertunduk takut. Ragu-ragu mereka mengangguk.
"Astagfirullah. Mana sekarang barang buktinya?"
Samuel maju. Dialah yang menyimpan barang bukti. Dua surat itu ia serahkan pada Kiai Jamal.
Tergesah Kiai Jamal membuka isinya, lalu membacanya cepat.
"Bagaimana ini bisa ada di tangan kalian?" tanya Kiai Jamal, sembari menghentak-hentakkan kertas itu di depan dua santri tersebut.
Suasana berubah tegang. Keheningan menjadi riuh sidang para tersangka. Entah, apa hanya dirinya saja, Nasya merasa, mata-mata bak busur panah itu membidiknya. Seakan dirinyalah dalang dari segala kerusuhan yang terjadi.
"Kok diem? Bagaimana surat ini ada di tangan kalian?" ulang Kiai Jamal, ketika dua santrinya terus bungkam.
"Mereka memerimanya saat bertemu mahrom, Kiai," sambar Rasyid.
"Meneng!" sentak Kiai Jamal. Bola matanya tak bergeser. Menatap lekat dua santri di hadapannya. "Yang aku tanya itu mereka. Tugasmu sudah cukup membawa mereka ke sini."
Rasyid pun diam. Langsung mundur beberapa langkah. Tak lagi ikut bicara.
"Siapa yang bertugas menjadi kurir?"
"Saya, Kiai." Santri berkaos hitam, bersarung sarimbit, mengaku meski terbatah.
"Siapa mahrommu?"
Santri itu mendongak. Ragu, ia melihat ke sisi kanan. Di sana berdiri dua santri putri dengan wajah tertekuk malu.
"Berbaju pink, Kiai. Dia sepupu saya."
Nasya tersentak. Santri putri yang ditunjuk itu, Rina. Ia hafal betul wajahnya, karena dialah salah satu dari tiga murid paling kritis di kelas.
"Nduk, apa kamu yang mengirim surat pada Masmu ini?" suara Kiai Jamal melunak.
Tak perlu ditanya beberapa kali seperti santri lainnya, Rina langsung menjawab tanpa ragu.
"Iya, Kiai. Saya menitipkan surat itu pada Mas Alan untuk diberikan pada Mas Dika."
Kiai Jamal mendesah kecewa. Ia kecolongan.
"Lalu, kamu, Nduk?" Kiai Jamal beralih pada santri berjilbab bunga.
"Ngapunten, Kiai. Saya khilaf. Saya menitipkan surat ke Mbak Rina untuk diberikan pada Mas Alan."
Kiai Jamal melantunkan istighfar beberapa kali. Tubuhnya terhuyung mundur. Kejadian itu nyatanya telah memukul telak egonya.
"Bagaimana kalian bisa melakukan perbuatan yang melanggar tatib pesantren!" Suara Amir menggelegar penuh amarah. Introgasi ia ambil alih.
"Saya tidak akan berani melakukannya, jika tidak ada yang mencontohkan. Saya melakukan itu karena terinspirasi dari Neng Nasya di kelas tadi siang." Rina menjawab tanpa pikir panjang.
Kali ini tak lagi satu atau dua, tapi seluruh pasang mata menyasarnya. Nyali Nasya menciut. Keberanian ditekuk mundur, lalu tergantikan rasa takut yang menjulang tinggi. Mata itu, mata yang menatapnya kecewa. Ia tak suka Amir mengulitinya layaknya tersangka.
"Jangan, fitnah!" Nasya melakukan pembelaan.
"Benar itu, Neng Nasya?" tanya Amir.
"Sumpah demi Allah, aku nggak melakukannya."
"Jangan bawa-bawa nama Allah, jika tidak mampu mempertanggung jawabkan." Setelah mengatakan cibiran itu, Amir langsung melengos.
Kesedihan serta merta singgah di hati Nasya. Makin minus saja nilainya di mata Amir. Kalau sudah begini, memetik sedikit cinta dari pemuda itu rasanya sudah tidak mungkin.
"Mau percaya atau tidak, aku tidak melakukan kesalahan yang mereka tuduhkan."
"Neng Nasya masih saja mengelak, ketika bukti sudah ada di depan mata?"
Nasya terkesiap. Laki-laki yang diharapkan mampu membelanya, malah makin menyudutkan.
"Tahan dulu, Ustad Amir. Kita tidak bisa berpegang pada kesaksian mereka berempat saja. Biar saya meminta tolong pengurus asrama putri untuk memanggil teman sekelas mereka." Azan menunjuk Rina.
Usulan yang disetujui setidaknya sebagian orang di ruangan itu, menghadirkan hawa lega bagi jantung Nasya yang siap meloncat dari gerongnya sewaktu-waktu. Kondisi tetap tegang. Semua diam menunggu kebenaran. Kiai Jamal duduk di singgasananya, bu nyai di sebelahnya. Azan mondar-mandir tak tenang. Sedang Amir, terlihat mendiskusikan sesuatu dengan beberapa santri yang bertugas menjadi petugas kedisiplinan.
Kemudian, kehadiran dua santri putri yang masuk bersama salah satu pengurus asrama menciptakan kembali keriuahan. Mendadak beberapa orang berlagak layaknya dewan yang paling berhak memutuskan dan menanyai saksi mata.
"Biar saya yang menanyai," putus Amir.
"Apakah Neng Nasya, menyuruh kalian menulis surat cinta saat mengajar di kelas tadi siang?" tanyanya tanpa mau basa-basi.
Dua santri putri itu saling pandang. Mereka mencari keselarasan jawaban. Lalu, seperti memberi kepercayaan pada santri yang lebih tahu, santri itu menggeleng mantap.
"Tidak, Ustad. Neng Nasya meminta kami membuat surat indah untuk orang terkasih seperti ibu, ayah atau mahrom kami yang lain. Memang Neng Nasya mencontohkan surat cinta yang beliau terima, tapi tidak meminta kami membuat hal yang sama."
Wajah tegang yang menggelayuti Kiai Jamal, bu nyai, Kamila dan Nasya seketika rontok. Kelegaan itu hadir bersama senandung tasbih yang memecah prasangka buruk di hati sebagian orang.
"Meski begitu, contoh seperti itu tidak bisa dibenarkan." Amir menoleh pada Nasya. Menganggap Nasya tetap bersalah, terlepas apa pun itu alasannya.
"Sekarang, kita tahu Neng Nasya, tidak bersalah. Berarti kamu yang berbohong." Tunjuk Azan pada Rina.
Gadis itu menunduk. Hukuman macam apa yang telah menunggunya selepas dari ndalem Kiai?
***


 rara_el_hasan
rara_el_hasan



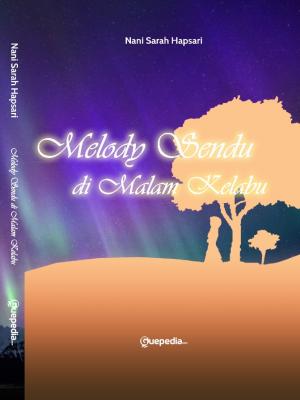






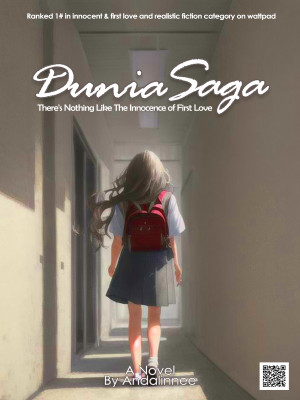
@Ardhio_Prantoko wah makasi banyak ya bang
Comment on chapter ***