Aku tidak ingin terlihat sekarat karena nyatanya tidak sekarat. Aku cuma terserang pusing dan mual. Namun, sakit ini sungguh menyiksa.
Pagi ini aku menunggu antrean di depan loket pendaftaran di klinik dokter umum. Duduk di bangku besi panjang, dan pantatku mulai terasa panas. Pusing kepala juga tambah tidak karuan. Huh! Memang wajib ya, klinik kursinya keras seperti ini? Seperti di terminal bus saja. Kenapa, sih, papa bersikeras membawaku ke dokter umum? Hasilnya pasti sama saja.
Satu hal membuatku senang. Kami bertiga; aku, mama dan papa layaknya keluarga harmonis. Bagaimana tidak, seorang anak perempuan sakit diantar ke klinik bersama mama dan papanya. Layaknya pasangan pengantin muda dengan bayinya yang terserang malaria. Namun aku bukan bayi itu, dan aku tidak terserang malaria.
Baiklah, mengapa aku berkata kami ‘layaknya’ keluarga harmonis? Itu karena keluargaku nyatanya tidak harmonis. Karena papa itu ...
“Bella Natalia!”
Ah, sebentar, aku dipanggil agar segera masuk ke ruang pemeriksaan. Nanti sajalah kuberitahu mengenai papa. Satu hal supaya tahu, sebetulnya aku malu papa dan mama turut serta masuk ke ruang pemeriksaan, diantar mereka saja malu. Aku bukan anak kecil lagi, umurku enam belas tahun.
Kami bertiga berada di dalam ruangan lima kali enam meter. Sejuk ber-AC. Papa dan mama duduk di sampingku. Papa di sebelah kanan, mama di sebelah kiri. Kami duduk berhadapan dengan dokter Haris. Mama memasang raut wajah cemas, sedangkan papa ... ah, wajah papa selalu terlihat seperti itu. Kaku. Papa menatap dokter Haris seolah ingin menusuknya dengan sebilah pedang.
“Jadi begini dokter,” kata mama memulai percakapan, “putri saya Bella, sering pusing dan mual, sakitnya datang dan pergi, tapi tak kunjung hilang. Kami sudah ke dokter berkali-kali.”
Dokter itu berdeham, lalu bertanya, “Boleh tahu sebelum ini dikasih obat apa, Nyonya?”
“Pil sakit kepala, dan obat asam lambung.”
“Apa ada keluhan lain selain pusing disertai mual?”
“Tidak ada, dok. Cuma pusing dan mual.” Mama menoleh ke arahku. “Iya kan, Bella?”
Aku merapatkan bibir dan menganggguk.
Dokter Haris sejenak memandang ke arahku dari balik kaca mata hipermetropi-nya. Beliau seumuran papa, tapi papa terlihat lebih gagah dibandingkan dokter Haris. Papa berbadan tinggi, tegap, sedangkan dokter Haris tampak lebih kurus dengan balutan jas putih.
“Kita periksa dulu ya, silakan merebah di sebelah sana.”
Dengan kikuk aku berjalan ke ranjang besi berlapis busa. Merebahkan badan, lalu menatap langit-langit. Dokter itu mengukur tekanan darah, kemudian memeriksa detak jantung. Perutku diketuk-ketuk beberapa kali.
“Bagus, tekanan darahnya normal, detak jantung juga baik.” Dokter itu mengalungkan stetoskop di leher lalu berjalan ke arah meja.
Aku bangkit, merapikan t-shirt lengan panjang biru yang kusut, lantas kembali duduk di kursi semula.
“Apakah putri Nyonya sudah melakukan scanning?” tanyanya kemudian.
“Sudah dok, tapi kata dokter yang memeriksa waktu itu, semua organ dalam Bella tidak ada masalah.”
“Sudah konsultasi masalah psikis?”
“Belum dokter.”
Dokter Haris berdeham lagi. “Mohon maaf sebelumnya Nyonya, dan Tuan ... begini, saran saya sebaiknya dilakukan pemeriksaan secara psikis. Putri Anda ini kemungkinan terkena gangguan somatoform. Ganguan fisik seperti nyeri, pusing, mual, namun medis tidak dapat menjelaskannya secara adekuat. Ini berhubungan dengan kondisi psikologi putri Anda. Jadi, Nyonya dan Tuan sebaiknya membawanya ke psikiater supaya bisa dicari latar belakang kondisi psikologi putri Anda.”
Telinga papa memerah. Papa menyilangkan kedua tangan di dada, dan menyeletuk, “Pusing kepala kok disuruh ke psikiater, bagaimana dokter ini?!”
“Pah!” Mama berseru lirih.
Dokter Haris tampaknya tersinggung.
Inilah yang ingin kukatakan. Papa itu merasa paling tahu. Papa itu pintar, tapi pintarnya kelewatan. Mama tidak sanggup seandainya harus berdebat dengan papa, tidak ada gunanya. Mama lebih banyak mengalah jika papa berbicara bernada sarkastik. Namun, kesabaran mama juga ada batasnya. Akhir-akhir ini mereka sering bertengkar mengenai penyakitku, karena papa selalu menolak saran mama untuk membawaku ke psikiater.
“Putri saya ini normal, dok, cuma pusing dan mual masa dibawa ke psikiater, bagaimana sih, dokter pikir putri saya kurang waras?”
“Pah, tolong jaga bicaramu!” Mama kembali memperingatkan papa.
“Maaf Tuan, saya cuma menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan mengenai putri Anda.”
Papa bangkit dari kursi. “Sudah, ayo kita pulang. Kita cari dokter lain saja!”
Aku memegang lengan mama dan tak berani berbicara apapun. Telapak tangan terasa dingin dan gemetaran. Sementara papa melangkah ke luar lebih dulu, membuka pintu dengan kasar.
Sebelum aku dan mama meninggalkan ruangan dokter Haris, mama mengucapkan sesuatu. “Terima kasih dok, mohon maafkan suami saya.”
“Tidak apa-apa Nyonya, tapi sebaiknya Nyonya memikirkan betul-betul kesehatan putri Nyonya.”
***
Ketika kami kembali ke mobil, aku menemukan ponsel tertinggal di jok belakang. Notifikasi kotak pesan Whatsapp penuh dari Vanesa. Aku membaca satu per satu sembari mengendurkan otot-otot leher yang tegang pada sandaran jok.
Today at 06:20
Vanesa: Woy bangun! Jangan molor mulu!
Vanesa: Ke Senayan, yuk!
Vanesa: Sori, gue baru ngasih tahu sekarang, soalnya tiba-tiba aja gue pengen refreshing.
Vanesa: Pengen olahraga ... sekalian cuci mata, hihi.
Vanesa: Siapa tahu ketemu cowok cakep.
Vanesa: Lo siap-siap sekarang oke, gue samperin. Soalnya agak siang gue sama mama mau pergi.
Vanesa: Bella ... ?
Vanesa: PING!
Vanesa: PING!
Vanesa: PING!
Aku menghela napas berat. Jari telunjuk mulai menari di layar ponsel 4,7 inches, membalas pesan Vanesa.
Aku: Sori Nes, gue habis dari klinik. Hape gue ketinggalan di mobil, nih baru aja keluar.
Tidak butuh waktu lama Vanesa membalasnya.
Vanesa: Bella, Lo sakit lagi?
Aku: Cuma pusing.
Vanesa: Tapi lo nggak perlu nginep di klinik kan?
Aku: Nggaklah, udah gue bilang ini lagi di mobil, mau pulang.
Vanesa: Gue ke rumah lo sekarang, ya?
Aku menoleh ke papa dan mama sebelum membalas. Mereka masih memasang wajah masam. Lantas mengetik lagi.
Aku: Nggak usah Nes, gue baik-baik aja kok, mama sama papa lagi runyam.
Vanesa: Mereka berantem lagi?
Aku mengetik balasan, tapi menghapus lagi. Pesan terakhir Vanesa kuabaikan. Kepala makin pusing jika membahas soal papa dan mama. Mendengarkan mereka berselisih paham saja membuatku muak.
“Pah, mama berpikir apa tidak sebaiknya les Bella dikurangi saja, dua kali seminggu sudah cukup, kasihan Bella sering pusing.”
“Bella baik-baik saja,” balas papa ketus, “dia cuma pusing kepala biasa. Buktinya hasil check-up Minggu lalu tidak ada apa-apa, semua bagus.”
“Justru itu Pah, mama memikirkan kata dokter Haris.”
“Sudahlah, tidak usah pikirkan kata dokter itu, nanti juga sembuh seperti biasanya. Bella akan tetap les privat lima kali seminggu. Bella itu harus pandai seperti papa, kelak Bella akan menjadi dokter supaya punya masa depan cemerlang.” Papa memutar kemudi ke arah kiri. “Omong-omong, mulai besok guru privat Bella akan papa ganti.”
“Ibu, Saras?” Mama menegaskan.
“Memangnya siapa lagi kalau bukan dia? Papa lihat cara Ibu Saras mengajar sangat kurang, papa akan ganti dengan kenalan papa.”
“Tapi Pah, Ibu Saras kan sudah dekat dengan keluarga kita, dia mengajar Bella sejak Bella SMP.”
“Makanya, Ibu Saras harus diganti. Dia tidak cocok lagi memberikan materi pelajaran SMA pada Bella. Bella harus dibimbing oleh guru SMA atau guru dari bimbingan belajar yang lebih profesional.”
“Kalau begitu, biarlah Bella les di bimbingan belajar saja, Pah. Paling tidak, Bella bisa berteman dengan yang lain.”
“Bella akan tetap les di rumah. Lagipula Bella kan bisa tetap berteman dengan Vanesa, putri Pak Sasongko itu. Papa tidak perlu khawatir Bella bergaul dengan putri keluarga terpelajar dan orangtuanya punya background yang jelas. Papa mengenal baik keluarga mereka. Zaman sekarang pergaulan anak remaja sangat mengkhawatirkan, Mah. Kau lihat sendiri kan berita kriminal di televisi? Harusnya kau lebih tahu bagaimana mengurus Bella, apa yang terbaik buat dia.”
Seketika mama diam. Sementara Aku hanya bisa mendengarkan mereka beragumentasi. Kalau diizinkan membuka mulut, akan kuberitahu mereka tentang keinginanku. Memberitahu papa bagaimana cara keluarga Vanesa menikmati hidup. Papa bilang mengenal keluarga Vanesa dengan baik? Huh, padahal papa tidak tahu cara mereka menikmati libur Natal bersama keluarga. Papa tidak pernah melakukan itu. Namun aku ingat, tradisi dalam keluarga ini seorang anak tidak boleh beragumen dengan orangtua. Maka, lebih baik aku diam.


 haribawa2018
haribawa2018








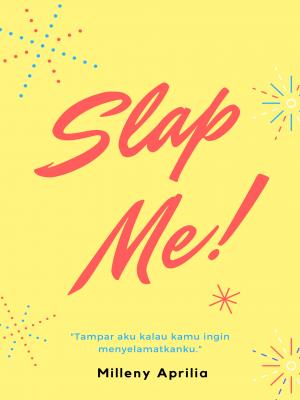





yang nyangka bella hamil silakan balas komenan saya
Comment on chapter Chapter 1