Gawain tak henti-hentinya berpikir ingatan macam apa yang sudah hilang. Dalam versi ingatannya kali ini, tak terbersit sepenggal memori apapun tentang perjalanannya bersama Abi melintasi Nixie. Yang ia ingat, ia bersama karavan dengan tiga Tigra—yang tak lain adalah abdi terpercaya Sofia yang hendak melapor apa yang terjadi di Grende—dan berhenti di desa Tulious seorang diri. Tambahannya, dalam versi ingatan kali ini, ia mengenal Abi dari Kurish, bukan dari siapapun. Kala itu, ia hendak memandangi bintang-bintang di langit laut, alhasil ia nekat memanjat tiang layar dan sampai di puncak. Malam itulah yang menjadi kesempatan Gawain bertemu dengan Abi.
Gawain ketakutan. Itu jelas bukan versi yang cocok dengan jurnalnya. Dan ia menyadari bahwa hilangnya ingatan kali ini karena kelalainya dalam bertindak kemarin.
Dalam buku jurnalnya, ia dengan gamblang menjelaskan bahwa ia pernah melintasi Nixie dengan bantuan seorang pengembara cerdik bernama Si Pembawa Lentera. Bagaimana ia bisa lupa? Sungguh, eksperimen nekatnya dengan mengendalikan darah untuk melapisi perisai secara terus-menerus guna menetralisir mantra Marlin secara absolut benar-benar menguras ingatannya. Memang benar ia tak terluka bahkan segores pun, tapi bayaran yang diminta cukuplah besar!
Peluh dingin kini terlihat berkucur di dahinya, meski tangannya yang gesit sedang merakit perangkap di salah satu pohon. Pikirannya berkalut. Apakah ia bisa mengingat Abi di kelak nanti?
“Rupanya kau ragu, Agwain,” tukas Ariesh dari belakang. Rupanya ia sudah selesai merakit perangkap dari mekanisme rahang perangkap beruang sederhana dari taring singa laut. Rumit, bahkan Gawain belum tentu bisa membuatnya seorang diri. Pemuda itu hanya mengandalkan lubang, mekanisme tali, atau rune. Ia tak berbangga diri dengan perangkapnya yang amat sederhana, tapi entah mengapa, keserhanaan pikirannya nantilah yang berhasil menguak misteri.
Gawain berusaha tersenyum agar Ariesh tak khawatir, tapi Ariesh lebih tahu senyum palsu Gawain hanya dari bagaimana cara Gawain menyudutkan bibirnya sendiri agar tampak manis. “Tidak apa-apa, Ser Ariesh, tidak apa-apa,” balasnya sembari berpaling dari Ariesh.
Tangan Ariesh segera menyambar Gawain dan mendorong bahunya ke pohon terdekat. Gawain tak berkutik, ia memang kehilangan semangat darinya. Ariesh menatap nanar pemuda itu, dimulai dari ujung rambutnya, raut wajahnya yang menyedihkan dan penuh pikiran, jari manis kirinya yang kini ditemani sebuah cincin, lalu pakaiannya yang berupa jubah abu-abu yang ringan dan sederhana, dan tak lupa aura yang terpancar. Ariesh tak tahan lagi, ia sudah gemas menanyai Gawain perihal apa yang terjadi. “Apa yang mengganggu fikiranmu, anak muda.”
Gawain diam, padahal dia kemarin bilang kepada Ariesh bahwa diam tak menyelesaikan masalah. Ia bicara sejenak dengan Florence dan meminta solusi dari berbagai pertimbangan. Dan akhirnya, ia mendapati satu solusi: ia akan separuh jujur pada Ariesh.
Ada beberapa pertimbangan mengapa ia lebih percaya Ariesh daripada Abi, misalnya saja ikatan antara Rei dan Ariesh yang lama, sementara bila ia jujur pada Abi, apa yang akan Abi lakukan? Mungkin saja ia akan membujuk Gawain untuk lari ke ujung dunia, melupakan segalanya dan memulai hidup baru dengan menghabiskan sisa umur abadi mereka. Abi pasti melakukan itu, karena di mata Abi, Gawain adalah orang kedua yang dapat ia kasihi dan percayai setelah ia dikhianati oleh kawan lamanya sendiri.
“Paman tahu sendiri bukan, bahwa setiap kekuatan pasti punya bayarannya sendiri. Pernahkah paman membayangkan bahwa ingatan kita adalah bayarannya?” tanya Gawain di tengah kesunyian hutan.
Ariesh tak butuh waktu lama untuk menyadari maksud Gawain yang gamblang semacam itu. Ia mendelikan matanya, tak percaya bahwa Gawain melakukan hal segila itu. Tapi apa alasannya? Ia tahu bahwa Gawain bukanlah orang yang ingin berkuasa; ia bukan pemuda yang menginginkan kekuatan untuk hal sesederhana itu, pasti ada hal lain seperti cinta untuk istrinya? Entahlah, Ariesh tua berusaha menerka-nerka.
Ariesh yang bijaksana bungkam, ia tak menemui solusi atau terobosan macam apapun di kepalanya karena ia tak pernah mengalami sendiri hal semacam itu. Akhirnya, ia memilih bertanya, “demi siapa kau melakukan semua ini?”
“Rasa sayang pada saudari dan istriku, serta kekerabatan erat dengan seluruh petualang yang pernah kutemui maupun yang belum.”
Dari sana, Ariesh tahu bahwa sang pemuda sedang bertarung dengan seisi dunia yang menjadi taruhannya. Ia tak gentar bila sang pemuda gagal, malahan ia bangga menyongsong kematiannya, atau bilamana Gawain berhasil maka ia akan hidup dengan rasa syukur yang tak henti karena Dewa dan Dewi masih mengizinkannya untuk sekali lagi menikmati bumi. Lantas, bagaimana dengan sang pemuda? Apa poin penting dari hidupnya selain pengorbanan?
Tidak ada yang menjawab di antara keduanya, pun toh, Gawain tak mengharapkan sebuah jawaban dari Ariesh, ia sudah tahu bahwa kebijaksanaan Ariesh kurang cocok untuk apa yang ia hadapi. Ia menunggu keheningan dunia sajalah yang menjawab semua pertanyaan. Gawain memilih pergi ke posnya yang berada di ujung bukit dan berdiam diri sembari mengelap pedang dua tangannya dengan kain yang telah dicelup dengan sebuah racun berbau manis dari sejenis katak. Ia tidak pernah tahu ada katak yang memiliki racun amat mematikan meskipun ia lama belajar ilmu alkimia. Baru kemarin ia tahu ada katak sejenis itu dari Florence dan menyarankannya sebagai strategi melemahkan Penyihir Abadi dengan cara sedemikian rupa.
Bertarung langsung dengan Penyihir Abadi bukanlah opsi yang tepat menurut Gawain. Kemungkinannya untuk menang tidak sampai lima puluh persen, itupun dengan segala kekuatan Florence. Caranya memang licik, tapi bukankah itu sudah menjadi ciri khasnya? Bukankah cara ia mengalahkan Oberon dengan cara yang lebih kotor? Sang pemuda tertawa kecil dengan betapa buruknya dia.
Perbincangan di antara keduanya berakhir. Ariesh memilih kembali ke kota, menyampaikan pesan Gawain kepada komplotannya untuk melanjutkan perjalanan menuju Pegunungan Berg yang terletak di seberang utara, melintasi laut dengan jarak tempuh dua hari. Berhubung kali ini adalah musim gugur, semua kapal yang membawa pasokan makanan akan ramai hilir-mudik dari Pelabuhan Nivas di Berg dan sebaliknya, itu berarti mereka beruntung sekali datang kali ini.
Saat Ariesh keluar dari kawasan Grende, dari kejauhan ia sudah mendapati dua Tigra menyusulnya dengan menaiki seekor kuda. Si hitam Panther turun, ia menyapa dan mencoba bicara dengan Ariesh. Bahkan sebelum Panther membuka mulut, Ariesh sudah menjawab, “tidak ada gunanya membujuk pemuda itu, dia keras kepala.”
“Bagaimana Anda yakin dengan sifat Gawain?”
Ariesh sudah tahu sosok Agwain punya samaran nama yang lain, tapi aneh rasanya bila samaran nama itu hanya dibalik antara huruf pertama dan kedua. Ia merenung sejenak, memikirkan jawaban yang tepat dan memuaskan kepada keduanya—terutama jawaban untuk memuaskan istri Gawain. “Aku tahu dia lahir di sini dan besar di sini,” jawabnya enteng.
“Lahir di sini dan besar di sini?” tanya Felice meyakinkan.
“Ah, dari caramu bicara, kalian masih belum mengenal Agwain bukan?”
Keduanya saling pandang, makin bingung dengan latar belakang yang disembunyikan oleh Gawain. “Jika Anda berkenan, maukah Anda bercerita tentang pemuda itu?”
Dengan mendahului keduanya, Ariesh mulai bercerita sembari menyeberangi jalanan sepi dipinggir ladang gandum yang masih coklat tua dan pendek. Angin dingin musim gugur mulai bercampur, itu artinya musim dingin mungkin datang lebih cepat dari perkiraan, dan itu menjadi peringatan bagi pemasok makanan agar mereka segera menyelesaikan muatan-muatan pangan yang akan dikirm.
Felice maju menyamai langkah Panther. Untuk kali ini, Felice adalah orang yang cocok untuk berbincang dengan Ariesh. Selain karena dia adalah wanita, Felice lebih paham bahasa lokal dan mudah mengontrol jalur perbincangan. “Jadi, darimana Aku harus bercerita?” tanya Ariesh memecah keheningan di antara ketiaganya. “Jangan terlalu berharap padaku, aku sendiri juga tidak tahu detail Agwain.”
“Baiklah,” balas Felice dengan anggukan. Ia menarik napas, lalu menghembuskannya perlahan. “Aku akan menanyakannya sekali lagi, Ser Ariesh. Bagaimana Anda yakin bahwa Gawain lahir dan dibesarkan di sini?”
“Separuh intuisi, separuh perkiraan. Kalian tahu Ser Rei?”
“Ah, si juragan penguasa separuh pasar Junier,” Felice berusaha mengingat-ingat tentang beberapa potongan cerita yang kemarin ia dengar dari berbagai orang saat ia mengumpulkan informasi. Cukup banyak, tapi tidak terlalu berguna. Dengan separuh mengingat, ia melanjutkan, “banyak orang bilang dia adalah pria yang baik. Ia bahkan pernah menyelamatkan Junier di tengah krisis sekaligus membangun lagi usahanya di saat kosongnya kas perusahannya sendiri.”
“Hebat bukan? Sekarang bayangkan, di balik semua kejadian itu hanya ada seorang pendeta muda yang membangun momentum agar hal itu terjadi. Itulah Agwain Septim.”
“Septim?” tanya Panther dan Felice bebarengan.
“Iya, dia berasal dari keluarga Septim, aku yakin akan hal itu. Bahkan ia punya surat serta harta sah atas nama dirinya. Jika kau tanya apakah hal ini benar, lebih baik kalian tanyakan saja padanya—oh hei, bisakah kalian membayangkan seorang pendeta berbohong? Pendeta muda yang memilih namanya agar dilupakan atas jasanya yang tak terhitung pada Junier? Ia amat mencintai kota ini, bahkan sering kali kulihat dia pergi ke sebuah kuil tua di bukit barat pada saat itu, berdoa tanpa suara dan menunduk lama di atas sepasang makam yang berjajar. Mungkin keluarga lamanya sebelum ia diadopsi oleh Septimus.”
Felice termenung, kembali berusaha mengingat. Kemarin malam, ia bertemu dengan dua orang penjaga makam di sebuah kedai pinggir kota. Penjaga makam itu ceria, hingga membuat Felice tertarik untuk bicara dengan keduanya. Ketika malam mulai larut dan gelas-gelas mulai menumpahkan isinya di meja, barulah mereka mau bercerita tentang pengalaman mereka.
Darah tigra Felice memang sanggup menahan pengaruh alkohol meskipun hanya sedikit, sehingga ia belum cukup mabuk untuk berdelusi tentang cerita yang ia dengar. Dari kedua pengakuan mereka, seorang menyatakan hal aneh, yaitu ia melihat seseorang bangkit dari kuburnya sendiri.
“Demi sumpahku sebagai penjaga makam pada Than’atos, aku melihat sendiri malam itu mayat putra keluarga Orkney yang kukuburkan bangkit dan menggedor-gedor pintu ku—”
“Arggh, kau mulai lagi Jun’ait, tidak ada hal semacam itu!” balas kawannya dengan membanting gelas logam penuh dengan anggur dingin.
“Jangan bilang kau lupa hasil investigasi Nona muda Rei! Ia mampu mengumpulkan banyak bukti bahwa insiden ini memang berkaitan dengan mayat! Mayat berjalan! Juga jangan lupa kabar dari Grende, Nixie, dan Larista! Semua ini berkaitan, Grey!”
“Terserah apa hasil investigasi, tapi bukankah semua ini berawal dari si pengkhianat Lothius itu bukan?”
“Kau masih saja menyalahkan pria malang itu? Bukankah sudah terbukti bahwa ia tak sepenuhnya bersalah? Pengadilan tinggi menyatakan bahwa mungkin ia dibawah pengaruh Penyihir Abadi, bukan sepenuhnya bekerja sama dengan Penyihir Abadi!” seru Jun’ait dengan menggebu-gebu, tapi ia mulai sempoyongan dengan tubuhnya sendiri lantas rubuh, disusul dengan temannya yang juga terjerembab ke bawah kolong meja, meninggalkan Felice yang sedari tadi mendengarkan dua orang pemabuk.
Felice mulai menjernihkan pikiran. Ia percaya dengan seorang pemabuk karena alkohol bakal mencabut saraf kesadaran mereka, membuat mereka jujur dengan hatinya. Dengan mengaitkan antara cerita dua orang mualim yang mabuk berat dengan pengakuan Ariesh, ia menyimpulkan satu hal mengapa Gawain menyembunyikan identitasnya: yaitu karena ia berasal dari Septim dan memiliki ikatan dengan Orkney.
“Agaknya, semua ini jadi masuk akal,” batinnya, “Penyihir Abadi mengincar satu-persatu Petinggi Asosiasi, dimulai dari Master Lothius lalu Master Septim. Kemungkinan besar, Gawain adalah tangan kanan Master Septim sendiri sebagai solusi dari krisis semacam ini. Dan tentunya, ia tak akan mudah membeberkan rahasianya bukan?” Kesimpulannya separuh benar, tapi itu cukup untuk meyakinkan Sofya nantinya dalam laporan agar ia tak menelusuri lagi rekam jejak Gawain.
“Jujur saja, seharusnya aku tak membicarakan ini dengan orang lain. Aku sendiri bahkan tak mengadukan Agwain ke Ser Rei sebagai penyelamat Junier yang sesungguhnya, bahkan Aku segera mundur setelah urusanku dengan beliau usai. Tapi, Aku rasa kalian adalah kawan yang cocok untuk ini, terutama Agwain kali ini membawa istrinya secara langsung.”
Felice dan Panther saling lirik satu sama lain. Pandangan mereka seolah-olah mengatakan, “bahkan istrinya sendiri tak tahu akan hal ini!” Felice tentunya geram, bukan hanya sebagai kawan namun juga sebagai kaum wanita. Bagaimana Si Pembawa Lentera bisa percaya pada orang yang bahkan tak bercerita tentang dirinya? Seyogyanya, mereka berdua akan menceritakannya pada Abi agar mencairkan suasana.
“Omong-omong, semoga perjalanan kalian selalu dikaruniai keselamatan. Perjalanan ke Berg tidaklah sulit, tapi ketika sampai di Berg kalian akan merasakan musim salju yang sesungguhnya!” ujar Ariesh yang bertepatan dengan sampainya mereka di gerbang kota. Ariesh yang rasa-rasanya masih enggan untuk kembali memilih berbalik dan mulai berbincang dengan penjaga yang lain, meninggalkan Panther dan Felice.
Tanpa mereka sadari sedari tadi, sebenarnya ada seseorang yang semenjak tadi mengawasi mereka dari salah satu sudut gerbang. Ia bersembunyi di ujung koridor terdekat dari jalan, duduk tenang dengan memegangi busur. Diam dan tak terdeteksi sama sekali dalam mengintai mangsa, terlatih untuk bersabar dan seorang pengamat yang jeli. Abi yang sedari tadi memang tak bisa mendengar, tapi hanya dari gerakan mulut ia tahu apa yang diperbincangkan. Ia menunggu hingga Felice dan Panther kembali ke penginapan, dan lantas ia pergi menggeluyur ke Grende tanpa seorang pun ketahui.
Tidak perlu waktu banyak, ia bisa tahu keberadaan Gawain di tengah luas dan rimbanya Grende. Ia berjalan tenang, ditemani dengan sepasang peri hutan yang menari dan bersiul di dua sisi pundaknya. Begitu melihat Gawain yang sedang duduk di atas tumpukan batu cadas sembari mengasah pedangnya, ia menghentikan langkahnya, mendongak menatap punggung Gawain dari belakang.
Hening, tidak ada dari keduanya memulai pembicaraan. Meski Gawain sudah tahu siapa yang datang, ia enggan bicara. Ia merasa bukan saatnya yang tepat untuk bicara dengan sang istri, ia terlalu fokus pada buruan yang mungkin saja di depannya. Lagipula, kebanggannya sebagai pria membuatnya tak mau berhadapan dengan tangan kosong. Ia berniat bicara setidaknya ketika ia berhasil menebas target mereka kali ini.
Abi yang dirundung rasa kegelisahan gadis akhirnya angkat bicara, “apa yang kau mau, Gawain?”
Gawain mengehentikan pekerjaannya, ia menaruh pedang dan batu asahnya di sebelah, diam lantas mendongak menuju langit seolah berdoa memohon jawaban yang memuaskan. Tapi ia tak menemuinya.
Abi memanjat cepat batuan cadas itu dan duduk di sebelah Gawain. Dengan mencoba berwajah manis, ia melirik Gawain yang selalu berparas dingin dan serius. Itu orang yang ia kasihi karena kelemahan hati di balik wajah datarnya. Sekarang ia bertanya-tanya, “apa tujuan Gawain untuk memenangkan pertandingan? Apa yang benar-benar ia raih? Apa yang benar-benar ia inginkan?”
Semuanya semu bagi Abi, mulai dari tujuan Gawain untuk memenangkan pertandingan. Ia pernah bilang bahwa ia hanya ingin hidup damai, tapi dengan tatapan yang hampa sekosong angkasa membuat Abi meragukannya. Ia sungkan untuk bertanya, tapi kali ini hati sang gadis dan dorongan intuisinya sebagai sang istri membuat ia berkata sekali lagi, “apa yang kau mau, Gawain?”
“Hidup, hanya hidup saja, istriku. Tidak ada yang lain.”
“Apa membunuh yang lain dapat menjamin hidupmu?”
“Tentu saja, untuk hidup, semua makhluk di dunia ini harus membunuh yang lain agar hidup.”
Ini sudah kesekian kalinya Gawain berkata hal sedemikian rupa, seolah tidak ada jalan yang lain bilamana tujuan Gawain hanyalah untuk hidup. Abi tahu bahwa beban pikiran Gawain banyak, salah satunya saja adalah keberadaan Florence yang bahkan belum tertorehkan, atau bagaimana kekuatan yang akan dihadapi lawan berikutnya. “Apakah ada kemungkinan mereka akan muncul di Junier?”
“Ada—”
“Lantas mengapa kau tetap tinggal dan menyuruh kami unt—”
“Aku bilang ada! Bukan pasti, Abi!” Gawain membentak, “terlambat satu hari saja dapat berakibat fatal! Bayangkan bila kita terlambat satu minggu! Semuanya akan berantakan! Bila saja yang nanti muncul di sini bukanlah salah satu dari mereka, kita tidak mengulur waktu terlalu banyak! Apa kau mengerti?!” Gawain bangkit dari duduknya, memunggungi Abi seraya bergumam pelan, “meskipun tinggal abu atau namaku kelak yang akan tersisa setelahnya, kalau tak salah kau pernah bilang begitu bukan?” dengan langkah sedikit terseok, sang pemuda meninggalkan istrinya.
Semenjak itu, keduanya mempertanyakan perasaan masing-masing.
***
Batang hidung Gawain bahkan tidak muncul ketika keberangkatan Abi dan yang lain. Abi tidak sedikitpun menoleh ke belakang. Semalaman penuh ia memikirkan apa yang ia bicarakan dengan Gawain. Apa ia memang benar menyukai Gawain dan sebaliknya? Apa Gawain membenci dirinya karena seorang Penyihir Abadi? Atau bagaimana? Sikap dingin Gawain amatlah berlebihan!
Tapi pikiran Abi berubah seketika ia membalik tubuhnya, tak sengaja melempar pandangan begitu Marlin mengajaknya bicara. Dengan nada halus, ia berkata, “lihatlah ke ujung atap kuil, lebih tepatnya di balik cerobong. Dengan matamu, kau bisa melihatnya bukan?”
Jauh, mungkin sekitar dua mil di atas bukit sana, seseorang sedang mengintip dari balik cerobong. Tidak terlihat, bahkan Panther dan Felice tak mengetahui bahwa setidaknya ada sepasang mata yang sedang mengawasi sedari tadi, tapi Marlin tua yang bijaksana tentunya tahu bahwa Lothius muda pasti memberikan salam perpisahan, entah bagaimana caranya.
Pemuda itu tersenyum samar, namun sedih karena sekali lagi ia menyakiti Abi. Apakah ia mampu jujur kepada perasaannya? Apakah ia terbutakan? Apakah ia malah mengecewakan? Ia ingin tahu itu.
Abi tersenyum dan membalasnya dengan kecupan selamat tinggal, sayang Gawain tak menyaksikannya secara langsung. Kapal mulai menarik jangkar dan menarik tali temali yang terikat rapi di palka pelabuhan, lalu selembar tirai berupa layar putih turun cepat. Langsung saja, angin yang bersahabat melambungkannya, meniup jauh kapal itu agar menjauh dari pelabuhan terujung di barat laut Unomi. Disusul sorak sorai dari beberapa pelancong dan pengangguran yang ketepatan saja duduk menunggu umpan ditarik mangsa yang kelaparan, sama laparnya dengan sang pemburu yang lemas melambaikan tangannya sedari lelah pulang membawa tangkapan berupa tiga ekor hiu.
Dengan terbitnya mentari di ufuk timur, membuat silau sosok pemuda. Sedetik kemudian, mata sang pemuda sudah tak tampak, juga diikuti dengan hawa keberadannya, seolah-olah sang mentari benar-benar menutupinya dengan selimut cahaya.
Makin jauh dari daratan, makin jelas pula tujuan yang ada di depan kelompok kecil itu—untuk memburu hal yang tak bisa dibunuh. Semuanya tentu saja meragukan kekuatan darah peri yang mungkin aja hanya bualan semata, tapi apakah mereka punya pilihan selain rasa percaya?
Perjalanan ke Berg baru saja dimulai.
***
Selama lima hari—mungkin, begitulah yang semua penumpang kapal hitung—mereka melintasi laut. Semakin mereka menuju ke utara, rasa senyap, sunyi, dan dingin makin menggerogoti tulang, bahkan ke jiwa. Nyanyian seram putri duyung laut tampak menggema sekaligus menggoda, membuat siapapun jua terhipnotis akan rayuan seorang pemangsa. Tapi beruntung sekali kapten kapal tuli adalah mualim yang anehnya mampu membedakan mana nyanyian manusia, nyanyian alam, dan nyanyian iblis. Sungguh aneh sekali, kapten berusia empat puluh tahun itu melihat suara, bukan mendengarnya, kasus unik yang bahkan membuat Marlin kagum sejenak sembari bergumam, “baru kali ini Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri talenta composer.”
Sejak saat itu, Marlin sering didapati menghabiskan waktunya bercengrakama dengan kapten kapal tuli itu. Keduanya diam tanpa suara, hanya memainkan mata. Kadang keduanya sumringah tanpa tawa, atau bahkan merenung senyap. Felice yang penasaran bertanya di hari keempat pelayaran. Marlin tua tertawa mendengar pertanyaan polos tentang apa yang mereka lakukan di depan kemudi kapal, lantas ia menjawab, “kami berbicara melalui lajur fikiran yang rumit. Yah, mungkin kau tak tahu, gadis muda, tapi ada satu metode sihir di mana kau bica bicara tanpa suara kerongkonganmu, tapi melalui suara fikiran dan hatimu.”
Felice tentunya mengangkat alis kebingungan dengan apa yang dimaksud, juga dengan sisa kelompok kecuali Abi. Ia langsung saja melirik gelang miliknya, lalu teringat akan percobaan kecil Gawain. Setelah makan malam, ia menyelinap keluar lantas menawarkan dirinya untuk menjadi pengamat di tiang tertinggi. Semua kelasi setuju saja, mereka amat terbuka menerima tawaran semacam itu.
Kini ia sendirian. Ia mendekatkan mulutnya ke gelang, lalu mencoba menyapa Gawain dengan harapan Gawain bisa menjawab di seberang sana. Zamrud hijau itu bersinar redup juga dengan mantra rumit yang melingkar di sana. Sepercik suara muncul dari sisi sana, sayang hanya suara lolongan serigala kesepian yang terdengar. Tapi aneh sekali, bukankah Gawain sendiri yang bilang jangan melepas gelang itu apapun yang terjadi, dan tak mungkin bukan Gawain tertidur tepat setelah makan malam?
Abi merasa sedikit khawatir. Ia memanggil sepasang peri laut dan lantas menyuruh mereka cepat mengirim pesan ke peri hutan untuk memberikan laporan. Lima belas menit ia mawas diri menunggu kepastian kabar. Saat ia melihat sepasang cahaya biru mendekat, ia serasa melompat untuk segera mendegar, namun bernapas lega ketika mendengar tidak ada apaun yang terjadi.
Kekhawatiran Abi baru reda ketika ia menjejakkan kaki di pelabuhan kecil yang tak bernama di Berg. Pelabuhan itu hanya diisi oleh dua sekoci yang hanya mampu menampung selusin orang dewasa. Tidak ada pemukiman yang terlihat di sekitar pelabuhan kecuali sebuah gubuk yang di dalamnya terdapat seorang pria tua dari ras Polaro, ras manusia beruang putih yang menunggu.
Suaranya berat, juga langkahnya yang gontai perlahan dan bekas luka yang menyobek mata kirinya membuat ia ditakuti meski ia sejatinya orang yang baik hati. Mengetahui sebuah kapal melempar sauh, ia segera keluar dengan lentera di tangan kiri, berjalan melintasi dalamnya salju yang bahkan menenggelamkan kakinya hingga ke lutut, namun berkat bulu putih tebalnya ia mampu berjalan dengan tenang meski hanya berbalut celana pendek sepaha.
Alfried, anak sang kapten yang sekaligus menjadi juru mudi pertama serta menjadi telinga dan mulut ayahnya sendiri, segera turun dengan tali sauh. Ia meluncur mulus di tali sauh, lalu mendarat dengan dua kaki. Kayu-kayu palang tak sekalipun berderak meski lumut dan rayap sudah menggerogoti. Dari sana Abi dapat menyimpulkan bahwa pemuda itu juga punya kemampuan akrobatik yang setara dengannya.
Kaki ringan sang pemuda itu bagai diangkat angin, keduanya tak sekalipun tenggelam di salju. Saat ia sampai, ia berbincang dengan pria Polaro tersebut. “Maaf Tuan Lennies, Anda kedatangan tamu. Tolong antarkan mereka ke kota untuk beristirahat, sementara ayahku akan ke Benteng Utara untuk memberi pasokan makanan.”
“Baiklah, untung saja ayahmu ingat untuk mampir ke sini! Jika tidak, mungkin mereka akan diusir oleh Para Penjaga! Memangnya, berapa orang yang kau antarkan ke sini?”
“Termasuk Aku, ada enam orang. Mereka adalah petualang andal! Mereka bahkan dapat mengalahkan tiga Mantikora!”
“Kau pasti bercan—” ucapan Lennies langsung berhenti ketika mendengar suara deburan. Rupanya itu Panther mencoba melompat seperti Alfried, namun tak memikirkan beban tubuhnya yang berbeda jauh ditambah lagi dengan pedang beratnya, alhasil palang-palang kayu itu remuk dan langsung ambruk jatuh ke laut dingin.
“Kau gegabah sekali, Panther!” seru Felice yang memilih menunggu tangga tali untuk turun. Ia tertawa terbahak-bahak ketika melihat Panther yang menggigil, terlebih-lebih bulu besarnya yang tampak menggembung akibat air. Panther mengibas-ngibaskan tubuhnya, melempar ribuan rintik air untuk keluar dari tubuhnya.
Marlin tua berdiri di sebelah Abi yang mengawasi dari pinggir kapal, ia bergumam berat, “dasar anak muda. Sekali saja melihat salju, mereka tergirang-girang. Herannya lagi, bukankah mereka setiap tahun melihatnya?” Ia menggeleng-gelenkang kepalanya, tahu betul tabiat yang dimiliki oleh ras tigra ketika menjejakan kakinya ke dingin dan lembutnya salju. Ia dan Medraut menyusul, sedangkan Abi mencoba mengirim pesan sekali lagi dengan peri laut untuk benar-benar memastikan, tapi begitu mendengar suara Gawain dari gelangnya ia mampu bernapas lega.
“Bagaimana keadaan di sana?” bisik Gawain melalui gelang. Sebuah napas berat bersahutan menyelingi ucapannya, seolah ia telah mengalami pertarungan berat.
“Baik. Bagaimana denganmu?” balas Abi.
“Cukup baik, kalau aku boleh bilang?”
“Apa ada pergerakan?” tanya Abi dengan nada cemas.
“Setidaknya ada hal yang ganjil, begitulah kami menyimpulkan.”
“Ganjil?” Peri tak bisa berbohong, la merasa ada yang tidak sejalan antara ucapan Gawain dan ungkapan peri. Tapi ia segera mengenyahkan pikiran itu tepat setelah angin dingin bercampur salju menerpa wajahnya. Ia segera menggigil, merasakan sendiri hawa dingin yang menjadi ciri khas dari daerah Berg yang terdiri dari lima pulau kecil dan satu pulau utama dengan beberapa puncak gunung yang bahkan terlihat dari Junier.
Sama seperti Alfried, ia tak kesulitan untuk melangkah di salju lantas mendahului yang lain dengan melihat-lihat pemandangan sekitar. Kalau ia boleh bilang, ia kurang cocok dengan medan semacam ini—hanya tanah lapang terbuka tanpa bayangan pohon tempat biasanya mampu menyelinap dan mengintai dengan tenang. Apalagi badai salju yang sering menerjang tentunya mengganggu pandangannya untuk membidik musuh. Ia menghembuskan napas, dari kepulan uap mulutnya ia mulai mengira-ngira suhu hingga kelembapan Berg, lantas menyimpulkan bahwa gaya bertarungnya tidak cocok dengan medan.
Lennies yang sedari tadi memandang langkah Abi yang ringan mulai penasaran. Ia tersenyum ramah lantas mengenalkan dirinya, “Lennies Edfier, Polaro, pemburu. Senang berkenal dengan Anda,” tukasnya dengan menyodorkan tangan kanannya secara ramah.
“Si Pembawa Lentera, manusia, pemburu dan petualang. Senang pula berkenalan dengan Anda, Ser Edfier.” Abi membalasnya dengan menyodorkan tangan. Dilihat dari ekspresi datar pria polaro itu, ia tahu bahwa namanya sebagai Si Pembawa Lentera tak pernah sampai di tanah asing ini, seolah-olah tanah ini memang berbeda dengan yang lain.
Marlin dan Medraut menyusul. Seperti biasa, Marlin menyunggingkan senyum ganjil dan Medraut tetap diam sembari memandangi Lennies dengan sorot mata tajam. Lennies tak terusik akan hal itu, malahan ia suka dengan cara pandang Medraut padanya—waspada. Setelah Felice dan Panther menyusul, kapal yang mereka tumpangi pun bertolak lagi menuju benteng yang ada di sisi lain pulau utama. Sang kapten tampak melambaikan tangannya, tapi ia tak terlihat berkat badai salju yang menerjang. Beberapa detik kemudian, badai seolah-olah menelan bulat kapal itu tanpa sisa.
Lennies memandangi kapal itu sejenak, lalu berbalik dengan mengangkat lenteranya setinggi bahu dan berjalan. Badai semakin mengamuk, tanpa disuruh siapapun semua orang tahu bahwa mereka harus mengikuti beruang kutub itu ke tempat perlindungan terdekat. Tidak ada kata yang keluar dari semua orang, bahkan Panther yang bermulut lebar pun tak bicara. Ia terlalu bergetar menggigil kedinginan setelah menyicipi sendiri dinginnya air Berg. Bulu tebalnya dari ras keturunan kucing tak membawa pengaruh apapun apalagi dengan keadaan basah kuyup semacam itu.
Ia hampir saja mengeluarkan keluhan dan sumpah serapah, mungkin saja dengan itu bisa menghangatkan tubuhnya dengan emosi mengapa mereka tak segera sampai di tempat perlindungan. Tapi begitu sebuah sepasang lentera terlihat bergentung tegak di sebuah tongkat logam, barulah ia menyadari bahwa mereka ternyata sudah sampai. Di belakang tongkat itu, ada sebuah goa yang dilindungi dengan gerbang kuningan yang tampak kokoh meski usang. Sesegera mungkin mereka berjalan ke tepian ceruk, meringkuk dari badai yang makin meraja-rela.
Panther muda langsung saja bergelung, ia sekarang tampak seperti bola bulu hitam, lucunya lagi ia juga bersin dengan suara khas ras kucing. Felice yang juga kedinginan menyandarkan dirinya ke pundak Panther. Ia manja mengelus-ngelus dan menenggelamkan wajahnya di pundak seorang kawan. Hangat, begitulah yang Panther rasakan dari Felice yang ukurannya setengah dari dirinya sendiri.
Gadis itu bertubuh ramping meski Felice lebih tua setidaknya dua tahun di atas Panther. Tahun ini, kalau tak salah hitung ia sekarang berusia 26 tahun jika menurut acuan penanggalan kaum manusia, maka mungkin saja Felice sekarang berusia 28 tahun, itu berarti ia hampir mencapai pertengahan hidupnya, itupun jika ia tak mati sebagai petualang nanti. Tugas yang mereka emban makin hari makin berat, bahkan mungkin saja dari enam orang ini, salah satu dari mereka mungkin mati di tanah asing atau bahkan tak mendapat perkuburan yang layak.
“Di mana pemanah itu?!” seru Lennies dengan nada cukup panik setelah mengetahui ada satu orang yang hilang dari kawanan. Mungkin saja ia langsung melompat tanpa dua kali berpikir jika saja Marlin tak mencegahnya dengan sentuhan menenangkan khasnya. Tangannya hangat bersinar, mungkin itulah yang menyebabkan pria tua itu bahkan tak kegigilan sedikitpun.
“Tenanglah, Ser Edfier. Dia adalah seorang pemburu andal. Kupastikan, ia sedang berkeliling melihat sekitar. Ia orang yang berhati-hati. Lagipula, ia bahkan mungkin sudah berada di atas menara kembar di atas sini.”
“Bagaimana Anda tahu? Bahkan dua menara itu sudah ditinggalkan!”
“Setidaknya, Aku pernah ke sini anak muda,” jawab Marlin dengan nada enggan lantas berbalik. “Aku rasa badai makin mengamuk, bukankah kita sebaiknya menikmati kehangatan di dalam daripada menunggu di sini?”
Lennies mendengus kesal, tapi pria tua itu ada benarnya. Lebih baik duduk menunggu bersama lima orang yang lain daripada memaksa diri untuk mengejar satu orang yang bahkan tak mungkin bisa diketahui keberadaannya. Dengan hidung beruangnya, ia mengambil napas lalu meniup sebuah lubang kecil. Dengung suara terdengar sayup-sayup, rupanya itu saluran untuk bicara. Lima detik hening, Lennies mulai khawatir. “Aku harap Vesil tak tidur di saat seperti ini, keterlaluan sekali jika ia tidur di saat badai.”
Sepuluh detik tanpa jawaban, hingga sebuah jawaban terdengar dari lubang. “Ser Lennies! Maaf, kami baru saja mengalami suatu masalah di sini! Beruntung—”
“Buka dahulu pintunya, keparat!” teriak Lennies dengan suara yang mirip lolongan panjang beruang kutub. Panther langsung lompat dengan bulu tegak disekujur tubuhnya. Ia langsung saja menunjukkan cakarnya, mulai mawas. Tapi yang hanya ia temui hanya sosok beruang yang tampak jengkel, dan sisanya tetap sama. Medraut dan Marlin tetap bersandar dengan tenang, Alfried tetap duduk sembari mencoba mematik api untuk menghangatkan diri, dan Felice tetap meringkuk tanpa suara.
Beberapa saat kemudian, barulah derit pintu terdengar dengan desing suatu mekanis rumit yang dirakit dari kumpulan uap dan gerigi. “Mekanisme Dwarvenia?” gumam Marlin yang kagum. “Tak kusangka ada peradaban Dwarven di sini.”
“Anda benar, ini reruntuhan yang cukup unik jika kuboleh bilang.”
“Kau tahu sejarah dari reruntuhan peradaban ini?”
Lennies menghimbau untuk masuk terlebih dahulu. Semua orang setuju dan mengangguk, kecuali Felice yang sedari tadi meringkuk, bahkan tak merespon sedari tadi. Melihat ada yang ganjil, Lennies segera menyambar tubuh gadis itu langsung menjunjungnya dengan kedua tangan. “Apa maksud An—”
“Jangan banyak tanya, nyawanya dalam taruhan,” ucapnya dingin. “Vesil, segera tutup gerbang dan beritahu dokter untuk segera menyiapkan air hangat!” teriaknya sembari menghadap atas. Rupanya, di atas sana ada seorang pria muda berumur dua puluh tahunan yang bertugas mengoperasikan mekanisme gerbang dan penyampaian pesan. Ia mengenakan jaket tebal berwarna putih—putih karena timbunan salju yang melekat di tiap kain bajunya. Tanpa disuruh, ia kembali ke ruang kendali, menarik tuas secepat mungkin dan bicara melalui pipa komunikasi kepada seberang.
Lennies tak banyak bicara, ia langsung berlari mengikuti lorong gua yang diterangi obor di kanan kirinya. Tak ada yang banyak tanya hingga mereka sampai di seberang lorong sempit tempat di mana cahaya tampak bergelimang. Tiga orang itu tentunya tercekat, tanpa suara. Kini sebuah pemandangan menakjubkan terlihat di depan mata mereka sendiri. Bahkan Marlin kehilangan kontur wajahnya sejenak, tapi berhasil mengembalikannya beberapa saat, sedangkan Medraut dan Panther tetap termenung lama.
Cahaya hangat, warnanya seperti api, namun seterang mentari, terletak tepat di tengah kota bawah tanah. Dari posisi tempat mereka berdiri sekarang, seseorang dapat melihat seisi kota di bawah sana dengan jelas. Kota bawah tanah yang terdiri dari ratusan bangunan berbentu batuan dengan lubang jendela serta ventilasi yang cukup sederhana. Terlihat jelas bahwa di balik dinginnya lingkungan yang kejam dan dinign di luar sana, di sini terdapat sebuah kota yang hangat disirami cahaya meski berada di bawah tanah. Sungguh menakjubkan, namun Panther dan Medraut mengurungkan niat mereka untuk kagum bilamana mengingat ada satu kawan yang tengah sekarat.
Keterburuan terlihat jelas di wajah Lennies. Tanpa pikir panjang lagi, ia melompat dari ujung tebing ke atap rumah terdekat yang dapat ia raih. Panther mengikuti, sementara yang lain tetap turun melintasi jalan turun biasa. Di sini, posisi Alfried menggantikan Lennies sebagai pemandu jalan. Ketika sampai di bawah, mereka langsung saja berjalan menuju jalan utama dan menemui seekor kucing hitam berukuran lima kaki sedang gugup sembari menggigiti jarinya di salah satu ujung jalan.
Beruntungnya, Panther hanya gugup bukan takut. Ia mengerti risiko menjadi prajurit dan menerimanya sepenuh hati. Ini bukan pertama kalinya ia melihat temannya sekarat, tapi ayolah, bahkan mereka baru saja sampai di medan tempur. “Kau baik-baik saja, kawan?” tanya Medraut.
“Cukup mengejutkan,” balas Panther dengan pias khawatir yang belum sirna, “cukup sulit untuk bertarung di medan semacam ini, tapi apa boleh buat? Kita sudah ditugaskan untuk berburu di sini.”
Lekas beberapa saat, Lennies keluar dari balik pintu geser yang terbuat dari kayu dengan seorang dokter. Dokter itu tampak muda, namun ungkapan muda bagi kaum elf mungkin berubah menjadi tua untuk kaum manusia biasa. Dia membawa beberapa benda kecil yang tampak kompak di tangannya dengan ukiran yang cukup lembut penuh tulisan asing. Anehnya, benda kompak itu memiliki aroma herbal berupa dari campuran jahe dan bawang.
Mengetahui bahwa benda yang bahkan hanya seukuran jari bayi itu menjadi perhatian, Lennies mulai menjelaskan, “kalian mungkin tak pernah tahu, tapi kami mengembangkan sebuah teknik pengobatan dengan benda sekecil ini.”
“Apa itu? Biji?”
“Bukan, kami menyebutnya tablet. Hampir sama seperti ramuan yang biasanya kalian buat, bedanya kami membuatnya menjadi padat lalu mencetaknya seperti ini. Lebih efisien dan lebih enak untuk ditelan. Omong-omong, telan obat penghangat ini. Campuran di dalamnya berkhasiat untuk menghangatkan tubuh. Cobalah.” Sang Dokter memberi masing-masing orang satu tablet kecuali Alfried yang rupanya sudah menelan terlebih dahulu ketika menjejakkan kaki di tanah Berg. “Kau masih menyimpan banyak kan? Ingat, memang rasanya lucu, tapi jangan kau makan lebih dari satu tiap harinya.”
“Baiklah, baiklah. Lagipula itu tablet terakhirku. Harganya masih sama bukan?”
“Iya, tapi berhubung kau membawa tamu baru kuberi kau diskon untuk saat ini. Bagaimana? Kau beruntung, pelaut. Omong-omong, Aku penasaran dengan kawanan ini—ah betapa tak sopannya diriku. Mari kita masuk ke klinik untuk berbincang hangat, lagipula atap gua sedikit tertembus angin badai.”
Lennies mengendus ke atas, “Anda benar. Bagaimana Anda menyadarinya?”
Dokter itu tersenyum sembari membuka pintu klinik dan menyuruh semua orang masuk, “tentu saja Aku tak menyadarinya Lennies; kami kaum Elf tak punya sensor panas setajam dirimu, apalagi Aku Elf yang payah dengan sihir. Tapi tadi ada seorang pemanah asing yang datang menemuiku. Katanya, ia tahu bahwa aku menjual obat penghangat tubuh dari orang-orang sekitar. Dilihat dari bajunya, ia bukan penduduk sini. Tapi hei, aneh sekali bukan? Ia seperti hantu saja, datang entah dari mana lantas bilang bahwa di dalam gua ini juga dingin. Anehnya lagi, setelah ia membayar, ia tampak tergesa—”
“Kemana orang itu?” tanya semua orang bebarengan.
“Pergi ke pusat kota, mungkin? Entahlah. Aku tak menyukai perangainya yang asing, kami kaum Elf memang benci sesuatu yang asing—artifisial dalam kata lain.”
“Meski kau menggunakan teknologi Dwarvenia?”
“Tidak-tidak. Argh, kau salah paham prajurit kucing. Aku tidak menolak dengan kemajuan teknologi, malahan Aku mengikutinya. Tapi hal ‘asing’ yang kumaksudkan di sini adalah pemanah itu. Naluriku menyatakan ada yang ganjal dari gadis itu.” Sang Dokter berjalan ke belakang, lalu kembali beberapa saat membawa dua nampan. Satu berisi jajaran kue, satunya lagi berisi enam gelas ramuan jahe yang kuat.
“Anda suka sekali dengan jahe,” tukas Marlin sembari menaruh tongkat kepercayaannya sejenak di belakang pintu geser. “Mengingatkanku pada budaya di Tenggara, tepatnya di tanah para nelayan tropika melaut. Bedanya, jahe di sana digunakan sebagai racikan bumbu makanan, bukan sebagai ramuan obat.” Marlin tua menjulurkan tangannya, “Marlin, penyihir, setengah Incubus.”
“Albien, apoteker namun bukan alkimiawan, Elf dari Hutan Magis Gardenia.”
“Gardenia?!” seru Marlin, “demi apa seorang Elf dari tanah Gardenia ke sini?”
“Pencarian jati diri. Ah, dari cara Anda bertanya, Anda tentunya pasti telah singgah di sana bukan? Apakah lama? Bagaimana keadaan di sana?”
“Aku tidak berlama-lama di sana; hanya singgah selama dua hari saja, itupun hanya beristirahat sejenak dari perjalanan panjang menuju Shari-La.”
“Sungguh sayang sekali bilamana Anda tak singgah lama, mungkin saja Anda bisa menikmati hidangan lezat di sana. Oh, bagaimana bila kubuatkan sekarang?”
“Ide bagus.” Langsung saja keduanya masuk ke dapur sembari berbincang hal yang lain. Cukup menakjubkan bagaimana cara Marlin mmampu memikat beragam orang untuk mampu mengikuti arah pembicaraannya. Secara tak langsung, itu sama saja dengan mengumpulkan informasi namun tanpa ada kesan paksaan. Pengalamannya yang lama berpetualang melintasi dunia sebagai seorang penyihir membuatnya mampu memahami bahasa universal, yaitu fikiran dan hati. Mantra rumit yang juga ia gunakan untuk bicara dengan kapten laut yang bisu itu.
Mungkin tidak ada yang menyadari selain Gawain dan Abi, tapi Marlin memang memiliki sifat memikat seorang Incubus. Jika kalian lebih resistan terhadap pengaruh semacam itu, maka kalian akan tahu bahwa sejatinya Marlin menguarkan bau mawar setiap saat. Itu unik. Secara biologis, bau mawar itu disebut Feromon—atau apalah itu—dan berfungsi untuk memikat lawan jenis. Marlin memang bersyukur ia diberkahi sifat semacam itu dari ayahnya, tapi tak menyangka ia kesulitan untuk muncul di pergaulan karena pengaruh Feromon mampu membuat wanita tergila-gila. Beruntungnya, ia mampu membatasi pengaruh itu meskipun tidak sepenuhnya. Oleh karena bau tubuhnya yang harum, ia dijuluki Mage of Flower.
“Begitulah kisah singkat mengapa ia luwes bicara dengan siapapun. Berbeda dengan Gawain yang memang memiliki kemampuan negosiasi yang baik, pak tua yang satu ini sulit dan bahkan takut untuk bicara kala itu. Huh, sungguh masa-masa sulit bila kuingat ia bahkan tak berani bicara dengan seorang gadis penjual buah plum kesukaannya. Tapi perjalanan sepuluh tahun terakhir ini mengubahnya sedikit, setidaknya, ia mampu berbicara meski mengandalkan kemampuannya itu. Licik, tapi itulah yang kusukai dari pak tua,” itulah penutup cerita dari celoteh Medraut. Semua orang diam, tak mampu merespon. Mereka cukup tercengang dan bertanya-tanya mengapa tiba-tiba seorang yang dingin di sepanjang jalan ini berbicara selain pedang dan Tyran. Apa ia sakit?
“Huh, dilihat dari wajah kalian, kalian mengira bahwa aku sakit, bukan? Ayolah, maafkan Aku bila memang dingin. Tapi wibawaku sebagai ksatria membuatku tak bisa tertawa selepas kalian.”
“Heh, ternyata kau banyak bicara ya,” Panther ikut mengakrabkan diri sembari merangkul Medraut. “Tak kusangka kau bisa bicara seluwes itu. Baiklah, mari kita minum-minum untuk merayakan pertemanan kita yang baru.”
“... kau tak mengajak Felice?”
“Felice sedang mengalami Hypotermia, ia sebaiknya tak keluar dari klinik ini dan beristirahat,” balas Lennies, “Alfried, tuntun mereka berdua ke kedai minum terdekat. Oh, juga kalian bertemu Si Pembawa Lentera di jalan, tolong sampaikan padanya bahwa sudah kusiapkan tempat menginap untuk kalian, agaknya sia-sia bila satu ruangan tidak terisi.”
“Baiklah, tuan beruang kutub yang baik hati. Kalau begitu, mari kita rayakan malam ini untuk berpesta sejenak sembari mengumpulkan informasi, kau ikut Ser Lennies?”
Dengan senyum yang memamerkan sederet giginya, mungkin semua orang akan ketakutan. Apalagi masih ada sepotong kecil daging ikan yang terselip di sela gusinya, juga ada beberapa taring yang tanggal dan masih berwarna merah darah, mungkin bekas pertarungan dengan predator laut yang menjadi bebuyutan alami beruang kutub, “tidak, Aku akan kembali ke pos ku di gerbang utama sembari memarahi Vesil atas keteledorannya.” Begitu keluar, empat orang itu berpisah. Tiga orang menuju pusat kota, sedangkan seorang beruang kutub bertolak darinya.
Di sisi lain, dari atas sana, lebih tepatnya dari salah satu ceruk kecil yang berada di pinggir kota, di mana ada sebuah saluran kecil yang hanya cukup untuk dipanjat satu orang untuk satu waktu, tampaklah seorang pemanah yang sedari tadi mengamati kota dari sudut pandang yang luas. Seperti kebiasaannya, ia sering mencari tempat tinggi, melihat sekeliling, lantas mengingat-ingat semua tempat dan lokasi strategis serta tempat yang mungkin saja menjadi pelarian mangsa.
Ia tak membutuhkan pena atau kain, ia sudah familiar dengan tempat semacam ini—tertutup. Ia merasa bisa mengendalikan pertempuran bila berada di kondisi seperti ini. Sekarang hanya mempersempit di mana letak musuh yang dimaksud dan itu pekerjaan yang amat sulit dilakukan. Kota dalam ini hanyalah sebagian kecil dari kepulauan Berg yang luas. Dengan waktu tak tentu, medan tempur yang kurang memadai, serta kekuatan musuh yang belum dimengerti membuat pertarungan ini menjadi pertaruhan yang cukup sulit.
Abi mengecek kembali barang bawaannya: busur perak dan dua lusin panah, sebotol racun yang siap dioles, belati di pinggang kiri, serta satu kantong darah peri. Fokus, begitulah Abi mensugesti dirinya sendiri, ia tahu ia hanya memiliki kesempatan yang terbatas. Sekarang, ia berusaha mengetahui dulu tentang kota didalam gua ini. Mungkin saja bukan, ia secara kebetulan menemui Penyihir Abadi yang menyamar sebagai penduduk?
***
“Nona muda, apakah Anda pendatang baru di kawasan ini?” tanya seorang penjual baju yang berada di kios. Penjual baju itu tersenyum ramah sembari menawarkan dagangan. “Ah, maaf, seharusnya Aku menawarkan baju yang lebih murah; kau sedang tak punya apa-apa kan? Aku mau menerima mata uang lain dengan syarat kau tak membeli barang lebih dari seratus Ardan, kau mengerti?”
Abi menaikkan alisnya. Siapa yang membutuhkan baju dingin? Ia tak merasa membutuhkan baju dingin selama ia bisa memanggil Peri Salju untuk memberi perlindungannya dari iklim ekstrim. Lagipula, dilihat dari cara bicara pedagang itu, Abi tentunya mampu menyimpulkan kemungkinan besar ia akan ditipu. Bagaimana seorang pendatang baru di sini mengetahui harga yang pas serta pertukaran mata uang yang ada di sini? Semisal, katakanlah Abi akan membeli satu setel baju dengan harga 50 Ardan. Pertanyaannya, apakah harga baju itu memang 50 Ardan dari awal, atau hanya berlaku ketika Abi baru saja berdiri di depan kios dan terbujuk untuk masuk melihat-lihat?
Idenya cukup sederhana dan ia tampaknya menyiapkannya dengan mulus. Mulai dari label harga yang memang sengaja tak dicantumkan, hingga melatih mati-matian untuk menampilkan senyum manis dari seorang Aligatra—etnik unik dari ras Lizardia yang mendiami rawa raksasa di Amarta. Meski tiap taringnya terlihat, tapi itu putih bersih, seolah ia tak pernah memakan daging hanya untuk mengejar cita-citanya sebagai nomaden yang melakukan jual-beli hingga sampai di sini.
Tertarik untuk bicara, Abi masuk kedalam kedai dan duduk di salah satu kursi, menunggu sang penjual selesai memilih beberapa setel baju yang ia rekomendasikan. Berhubung hanya mereka berdua di kios itu, Abi mulai bicara. “Sejak kapan Anda menetap di sini?”
“Kenapa?”
“Dilihat bagaimana Anda bicara, Anda rupanya seorang mantan petualang, bukan? Anda memiliki kemampuan negosiasi yang cukup mumpuni. Lagipula, bagaimana ceritanya ras Alligatra bisa jauh ke sini? Rupanya kota ini amat unik.”
Pria itu diam lama, ia bahkan berhenti mengambil baju rekomendasinya, “nona muda, kau juga petualang bukan? Hei, bisakah kita bicara sejenak. Sudah lama sekali Aku tak melihat seorang petualang datang ke kota ini.” Abi mengangguk setuju saja, tidak ada salahnya menemani seorang pria yang mungkin saja kesepian. “Dari mana aku bicara?”
“Alasan, aku penasaran dengan alasan mengapa Anda kesini?”
Pria itu tertawa. Abi terkesan dengan cara pria itu tertawa. Ia lepas, namun bukan tawa seorang predator yang keji, melainkan seorang mualim sederhana yang jujur. “Mungkin bodoh bila kau dengar—tertawalah bila mau—tapi ketahuilah, sejatinya niatanku ke Utara untuk menemui tanah para peri. Iya, iya, kutahu bahwa itu mimpi bodoh.” Kesan dari cara pengucapannya yang cepat membuat si nona muda tahu bahwa pria di depannya itu sering ditertawakan secara terang-terangan.
“Semua mimpi ada, bukan untuk ditertawakan, tapi diwujudkan.”
“Nona muda, kau tak mengerti. Tak semua mimpi dapat diwujudkan—lebih tepatnya dikabulkan. Jika semua angan dan mimpi mampu dikabulkan oleh Dewa dan Dewi—maaf bila Anda tak percaya mereka—maka istilah ‘mimpi’ tak kan pernah ada.”
“Memang Dewa dan Dewi tak mengabulkan semuanya, Tuan Alligatra yang baik hati. Tapi mereka juga tidak meninggalkan umatnya, bukan? Coba tengoklah, bukankah Anda menemukan kejayaan tersendiri meski tak menemui Tanah Para Peri, Tír na nÓg?”
“Ah, nona muda bahkan pernah mendengar nama tanah itu! Apakah Anda juga bermimpi untuk ke sana suatu hari?”
“Tidak. Hanya beberapa kekhawatiran dan kenagan buruk saja yang ada di sana.”
“Tentu saja, bukan? Perairan Iblis memang tak bisa ditembus dengan cara biasa! Hanya orang gila dan buta mimpi saja yang mau berlayar ke sana. Demi Dewa dan Dewi, tak kusangka Aku bertemu dengan seorang gadis muda seperti Anda. Omong-omong, dengan siapa nona muda datang?” untungnya, pria Alligatra itu salah memahami Abi.
“Dengan petualang yang lain, baru saja datang dua atau tiga jam yang lalu, memangnya kenapa?”
“Sekarang kubalik bertanya: untuk apa Anda datang ke sini? Pertempuran dengan Penyihir Abadi sudah usai bukan? Aku sempat curi-curi dengar dari Junier bahwa perang besar sudah lama berlarut. Oh iya, alasan lain mengapa pria tua ini bermukim di tanah dingin ini juga karena mencari rasa aman. Yah, memang Aku adalah pengecut. Bahkan Aku mengecewakan teman-temanku dengan mati sebagai alasanku untuk lari dari pertempuran besar.”
Waktu tetap berdetak, namun serasa melambat bagi Abi. Ah, itu kemampuan yang tak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Kadang kala, tanpa ia sadari ia membuat aliran waktu terasa melambat. Sering kali ia mendapati dirinya sedang menekuri sebuah pikiran yang rumit, dan itu benar. Penyihir muda yang satu ini berpikir perlahan, mengingat mungkin aja ia yang dulu berbeda dengan sekarang. Tak sekalipun ia bicara dengan Half-Beast setelah malam lama itu, malam di mana ia dikhianati oleh kawannya sendiri.
Ah, itu malam yang amat lama untuk dikenang. Beberapa potong ingatan terlampir sejenak di depan matanya. Pahit jika ia mulai mengingatnya sekarang. Lagipula, kawan lamanya itu pasti sudah lama mati, Abi sendirilah penyihir terkutuk dari Salem yang dimaksudkan, tidak ada yang tersisa selain dirinya sendiri, pun zaman sudah lama berubah.
“Aku pernah mengenal seorang kapten—kini demi kehormatannya sebagai kapten yang pemberani, kukatakan satu hal yang paling kuingat darinya, ‘Aku tidak tertarik dengan hasil yang kuraih, tapi perjalanan yang kuarungi!’ Abi mengatakan itu dengan nada yang persis seperti Hartein. Ia tak tanggung-tanggung berdiri.
Pria Alligatra yang baik hati, begitu pikir Abi terhadap pria itu. Setelah melakukan pertimbangan, tak salah untuk membeli setidaknya satu setel baju khas Berg yang dingin untuk rasa hormat. Sudah lama juga Abi muda tak bicara sesemangat itu, merasa bahwa ia mampu jujur di orang asing. Apakah orang yang ia temui itu mengingatkannya pada kebaikan seorang Half-Beast? Ia tak sepenuhnya membenci Half-Beast, tapi ia punya kesan tersendiri yang membekas, dan menempa dirinya menjadi seperti ini.
Baju petualang yang baru kini sudah ia kenakan. Warnanya tak beda jauh dari miliknya yang lama; bauran antara putih dengan biru langit, warna yang sekiranya tak mencolok di luar sana. Kain yang ia pilih juga khusus untuk tubuh kecilnya, ia tak terlalu terbebani meski tetap menjaga kehangatan tubuhnya. Setelah membayar dengan harga yang cukup mahal untuk ukuran kantong kecilnya, sang penyihir muda keluar dengan membungkuk hormat.
Sebelum ia benar-benar pergi, ia mengenalkan dirinya sekali lagi, “Si Pembawa Lentera, Anda mungkin tak pernah mendengar nama itu bukan?”
“Maaf, tidak pernah mendengarnya. Tapi kau cukup baik hati memberi namamu—kau mengharapkan kita bertemu lagi, bukan? Baiklah,” pria itu menunduk, membuka kerahnya hingga ke dada, memamerkan dada dari ras Lizardia, tapi anehnya ia bermoncong buaya. Dan jika diamatai sekali lagi, ia tak memiliki sisik yang keras seperti buaya. Malahan, sisiknya licin. Mungkin, ada alasan tersendiri ia memiliki mulut seperti buaya. “Mantan prajurit, lalu mati, menjadi petualang, Ja’ish dari Amarta. Kuharap kita bisa bertemu lagi, nona muda.”


 KurniaRamdan39
KurniaRamdan39

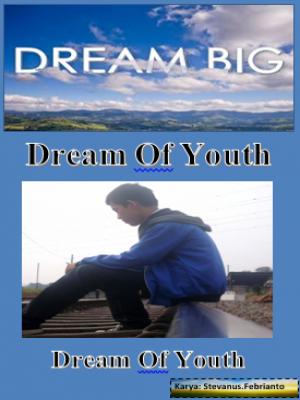









ntap
Comment on chapter Fiveteen: Persona