Sudah pukul lima sore, perempuan itu malah mampir ke sebuah saung di sisi jalan, beberapa gang sebelum tempat tinggal sementaranya di perantauan. Langit masih cerah, tentu. Guratan jingga belum sepenuhnya mengisi pendar cahaya, yang sebelumnya berwarna biru-putih. Kedua kaki mengayun pelan menikmati melodi alam. Tenang, menyenangkan.
Yaa habiibal qolbiii ...
Dering handphone menggema, terlantun sholawat yang memang sengaja disetel untuk panggilan masuk. Lyra mengangkat benda tersebut dan memulai obrolan dengan pemanggil, ternyata ibunya.
“Waalaikumsalam,” ujar Lyra dengan suara lembut. “Iya, teteh baik disini. Ibu sama Bapak gimana? Adek sekolahnya lancar, Bu?”
Lyra tertegun sebentar, menunggu jawaban dari seberang. Baru beberapa saat ia mendengarkan, raut yang semula cerah berubah masam.
Kulit wajah gadis itu memerah, sendu menyelimuti. Gejolak yang memuncak ditahannya, dengan perlahan menutup telepon. “Teteh kesana secepatnya, Bu. Assalamualaikum,” sahutnya mengakhiri pembicaraan.
Tangis tumpah, kepala menengadah pada barisan awan yang telah hampir seluruhnya terkontaminasi jingga. Teringat sepotong kalimat yang ia dengar kemarin, Mario Teguh dadakan.
Gelar macam apa itu? “Tidak pantas, tidak pantas!” pekik Lyra kepada diri sendiri. Kuat di luar, namun rapuh di dalam. Lyra ingin menangis sejadi-jadinya. Namun segera air mata diseka, lantas bangkit dan merapikan penampilan. Kemudian berlari sekencang-kencangnya.
**
Sekali lagi, sepoi angin perlahan menyapu duka yang sempat mendera. Meski sembab, Lyra nyatanya telah berhasil meyakinkan diri, berusaha untuk tidak terluka. Untung saja pimpinan restaurant tempat ia bekerja memberi izin cuti dadakan kepadanya selama seminggu, bahkan bisa ditambah jika memang belum cukup.
“Aku memang cengeng,” katanya memaki diri sendiri. Kemudian memasang headset di telinga untuk meminimalisir pandangan orang terhadap dirinya, yang mungkin di anggap gila karena berbicara sendiri. Yah, meski sebenarnya ia tidak menyetel musik satupun. “Masalah begini saja aku down, padahal sudah sering mendengar curhatan teman-teman tentang beban mereka yang lebih berat dari pada diriku. Ah, remahan rengginang.”
Kedua telapaknya ia masukkan ke dalam jaket jeans, setelah sebelumnya memasang masker untuk menghindari ‘godaan’ orang-orang iseng sepanjang jalan, meski tidak terlalu ampuh. Setidaknya, Lyra sedikit merasa nyaman dari manusia kurang kerjaan itu.
Ia menerawang pada jalanan kota Cirebon yang ramai. Memang sengaja Lyra melewati jalan raya, tidak seperti biasanya yang melewati jalan pintas. Seperti saat duduk di saung pinggir jalan tadi, misalnya. Mungkin kebisingan dan pemandangan senja yang mulai pudar, dapat mengobati kepanikan diri atas kabar buruk yang baru saja diterima.
Lyra menarik napas dalam-dalam. Menguatkan kaki yang lemas atas kecemasan yang tidak juga menghilang. Dada terasa sesak, dan bulir bening kian menyesak. Berulang kali ditengadahkan wajah yang memerah menghadap langit, menahan agar emosi tidak tumpah. Karena sekali menangis, sulit bagi gadis itu untuk berhenti. “Tidak, aku tidak boleh menyerah. Mario Teguh dadakan!”
**
“Kamu mau pulang?” tanya Vena, yang baru saja mencapai daun pintu. Ketika didapatinya rekan sekamar tengah bergelut dengan beberapa pakaian dan bawaan lain, sampai ia lupa mengucap salam.
“Waalaikumsalam,” sahut Lyra, masih terfokus pada tumpukan pakaian yang tengah disusunnya pada sebuah tas berukuran sedang. “Lima rasanya cukup,” katanya setelah menghitung isi tas tersebut.
“Hei, Lyra. Pertanyaan aku nggak dijawab.”
Lyra menoleh sebentar pada temannya. Sosok pria asing mengikuti gadis itu dari belakang, Lyra hanya mengulas senyum tipis. Sedikit tampan bermata sipit, namun gaya lelaki itu membuat Lyra bergidik. Tatto di dada kanan yang terlihat sedikit meski tertutup kerah pakaian, anting hitam—yang entah namanya apa—tersemat pada telinga kiri, kemudian rambut cepak dengan warna coklat di beberapa helai bagian depan. Pasti dialah yang dimaksud Vena tempo hari. Gadis itu hanya beristigfar setelah mengetahui first sight sahabatnya, yang memiliki type jauh berbeda dari gebetan terakhir Vena di masa sekolah.
“Kamu sendiri nggak ngucap salam. Udah kaya setan, deh.”
“Assemm.”
“Lain kali, kalau mau dianggap, ya pakai etika masuknya.” Dia sudah masa bodoh dengan sahabatnya yang mungkin tersinggung. Karena etika adalah nomor satu dimanapun, termasuk kepada orang yang telah sangat dekat dengannya. Setidaknya hal tersebut ajaran orang tua dan guru yang berusaha diingat meski telah sangat jauh dari rumah. Lyra menggendong bawaannya, kemudian memakai sandal selop yang terdapat di belakang pintu. “Aku pulang, ya.”
”Eh, tapi kamu pulang kenapa?”
“Bapakku masuk rumah sakit, aku izin kerja seminggu,” tutur Lyra dengan susah payah menahan massa tas yang ternyata lebih berat dari dugaan. Padahal, isinya haya beberapa baju, oleh-oleh yang dibeli mendadak sepulang kerja, dan make up serta peralatan penunjang yang rutin dibawa kemana-mana. “Kamu baik-baik, ya. Jangan macem-macem. Jangan rindu.”
“Pret.” Vena terkikik geli.
Mereka bersalaman, kemudian Lyra menunduk melewati lelaki yang kemungkinan mengantar Vena pulang. “Maaf, Mas. Laki-laki dilarang masuk kost wanita. Assalamualaikum.”
“Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu Hajah.”
Lyra memoleh pada daun pintu sekali lagi, mendapati Vena masih berdiri disana. Sedang si pria terduduk di lantai kosong depan kamar kost mereka. Hatinya sedikit lega. “Kalau rindu bilang, ya,” pekik Lyra seraya tertawa.


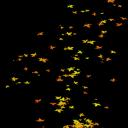 PenaLara
PenaLara










@yurriansan Siyap, Mom. Thank you ^^
Comment on chapter Bagian 3 - Langit; Awan Mendung