Langit jingga menyapa, bersama semilir angin yang menyeret ombak ke tepi. Kicau burung sahut menyahut, bersiap menyambut senja bersama kawanannya. Berbondong-bondong manusia memadati, menanti pemandangan indah di penghujung hari.
“Ra, sini merapat,” panggil seorang gadis berhijab segi empat tipis, dengan pakaian berwarna maroon yang sederhana, teramat serasi dengan penutup kepalanya.
“Ah, iya.” Lyra mendekati Vena, yang menepi pada rangkaian bebatuan bibir pantai. Seraya terduduk di sisi, perempuan dengan gamis dan hijab segi empat tebal tersebut berceloteh, “Tumben sekali kamu pulang sore. Toko tutup lebih awal, ‘kah?”
Vena hanya mengulas senyum, rona bahagia terpancar jelas pada wajah oval nun tirusnya. Sepersekian detik bisu, Lyra memulai kembali obrolan. “Tidak ingin berbagi bahagiamu?”
“Haha, kamu terlalu formal,” kelakar Vena, lantas tertawa gemas. “Aku mau cerita, tapi jangan diketawain, yah?”
“Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Cerita mah, cerita aja keles.”
“Asem,” dengus Vena kesal, namun tetap melanjutkan, “Aku jatuh cinta pandangan pertama sama cowok, di toko yang agak jauh dari tempatku sekarang.”
Lyra terdiam mendengarkan, meski hatinya bergemuruh. Kata ‘cinta’ terlalu sensitif untuk dirinya, apalagi jika cinta yang dimaksud hanya untuk main-main. Cinta sebelum halal, misalnya.
“Nah, dia itu nawarin aku kerja jadi admin di tokonya. Gajinya sih, cuma beda sedikit, Ra. Tapi ‘kan, ini kesempatan. Jadi, aku keluar dari tempat kerjaku sekarang. Menurut kamu, langkahku bener nggak, ya?”
Lyra merangkul sahabatnya itu, “Aku percaya sama semua keputusanmu. Pasti kamu sudah memikirkan matang-matang perihal ke depannya, bukan? Tapi saranku, jangan terlalu cepat menaruh hati, apalagi memberikan seluruh perasaan kepada orang yang baru kamu kenal. Kita nggak tahu isi hati seseorang, sayang.”
“Ih, geli. Sayang-sayang,” pekik Vena dengan raut di lebih-lebihkan. Lyra yang tadinya ingin memberi wejangan lebih lanjut, menjadi sakit perut karena terbahak-bahak. Terlihat berlebihan, memang. Namun ikatan pertemanan mereka memang se-konyol itu. “Daku serius, woy.”
“Daku lima ribu rius,” tantang Vena dengan tatapan tajam yang menggelikan. “Tadi bukannya minta pendapat? Dasar nenek lampir!” sungut Lyra memajukan bibirnya.
“Hahaha, mak Erot ngambek!”
“Budu!”
**
Cahaya berpendar kian menguning, suasana menjadi sedikit remang. Pemandangan yang terlalu indah, sungguh. Seluruh penat pantas luruh.
“Ra, kamu nggak berniat pindah kerja lagi, ‘kan?”
Yang ditanya hanya mengangguk asal, terlalu fokus dengan mentari yang hendak menuju perpisahan. “Aku mau tetep nge-kost sama kamu, walaupun tempat kerjanya jauh dari kost-an kita.”
“Kenapa? Bukannya berat di ongkos?”
“Karena kamu sahabatku sejak sekolah, dan hanya kamu teman yang membuat aku nyaman,” ujar Vena menerangkan. “Juga kadang jadi titisan Mario Teguh dadakan, ‘kan lumayan.”
“Pret!”
“Serius loh, Ra,” sahut Vena meyakinkan. “Kamu beneran nggak akan pindah, ‘kan? Atau meraih cita-cita kamu ke negeri China, ‘kan?”
“Ngapain ke China segala, cita-citaku terlalu sederhana untuk digapai sampai kesana.”
Vena tergugah, mencoba-coba mengingat, “Cita-cita yang kamu rahasiakan sejak sekolah itu?”
Lyra mengangguk, masih menerawang pada awan yang kian berubah menjadi jingga. “Aku hanya ingin menjadi langit.”
“Langit?” ulang Vena tidak mengerti.
“Aku hanya ingin menjadi langit, tempat bernaung semua harapan, cita, dan keluh orang-orang. Tidak apa jika bergerak lambat, asal dapat menemani mereka mencapai tujuannya,” tutur Lyra pelan namun terdengar elegan dan percaya diri, mirip penyair di televisi.
“Pret! Dasar sok puitis.”
“Budu! Hahaha.”
Senja memudar, membawa harapan dan luka, mungkin saja. Lyra meneguk salivanya kasar. Bulir bening hampir jatuh, jika saja sahabatnya tidak menyadarkan dia untuk segera beranjak pulang. Entahlah, perih kini menjalar di hati. Sedang ia tidak paham apa yang akan terjadi padanya nanti. Muncul sebuah firasat buruk ...


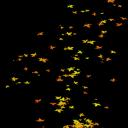 PenaLara
PenaLara








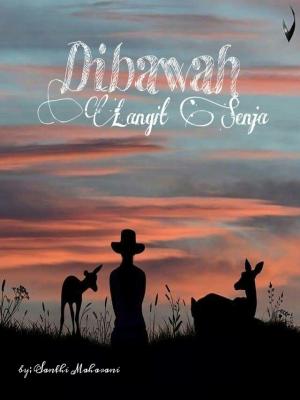
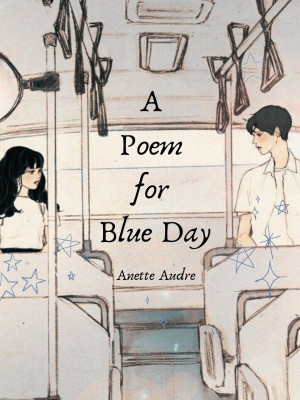
@yurriansan Siyap, Mom. Thank you ^^
Comment on chapter Bagian 3 - Langit; Awan Mendung