Nadia menarik tali ranselnya, mengkeret. Tidak peduli apa yang dikatakan orang tentang calon pewaris Safira Brahmadibrata, Nadia tidak suka—dan tidak akan pernah terbiasa—jadi pusat perhatian.
Nadia mencuri-curi lirik ke sebelah.
Akhirnya izin untuk melanjutkan SMA sudah turun dari Nenek. Namun, dengan tambahan: Rena juga pindah ke Wadit. Sekarang, sepupunya itu berdiri di sampingnya, kedua lengannya menggantung di sisi tubuhnya dengan santai, dan wajahnya terangkat penuh percaya diri.
Dalam hati Nadia bertanya-tanya mengapa mereka begitu berbeda.
Rena kira-kira setinggi Ken. Itu sebelum dia mengenakan ankle boots hak tiga inci. Seragam sekolah yang berupa kemeja abu-abu, rok rimpel, dan jas cokelat yang keliatan kusam dan biasa banget itu nampak gaya di badannya. Rambut Rena hitam berkilau, dipotong bob sebahu dan melambai aduhai saat tersapu angin, tidak seperti rambut bergelombang Nadia yang berwarna tanggung antara pirang, pink, dan merah gosong, yang mengembang seperti bolu dikasih baking powder.
“Aku mesti kemana dulu nih, Nad?” tanya Rena ringan.
“Ng… mungkin ke ruang guru dulu, lihat kelas dan jadwal pelajaran,” kata Nadia.
“Oke. Tunjukin jalannya dong.”
“Ke sini,” kata Nadia sambil berjalan menuntun Rena menuju ruang guru.
Nadia baru bisa bicara dengan Nenek mengenai kelanjutan sekolahnya hari Selasa kemarin. Sebetulnya beliau masih enggan memberinya izin, hanya saja ketika pembicaraan akan disudahi, Rena mengetuk ruang kerja Nenek dan tiba-tiba memberi Nenek inspirasi.
Ini bukan pertama kalinya Nadia merasa Nenek memiliki sadisme tingkat tinggi, tetapi memaksa Nadia berdekatan dengan Rena setiap hari rasanya sudah melampaui batas kejam.
“Nadiiiiaaaa!!!” pria berkostum batik Cirebon tiba-tiba melompat dari kursinya. Seruannya membuat guru-guru lain yang ada di ruangan itu menoleh. Nadia setengah berharap beliau tidak melakukannya. “Akhirnya kamu masuk sekolah juga. Si Ken Ratu itu tidak bilang apa-apa sama Bapak. Nah, bagaimana keadaanmu? Nenekmu sehat?”
Nadia cuma bisa mencicit, “Se-sehat, Pak. Ng… ini sepupu saya.”
Bos menoleh ke si cantik di sebelah Nadia.
“Ah ya, Renata bukan? Selamat datang di Waditranagara. Nah, bagaimana, hari pertama ini, tegang tidak?”
Senyum Renata mengembang. “Nggak, Pak. Sebaliknya malah, saya seneng banget. Dari dulu pengen banget satu sekolah sama Nadia. Tadinya Nadia di sini cuma setahun aja, makanya saya masuk sekolah lain. Tapi karena sekarang Nenek sudah nentuin Nadia di sini sampai lulus, saya akhirnya minta dipindah ke sini.”
“Bagus, bagus,” Bos manggut-manggut, membuat Nadia bertanya-tanya apa yang menurutnya bagus. Rena berbohong begitu lancar sampai Nadia sendiri nyaris percaya.
Bos membuka sebuah map berisi berkas data pribadi Rena, membuka-bukanya sampai halaman terakhir.
“Roro Renata Himawan Brahmadibrata,” Bos membaca keras-keras. “Kamu di kelas 2B. Wali kelasmu Bu Susi. Sebentar, Bapak panggilkan. Bu Suuuus!!!”
Seorang wanita yang sedang mengobrol di bagian dalam ruangan menoleh. Rena terkesiap melihatnya. Nadia hampir nyengir. Pastilah, pikirnya. Bu Susi itu perawakannya standar, tapi make up tebalnya itu nggak standar sama sekali. Dio pernah berkomentar, mestinya ada asosiasi standardisasi ketebalan make up, karena Bu Susi jelas-jelas kelihatan seperti pakai satu pak sekaligus!
“Kenapa, Pak?” tanyanya galak.
“Ini, sepupunya Nadia.”
“Oh!” Bu Susi buru-buru jaim. “Renata Brahmadibrata ya? Ya, saya sudah baca profil kamu. Selamat datang di Wadit.”
Lalu mereka berbasa-basi secukupnya. Bu Susi mengambil beberapa lembar kertas dari mejanya dan menyerahkannya pada Rena. “Ini jadwal pelajaran dan kuesioner. Mestinya kuesioner ini diisi sebelum kamu masuk, tapi kamu masuknya agak mendadak. Nadia, bisa antarkan sepupu kamu ke kelasnya kan?”
Nadia mengangguk.
“Dua guru itu kenapa sih?” gumam Rena saat mereka sudah lumayan jauh dari ruang guru.
“Katanya udah musuhan dari lama,” bisik Nadia. “Nggak tau kenapa.”
Perjalanan menuju kelas benar-benar membuat Nadia jengah. Dia mulai bertanya-tanya, apakah selama sisa dua tahun di SMA dia akan terus dibayang-bayangi Rena seperti ini.
Namun, setidaknya Nadia punya Ken yang berkata akan menjadi temannya. Selain itu, ada Dio, yang meskipun kata-katanya selalu nyelekit, tetapi akan Nadia coba lihat sisi positifnya.
Tinggal satu hal… Nadia diam-diam melirik Rena.
Sepupunya itu terlihat begitu bersinar. Wajahnya terangkat, bibirnya tersenyum. Bagaimana agar bisa kelihatan cerah seperti itu?
Begitu melewati pintu kelas 2H, yang terletak lebih dekat ke tangga, sebuah suara meneriakkan nama Nadia persis seperti wali kelasnya di ruang guru tadi.
Nadia spontan berhenti dan menoleh. Ken duduk di kursinya dan melambai ke arahnya. Dia terlihat seperti sedang mengobrol dengan Dio ketika melihat Nadia lewat.
Nadia mengangkat satu tangannya dengan canggung. “Pagi, Ken,” sapanya pelan.
Tentu saja, Ken tidak mendengarnya karena dia berada di pojok ruangan, sementara Nadia di pintu. Tapi tidak mengapa, karena Ken bergegas menyongsongnya. Dari dekat, Nadia bisa melihat plester cokelat menempel di dekat alisnya. Nadia tidak sempat menanyakan perihal itu karena Ken langsung menyerocos.
“Jadi akhirnya kamu boleh lanjut? Kok nggak ngabarin sih? Aku udah tegang dari kemarin-kemarin. Bukannya mau nanya nenek kamu dulu?”
“Maaf Ken, nggak sempat. Saya baru ngobrol dengan Nenek dua hari lalu, lalu harus bantu Rena persiapan pindah ke sini,” kata Nadia.
Saat itulah Ken menyadari sosok lain di pintu. Ken terlihat terkejut.
“Um… kenalin, ini Rena, sepupu saya,” kata Nadia. Kemudian tersadar. “Oh, iya… um… kalian udah kenal ya?”
“Nggak kok, belum,” kata Rena, mengibaskan rambutnya, secara enteng menganggap pertemuan mereka di ruang tamu anggrek tidak pernah terjadi. Ken nampak setengah lega, setengah salting. “Aku Renata, sepupunya Nadia. Kita dulu satu SMP, tapi nggak pernah sekelas. Jadi mungkin kamu nggak tau aku.”
Ken menyambut tangan Rena yang terulur, tidak mengerti bagaimana menyikapi orang seperti ini.
“Eeh… iya… aku Ken. Ngggg…”
“Dio!” Rena tiba-tiba memanggil Dio, memberinya lambaian enerjik. Spontan, anak-anak cowok yang ada di dalam kelas menoleh ke arah Dio, nampak penasaran sekaligus iri.
Sementara itu, yang dipanggil malah… pura-pura tidak mendengar dan menatap ke luar jendela. Nadia—meskipun dia merasa bersalah mengakuinya—merasa agak lega melihatnya, entah mengapa.
Rena menyelonong masuk kelas.
“Dio, kamu kenapa? Jatoh?” tanyanya sambil duduk di kursi Ken. Tangannya langsung terjulur ke wajah cowok itu, memeriksa kepalanya. Dio segera melepaskan diri dengan eskpresi gusar.
“Dio kenapa?” tanya Nadia kepada Ken.
Yang ditanya malah menggaruk belakang kepala sambil melirik ke langit-langit. “Euh… itu…”
Dia diselamatkan dari menjawab oleh dering bel jam pertama.
~ ~ ~
“Jadi, Senin kemarin Dio menghajar lima puluh preman sampai semuanya masuk IGD?” Rena menyeletuk.
Dio tersedak roti.
“Apa?!” seru Ken, nasi goreng di mulutnya hampir tersembur.
Nadia refleks melirik perban di sisi kepala Dio, yang menyibak sebagian rambutnya ke arah yang tidak beraturan, menutupi luka jahitannya.
Nadia hanya baru dengar sekilas dari Ken bahwa Dio tidak terluka karena jatuh. Dia belum tahu apa persisnya yang menimpa Dio. Sekarang, berbagai skenario menakutkan membanjiri pikiran Nadia.
“Kata siapa tuh?” kata Dio tajam.
Ken berkeras kelompok curhat mereka makan siang bareng untuk bertukar kabar masing-masing, sehingga akhirnya mereka pun nongkrong di bawah pohon di luar kantin seperti biasa. Rencananya mereka mau membicarakan masalah Nenek sekalian mengisi buku curhat, tapi dengan adanya tambahan sepupu Nadia, yang membuat membicarakan perihal Nenek jadi kurang leluasa, akhirnya mereka memilih topik lain.
Dan topik itu adalah tatapan ke arah mereka yang lebih intens daripada yang pernah dirasakan Nadia. Dio, yang menerima seluruh tatapan penuh rasa ingin tahu itu, mengeluh-ngeluh terus sepanjang perjalanan menuju kantin.
“Aku ngobrol sama anak-anak di kelas tadi,” jelas Rena. “Katanya Senin kemarin ada bentrokan di deket sini. Katanya Dio dan wakil ketua OSIS dikeroyok. Lima puluh preman masuk rumah sakit sementara si wakil ketua OSIS selamat tanpa cedera.”
“Enak aja,” kata Dio. “Gue korban tau. Yang ngehajar mereka si tengil ini nih. Kenapa jadi gue yang tertuduh?”
Rena mengangguk. “Aku tau kok, Di. Kamu nggak mungkin ngelakuin itu. Pasti Ken, kan?” Rena menunjuk Ken dengan sendok.
Ken gelagapan.
“Berlebihan! Paling kemaren cuma ada dua puluh orang, dan yang pingsan paling lima. Lagian, aku juga cedera tau, liat nih?! Lagian, pada tau darimana sih?”
“Mukulin dua puluh orang itu udah nggak wajar, tau,” sela Dio.
“Iya, bener,” sahut Rena. “Makanya Dio, jangan gaul sama preman! Begini akibatnya!”
Bibir atas Ken berkedut mendengarnya. Nadia berkomentar dalam hati. Padahal tadi pagi Rena sudah repot-repot pura-pura tidak kenal, sekarang keluar sikap aslinya.
“Minimal yang ini bilang udah insyaf,” kata Dio, menyeringai.
“Aku bukan preman!” sanggah Ken keras.
“Jadi sebetulnya kejadiannya bagaimana, Ken?” tanya Nadia, berharap apa yang dipikirkannya tidak benar.
Ken, yang sedang memelototi Dio, mendesah. Dia menjejalkan dua sendok nasi goreng ke mulutnya dan mengunyah cepat sebelum menjawab, “Entah deh. Dulu aku punya banyak musuh, sih…”
“Yakin cuma dulu?” cibir Dio. Ken mengacungkan garpunya. Dio mengangkat tangan.
“Jadi Nad, Ken ini di SMP kami terkenal banget sebagai ketua preman,” kata Rena, tiba-tiba jadi pembocor informasi. Nadia jadi bertanya-tanya mengapa sepupunya yang biasanya ramah kepada semua orang—kecuali Nadia—itu bersikap judes Ken. Apakah karena mereka saling menganggap saingan? Dari gelagatnya, Rena terlihat menyukai Dio, sementara Dio lebih akrab dengan Ken. Nadia tidak bisa berpihak pada siapa-siapa soal itu, tapi dia berharap mereka tidak menganggapnya saingan juga.
Nadia sudah punya terlalu banyak musuh tanpa ditambah Ken memusuhinya juga.
Atau mungkin, Nadialah penyebabnya?
“Kenapa kamu tiba-tiba jadi ember?” kata Ken, memandang Rena tajam-tajam.
Rena mengabaikannya, melanjutkan bicara kepada Nadia seolah-olah Nadia yang meminta.
“Anak buahnya semua preman satu sekolahan. Dia juga banyak menghajar preman-preman dari sekolah lain, malah anak-anak SMA dan preman yang udah dewasa juga habis dilibas sama dia!”
“Kenapa kedengerannya aku macho banget gitu?” protes Ken.
“Kenapa kedengerannya lo kayak merasa dipuji?” timpal Dio.
Kalau mau adil, tanpa memandang preman atau bukan, punya cukup kharisma sampai diikuti banyak orang adalah karakteristik seorang pemimpin, dan itu sifat yang harus dipertahankan. Sesuatu yang jelas tidak dipunyai Nadia. Mungkin itu jugalah alasan kenapa Nadia merasa bisa memercayai Ken. Sebelum dapat ditahannya, sebuah komentar keluar dari mulutnya. “Ken hebat…”
“Omaigat,” kata Dio dengan nada terguncang.
Ken menoyor Dio dari samping. “Tapi Nad, aku nggak sehebat itu kok…” katanya dengan wajah tersipu.
“Jadi sebenernya lo bangga jadi ketua preman?” Dio ternganga.
“Yaudah sih, masalah buat eloh?” cibir Ken.
“Iya, masalah. Karena lo bisa tambah gede kepala. Lo lupa kejadian Sabtu kemaren? Sampe mobilnya Nadia ikut jadi korban. Emang lo nggak kasian ama tuh mobil?”
“Ada apa Sabtu kemaren?” tanya Rena.
Nadia mengigiti bibir bawahnya, sementara ingatan akan salah satu mobilnya yang pulang dalam keadaan tidak utuh menyeruak. Mestinya dia meminjam salah satu mobil operasional Nenek waktu itu.
“Itu karena mereka mengincar saya,” katanya dengan suara sangat pelan. “Maaf ya, Ken, Dio, kalian jadi kena bahaya.”
“Ada apa sih?” Rena mengulang pertanyaannya, menatap Dio dan Nadia bolak-balik.
“Soalnya… yang diserang waktu itu mobil yang biasa saya pakai,” jelas Nadia, berusaha tidak mengindahkan rasa penasaran Rena. “Lalu soal kerusuhan kemarin mungkin—“
“Nggak, nggak, nggak,” potong Ken. “Kamu kan anak rumahan, jadi kamu bisa dapet musuh darimana?”
Nadia tersenyum kecut. Ken terlalu polos untuk ukuran mantan ketua preman.
Dio melanjutkan, mengacungkan jempolnya ke arah Ken, “Terus, yang kemaren itu jelas-jelas bilang mau bikin perhitungan sama dia.”
“Iya, bener Nad,” Ken mengangguk. “Yang kemaren memang nyariin aku. Walaupun aku bingung juga sih mereka darimana.”
“Si ketua mereka bilang, lo udah kebanyakan bikin masalah sama anak buahnya,” kata Dio mengingatkan. Ken mengerang.
“Aku udah bolak-balik mikirin ini, tapi buntu! Aku kan udah setahun nggak ikut-ikut begituan! Trus mereka mau bikin perhitungan apaan?”
“Kalo kata gue sih, bisa jadi karena orang-orang itu baru punya kesempatan sekarang. Mungkin setelah lo nggak mukulin anak orang di sana-sini selama setahun, mereka kira kesaktian lo udah luntur apa gimana.”
“Emangnya aku pendekar dari gua hantu, pake ada kesaktian segala...” gumam Ken.
Dio mengangkat bahu dengan enteng.
“Menurutku, kalian salah paham soal sesuatu,” ujar Rena. “Kalian kira karena Nadia nggak pernah keluar rumah, dia nggak punya musuh? Kalian salah besar. Justru musuh Nadia banyak. Memangnya keluarga sebesar Brahmadibrata bisa akur semua?”
Nadia spontan menoleh dengan sangat cepat ke arah sepupunya itu, memberinya pandangan memperingatkan. “Ren, kamu nggak perlu membicarakan itu.”
Dio dan Ken bertukar pandangan lewat punggung Rena, sementara Rena menyeringai ke arah sepupunya melewati Ken.
“Kenapa, Nad, takut temen-temen kamu ini jadi nggak mau temenan sama kamu lagi?”
“Apaan sih?” tukas Ken, lebih emosi daripada sebelum-sebelumnya. “Aku nggak gitu. Aku nggak nggak mau temenan cuma karena temenku diincar preman!”
“Lo sendiri preman, gitu!” celetuk Dio, tapi Ken mengabaikannya.
“Jangan-jangan kamu juga musuh Nadia ya?” tuduhnya. “Kamu kan barusan bilang di keluarga kalian ada yang musuhin Nadia. Itu kamu kan?”
“Hei! Aku nggak suka kamu ngomong gitu ke aku!”
“Aku juga nggak suka kamu ngomong gitu ke Nadia.”
Nadia dengan panik meraih tangan Ken, berharap bisa menghentikannya. “Ken, saya nggak apa-apa.”
Ken tidak menggubrisnya, kedua matanya terpancang ke wajah Rena dengan berapi-api. “Kalo dipikir-pikir, cuma kamu yang tau aku sama Dio dateng ke rumah Nadia kemaren. Jangan-jangan kamu yang ngasih tau anak-anak geng itu buat nyerang mobil Nadia!”
“Hei!” Rena berdiri sambil menghentakkan kaki. “Jangan sembarangan nuduh! Ngasal banget sih jadi orang!”
“Terus?” tantang Ken. “Emang kamu kan yang nyuruh?”
“Ken, tolong, udah,” pinta Nadia, ikut berdiri juga, menarik-narik tangan Ken.
Akhirnya, Dio mengambil posisi di antara Rena dan Ken, tangannya terjulur dengan maksud menghalangi.
“Udah, udah, kalian malah jadi tontonan kalo berantem di sini!”
“Dia tuh yang mulai,” tunjuk Rena.
“Ren,” tegur Dio sengit, membuat Rena tersentak. “Lo diem deh. Ken, lo juga jangan asal nuduh. Kalo Rena itu seperti yang lo bilang, ngapain dia nyuruh anak-anak geng ngejar mobilnya? Dia tau di dalemnya nggak ada Nadia. Jadi buat apa?”
“Yaa, nggak tau. Mungkin dia sirik mobilnya Nadia lebih bagus daripada punya dia,” kata Ken pedas.
“Enak aja! Mobilku masih lebih keren daripada mobil butut itu!” bantah Rena.
“Sekarang udah jadi butut karena kamu rusakin!”
“Aku nggak ngerusakin mobil itu! Kamu nggak punya bukti, nggak usah sok yakin! Dasar preman!”
“Kamu mau tau, preman itu kayak apa, hahh?!!!” Ken menarik lengan bajunya ke atas. Sekilas Nadia melihat lebam keunguan di baliknya sebelum lengan baju itu kembali turun.
“Hei hei hei,” Dio memalangkan kedua lengannya di antara Rena dan Ken, “udah, kalian tuh ngedebatin sesuatu yang nggak jelas, tau nggak? Liat tuh, Nadia aja santai.”
Tapi kata-katanya malah membuat Rena mendelik kepada Nadia. “Jadi kayak gini ya temen kamu? Nggak berkelas! Bikin malu nama keluarga aja!”
“Beraninya cuma sama yang nggak ngelawan!” sambar Ken. “Sini, kalo mau berantem sini, sama aku!”
“Ken!” bentak Dio, cepat-cepat menangkap tangan Ken yang sudah siap menyerang. Tapi Ken yang—jelas-jelas—lebih kuat dari Dio bisa melepaskan diri dengan mudah. Akhirnya Dio tidak punya ide selain memeluk Ken dari belakang dan menariknya mundur. “Lo udah brenti jadi preman, kan? Lo mau ketauan Bos? Lo mau diskors?!”
Kata yang terakhir membuat Ken berhenti meronta. Namun, dia masih menatap Rena dengan mata terbelalak.
“Ada apa ini?! Bertengkar di siang bolong?!” suara Bos tiba-tiba mengguyur mereka seperti air dingin.
Dio buru-buru melepaskan Ken. Nadia merapat sambil menunduk, tapi diam-diam mencuri pandang ke sekeliling. Rupanya orang-orang di kantin dengan terang-terangan sedang menatapi mereka. Pertengkaran Ken dan Rena pasti sangat keras. Bos saja sampai terpanggil.
Atau Bos memiliki sensor kerusuhan.
“Bukan, Pak,” Rena menjawab dengan suara mantap. Meskipun begitu, Nadia melihat kedua tangannya yang tergenggam gemetaran. “Kami cuma lagi mengobrol.”
Bos tidak percaya, alisnya bertaut dan bibirnya mencibir.
“Yasudahlah, saya tidak peduli,” katanya akhirnya. Dia menarik setumpuk kertas dari kepitan di ketiaknya dan menepuk kepala Ken dengannya. “Nah, ini tugas baru kalian. Kerjakan yang baik ya, kalau tidak nanti saya suruh shuttle run seratus balikan. Hahahahaha…”
Kemudian beliau pergi sama mendadaknya dengan datangnya.
Ken memegang kertas-kertas itu dengan dua tangan.
“Apaan sih?” selidik Dio.
“Ini PR sama kuis-kuis kemaren,” sahut Ken, terbengong-bengong.
“Oh,” kata Dio mengerti. “Buat Nadia ya? Niat banget si Bos.”
“Jadi itu tugas susulan buat Nadia?” Rena nimbrung, entah bagaimana dia seperti menganggap adu mulutnya dengan Ken barusan tidak terjadi. “Kenapa dia bilang tugas buat kalian?”
Ken nyengir mengejek. “Masa kamu nggak ngerti? Maksudnya supaya kita ngebantuin Nadia ngerjain.”
“Wah, nggak usah repot-repot,” kata Nadia buru-buru.
“Nggak apa-apa kok, Nad. Aku mau banget bantu! Lagian ini banyak banget.”
“Gimana lo bisa bantuin, kuis lo kemaren harus remed gitu?” kata Dio. Lalu dengan cekatan berkelit sebelum bogem Ken mengenai kepalanya.
“Nggak usah ngebocorin info nggak penting! Lagian kamu juga bantuin! Weekend ini yuk? Sabtu gimana?”
Dio berjengit, seperti baru menginjak sesuatu yang tajam. Atau menginjak kotoran.
“Kenapa, mau mangkir?!” labrak Ken langsung.
Dio mendelik. “Gue nggak bisa kemana-mana Sabtu ini. Nyokap gue balik, minta dijemput di bandara.”
Ken nampak terkejut. “Tante Dita? Kok tiba-tiba? Kamu mau ngebohongin aku ya?!”
“Ih, gak elit banget ngebohongin lo,” tukas Dio dengan nada jijik. “Lagian, lo lupa gue baru ketiban musibah? Udah lo yang nyebabin juga, berlagak nggak dosa. Gara-gara urusan rumah sakit, nyokap jadi ditelepon. Pulang deh dia.”
“Emang mamanya Dio dimana?” Rena menyela.
“Belanda, dan bahagia di sana berdua doang sama bokap. Berasa honeymoon tiap hari.”
“Gaia nggak dihitung?” serobot Ken.
“Dia kan asrama.”
“Siapa tuh?” tanya, lagi-lagi, Rena.
“Adik gue. Udah ah, ga usah tanya-tanya!”
“Kak Artemis pulang juga nggak?” Ken bertanya lagi.
Sekilas Dio kelihatan ngeri. “Untungnya enggak. Kalo dia tau gue baru dipukulin, dia pasti udah nelepon buat ngetawain gue. Semoga nyokap lupa ngasih tau dia saking paniknya.”
Ken nampak sangsi.
“Artemis itu kakaknya Dio?” kata Rena, masih bersemangat menyela.
“Yaudah kalo kamu ngejemput Sabtu, kita ketemuan Minggu!” putus Ken.
Dio terbelalak. “Lo lupa nyokap gue? Seduaharian Sabtu-Minggu itu gue bakal terkurung di rumah, tau!”
“Enggak apa-apa, Ken, saya bisa coba kerjakan sendiri,” kata Nadia akhirnya. “Saya nggak mau merepotkan.”
“Nggak usah sungkan gitu, Nad,” kata Ken tidak mau kalah. “Nggak ngerepotin kok!”
“Masa kamu nggak ngerti?” kata Rena, kesal karena diabaikan. “Maksudnya Nadia tuh dia nggak butuh bantuan kalian, karena justru nanti kalian yang ngerepotin dia.”
Ken jadi terdiam mendengar itu.
Nadia merasa wajahnya memanas. Dia ingin menyanggah, tetapi setelah lewat beberapa detik, rasanya sudah terlambat. Seharusnya dia langsung menepis kata-kata Rena.
Dio mengeluh.
Dia ingin diam saja dan bersyukur, karena mereka jadi tidak akan mengerjakan tugas bersama-sama. Tapi melihat kedua cewek satu kelompoknya yang nampak lebih canggung daripada orang ansos bertemu orang ansos, dia jadi merasa harus melakukan sesuatu.
Bukannya dia peduli ya.
“Kalian ngelamun ya?” katanya dengan nada kesal. Dia tidak tahu berapa persen dalam intonasinya itu yang murni dari kekesalan. “Ini tugas dari Bos. Kalo Bos nyuruh kerjain bareng, berarti emang terpaksa kita kerjain bareng. Gimana kalo hari ini aja pulang sekolah?”
Nadia langsung mengiyakan, segera menyambar kesempatan untuk mencairkan kekakuan. “Di rumah saya saja, saya pesankan mobil untuk jemput.”
Meskipun begitu, Nadia merasa Dio seperti menyesali diri, seolah-olah baru saja membuat keputusan terbodoh seumur hidupnya.


 drei
drei

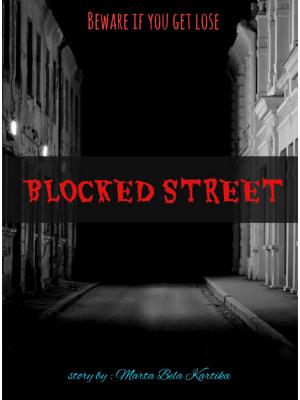








95 banding lima, auto sakit perut ketawa cekikikan. Tenyata kalau di perhatiin tokoh Ken, karakternya hampir mirip dengan, tokoh Tio di ceritaku.
Comment on chapter Satu