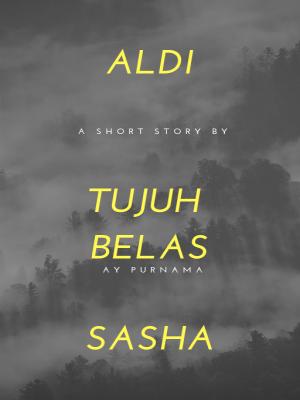“Door, door, pyuuss.”
Derap kaki kecil yang berlarian di tempat itu, tangan kecil yang memegang pistol mainan, juga topi yang kebesaran menutupi mata dan sebagian wajahnya. “Aku akan mengirimkan senjata nuklir. Pasukan siap... serang dia !” suaranya memenuhi ruangan lalu berkelarian lagi dan bersembunyi di belakang lemari yang berisi perabotan makan yang tertata rapi.
Jati Wangsa atau sebut saja Anca, lelaki yang hampir berumur tiga puluh tujuh itu hanya terkekeh melihat tingkah bocah kecil yang berkelarian di sekitarnya. Dia mencuci piring bekas makanan yang disajikan bagi para pelanggan yang sering mampir di kafe miliknya. Eudaemonia, kafe kecil yang ia jadikan ladang bisnis demi menghidupi dirinya sendiri dan juga bocah kecil yang sejak tadi kelihatan gembira setelah pulang sekolah itu.
“Kau harus melepas seragam sekolahmu dulu, lalu kau bisa bermain lagi,” kata Anca, ayahnya yang hendak menangkap tubuh kecil itu. Tapi tetap saja, dia tidak bisa. Karena bocah kecil itu amat lincah dalam hal melarikan diri dari sang ayah.
“Atau... aku tidak akan mengijinkanmu bermain bersama paman Jingga lagi!” seru Anca kewalahan.
Berhasil, dia menangkap bocah kecil yang baru berumur delapan tahun itu. Lalu menggendongnya dan membawanya ke kamar, dia tidak peduli meski bocah kecil itu merengek minta untuk diturunkan.
“Jingga, lanjutkan pekerjaanku!” teriaknya sebelum menaiki tangga kayu yang menghubungkan antara kafe dan rumahnya. Dia menjatuhkan bocah kecil itu di atas kasur, lalu melipat tangan di bawah dada.
“Bukankah ayah sudah bilang, setelah pulang sekolah kau harus--”
“Mengganti seragam sekolah, mencuci tangan dan kaki lalu makan siang. Setelah itu tidur siang dan baru boleh bermain,” kata bocah kecil itu polos. “Door, door,” katanya sambil memainkan pistol mainan miliknya. “Tapi ayah... aku mau bermain kapten bajak laut bersama paman Jingga. Kenapa ayah melarangku? Padahal aku cuman bermain di sekitar rumah, aku tidak bermain kotor-kotoran,” katanya membela diri.
Anca hanya menghela panjang. Selalu saja, bocah kecil yang berumur delapan tahun itu selalu tahu bagaimana cara menjawab ucapannya. Dia memang tidak pernah marah pada bocah kecil itu. Kau harus tahu, bahwa bocah kecil itu merupakan hidupnya. Kalau tidak ada si bocah kecil ini, mungkin dia tidak berarti apa-apa, pun dia mungkin akan memutuskan untuk mengakhiri hidup saat dirinya berumur dua puluhan lalu.
“Tapi ini bekas keringatmu, anakku. Bagaimana jika teman-temanmu mencium bau acem dari pakaianmu? Bukankah kau akan malu sendiri?” Anca dengan pelan berkata pada si bocah kecil, sambil duduk di hadapannya, dia mengelus lembut dengan penuh sayang rambut cepak anaknya.
“Baik ayah,” kata si bocah kecil, lalu melepaskan seragam sekolahnya.
Anca memperhatikan bagaimana anaknya itu mengganti dan menggantung seragam sekolah di lemari gantungan berwarna cokelat maroon itu. Dia senang karena bisa mengawasi pertumbuhan anaknya, menjadi orang tua tunggal mungkin bukan hal yang mudah, tapi Anca menikmatinya. Satu-satunya yang dipunyai adalah bocah kecil itu, jadi bagaimana mungkin Anca bisa marah pada darah dagingnya sendiri. Dia memberikan perlakuan yang lembut dan seluruh kasih sayangnya pada anak kecil itu.
“Sudah... sekarang, apakah aku boleh bermain lagi dengan paman Jingga?” tanya Senja berdiri di depannya.
Anca mengangguk, dan si bocah kecil itu merasa senang. Dengan sigap bocah itu mengambil pistol mainannya dan berlari lewat pintu kamar. Langkah kakinya yang menuruni tangga kayu masih terdengar di telinga Anca sehingga lelaki itu tampak khawatir. “Hati-hati nanti kau jatuh nak,” teriak Anca yang ikut keluar, lalu menutup pintu kamar.
“Kita bermain lagi paman, ayah sudah mengijinkanku. Sebentar lagi aku akan menarik pelatukku dan akan menembak para bajak laut. Door... door,” teriak Senja.
Orang yang dipanggil paman adalah Jingga Petala, lelaki itu hanya menggeleng-geleng, untung saja dia sudah selesai mencuci piring. Mereka tinggal menunggu pengunjung yang datang lagi.
Kafe itu menyatu dengan rumah Anca. Rumah mereka berada di lantai atas, dan kafe berada di lantai bawah. Para pengunjung senang melihat tawa renyah bocah kecil yang kadang bermain di sekitar ayahnya yang sedang bekerja, pun mereka juga menyukai sikap ramah dari si pemilik dan lucunya tingkah si bocah kecil itu.
“Hati-hati Senja, ada pengunjung yang datang,” Anca memperingati.
Senja Kala, memiliki wajah seperti Anca dan mengambil mata ibunya. Rambut yang bagian depan jatuh di dahinya, wajahnya kelihatan kesal. Senja duduk di kursi bartender dan memainkan pistol-pistolnya di sana. Pengunjung memang gemas terhadapnya, tapi Anca sangat mengkhawatirkan anaknya, alih-alih bocah kecil itu menabrak pengunjung yang datang lalu jatuh, atau menabrak Jingga ataupun dirinya yang sedang menyajikan pesanan pengunjung. Jangan salah, bocah kecil itu juga lumayan ceroboh.
“Kau harus makan dulu ya,” kata Anca menyajikan makanan untuknya, lalu si bocah tampak memakan makanannya dengan lahap. Begitulah menjadi orang tua tunggal, disatu sisi Anca harus bisa sebagai ibu, juga disisi lainnya, dia juga harus bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, untuk menghidupi dan menyekolahkan anaknya yang masih berumur delapan tahun itu.
Mungkin Anca tidak berniat membuka usaha kafe, kalau saja –Jingga, temannya itu tidak menawarkan untuk bekerjasama. Jingga adalah temannya dulu sewaktu mereka di kemiliteran. Lelaki itu juga memutuskan untuk berhenti menjadi seorang militer setelah dua tahun Anca memundurkan diri. Sampai sekarang ini, Jingga belum memberitahu Anca alasan kenapa lelaki itu berhenti dan memilih usaha seperti ini. Tapi, Anca juga merasa senang karenanya. Bagaimana tidak? Lelaki itu juga pandai memasak dan melayani para pelanggan dengan baik.
“Jingga, meja 12. Pain d’epice dan Monbazillac,” kata Anca yang masih menemani putranya makan. Sepertinya dia harus mencari pekerja tambahan, tidak cukup hanya mereka berdua saja. Mereka juga sering kewalahan menerima pelanggan yang berdatangan.
Setelah Senja menghabiskan makanannya, Anca menyuruh bocah kecil itu kembali bermain, lalu dia sendiri kembali sibuk membantu Jingga melayani para pelanggan yang datang ke kafe. Eudaemonia, kafe yang buka beberapa minggu yang lalu. Letak kafe itu di pinggir jalan, dan suasananya juga tenang. Kafe eudaemonia terkesan klasik, karena Anca memang menyukai hal-hal yang berbau klasik. ‘Hungarian Dance’ dari Johannes Brams menguasai ruangan, suara itu keluar dari tape yang ada di sebelah meja dapur. Para pengunjung yang datang langsung menuju meja kosong, dan Jingga langsung menghampiri tiap meja yang baru diisi, bak pelayan yang baik, dia menawarkan beberapa menu spesial mereka hari ini.
Anca merasa beruntung, karena Jingga seorang koki sekaligus pelayan hebat. Apalagi lelaki itu juga sangat bisa mengambil hati Senja, anaknya. Jadi kadang dia tidak kewalahan, jika bocah kecil itu rewel. Mungkin iya, Senja sering rewel diusia lima sampai tujuh tahun. Sebagai orang tua tunggal, Anca harus siaga setiap saat. Apalagi saat bocah kecil itu merengek meminta untuk bertemu ibunya, Anca tidak tidur semalaman dan menggendongnya sampai pagi. Mengajaknya berbicara perlahan, menceritakannya banyak hal, setidaknya pembicaraan tidak mengarah ke ‘Ibu’ terus.
Tapi lihat sekarang, bocah itu menikmati usia delapan tahunnya. Anca puas saat melihat anaknya itu tertawa lebar, juga saat para pelanggan mengajaknya mengobrol. Kadang setiap kali bocah kecil itu sekolah, para pelangganpun sering menanyakannya. Bocah kecil itu, mengikuti sifat Meera, mendiang istrinya. Juga dari bocah yang sekecil itu, dia dapat melihat mendiang istrinya, mata Senja mirip seperti Meera, juga bibirnya yang kecil.


 Zaa_oreoreo
Zaa_oreoreo