PROLOG
Semua orang pasti pernah merasakan jatuh cinta, jantung berdebar bahkan gugup. Jatuh cinta adalah hal yang sangat mengesankan dalam hidup. Walaupun, kebanyakan orang tidak mengerti mengapa setiap orang bisa jatuh cinta. Kenyamanan adalah hal utama terbentuknya sebuah cinta. Kenyamanan yang menimbulkan kedekatan antara satu sama lain tanpa disadari berubah menjadi perasaan cinta.
Cinta juga bisa timbul karena ketertarikan dengan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Seperti ketertarikan aku kepada Mario, Mario Kenids. Golongan darah O, pembalap motor yang tergila-gila dengan miniatur tiruan superhero atau biasa disebut action figure, benci makanan pedas, dan bisa sangat agresif jika disinggung mengenai hobinya yang menurutku itu terlalu berlebihan.
Kali pertama aku bertemu Mario saat Masa Orientasi Sekolah. Hari itu saat di mana aku kebingungan mencari seorang teman, berjalan lurus tanpa tahu arah tujuan. Begitu semua orang sudah mendapatkan teman barunya, aku mulai gelisah, tiba-tiba seorang lelaki bertubuh tinggi berdiri di hadapanku dengan tangan terulur dan bilang, “Ini minum”. Saat itu, aku berdiri dengan tampang kusut yang menjijikan. Sementara dia, mengulurkan sebotol minuman dingin sambil terus menatapku, seakan berharap aku akan mengambil minuman itu dan membalas ucapan yang dia katakan.
Oke, harus aku akui waktu itu, pikiran terakhir yang melintas di pikiranku yang sedang butuh teman bukanlah keinginan untuk minum yang diberikan dia untukku. Aku berpikir – eh, ini cowok aneh banget. No, that guy, he is actually really handsome. Tinggi, berkaki jenjang, dan rambut dengan model cepak belah samping. Dia juga mengenakan parfum yang membuat hidungku betah dengan wanginya, mulai dari atas sampai bawah penampilannya benar-benar paling top di antara cowok yang lain. Wajahnya segitiga terbalik, kumis tipis di atas bibirnya. Mulutnya mengunyah permen karet sedangkan matanya masih terus memandang ke arahku. Dan tangannya – terlihat kekar, terjulur memberi sebotol air yang tidak dibutuhkan olehku.
“Hei, ini untuk kamu...,” ulangnya, kali ini dia tersenyum singkat dan itu benar-benar manis.
Respons aku kurang lebih adalah raut aneh yang mungkin menyebalkan baginya. Dia lalu menaikkan sebelah alis dan membuka segel tutupnya dengan sekali putar. “Masih baru, belum aku minum.”
Aku baru saja mau protes dengan bilang orang mana yang mengira sebotol air yang masih bersegel sudah di minum? Dan pada saat itu aku menyadari jika dia berpendapat bahwa gadis yang kini berdiri di hadapannya adalah gadis bodoh.
Tatapan yang merendahkan – tapi, tatapan itu sama sekali tidak menyinggung perasaanku, terlihat aneh dan sangat jauh berbeda dari sikapku yang selalu bawa perasaan. Aku pikir, aku menyukainya.
Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin pemberian minum dan wajah kusut yang menjijikan itu adalah takdir, permainan hidup yang bertujuan untuk mempertemukan aku dengan dia. Sebotol air itu sepertinya menjadi salah satu benda yang menjadi saksi bisu pertemuan aku dengannya. Aku benar-benar terpana dengan sikapnya yang peduli, ketika dia berjalan pergi setelah mengatakan, “Diminum airnya, muka kamu kayaknya capek banget. Kalau butuh sesuatu, aku ada di seberang sana.” Sampai aku sadar, sedari tadi aku masih memegang botol air yang sudah terbuka tutupnya.
Dan akhirnya adalah sejarah. Kalian pasti tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tepatnya begini sejarah kami: Aku dan dia bertemu, kami sahabatan, lalu aku jatuh cinta tapi bertolak belakang dengan dia – dia memilih gadis lain, terjadi konflik, dan akhirnya kami tidak bisa bersama.
🛵
Kuingin marah, melampiaskan. Tapi kuhanyalah sendiri di sini
Ingin kutunjukkan pada siapa saja yang ada bahwa hatiku kecewa
.
Aku duduk di kursi dengan meja kecil di sebuah kafe ramai di kota Bandung, gelas besar yang sudah berair di atas meja, menahan kecewa yang amat sangat. It’s almost midnight and i wait alone at the cafe while the others pair up. Aku mengusap mata yang pandangannya mulai memburam, lalu memfokuskan pada sekeliling. Kafe ini, cukup ramai meskipun dalam jam yang seharusnya digunakan untuk berisitirahat di rumah. Mungkin karena ini malam minggu dan banyak orang yang mencari tempat nongkrong. Aku melihat beberapa orang yang saling berpelukan ketika sang kekasih datang, pasangan yang saling menyuapi makanan yang mereka pesan dan menyeka ujung bibir pasangan ketika ada saus menempel di sana, lalu mereka tersenyum lebar, orang sepertiku yang harus puas dengan Caramel Macchiato dalam gelas dengan es batu yang mulai menghilang di atas permukaannya – sangat memprihatinkan.
Dalam hidup ini banyak hal yang membuat perasaan sakit dan kecewa. Memang, semua kekecewaan pada dasarnya adalah kesalahan diri sendiri, kita yang berekspektasi. Dan ketika seluruh ekspektasi dan harapan tidak berjalan lancar maka timbul perasaan kecewa. Banyak hal dalam hidup ini yang kadang terasa pedih karena terluka oleh harapan-harapan yang dibuat sendiri. Harapan terhadap seseorang yang dicintai, misalnya.
Menunggu bukan perkara mudah dan menyenangkan. Kadang-kadang menunggu menguras segala kesabaran. Sedetik menunggu di sini terasa seperti seharian. Begitulah aku, dengan kesabaran menunggunya – entah bagaimana ujungnya aku akan tetap membunuh rasa sabar.
Rasa hampa, kesal, dan amarah sungguh merasuk jiwa di saat menunggu orang yang diinginkan tak kunjung datang. Sungguh sakit dikecewakan dalam harapan besar untuk membunuh kesepian yang dirasakan. Aku tak bisa mengadu atas apa yang mematahkan harapan kepada seseorang yang dicintai.
Mengingatnya sekarang membawa kembali kejadian-kejadian lama yang pernah terjadi dan membuatku sesak.
Setelah menunggu sekian lama, akhirnya aku menyerah. Aku bangkit menuju pintu keluar. Sejenak, aku berhenti, tepat di samping meja kasir. Detik ini, aku berdiri di tempat yang sama seperti dua tahun lalu, duduk di kursi yang sama, dan memesan minuman yang sama.
Aku mengingat ucapanku yang lalu. Jika pada akhirnya tidak bisa mewujudkan, kenapa dari awal kau selalu memberi harapan?


 Firan
Firan










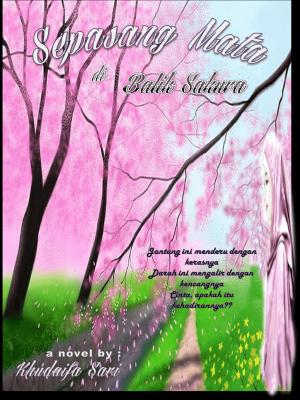
@Firan salam kenal juga.ayok mmpir je critaku yg baru. Jdulnya guruku bagus :D. Msh bnyk kurangnya juga. Akutunggu yaaa.... Trins
Comment on chapter PROLOG