Aku benci keadaan dimana saat kau membuka mata, kau tidak melihatku. Aku benci keadaan dimana aku tak bisa mengajarkanmu berjalan. Aku benci keadaan dimana aku tak bisa mendengar celotehanmu tentang kampus impian dan susahnya belajar matematika. Dan aku benci keadaan ini!—Revandira Papinka.
***
Revan menggenggam sepasang telapak tangannya erat. Entah sudah berapa kali lelaki itu mondar-mandir di depan ruang operasi—yang telah berlangsung selama satu jam. Revan duduk sembari menghembuskan nafas lelah.
“Harzel baik-baik aja, Van,” tutur Keyla menenangkan.
Beberapa teman Harzel berkumpul di depan ruang operasi. Menunggu dokter keluar dan berharap mendapatkan kabar baik. Sedangkan Sinta memejamkan mata di bahu suaminya. Matanya sembab dan wajahnya pucat.
Misella sudah di makamkan di salah satu tempat pemakaman umum. Hampir rata-rata anak-anak di sekolah dan guru-guru berdatangan mengantar raga itu ke tempat peristirahatan terakhir. Revan yang sedari tadi terdiam memutuskan untuk pulang terakhir dari pusara Misella.
Lelaki itu menaruh satu bucket bunga di atas pusara itu.
“Bukan ini yang Harzel harapkan,” tutur Revan lembut, “Dia mau lo bilang ‘maaf’ dan semuanya akan baik-baik aja.”
Lelaki itu terdiam cukup lama. Kecewa sekaligus menyesal atas insiden yang menimpa Misella. Menyesal karena sebelumnya ia begitu membenci gadis itu.
Revan kehabisan kata-kata, kemudian memutuskan untuk pergi.
Sebelum melangkah, lelaki itu menolah. Matanya berkaca-kaca. Dadanya sesak.
“Maaf..” Ucapnya terbata, “Maafin gue, Sel.”
***
Operasi selesai. Namun Harzel belum bisa dilihat secara langsung. Mereka hanya bisa menatap gadis itu dari kaca ruang ICU.
Princess Harzel terkulai lemah tak sadarkan diri. Badan gadis itu lebih kurus dari sebelumnya. Wajahnya pucat dan rona merah di bibirnya hilang seketika. Matanya terpejam dibalut kain kassa berwarna putih. Keadaan gadis itu memprihatinkan.
Revan ingat ketika Harzel akan memasuki ruang operasi. Gadis itu memegang tangannya kemudian berkata lirih, “Gue nggak takut operasi,” gadis itu tersenyum, “Karna gue mau liat seberapa bagus kejutan ulang tahun yang lo kasih.”
Revan mengangguk. Berharap Harzel benar-benar bisa melihat kejutan yang ia siapkan. Itu adalah harapan dan keinginan terbesarnya saat ini.
***
Revan menutup telpon setelah memesan kado dan kue untuk ulang tahun Harzel. Lelaki itu mengadakan pesta kecil-kecilan yang dihadiri oleh orang-orang terdekat gadis itu. Dokter berkata bahwa kemungkinan 2 hari lagi Harzel sudah sadar. Namun perban yang melapisi mata gadis itu belum bisa dilepas.
“Gue bakal buat pesta lagi kalo dia udah bisa ngeliat,” ujar Revan.
“Sebaiknya lo makan trus tidur, Van! Lo kusut banget tau nggak,” komentar Bimo memperhatikan keadaan Revan yang berantakan.
“Tapi gue tetep ganteng, kan?” Revan menyunggingkan senyum yang dipaksakan. Teman-temannya hanya menggelengkan kepala.
Merasakan Handphone miliknya bergetar, Revan meraihnya di saku celana yang ia kenakan. Nafasnya tercekat melihat nama yang tertera di layar telpon. Lelaki itu mengangkatnya.
Cukup lama keduanya terdiam. Kemudian terdengar suara wanita di seberang sana.
“Revan..”
Revan menarik nafas panjangnya, “Mama..”
“Mama denger dari Adrian, Harzel kecelakaan..” Perempuan itu menarik nafasnya. Suaranya serak, “30 menit lagi Mama berangkat dari London. Kemungkinan jam 7 malam ini sudah transit di Istanbul dan jam 6 sore besok sudah di Indonesia. Mau liat keadaan dia. Mama harap kamu nggak keberatan.”
Revan membisu. Lelaki itu sibuk mengatur nafasnya sendiri. Menyadari teman-teman memperhatikan dirinya, Revan melangkah menjauh. Mencari tempat yang aman untuk bicara kepada Dewi.
“Kalau kamu keberatan lihat Mama,” Suara wanita itu makin serak, “Kamu bisa pergi sementara Mama bersama Harzel.”
“Cukup Ma..” tutur Revan lembut. Mata lelaki itu mulai berkaca-kaca.
Seketika, perkataan Harzel terngiang-ngiang di fikirannya. Dan semenjak Harzel mengatakan itu, Revan membenarkannya. Mamanya tersesat. Mamanya terluka. Mamanya depresi. Dan ia harus membuka hatinya perlahan.
“Maaf, Ma..” tutur Revan. Tangisnya pecah seketika.
“Revan..” seru Dewi lirih. Antara kaget sekaligus terharu. Itu merupakan kata ‘maaf’ pertama yang Revan ucapkan padanya.
“Harzel bener,” lelaki itu menyeka air matanya, “Papa bakalan sedih kalau tahu anak nakalnya nggak bisa maafin istrinya. Bener, kan?”
Dewi terdiam sembari memecahkan tangisnya. Wanita itu sangat bahagia.
“Aku bakal jemput Mama di bandara. Dan besok.. kita rayain ulang tahun Harzel sama-sama.”
Dewi mengangguk, “Baiklah. Tunggu Mama!”
***
Revan mondar-mandir sembari menatap layar ponselnya. Hari sudah menunjukkan pukul 20.00, namun Dewi belum menelponnya juga. Jujur saja, Revan merasa gelisah. Sebelum berangkat dari Istanbul, Turkey, Dewi mengabarkan bahwa sebentar lagi pesawat yang ia naiki berangkat. Tak ada delay. Dan seharusnya... jam 6 sore tadi pesawat itu tiba di bandara Soekarno-Hatta.
Revan berdiri kurang lebih selama 5 jam—di depan ruang tunggu Internasional. Dewi Annisa—yang ia harapkan muncul sembari tersenyum kemudian memeluknya—tak kunjung datang.
Ponselnya berdering. Keyla menelpon.
“Ya, Key?”
“Mama lo udah sampe?” tanya Keyla. Nada suara gadis itu penuh kekhawatiran.
“Belum Key. Harzel nggakpapa?” tanya Revan.
“Harzel nggakpapa,” Keyla menarik nafas, “Gue lagi nyetir, Van. Bentar lagi sampe ke Bandara. Lo jangan kemana-mana, ya?”
Revan menghela nafas malas. Ada apa Keyla repot-repot menyetir dari Depok? Menjemputnya? “Buat apa kesini, Key? Gue bisa naik taksi.”
TUT!! TUT!!
Telepon dimatikan.
15 menit kemudian, Keyla tiba di bandara. Gadis itu berlari-lari kecil. Memasang tampang panik. Namun Keyla—yang terkenal kuat—bisa mengkondisikan segalanya. Ia bahkan menyunggingkan senyum selama berlarian. Menatap Revan dari kejauhan.
“Van..” Keyla mengatur nafasnya sebisa mungkin, “Gue mau nunjukkin sesuatu.”
Revan mengangkat alis, penasaran atas apa yang ingin gadis itu tunjukkan.
Keyla merogoh saku tasnya, mengeluarkan tablet kemudian menunjukkan artikel yang berisi berita terbaru kepada Revan. Revan meraih tablet itu dengan raut wajah tegang.
Revan menatap berita itu dengan mata melotot. Wajahnya menegang. Jantungnya memompa darah begitu keras hingga kakinya keram tak berasa.
Pesawat dari Istanbul, Turkey Tujuan Jakarta, Indonesia Jatuh Terbakar
Revan terdiam cukup lama. Hanya membaca judul artikel tanpa melihat isinya. Ia tak sanggup melakukannya.
Revan mengembalikan tablet milik Keyla, “Lo fikir pesawat dari Istanbul ke Jakarta cuma satu?” Lelaki itu mendengus, “Itu bukan pesawat mama gue.”
Lelaki itu mendekati tempat kedatangan penumpang. Rahangnya mengeras. Tidak mungkin!
Keyla mendekati Revan. Ia menyentuh bahu lelaki itu dengan perasaan gundah. Revan kembali menegang. Matanya berkaca-kaca.
Hatinya semakin mencelos melihat pemandangan di sekitarnya. Orang-orang yang memenuhi bandara ricuh atas berita yang baru saja tersebar. Orang-orang yang menunggu keluarganya tiba—seperti Revan—tak jarang menangis histeris. Berita fakta itu tersebar begitu cepat. Dan Revan tak dapat mengingkari bahwa pesawat yang kecelakaan itu adalah pesawat yang dinaiki Ibunya—Dewi Annisa.
Revan melemas. Wajahnya memucat. Dunia serasa menghantamnya. Kiamat. Tak ada lagi yang tersisa. Lelaki itu terduduk. Keyla sontak memeluknya erat. Revan sama sekali tidak menangis. Mungkin belum. Ia masih belum sepenuhnya percaya.
Wanita yang ingin segera ia peluk—entah kapan lelaki itu bisa melakukannya lagi.
“Revan, mungkin aja ada penumpang yang selamat, kan?” tanya Keyla menenangkan, “Berdoa aja itu Mama lo.”
Dan hingga tengah malam lelaki itu menunggu artikel terbaru—berharap isinya kabar baik—tak kunjung datang. Entah sudah berapa kali keluarganya menelpon, ada yang bertanya, memberi dukungan, mengungkapkan belas kasihan. Cuih! Revan tak butuh itu. Ia ingin Dewi Annisa kembali padanya.
Setelah beberapa lama. Lelaki itu menangis. Sendirian di lorong rumah sakit yang sepi. Gelap. Dan mencekam
Revan menatap foto Arnold. Air matanya menetes mengenai wajah lelaki yang tersenyum di foto itu.
“Maaf Pa..” Revan terisak. Berkali-kali ia mengatakan ‘maaf’ pada selembar foto di depannya sembari mengeluarkan tangis sederas-derasnya.
“Aku anak yang payah,” tuturnya di sela isak tangis, “Aku mengacuhkan wanita yang melahirkanku. Aku nggak bisa menjaga wanita yang Papa cintai. Aku..” Lelaki itu menangis. Kali ini lebih keras dari sebelumnya.
Seharusnya ia mendengarkan Harzel di foodcourt itu. Seharusnya ia peka atas sindiran Adrian. Seharusnya ia mengerti bahwa Dewi begitu mencintai Arnold sampai-sampai menyibukkan diri dengan berkarir agar kenangan pahit itu tidak mengganggunya. Harusnya ia menjadi pelindung ibunya, berada disisinya. Bukan justru pergi dan melontarkan kata-kata kasar.
Revan menghembuskan nafasnya yang mulai tak teratur. Tubuhnya tidak kuat lagi. Berharap seseorang menemukan dirinya jika nanti ia jatuh pingsan.
“Van..” Seseorang menyenggol bahunya.
Adrian.
Revan menoleh dengan mata yang memerah. Tidak berkata apa-apa.
“Kami semua nyari elo,” ujar Adrian. Mencoba setenang mungkin, “Kita berangkat ke Istanbul jam 3 nanti. Gue udah pesen tiket,” Adrian duduk di sebelah Revan, “Semua korban di bawa ke rumah sakit di Istanbul.”
Revan mengusap air matanya. Tanpa ragu, lelaki itu mengangguk mantap.
Adrian menarik nafas panjang, “Lo nggak mau pamit dulu?”
Revan terdiam. Sejenak, Princess Harzel—yang memenuhi fikirannya beberapa hari ini—menghilang begitu terdengar kabar menyakitkan itu.
Revan berdiri, kemudian menepuk bahu Adrian.
“Gue ke kamar Harzel dulu!”
***
Tepat jam 12 malam.
Revan duduk di sebelah ranjang Harzel sembari memegang kue ulang tahun yang telah ia pesan. Teman-teman terdekat Harzel, menunggu di depan kamar. Memberi waktu kepada Revan dan Harzel. Hanya berdua.
Gadis itu belum sadarkan diri. Matanya masih terbalut perban. Nafasnya naik turun beraturan. Bibirnya pucat. Dan tubuhnya mengurus. Sungguh! Revan benci melihat keadaan Harzel—si gadis lincah—terkulai lemas seperti sekarat.
“Selamat Ulang Tahun.”
Revan mengusap rambut Harzel. Menyingkirkan anak-anak rambut yang memenuhi wajah gadis itu.
“Gue benci keadaan dimana pertama kali lo buka mata—lo nggak liat gue,” tutur lelaki itu dengan suara serak. Tangisnya di tahan sebisa mungkin, “Gue benci keadaan dimana gue nggak bisa bantu ngajarin lo jalan. Nggak bisa dengerin celotehan tentang kampus impian lo dan susahnya belajar matematika.”
“Gue benci keadaan dimana gue nggak bisa traktir lo es krim waktu elo udah sembuh.”
“Dan gue benci keadaan ini!”
Lelaki itu menangis. Kemudian menutup wajah dengan telapak tangannya agar air bening itu tak jatuh mengenai Harzel.
“Gue harus pergi..” tuturnya di sela isak tangis, “Dan lo nggak perlu tau alasannya.”
Revan mengusap air matanya, “Masalah lo udah banyak, gue nggak mau nambah masalah lagi. Cukup lo anggap gue cowok brengsek yang ninggalin lo begitu aja.”
Revan mengusap puncak kepala Harzel, “Dan kalau keadaannya udah membaik, gue bakal cari lo sampe kapanpun. Gue janji!”
Revan mengecup pipi kanan Harzel yang dingin, “Gue sayang elo.”
Lelaki itu berdiri, menaruh kue ulang tahun di atas meja sebelah ranjang, kemudian melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia takut menoleh. Takut kembali memeluk Harzel dan tak mau pergi dari sana. Sungguh, kejadian demi kejadian menimbulkan kepiluan yang luar biasa di benaknya. Dadanya sesak. Revan bahkan kesulitan bernafas.
Revan membuka pintu kamar rawat, kemudian keluar. Teman-temannya—Faraz, Bimo, Vino, Liana, dan Sasha—berhambur memeluknya. Revan mengangguk, mengisyaratkan bahwa ia tidak apa-apa.
Revan mengiringi langkah Adrian. Dan beberapa langkah kemudian, ia melirik Harzel dari kaca tembus pandang. Gadis itu belum sadar.
Gue harap, lo suka kado terindah dari gue. Gumam Revan dalam hati.


 gigikelinci21
gigikelinci21







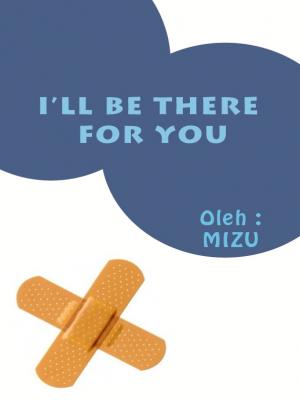

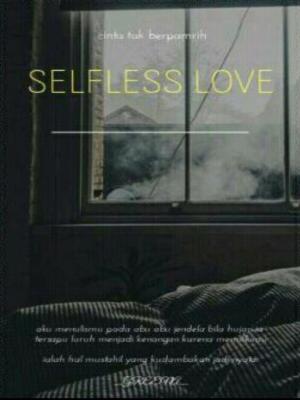
seperti lagi baca novel terjemahan. hehe. bahasanya enak dan mudah dipahami. udah kulike dan komen storymu. mampir dan like storyku juga ya. thankyouu
Comment on chapter PROLOG