Tujuh permata menghiasi langit Banjarnegara. Mereka memancarkan cahaya biru yang cemerlang. Meski tertutup kabut, tapi sinarnya tetap paling mencuri perhatian.
Bintang tujuh bidadari. Begitu, bapak menyebutnya.
Aku selalu menyukainya. Setiap cerita yang dituturkan bapak tentang bintang-bintang itu, membuatku ingin menjadi bagian dari mereka. Aku juga ingin seperti bintang, bercahaya, indah, dan dikagumi semua orang.
"Mereka itu, bidadari yang kadang turun ke bumi untuk mandi. Kalau turun hujan saat cuaca cerah, artinya mereka akan benar-benar turun. Jejak langkah mereka menciptakan tujuh warna yang berbeda, dan kita menyebutnya pelangi."
Aku mengangguk-angguk sambil sok berpikir, membayangkan bagaimana para bidadari itu turun dari langit, terus numpang mandi di bumi.
Bapak menarik tubuh kecilku dalam pangkuan, sarung yang ia kenakan membuatku merasa sedikit lebih hangat dari sebelumnya. Mataku masih terpaku pada langit sebelah barat. Saat masih kecil, teras rumah selalu menjadi tempat paling favorit buat melihat bintang.
"Kalau nanti Jea udah gede, Jea mau jadi bidadari." Aku mendongak, menjumpai wajah yang menampilkan senyum kebapakan.
"Jea juga mau tinggal di langit, Jea mau jadi seperti bintang yang bersinar. Seperti Mamak, boleh kan, Pak?"
Kadang tujuh bintang itu berdampingan dengan satu bintang, yang cahayanya tak kalah terang.
Menurut Asrul, mereka adalah gugus bintang Pleiades. Atau orang jawa menyebutnya Lintang Wuluh, yang sedang berdampingan dengan Planet Venus. Seperti april lalu, pemandangan langit senja menyajikan keindahan yang luar biasa. Saat Venus dan Lintang Wuluh hanya terpisah sekitar 2,5 derajat. Mereka berada pada 27° di atas horizon barat daya.
Pada saat konjungsi, Venus berada pada magnitudo -4,5, dan Pleiades ada di magnitudo 1,6. Saat itu, keduanya bisa kulihat dengan mata telanjang.
Tapi, apa pun penjelasan yang Asrul katakan, bagiku cerita bapak jauh lebih menarik. Aku percaya, satu bintang yang hanya terlihat pada malam tertentu, adalah mamak yang sedang merindukanku. Dan suatu saat nanti, aku ingin seperti mamak. Hidup sebagai cahaya bagi kegelapan malam. Walau hanya setitik kecil, tapi bintang selalu indah menurutku.
"Sekarang pun, Jea adalah bidadari di mata Bapak." Lelaki itu mengusap puncak kepalaku, lalu menciumnya. "Jea itu bidadarinya bapak, dan calon bidadari di surganya Allah."
"Apa Mamak juga bidadari surga?" Pertanyaanku masih sangat polos. Bapak diam sejenak, menatapku sayu sebelum menjawab.
“Iya, Nduk. Mamakmu adalah bidadari yang memiliki hati sangat putih. Dia orang yang paling menyayangimu, kamu lihat sendiri, kan?" pandangan Bapak beralih ke langit. "Sinarnya juga putih dan terang. Itu karena Mamakmu ingin menunjukkan, betapa dia sangat menyayangimu." Ada sesuatu yang bapak sembunyikan di balik mata itu, entah apa, tapi aku bisa merasakannya.
"Kalau mamak sayang sama Jea, kenapa ninggalin Jea sendirian? Harusnya kita jadi bidadari sama-sama, nanti Bapak yang jadi pangerannya." Bibirku manyun beberapa senti. Tangan bapak mengusap-usap lenganku, mencoba mengusir dingin yang tak tahu diri.
Angin yang berembus menelisik dedaunan, membawa ingatanku jauh ke seberang. Lintang Kartika masih bersinar seperti bertahun-tahun lalu. Masih seindah saat bapak selalu bersamaku.
"Masih bermimpi menjadi bidadari?"
Seseorang mendorong ayunan yang kududuki. Dan suara yang barusan kudengar, itu milik Ayas.
Mataku terpejam, menikmati ayunan yang didorong berkali-kali. Andai aku boleh memilih, aku ingin selamanya hidup sebagai anak kecil. Bukan bidadari seperti keinginanku dulu, hanya gadis kecil yang disayangi semua orang. Yang bisa selalu bercanda dan tertawa bersama bapak. Memandangi langit di pangkuannya, dan meceritakan banyak hal tentang sosok mamak. Andai mamak masih tinggal di bumi, aku pasti lebih bahagia lagi.
Tapi kenyataannya, waktu sangatlah keras kepala. Dia tidak peduli sekeras apa manusia berusaha menggenggam sebuah cerita, dia tidak pernah mau berhenti, atau mundur barang sedetik. Dia mengubah banyak hal secara paksa. Meski tidak mempengaruhi perasaanku terhadap Gus Ayas. Tapi waktu juga yang memaksaku untuk menjauhinya saat ini.
"Aku nggak mau jadi bidadari. Tapi aku ingin hidup seperti bintang."
"Bintang?" Dia berhenti sejenak, "kamu bahkan Lintang Kartika. Bintangnya bintang, Jea." Ayas menahan tali ayunan dan kakiku turun menyentuh tanah. "Kamu adalah cahaya paling terang, yang membuatku merasakan keindahan semesta, hanya dengan melihatmu."
Sehelai daun sawo jatuh di pangkuan. Menurut kepercayaan orang jawa, ketiban daun kering itu artinya ketiban sial, kita harus meludahinya agar kutukan sial itu tidak terjadi. Tapi aku hanya tersenyum, memainkan daun kering itu, lalu menerbangkannya ke sembarang arah.
Ayas sudah berdiri di hadapanku. Di tangannya ada kitab Safinatun-Najah, yang tadi ia gunakan untuk panduan kultum setelah tarawih.
"Bintangnya bintang?" Aku membeo seperti orang linglung. Dia pasti sedang bercanda, atau minimal mengejekku. Bagaimana mungkin aku menjadi bintang di atas bintang, sementara hatiku masih dipenuhi kegelapan.
"Gus," panggilku, setelah seluruh kesadaranku kembali. Yang dipanggil hanya menjawab dengan kedipan mata. Untuk beberapa detik pandanganku berada satu garis lurus dengannya, sebelum aku memilih untuk mengalihkannya pada tanah yang kupijak.
"Maaf, karena aku pergi begitu saja," kalimatku tertahan. Sesak saat harus mengingat tentang beberapa tahun lalu. "saat itu, aku hanya memikirkan bapak, sampai begitu egois padamu."
"Semudah itu?" nada bicaranya sarkatis. "Setelah kamu membuatku terjaga setiap malam. Menghapal seribu bait syair, dan menjadikanku manusia paling kutu dalam memahami kitab Alfiyah, lalu setelah itu kamu pergi seenaknya. Sekarang kamu hanya menebusnya dengan satu kata maaf?" Jawabannya membuatku semakin merasa bersalah. Ayas ternyata sangat pandai mendramatisir keadaan. "Maaf," gumamku lirih. Mungkin hanya bisa didengar oleh kelelawar yang melintas.
"Jea, kamu dengar aku. Aku tidak butuh mendengar kata maaf, atau mendengar alasanmu pergi. Aku hanya ingin kamu kembali tanpa alasan. Aku bukan lagi mencintaimu karena membutuhkan, tapi aku membutuhkanmu, karena mencintaimu. Aku bukan ingin bersamamu karena berpikir bahwa denganmu aku akan tetap hidup, tapi aku merasa tanpamu aku tidak bisa hidup."
Dia masih suka membual. Ya Allah, kenapa Ayas begitu keras kepala? Hatiku susah payah menafikan keberadaannya, tapi dengan mudah dia menarik kembali perasaan yang ingin kubuang jauh-jauh.
"Sudah malam," aku bangkit dari ayunan. "sudah waktunya tidur, nanti harus bangun lebih awal untuk masak sahur. Njenengan juga harus istirahat."
Aku membalik tubuh dengan cepat. Menyembunyikan airmata yang turun secara perlahan. Sesak yang kurasa semakin memenuhi rongga dada. Aku berjalan masuk melalui pintu belakang. Kamarku tepat di samping dapur. Berhadapan dengan kamar Simbah.
"Jea."
Suara itu memaksa langkahku berhenti. Aku hanya diam tanpa menoleh, dan menunggu apa yang akan dia katakan.
"Assalamualaikum,"
"Wa'alaikumussalam warahmatullah."
***
Jam dinding sudah menunjukkan pukul duabelas kurang lima menit. Artinya, masih ada sekitar tiga jam untuk tidur.
Dan kalau pergi mencari bapak, waktuku masih cukup banyak. Selama ini, setiap kali menembus dimensi lain, waktu yang kulalui menjadi berkali-kali lipat lebih lama dari alam nyata.
Aku memang sering kesulitan melakukan hal itu, bahkan sering gagal. Tapi sekarang, hanya dengan memikirkan tempat yang kuinginkan, dalam sekejap akan berpindah ke sana. Walau kadang masih mendarat di tempat yang kurang tepat.
"Whoaaaaaaa!" Aku mendarat di batang pohon pinus yang cukup kecil. Kalau tidak bisa menjaga keseimbangan tubuh, pasti terjatuh.
"Masih belum kapok datang ke sini?"
Seorang anak kecil yang sering muncul di mimpiku, sedang duduk santai di atas batang pohon yang lebih tinggi. Ia menggigiti akar ilalang dengan cara yang nggak biasa, seolah itu adalah makanan paling nikmat.
"Sebelum menemukan bapak, aku akan selalu datang." Aku melompat, anak itu mengikuti. Dia juga menyandang busur panah yang sama denganku.
"Seyakin apa kamu kalau bapakmu ada di sini?" langkahku terhenti sejenak.
"Seyakin aku melihatmu ada di hadapanku, Bocil!"
Dia malah terkekeh meremehkan. "Kamu bahkan tahu aku nggak nyata. Jadi kurasa usahamu juga akan sia-sia."
Dasar bocil kurang ajar. Setiap kali muncul, dia selalu menggoyahkan keyakinanku tentang bapak.
Mereka bilang bapak hilang di sini. Setidaknya aku menemukan satu petunjuk saja, apa bapak masih hidup atau benar-benar sudah meninggal. Tapi Bocah perempuan berambut keriting itu selalu mengacaukan rencanaku.
Kulayangkan busur panah untuk menggetok kepalanya, tapi dia malah menghilang.
"Aku di sini, Jea."
Bocah itu muncul lagi, menarik jilbabku sampai menutupi wajah.
Dunia mimpi yang kudatangi benar-benar mirip dunia sihir. Semua yang ada di sini memiliki kekuatan aneh. Sepertinya hanya aku yang mengandalkan kekuatan pikiran. Lihat saja, rumput-rumput yang ada di sini, pohon-pohonnya, mereka semua bisa bicara dan mengolok kedatanganku yang menurut mereka hanya kebodohan. Di sini, anginpun bisa mempunyai wajah.
Aku membenahi jilbab yang menghalangi pandangan. Dan bocah kecil itu sudah menghilang. Kabar buruknya lagi, aku sudah berpindah tempat. Sebuah rimba yang dipenuhi kabut pekat.
Jalanan yang lurus membentang luas di hadapanku. Aku mencoba menerobos badai yang menerbangkan debu hitam, entah dari mana mereka datang. Samar-samar, aku melihat seseorang berjalan menjauh. Langkahku terseret susah payah.
"Bapak! Jangan tinggalin Jea."
Isakku tak tertahan. Langkahku semakin berat. Wajah orang itu tak dapat kulihat, tapi aku yakin, dia memang bapak. Seorang ayah yang selalu kurindukan. Tapi dia sama sekali tidak menoleh. Apa mungkin bapak tidak mendengarku?
Kabut hitam perlahan memudar, segalanya terlihat lebih nyata. Rumput dan pohon-pohon di sekitar sini sudah kembali normal, seperti pohon biasa, tanpa tangan, tanpa mulut dan tidak bergerak. Tapi kenyataan yang paling pahit adalah, aku. Aku menemukan diriku yang hanya seorang diri. Benar benar sendiri. Tubuhku luruh seolah tak lagi disangga tulang. Aku tersimpuh di atas rerumputan yang sedang mentertawakan kelemahanku.
"Jea!" Satu panggilan dari suara yang tak asing.
"Je," suara itu semakin jelas, tapi tidak ada siapa-siapa di sini. Kulihat ke atas pepohonan, tapi nihil. Bocah kecil pengganggu itu juga tidak terlihat. Aku sendirian.
"Jeaaaaaaaaa!"
Suara yang melengking, menyeret paksa tubuhku kembali ke alam nyata.
"Astagfirullahhal'adzim."
Aku terbangun dan langsung meludah ke kiri sebanyak tiga kali.
"Jeaaa!" Marningsih duduk di sebelahku, mengusap-usap lengannya yang terkena ludah.
"Jorok banget, sih. Ya ampun, padahal tadi aku udah mandi, udah ganti baju, udah wangi, malah dikasih jigong!"
"Haaaah! Kok kamu di sini?" Mataku tertuju pada jam dinding, ternyata sudah setengah tiga.
"Ya iyalah, namanya juga orang baik, jadi aku mau bantuin masak. Kirainku udah bangun malah masih ngiler. Nggak malu apa sama Mas Ayas? Dia aja udah lagi baca Qur'an, eh, yang cewek masih ngebo."
Iya, kah? Memangnya Ayas bisa bangun cepet, ya? Ini kabar baru lagi buatku.
"Malah bengong. Buruan bangun, tahajud dulu. Biar aku bantu nyiapin bahan masakan." Marningsih menyeret tanganku dengan kasar, sampai hampir jatuh dari kasur. Beginilah nasib punya sepupu anarkis yang rumahnya dekat. Sudah anarkis, hobinya ngintilin Ayas pula. Jadilah pagiku penuh kekacauan. Mungkin ini alamat dari ketiban daun kering malam tadi. Aku kedatangan sial di pagi buta.


 MandisParawansa
MandisParawansa



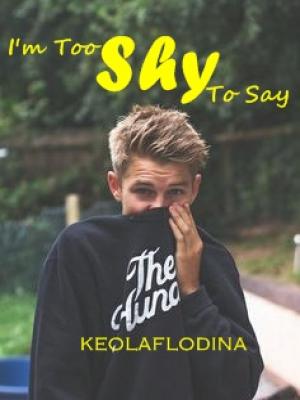






@ReonA Makasih, Kak. Baca semuanyaa, yaaa. Bantu krisannya jugaaaa.
Comment on chapter Prolog