BAB 3
Batu Karang Batulo
Hari pertama Salim sekolah berjalan dengan baik. Ia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Salim termasuk murid yang cerdas di dalam kelasnya karena sudah bisa membaca, menghitung, dan menulis walaupun belum begitu lancar. Namun, untuk ukuran anak yang baru menyicipi bangku sekolah, itu sudah jauh dari kata biasa. Kini setiap ke sekolah, ia berbarengan bersama kakakku, Iman dan Zura. Saat itu usiaku masih 5 tahun.
Setiap libur sekolah tiba, kami selalu mengunjungi rumah nenek dan rumah tante (adik dari Bapak) di Batulo (salah satu nama jalan di Kota Baubau) yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah nenek, namun sedikit jauh dari rumah kami. Jarak Betoambari ke Batulo ± 7,5km. Saat ke rumah tante, kami selalu bermain bersama para sepupu yang usianya tidak berbeda jauh dari kami. Jarak rumah Tante ke rumah Nenek hanya butuh 5 menit dengan berjalan kaki.
Tempat bermain favorit yang sering kami kunjungi adalah laut yang berada tepat di belakang rumah tanteku. Kira-kira berkisar 100 meter jarak antara laut dan rumah beliau. Laut batulo sangat jernih, dengan batu karang yang menjulang dari permukaan pesisir laut bisa kami nikmati. Panorama alam yang begitu sempurna membuat mata kami tidak henti-hentinya menatap dengan penuh senyuman, dengan pancaran alam yang begitu indah membuat kami sangat betah berlama-lama main di laut. Laut ini memang sepi, tak seramai pantai wisata lainnya. Walaupun demikian, kami selalu sabar menanti hingga air mulai surut, agar kami bisa turun ketepian laut. Bermain air. Kami seperti menemukan kebahagiaan dari setiap butir air yang menyentuh manja kulit kami. Pinggiran Laut Batulo memang sering dijadikan sebagai tempat bersandarnya perahu-perahu para nelayan. Namun, walaupun demikian, laut ini sangat bersih dan tidak mengurangi keindahannya. Para nelayan selalu menjaga kebersihan pesisir laut ini, karena laut sudah menjadi tempat mereka mencari nafkah untuk makan sehari-hari. Kota Baubau mempunyai wilayah daratan seluas 221,00 km² serta luas laut yang mencapai 30 km² hingga potensial untuk pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut.
Kebiasaan kami selain mandi di laut, kami pun sering memancing. Membawa jala istilah yang kami pakai untuk menyebut jaring-jaring kecil untuk menangkap ikan sering kami siapkan terlebih dahulu sebelum bermain. Saat air laut mulai surut, kami baru bisa beraksi. Biasanya air mulai surut sekitar jam setengah 4 sore. Pasang surut air laut terjadi karena adanya pergerakan naik atau turunnya posisi permukaan perairan laut secara berkala yang disebabkan oleh gaya gravitasi dan gaya tarik menarik benda astronomi oleh matahari.
Disaat air sudah mulai surut, kami dengan sigap lari ketepian laut. Rutinitas yang kami lakukan berbeda-beda. Ada yang mencari keong di pinggiran laut, ada yang menebarkan jalanya untuk menangkap ikan, adapula yang bermain dengan pasir laut yang memiliki banyak batu karang. Melihat pemandangan laut yang sangat indah, hanya dengan berjalan ke belakang rumah Tante, kaki kami sudah bisa menapaki pasir putih dan kami bisa memanjakan mata untuk menikmati indahnya panorama alam laut yang sangat luar biasa itu. Sungguh indah ciptaan Allah, “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?” (QS ar-Rahman: 55)
Laut yang menjadi tempat kami bermain memiliki banyak batu karang serta sisa-sisa besi berkarat yang tertinggal dan sudah tak berbentuk lagi. Entah berapa usia peninggalan besi berkarat yang kini telah menjadi rongsokan tak berfungsi. Sebenarnya apa yang sudah pernah terjadi di sini. Laut ini seakan menjadi saksi bisu kejadian dimasa lampau.
Siang menjelang sore kala itu laut sedang surut. Aku, ketiga kakakku, Salim, Iman, dan Zura serta ketiga sepupuku, Mane, Eka, dan Ape memutuskan untuk bermain di laut belakang rumah mereka. Mengumpulkan keong-keong dan kerang, memilah batu yang unik seperti batu kerikil, menangkap ikan dengan jala yang sudah kami siapkan menjadi aktivitas yang sangat tidak membosankan. Mengguyur badan kami dengan air laut, berlari-lari di tepian laut hingga batu karang yang keras dan sedikit tajam itu sudah tak berasa di kaki kami.
Sibuk dengan main air, mencari keong untuk dijadikan permainan “Pekatende” semacam permainan bola bekel serta mencari kerang, mencari batu-batu unik, dan menangkap ikan membuat kami terhanyut dengan permainan kami. Satu persatu kami mulai berpencar mencari kesenangan masing-masing. Saking sibuknya, hingga kami tak memperhatikan satu sama lain. Tak terkecuali Salim yang lagi berjalan menuju besi berkarat nan tajam yang sudah tak karuan bentuknya. Entah apa yang dicari Salim sehingga mendekati besi tua itu. Anak ini memang selalu penasaran dengan apapun yang dilihatnya. Ia mendekati dan tanpa ia sadari betisnya robek terkena besi tua karatan yang bertengger di sebelah perahu para nelayan. Darah bercucuran deras. Luka robekan sekitar 3cm. Salim yang belum sadar akan hal itu, menunduk ke bawah kakinya dan melihat cucuran darah sudah mengalir deras di betisnya. Kami semua panik melihat kejadian itu. Rasa tegang tiba-tiba menggetarkan dada kami. Ketakutan menghantui pikiran kami melihat darah yang tidak berhenti keluar dari betis Salim. Warna merah jernih seperti pewarna kesumba (Kesumba merupakan tanaman perdu yang dikenal sebagai penghasil pigmen merah (bixin) dan penghasil norbixin atau pewarna alami untuk makanan dan kosmetik) yang sering kami gunakan untuk mewarnai baju. Salim dengan tenang dan santainya tidak mengeluh sama sekali. Seakan-akan hanya rekayasa belaka yang dibuatnya agar kami semua panik.
“Kakimu berdarah. Kena apa itu, Bau?” sapa kakakku, Iman dengan paniknya.
“Da kena besi itu kayanya. Tapi, tidak sakit, kok. Tenang saja.” da = “dia” yang ditujukan pada betisnya.” jawabnya santai sambil menunjuk besi yang ada di belakangnya. Salim mencuci betisnya yang penuh darah dengan air laut.
Kami yang melihat kejadian itu seakan tersihir. Kami berhenti bermain dan langsung buru-buru menuju kerumah nenek. Dengan baju basah yang masih melekat di badan, sepanjang jalan dari laut ke rumah nenek, aku, Iman, dan Zura ketakutan, namun Salim malah hanya tersenyum seakan tak terjadi apa-apa padanya. Kami mempercepat gerakan kaki untuk melangkah. Cucuran darah yang mengalir dari betis Salim tak kunjung berhenti. Untuk sampai ke rumah Nenek, kami harus melewati hutan kecil yang jaraknya sepanjang 150meter. Hutan kecil ini memang sedikit rada angker bagi kami. Bagaimana tidak, tiap kami melewatinya, kami selalu dibuat merinding sebab harus melihat biji-biji merah berbintik hitam mengkilat licin yang bertebaran di bawah tanah. Kami menyebutnya biji mata setan. Pohon saga penghasil biji yang menyeramkan untuk kami, tertancap dengan sangat kokoh.
Pada era 1990-an mata setan ini sangat tenar kisahnya di kalangan kami. Saat kami kecil, biji mata setan ini konon adalah mata setan yang berjatuhan di hutan yang biasa kami lalui. Setan semacam drakula yang katanya memangsa anak bayi dan janin yang masih dalam kandungan. Sadis sekali. Jadi, saat isu tak berdasar itu muncul ke permukaan, banyak ibu-ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan, menggantungkan bawang putih ke baju mereka dan baju bayinya. Mereka berkeyakinan bahwa dengan bawang putih akan mengusir setan jahat yang mengganggu.
Kami terus berjalan beriringan. Kami sudah tidak peduli dengan hutan yang kami lalui di sepanjang jalan. Kami hanya fokus pada luka betis Salim. Kami tak pernah membayangkan kemarahan Bapak pada kami nantinya. Kami sangat tau persis kalau di antara kami ada yang terluka, suara oktaf Bapak sudah pasti menggelegar di dalam rumah detik itu juga.
“Sudah, santai saja Mi jalannya. Capek saya ikut gerakan kalian,” kata Salim yang mulai ngos-ngosan mengikuti langkah kami yang makin cepat seakan sedang berlomba untuk jalan cepat. Darah Salim mulai membuat jejak di sepanjang jalan kami. “Mi= kata tambahan sebagai penghias kalimat, biasanya terletak di belakang kata. Tak memiliki makna yang berarti.”
“Santai… santai… santai!!! Bagaimana bisa santai. Ko tidak liatkah itu darah kakimu tidak berhenti-henti. Sudah kaya pancoran keran,” kata Zura yang menarik tangan Salim agar tak berhenti berjalan.
“Tenang saja. Tidak sakit ini. Saya saja heran kenapa berdarah, padahal tidak sakit sama sekali. Serius saya ini! Tidak bohong. Sebentar, kita berhenti dulu! Mungkin tadi itu ada cat warna merah di besinya itu,” kata Salim dengan wajah serius yang tiba-tiba menghentikan langkahnya.
“Kau serius itu, Bau?” langkah kaki Iman pun terhenti. Ternyata ia juga penasaran. Kami berempat pun berhenti sejenak.
“Seriuslah saya. Sebentar saya raba dulu. Ada lukanya apa tidak,” kata Salim yang tangannya mulai meraba luka di betisnya. “Aduuuhhh!” Salim menarik tangannya, seperti terkena setruman listrik.
“Bagaimana?” kata Zura. Kami penasaran mendengar pernyataannya.
“Luka benaran kayaknya. Dia sakit pas saya pegang,” katanya tersenyum nyengir sambil melap tangannya ke baju yang ia kenakan.
“Ahhh, bodohnya Mi kita juga. Mana ada cat air mengalir terus begitu,” kata Iman yang kini melanjutkan perjalanan.
“Ehh, tunggu dulu…” Salim berhenti kembali.
“Kenapa lagi la bau eeee,” kata Zura yang mulai gemes dengan tingkah adiknya itu. Kami semua menoleh kearah Salim.
“Kalian tidak taukah, gosib-gosib terkini, kalau katanya sekarang lagi banyak setan yang cari darah manusia? Coba kau perhatikan itu darahku yang menetes sepanjang perjalanan kita ini,” Salim membalikan badannya sambil menunjuk jejak darah yang membekas sepanjang perjalanan kami. Kami pun mulai menyimak kembali ceritanya.
“Kalian tahu, kan? Kalau ada darah begitu, nanti setan drakulanya dia kejar kita. Dia pasti datang itu nanti. Coba saja kalau kalian tidak percaya. Tunggu Mi sebentar lagi. Saya juga penasaran soalnya,” kata Salim memajang muka serius penuh ekspresi. Kami menengok kebelakang. Kami sangat khawatir sekali kalau benar-benar drakula itu akan datang menghampiri kami yang tak berdaya ini. Kami dibuat gemetar. Kaki kami seakan kaku menunggu apa yang akan terjadi pada nasib kami. Kami seakan pasrah jikalau hari itu nyawa kami melayang karena tergigit oleh drakula pemangsa darah manusia itu. Kami menunggu sambil berpegangan tangan hampir 2 menit. Namun, setannya tak kunjung datang.
“Kenapa tiba-tiba bulu kudukku rasanya berdiri semua e?” kata Salim dengan wajah yang serius.
“Ahhh, serius kau ini. Jangan kau takut-takutkan kita,” Iman mulai tak konsentrasi. Kami ketakutan seperti mati rasa di sekujur tubuh.
“Serius ini. Kedinginan saya. Makanya merinding ini buluku,” Salim menertawakan ekspresi muka tegang kami yang jeleknya minta ampun.
“Lagian mau-maunya kalian percaya sama hal seperti itu. Mana ada drakula. Terlalu banyak nonton TV kalian ini. Dibodoh-bodohi sama film,” kata Salim yang tak henti-hentinya ketawa ngakak sambil menggeleng-gelengkan kepalanya melihat muka kami yang tiba-tiba berubah menjadi sangat marah karena telah ditakut-takuti olehnya.
“Gila benar kau ini, Bau. Kau tidak tau kah kalau rasanya kakiku ini dia kaku sekali???” kata Zura dengan muka yang amat sangat marah. Dia seakan ingin menerkam Salim. Kami pun melanjutkan perjalanan sampai ke rumah nenek.
Kami tak lagi memikirkan sang drakula mitos orang-orang yang lagi membuming itu. Pikiran kami kini kembali fokus ke kondisi kaki Salim. Sepertinya kami lebih takut melihat Bapak marah dari pada harus bertemu drakula itu.
Gerakan kaki kami dipercepat, hingga tibalah kami di rumah Nenek. Mama yang kala itu sedang duduk ngobrol di ruang tamu, seketika bangkit dari kursinya dan menghampiri kami yang baru saja masuk. Mama kaget sejadi-jadinya melihat Salim datang dengan luka di betis. Nenek pun tak kalah paniknya melihat cucunya sudah beroleskan darah segar. Hari itu kebetulan Bapak tak ikut bersama dengan kami. Bapak lagi ada urusan yang harus diselesaikan, begitu kata mamaku. Mama tak banyak bersua. Ia langsung mengambil serbet yang masih bersih di atas meja untuk menghentikan darah yang mulai mengering namun masih saja mengalir.
“Tadi kena besi di laut, Ma, tapi tidak sakit, kok,” Salim berusaha menenangkan Mama yang terlihat sekali tak bisa menyembunyikan rasa paniknya.
Tanpa basa-basi Mama langsung membawa Salim ke mantri terdekat dari rumah Nenek. Kala itu masih terlalu susah untuk mencari dokter yang buka praktek. Biasanya dokter hanya bisa kami temukan di RS. Untuk sampai ke RS, pasti akan memakan waktu. Mantri memang yang paling banyak saat itu. Dengan empat jahitan luka di betis tanpa tangisan dari Salim, akhirnya iapun dibawa pulang kembali oleh Mama ke rumah Nenek. Jam terus berputar. Tidak terasa pukul 19.00 menunjukkan waktunya. Saatnya kami pulang.
Setibanya di rumah, Bapak sudah menunggu kami di depan rumah. Menyambut kedatangan kami. Anehnya hari itu, Bapak tidak marah sama sekali pada kami saat melihat kecerobohan kami hingga meninggalkan luka di betis Salim. Bapak hanya bertanya pada Mama apa yang telah terjadi. Setelah mendapat penjelasan dari Mama, Bapak hanya menasehati kami, “Kalian harus lebih berhati-hati dan saling menjaga, karena Bapak tak akan selamanya bisa menjaga kalian.”
Sangat tidak biasa kalau bapak menanggapi hal seperti ini dengan sangat biasa dan santai. Bapak biasanya pasti marah kalau kami nakal apalagi sampai ada yang terluka. Jatuh dari tangga rumah yang anak tangganya hanya tiga tanjakan bisa membuat Bapak memarahi kami tanpa henti. Tapi, ada yang berbeda dari sikapnya hari itu.
Kutatap wajah Bapakku. Kuperhatikan tiap tingkahnya. Sepertinya ia banyak pikiran hari itu sehingga tidak ada lagi semangat yang kutengok dari wajahnya. Setelah masuk rumah, Bapak langsung masuk kamar. Tidak biasanya beliau bersikap dingin seperti itu. Biasanya kami habiskan waktu malam kami dengan bercanda gurau di depan TV dan bermain dengan kucing peliharaan kami yang ditemukan Bapak di depan rumah sebulan yang lalu.
Kucing kecil buluk yang malang dan tak terurus itu ditemukan Bapak di pojok teras belakang rumahku. Kira-kira usianya saat itu 3 minggu. Dengan bulu berwarna coklat dan terdapat tanda hitam bulat seperti tompel di dekat mulutnya. Saat ditemukan, kondisi kucing itu seakan tak punya harapan hidup. Kurus dan lusuh. Sekali keserempet oleh kaki orang dewasa, mungkin langsung tak bernyawa. Jika angin kencang berhembus, ia pun mungkin akan diterbangkan tak tentu arah. Bapak memang pecinta kucing. Ia memberi makan kucing itu dan menjadikan kucingnya bagian dari penjaga rumah kami. Kami merawat dan mengasuh kucing berwarna kuning kecokelatan itu dengan sangat baik. Kini bulunya yang sangat kotor dan tak terurus itu menjadi bulu yang bersih dan sangat lembut. Tiap hari diberi makan dan dirawat. Kucing peliharaan ini diberi nama Tanda Muncu yang artinya tanda yang ada di mulut. Muncu diambil dari bahasa daerah Baubau yang artinya ‘mulut’. Kucing yang sangat disayangi oleh keluargaku ini tiap hari diberi makan, diajari, hingga saat ingin buang air besar maupun kecil si Tanda Muncu selalu ke WC dan hanya mau makan kalau diberi makanan. Kucing yang kami rawat bersama dalam rumah ini selalu menjaga rumah kami saat kami tidak berada di rumah.
***
Keesokan harinya, aktivitas dimulai seperti biasa. Mama, Bapak, Iman, Zura ke sekolah, kecuali Salim. Kakinya masih luka, hingga mengharuskannya menetap di rumah untuk hari ini. Ia tak diizinkan keluar rumah dan bermain di luar. Biasanya aku dibawa untuk ikut bersama Mama ke sekolah saat Mama mengajar, namun karena Salim sendirian di rumah, jadi aku diutus Mama untuk menemani kakakku yang lagi sakit itu.
Hari itu teman sepermainanku, Elin (tetangga yang rumahnya persis di samping kanan rumahku) mengajakku untuk main ke rumahnya. Elin adalah anak ke-3 dari 4 bersaudara. Kakak pertamanya adalah Mail yang juga teman dari Iman dan Salim karena usia mereka hampir sama.
“Kau jaga rumah dulu e. Saya mau main dulu di rumahnya Wa Elin,” kataku pada Salim. Kami berempat memang tidak pernah memanggil dengan menggunakan sebutan kakak di depan nama. Iman dipanggil tanpa ada sebutan kakak di depannya. Sengaja seperti itu agar tidak ada jarak pemisah di antara kami dan kami lebih nyaman dan merasa lebih akrab tanpa mengurangi rasa hormat kami pada kakak yang lebih tua.
“Iyo, sana mi,” jawabnya yang sedang asyik menonton TV. Akupun bergegas keluar rumah dan bermain di rumah Elin.
Bermain petak umpet, bermain karet, semua jenis permainan anak kecil kami jabanin. Karena keseruanku bermain, aku tidak sadar kalau sudah hampir jam setengah 1 siang aku bermain di rumah Elin. Mamanya Elin pun yang sudah selesai masak mempersilakan aku untuk makan sebelum pulang ke rumah.
“Dini… sebelum pulang, nanti kau makan sama Wa Elin dulu, ya,” kata mamanya Elin padaku. Akupun mengiyakannya. Maklumlah masih anak kecil. Tak ditawarkan pun mata kami sudah jelalatan mencari makanan. Aku dan Elin pun makan bersama. Makanan yang disajikan di rumah Elin tak jauh berbeda dengan yang biasa Mama masak. Rasa laparku benar-benar tergugah setelah melihat masakan mamanya Elin. Aku lahap sekali, seakan rongga di perutku tak ada sela. Rasa ngantukku pun melanda dengan sangat kencang. Aku berpamitan pulang ke rumah untuk tidur. Setibanya di rumah, ternyata keluargaku sudah berkumpul. Ada ketiga kakakku, Mama, dan Bapak yang sedang duduk menungguku di ruang makan. Keluarga kami memang selalu makan bersama.
“Assalamualaikum,” salamku saat masuk rumah.
“Waalaikumsalam,” jawab kompak keluargaku yang sedang menungguku makan di meja makan.
“Kemana saja, Nak? Ayo, makan dulu,” kata mamaku yang sedang menyendok nasi untuk Bapak.
“Saya sudah makan, Ma, di rumah Wa Elin,” jawabku singkat. Tiba-tiba Bapak langsung bangkit dari kursinya dan memanggilku. Ia melotot melihatku, namun lototannya hari itu nampak sedikit sayu. Tidak seperti biasanya. Tidak sesangar dan sesadis biasanya. Walau demikian, aku tak kuasa menatap matanya. Kudekati Bapak sambil menunduk.
“Di luar sana masih banyak orang yang susah cari makan. Kamu yang hanya main saja sudah bisa dapat jatah makan. Bukannya Bapak melarang kamu terima ataupun menolak pemberian rezki dari Allah. Tapi, Bapak mau kalian dapat sesuatu dari orang lain itu karena kalian ada usahanya. Setidaknya Bapak bisa mengajari kalian dari kecil, untuk bisa memahami arti mendapatkan sesuatu dengan usaha, bukan hanya menerima. Itu hanya bikin kalian manja dan tidak mau kerja keras nantinya,” kata Bapak tegas.
“Nak, Bapak ingin kalian lebih banyak memberi dari pada menerima. Bantulah dan berilah orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Lebih baik tangan di atas dari pada di bawah,” Bapak menurunkan nada suaranya. Oktafnya turun drastis sampai dengan nada yang lebih slow, namun aku masih tetap dengan posisi menunduk. Sepertinya Bapak sangat paham kalau aku benar-benar takut jika ia sedang marah.
Aku menangis tersedu-sedu. Bapak selalu terlihat ganas saat marah. Namun, ia tak pernah sekalipun memukul kami. Suaranya memang lantang sekali dan matanya tajam menusuk.
Bapak mendekat padaku dan mengusap rambutku dengan sangat lembut. Rasa ngantuk yang mendera kini hilang seketika. Mulai saat itu, tertanam di memori ingatanku kalau kita tidak boleh mendapatkan sesuatu secara instan jika tidak dibarengi dengan usaha dan kerja keras. Tidak boleh menjadi anak manja. Harus belajar mandiri untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Harus selalu membantu sesama. Bapakku memang mendidik kami agar bisa mandiri sejak kecil. Bapak tidak ingin kami jadi anak lemah yang selalu dimanjakan. Aku tahu Bapak keras pada kami karena beliau tidak ingin kami menjadi peminta, tapi harus menjadi pemberi. Kami diajarkan untuk berusaha. Urusan hasil biarkan menjadi urusan Allah.
Bapak memang sangat istimewa untuk kami. Disaat Bapak marah, Bapak memang sangat menakutkan. Tapi, kami tahu jelas bahwa ia melakukan itu semua untuk kebaikan dan kami yakin suatu saat nanti kami bisa menerapkan semua pelajaran yang beliau ajarkan untuk kami kelak.


 IndyNurliza
IndyNurliza








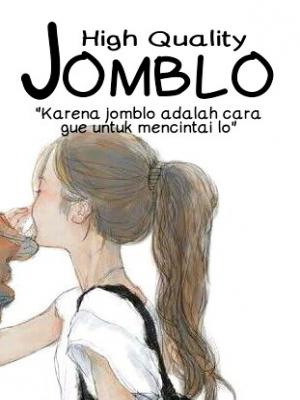

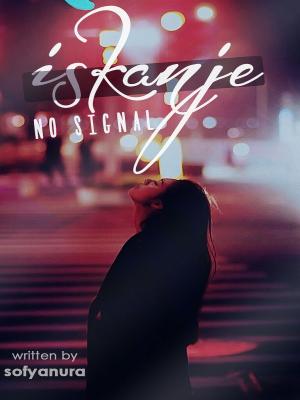



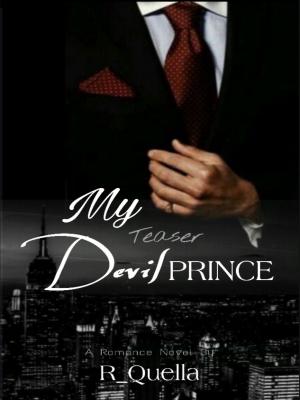


Mantaap
Comment on chapter BAB 1 : Colorful Life