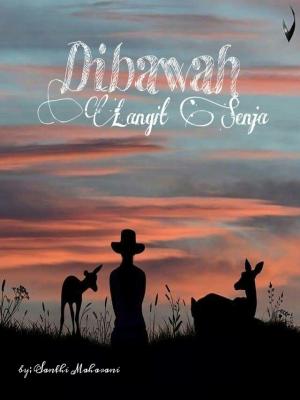Keputusan Akhir
Di perempatan jalan ini kita berpisah
Hanya karena berbeda arah
--Obic Adnanie--
J u l i a n
Pagi itu maison de rêve cukup tenang. Gue gak tahu hari libur nasional apa yang menyebabkan anak-anak masih tertidur dengan nyenyak di kamarnya masing-masing—termasuk Dennis dan Cakka. Sayangnya, gue harus terbangun di pagi hari yang cerah ini karena perut gue sangat sakit dan gak bisa ditoleransi lagi.
Walaupun gue terburu-buru berlari ke arah kamar mandi, mata gue sempat menangkap pintu kamar Jhordan—yang terletak di lantai atas—terbuka. Gak biasanya gue melihat pintu kamarnya terbuka, apalagi di hari libur seperti ini. Biasanya, pintu itu akan tertutup sampai tengah hari, dan gue tahu, pintu yang terbuka itu lah yang menandakan bahwa Jhordan belum pulang.
“BAANG IJUUUUL,” pintu kamar mandi diketok dengan hebohnya, membuat gue tersentak dan bangun dari lamunan gue yang sedang memikirkan Jhordan. “Bang! Bang…. Oy! Lama banget sih, Bang, Cakka gak kuat.”
Gue mengernyit kesal. Ya, lagian, selalu aja begini. Setiap gue lagi nongkrong indah di kamar mandi, pasti ada yang mengganggu. “Di kamar mandi atas aja kenapa, sih. Kamar lo kan di atas,” jawab gue pelan. Tapi, ketokan itu semakin kuat dan membuat gue akhirnya mengalah untuk segera keluar dari kamar mandi.
“Di atas ada Bang Sena, gak tahu lagi semedi kali di kamar mandi,” jawabnya Cakka sambil menahan sakit perutnya. “Lama banget dari tadi, udah satu jam kayaknya.”
Gue berakhir membuka pintu cepat dan segera keluar. “Kenapa gak dari tadi sih?”
“Ya, kan tadi belum pengen berak, Bang. Gimana, sih, Abang malah ngatur-ngatur jadwal berak Cakka?” Cakka misuh-misuh sambil segera memasuki kamar mandi dan menutup pintunya kencang.
Gue menggeleng-gelengkan kepala, terlebih ketika ternyata kamar mandi atas juga sedang diketok-ketok dengan heboh. “Sen! Sen! Gue gak kuat, buruan!” Ujar Dennis panik. “Sen, kalau gak keluar-keluar, gue terpaksa lari ke rumah Babeh Rahmat, nih.”
“YA UDAH KE SANA AJA!”
“Ih buruan sih, Sen, ini gue juga gak kuat,” Yoga ikut-ikut memegang perutnya sambil meringis. Kalau Jhordan gak lagi kabur dari sini, pasti dia juga ikut mengantri di belakang Yoga, atau mungkin dia akan menyerobot antrian dengan semena-mena.
Jhordan tidur di mana, dah. Udah makan apa belum tuh bocah. Mending kalau dia pulang ke rumahnya, seenggaknya walaupun dia gak berinteraksi sedikit pun dengan bapaknya, di sana Jhordan gak akan mati kelaparan. Tapi sekarang? Telepon gue gak diangkat, chat-chat gue hanya berakhir dalam tanda ‘read’. Ah elah, ke mana sih si Jhordan ini?
“Heh-heh, mau ke mana lo?” Tanya gue pada Brian yang keluar kamar tiba-tiba dan melangkahkan kakinya menuju ke kamar mandi.
“Ada siapa di dalem?”
“Cakka,” jawab gue. “Lo sakit perut juga?”
“Iya, sakit banget,” jawab Brian, meringis juga. “Ka, buruan deh, gue sakit perut!”
Gue mengernyit melihat seisi kos menjadi heboh berebut kamar mandi. Lah, kenapa pada sakit perut semua, sih? Seinget gue, setelah makan malam kemarin semua anak langsung tidur. Yang jelas sih, tadi pagi gue bener-bener sakit perut karena gue makan makanan yang cukup pedas saat malam, tapi mereka? Nasi goreng gak akan bikin mereka tiba-tiba jadi mules kayak gitu, kan?
Tadi malam, rencananya Yoga akan memasak untuk kita semua—kebetulan karena besoknya pun akan libur, tetapi rencananya berubah ketika tiba-tiba Dennis yang baru pulang dari masjid membawa sekantong nasi goreng. Kata Dennis, anak Babeh Rahmat sedang pulang dari rantauannya, dan Babeh pun akhirnya memberikan sekantong makanan tersebut, sekalian membelikan untuk anaknya.
Kalau memang masalahnya ada di nasi goreng itu, kemungkinan besar Babeh Rahmat dan anaknya sedang berebut kamar mandi. “Heh, Jul, lo gak akan kemana-mana hari ini?” Tanya Yoga dari lantai atas, masih mondar-mandir gak jelas menahan sakit perutnya.
“Gak tahu,” jawab gue asal. Pikiran gue berkelana mengingat ada jadwal apa gue hari ini—ciela sok sibuk banget gue. Kalau gue pikir-pikir sih, kayaknya gak ada rapat hari ini. Bagus lah, gue bisa tidur seharian. “Kayanya aing gak ada jadwal apa-apa deh. Maneh juga?”
“Gue….,” Yoga terlihat berpikir. “Rapat kayaknya.”
Gue mendengus, “Iya, tau lah orang sibuk mah beda,” ujar gue sambil memasuki kamar, sebelum akhirnya suara Yoga kembali mampir di telinga gue. “Eh teater lo itu kapan, sih? Gue gak sabar pengen nonton,” ujar Yoga sambil nyengir.
Mendengarnya, gue hanya diam dan gak kunjung menjawab. Gimana caranya gue harus cerita sama mereka ketika sejak setengah tahun kemarin gue sudah koar-koar akan menjadi pemeran utama di The Mask? Gue kalah sebelum bertanding, gue sendiri tahu akan hal itu. Tapi, walaupun gue bukan orang yang mudah mengalah untuk mendapatkan sesuatu, kali ini gue harus.
Gue berakhir nyengir dan menjawab ragu, “Tunggu aja ya, kabarnya.” Berniat ingin segera keluar dari pertanyaan-pertanyaan Yoga yang gak puas mendengar jawaban gue, suaranya malah mendistraksi gue kembali, “Tuh kan, lo gak cerita sama gue.”
Yoga menghela napas, “Tungguin gue di dapur, temenin gue masak.”
Gue mengangguk-angguk, mengubah destinasi gue menuju dapur. Setelahnya, gue hanya termenung di sudut meja makan. Gue—yang tadinya sudah sedikit demi sedikit melupakan—akhirnya teringat kembali. Gue harus gimana kalau gue memang gak bisa?
Dulu—mungkin sekitar lima tahun yang lalu?—ekskul teater di sekolah gue adalah ekskul yang sangat diminati oleh banyak orang. Gak perlu tanya kenapa, selain karena ekskul teater berdedikasi tinggi dalam peningkatan prestasi sekolah, keberadaan seorang Oryza Atjana yang sangat eye catching memang menarik para murid untuk mau bersenggol-senggolan demi mendapat formulir teater.
Saking terkenalnya ekskul teater sekolah gue, dan saking banyak peminatnya, cara masuk ke dalam ekskul teater mulai berubah—mulai dari seleksi biasa, hingga akhirnya banyak permainan uang. Gue kadang gak mengerti, sepenting apa sih ekskul teater buat mereka-mereka yang rela merelakan uangnya—yang buat gue udah bisa jadi biaya hidup gue selama satu tahun? Toh mereka gak akan dikeluarkan dari sekolah hanya karena gak bisa ikut ekskul teater? Toh ada ekskul-ekskul lainnya yang sama bagusnya? Gak ikut ekskul teater juga gak akan membuat lo mati.
Perlahan, setelah mengenal Oryza Atjana lebih dekat, akhirnya gue mengerti.
Dan setelah Oryza Atjana menghancurkan masa lalu gue, akhirnya gue sangat-sangat mengerti.
“Julian,” tanya Oryza waktu itu. “Lo kenapa sih suka teater?”
Gue menoleh dan mendapati matanya berbinar-binar penasaran. “Buat gue, tampil di pementasan teater bisa bikin gue jadi orang lain. Bukan berarti gue gak suka jadi diri sendiri, tapi rasanya beda banget ketika gue coba memahami karakter orang lain.”
Oryza mengangguk-angguk paham. “Seandainya, Yan, seandainya lo gak bisa lanjut di teater ini, gimana?”
Gue mengerutkan dahi gue, membuat kedua ujung alis gue menyatu. “Maksudnya?” Hari itu gue gak mengerti maksud pertanyaan Oryza, dan dia pun hanya membalas dengan sebuah senyuman—senyuman yang gue kira adalah senyuman paling tulus dari dalam hati dia buat gue.
Setelah pertanyaan dia hari itu, semuanya berjalan biasa saja. Seorang Julian bahkan menjadi sangat dekat dengan Oryza. Oryza selalu menjadi orang yang duduk di motor gue setiap sore hari, dia juga akan menjadi seseorang yang menemani gue di kantin sambil berlatih dialog.
Gue pernah berbincang-bincang dengan Mama mengenai Oryza, dan mengenai masa depan gue. Mendengar gue yang bergelut di bidang teater, Mama sangat bangga. Toh Mama juga adalah seorang violis yang sangat handal, yang sering tergabung dalam orkestra-orkestra besar atau sebagai pengiring pada teater kelas dunia. Tapi, tidak dengan Papa yang mengatakan bahwa sudah semestinya anak laki-laki masuk jurusan yang punya prospek kerja besar di masa depan.
Meski Papa sebenarnya gak ‘terlalu’ memaksa gue, sedikit banyak omongannya mempengaruhi cara gue dalam berpikir, membuat gue akhirnya ingin membuktikan pada Papa, bahwa gak harus dengan menjadi anak teknik atau menjadi dokter untuk sukses.
Salah satu pembuktian itu ingin gue lakukan di sebuah pementasan teater yang judulnya sudah terpampang besar di mading sekolah. Sampai saat ini, gue masih ingat judulnya, Lonely. Jadwal casting pun sudah gue catat baik-baik. Pemeran utamanya fleksibel, bisa laki-laki bisa juga perempuan, yang mengakibatkan tidak adanya peran utama wanita dan peran utama laki-laki.
Dan yang paling membuat gue ingin ikut di sana adalah, jika kelompok teater itu menang di perlombaan, para pemain terbaiknya akan mendapatkan beasiswa ke luar negeri untuk kuliah, sekaligus tergabung dalam kelompok teater dunia ternama. Papa dan Mama gak perlu lagi memikirkan biaya kuliah gue, itu yang gue inginkan saat itu.
Semua orang mengenal gue sebagai sosok yang sangat ambisius—di bidang teater, bukan di bidang pelajaran. Menurut mereka, gue bisa memainkan banyak karakter dengan baik, gue juga sangat cepat berlatih, dan mudah sekali menghapal dialog, maka dari itu banyak orang yang ingin gue menjadi pemeran utama di Lonely.
Tapi, lo tahu kan, siapa saingan gue untuk menjadi pemeran utama di sana?
Ya, Oryza Atjana.
“Julian, sumpah ya, maneh keren banget woy kalau jadi pemeran utama di sini!” Temen gue dulu—Gifari namanya—berlari-lari menuju kelas gue untuk menunjukkan poster sebesar daun pintu yang sudah ia gulung. “Maneh harus ikutan casting. Cocok pisan!”
“Iya, gue emang mau ikut casting, kok…”
“Saingan maneh Oryza, tapi aing yakin sih pasti maneh yang menang,” ujar Gifari sambil memasukkan poster itu ke dalam tas gue hingga tas gue gak bisa ditutup.
Dulu gue gak pernah menganggap Oryza sebagai saingan gue. Gue menganggap dia sebagai….cinta pertama gue. Sebagaimana gue saat ini yang petakilan dan sering banget bercanda, dulu gue juga begitu. Gue tipe anak yang sebenernya gak badung-badung amat, gue masih siswa dalam batas wajar. Tapi walaupun gue sering bercanda dan ngegodain cewek-cewek kelas—sebenarnya gue gak ada maksud apa pun, seneng aja liat mereka teriak-teriak—saat berhadapan dengan Oryza, gue bisa menjadi manusia yang diam seribu bahasa.
Oryza Atjana added you by phone number.
[Oryza Atjana]
Halo, ini Julian yang anak teater, kan?
“Men! Oryza ngechat aing woy, gila aing mimpi apa semalam?” Gue menabok punggung Gifari yang sedang serius mengerjakan tugas saat itu. Sama kagetnya dengan gue, Gifari berakhir naik ke atas kursi dan memandangi handphone gue dari atas. Tau dah apa faedahnya naik-naik begitu, padahal tinggal liat doang. “Demi apa? Oryza anak bahasa yang ada di teater itu kan? Kan bareng lo juga, Jul?”
“Iya, tapi kan gue gak pernah ngobrol,” jawab gue sambil sibuk memikirkan balasan yang tepat.
[Julian]
Iya? Ada apa, ya?
“Udah keren belum jawaban gue, Gif? Cool gitu, kan?”
“Halah,” Gifari mencibir. “Keren tuh kalau lo jawab ‘Y’ doang.”
“Jahat bego itu mah,” gue menoyor Gifari,
[Oryza]
Bisa ketemu gak?
Hari itu mata gue terbelalak. Oryza? Ngajak gue ketemu? Gue baca puisi di depan aja terbata-bata, apalagi kalau gue harus ngomong di hadapan Oryza? Gue kira, dia mengajak gue bertemu untuk urusan teater, tapi ternyata dia mengajak gue makan saat itu, berdua, di sudut kantin, diiringi semilir angin senja.
Udah keren belum suasana tempat gue jatuh cinta pertama kali?
Tepat saat itu lah, Oryza bertanya kenapa gue suka teater. Sebenarnya, gue gak tahu apa yang membuat gue jatuh cinta pada Oryza. Kalau dibilang cantik, Oryza sangat-sangat cantik, tapi gue gak suka dia karena hal itu.
Gak pernah satu hari pun gue berpikir untuk menembak Oryza dan menjadikannya pacar gue. Gue pikir, kita yang cukup dekat setelah pertemuan itu sudah cukup bagi gue. Yang penting, kita bisa sering bareng sepulang latihan.
Tapi, pada tanggal 14 Maret 2014, Oryza Atjana mengajak gue bertemu lagi—tiba-tiba. Dia menyatakan perasaannya pada gue. Gue yang sama sekali gak mengerti dengan perasaan gue sendiri hanya berkata, “Kok cewek yang nembak, sih?” Kemudian kita sama-sama tertawa. “Gue aja ya, yang nembak?”
Gue berakhir meminta dia menjadi pacar gue.
Dan saat ini, keputusan itu adalah keputusan yang paling gue sesali saat ini.
***
O r y z a
Cinta pertama.
Berbicara tentang cinta pertama mungkin lucu. Cinta pertama bisa datang ketika lo gak sengaja bersenggolan dengan seseorang di dalam bus. Atau bisa saja ketika lo duduk di suatu tempat sendirian, dan tiba-tiba ada seseorang yang datang duduk di sebelah lo, berakhir dengan kepo tentang segala sesuatu tentang lo.
Ada orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama, ada orang yang butuh banyak percakapan untuk membuatnya jatuh cinta. Ada orang yang sadar bahwa dia telah bertemu dengan cinta pertamanya, ada juga orang yang sama sekali gak sadar, dan baru menyadarinya setelah cinta pertama dia mulai pergi dari hidupnya.
Gue adalah orang yang kedua.
“Oryza, lo kenal Julian?” Tanya Tasya, teman gue saat SMA dulu.
Gue mengernyit saat itu, “Julian?” Gue bukan tipe orang yang senang memperhatikan keadaan sekitar, apalagi menghapalkan nama orang di sekitar gue. “Anak teater juga?”
“Iya anjir, lo masa gak tahu,” jawab Tasya, tangannya masih menulis sesuatu di atas bukunya. “Dia bagus banget loh, gila pokoknya. Suaranya bagus, dan aktingnya mantep banget. Pokoknya parah sih, cocok kalau kalian jadi pasangan pemeran utama.”
“Oh iya?”
Satu hal yang gue pikirkan saat mendengar seseorang yang lebih bagus dari gue—mau itu soal pelajaran, soal teater, dan lain-lain—adalah merasa bahwa dia adalah saingan terberat gue. Walaupun bahkan gue belum tahu Julian itu yang mana.
“Lo punya info-info soal teater kita gak dari bokap lo? Pertunjukan baru yang bagus gitu? Atau lomba-lomba?” Tanya Tasya lagi.
Papa gue adalah ketua komite di sekolah gue, orang yang cukup berpengaruh dalam pembuatan keputusan di sana, sekaligus sebagai donator sekolah. Papa gue pun adalah orang yang cukup ribet dengan masa depan gue—bahkan terkadang seringkali ikut campur. Papa sering mengontrol ekskul teater gue dan ingin agar gue menjadi yang terbaik di sana agar memudahkan masa depan gue. Maka dari itu, jika ada info apa pun, Papa akan sangat cepat mendapatkannya, dan akan memberitahukan kepada gue terlebih dahulu sebelum akhirnya disebarluaskan.
“Iya, katanya ada lomba teater nasional, hadiahnya ada beasiswa dan masuk kelompok teater besar dunia nantinya,” jawab gue pelan.
Gue tahu reaksi excited apa yang akan dikeluarkan oleh Tasya. Tasya juga adalah salah satu anak teater yang cukup baik dalam bermain peran, salah satu saingan yang cukup berat juga buat gue. Maka dari itu, pada awalnya gue enggan memberitahukan berita ini, tapi…
“Hah? Serius? Wah, pengen banget gue,” ujarnya. “Tapi kayaknya gak mungkin jadi pemeran utama, kan ada lo,” jawabnya.
Diam-diam gue tersenyum.
Setelah pengumuman itu ditempel di mading, gue bisa melihat banyak anak yang tertarik dan berencana ikut casting—tetapi bukan jadi pemeran utama, mereka terlalu takut untuk bersaing dengan gue.
Kecuali satu orang.
Seorang anak yang saat itu kemejanya keluar dari celana abu-abunya, tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, dan matanya sipit. Walau begitu, gue bisa melihat bagaimana senangnya dia.
“Julian!”
Gue menoleh ketika seseorang memanggil nama anak itu. Oh, jadi itu yang namanya Julian, gue gak pernah menyadari kehadiran dia di ruang latihan. Yang gue ingat, Tasya pernah sekali menyebut namanya.
Dan dia bilang kalau Julian sangat bagus untuk pasangan pemeran utama gue.
“Lo mau ikut casting jadi pemeran utama kan, Yan?”
“Yo-i!” Jawab Julian pasti sambil tersenyum.
“Gue tunggu lo di teater nasional nanti!”
Mendengar jawaban dia, tiba-tiba timbul suatu perasaan takut dalam diri gue. Takut kalau bukan gue yang jadi pemeran utamanya, karena pemeran utamanya hanya satu, tidak ada pemeran utama laki-laki atau pemeran utama wanita. Tiba-tiba gue takut kalau gue….
[Papa]
Kamu harus jadi pemeran utamanya ya.
Takut kalau gue kalah dan mengecewakan Papa.
Tangan gue berakhir mencari-cari kontak Julian di grup anak teater. Gue gak pernah tahu, kalau hal yang gue lakukan selanjutnya adalah hal terbodoh yang pernah gue lakukan seumur hidup gue.
Terlalu bodoh karena gue harus melewatkan cinta pertama gue hanya karena sebuah ambisi.
Dan saat ini, terlalu terlambat untuk meperbaiki semuanya. Gue dan Julian sudah bagaikan dua orang yang berpisah di perempatan jalan, karena berbeda arah untuk kembali.
***
Y o g a
“Haduh, sakit banget perut gue!” Gue mengusap-usap perut gue sambil menghampiri Julian yang sedang duduk di sudut meja makan sambil bengong. “Woy! Bengong aja lo Panjul,” gue menabok punggung dia keras.
“Anjir! Kaget,” jawabnya dengan nada yang gak kaget. “Lama amat sih, lo boker apa tamasya di kamar mandi?”
Gue terkekeh kemudian duduk di sebelah Julian. “Kayaknya nasi goreng yang dibawa Dennis kemarin mengandung racun anjir. Kalau enggak, kenapa kita semua rebutan kamar mandi dari tadi? Kan gak masuk akal.”
“Ya udah yang penting udah makan,” jawab Julian. “Dan udah dikeluarin.” Kalau mukanya yang biasanya pengen gue tampol itu udah datar kayak gini, pasti ada sesuatu.
“Napa sih, Yan?”
“Kenapa emang?”
“Ya elu kenapaa?”
“Gak apa-apa,” jawab Julian pelan. “Gue minta maaf ya, kalau gue gak jadi ngundang kalian semua buat nonton gue lomba nanti.”
Gue terdiam. Sebenarnya, gue tahu apa yang terjadi pada Julian, tapi kemarin-kemarin, gue masih berusaha untuk gak bertanya. Ya, lo tahu lah, gimana sih rasanya mimpi lo yang sudah di depan mata tiba-tiba direnggut begitu aja? Walaupun Julian tampaknya kuat dan kadang menjadi pelindung buat anak-anak di sini, sebenarnya gak begitu. Walaupun dia sering tertawa dan sangat maceuh—hmm, maceuh itu apa ya, petakilan kayaknya—tapi sebenarnya dia gak sekuat itu.
Setiap dia bercerita tentang masalahnya, gue selalu bisa melihat seberapa berat beban yang sebenarnya ditanggungnya. “Lo gak mau cerita kenapa tiba-tiba lo harus menyerah sama mimpi lo?”
“Oryza,” jawab Julian pelan, seakan enggan menyebutkan kata tersebut, membuat gue mengernyit karena gue gak tahu. “Oryza siapa?”
“Mantan gue,” jawabnya.
“Terus?”
“Ya, gara-gara ada dia,” jawabnya lagi. “Gue pernah punya masalah sama dia dulu.” Jawabnya singkat, membuat gue mengangguk-angguk dan mengerti kalau dia belum siap menceritakan masalahnya.
“Lo boleh cerita sama gue kapan aja.”
Julian tersenyum simpul. “Maaf ya, gue tuh masih bingung gitu sama diri sendiri. Gak tahu kenapa. Nanti, kalau gue udah meluruskan hati dan niat baru gue cerita.”
“Meluruskan hati dan niat udah kayak mau puasa aja lo,” jawab gue lagi. Dijawab dengan kekehan Julian yang tidak berisi.
“BANG YOGAAAA! LAPER NIH LAPER,” Sena menyerobot masuk ke dalam dapur dan duduk di sebelah gue. “Eh, kenapa nih mellow mellow gini?” Pandangan Sena bergantian menuju gue dan Julian. Alisnya mengangkat penasaran, tapi gue dan Julian malah bertatap-tatapan.
“Gak,” jawab kita bebarengan. Sena hanya mengerucutkan bibirnya dan mengangguk-angguk. “Bang Yoga gak berencana memasak makanan? Kita semua udah ngeluarin isi perut, butuh tenaga pula, jadi kudu makan, hehehe,” ujar Sena lagi. “Ini mah kita harus nuntut tukang nasi goreng yang dibeli Babeh Rahmat! Masa kita semua jadi mules kayak gini, sih.”
“Udah biarin aja, Sen. Yang penting udah dikeluarin,” jawab gue. “Mau masak apa? Sayur aja ya? Beliin cabe dong, Sen. Gak enak kalau gak pake cabe.”
“Lah ini cabe?” Brian yang tiba-tiba datang menunjuk Julian, yang kemudian dibalas tatapan sinis Julian yang sedang gak mood bercanda. Gue mengirimkan tatapan maut pada Brian yang tingkat kepekaannya di bawah negatif satu, membuat dia mengernyit, “Apaan sih, Bang?”
“Udah, jangan ganggu si Panjul,” jawab gue. Sementara itu, Brian mengerucutkan bibirnya mengerti, lalu menjadi diam. “Eh, Sen, lo kalau mau beli cabe ke warung Bi Idah titip itu dong, pomade, hehehe.”
“Ngapain anjir…ngapain pakai pomade, tumben banget lo, biasa rambut kayak tarzan aja sok-sokan pake pomade,” Sena mendengus. “Lagian siapa juga yang mau ke warung Bi Idah. Lo minta aja tuh pomade punya si Dennis, dijamin langsung klimis seratus persen, membuat para wanita tertarik melihat rambut lo!”
“Gak ah, serem gangguin Dennis,” Brian mengangkat bahunya ogah-ogahan. “Eh, btw, Sen, lo kalau pergi ke warung terus si Bi Idah-nya gak ada lo manggilnya gimana?”
“Ya tinggal panggil aja, Yaaaan,” jawab Sena kesal. “Lo panggil aja yang keras, ‘Bi Idaaah mau beli pomade’ ribet amat sih.” Sena mendengus kesal sambil menyomot makanan yang ada di meja makan—sisa kemarin.
Brian terkekeh. “Yaa, gue kira lo ngomong, ‘beliiiii, beliiii, beliiii’ sampai Bi Idah keluar gitu.”
“Sambil mainin beras ya?”
“Heeuh, dulu gue waktu kecil kayak gitu anjir hahaha,” jawab Brian, kemudian tertawa terbahak-bahak.
Gue menggeleng-gelengkan kepala melihat bocah-bocah itu tertawa. “Bang Yoga, ada gosip terbaru gak?” Tanya Sena sambil mengedip-ngedipkan matanya.
“Gosip apaan? Udah sana lo sama Brian beli cabe gih, gue jadi gak bisa masak kalau belum ada cabe,” ujar gue—mengusir dengan halus dua bocah yang makin mengganggu mood Julian.
“Uangnya?” Tanya Sena sambil menyodorkan telapak tangannya.
“Yaaaa pake uang lo dulu, cabe mah cuma tiga ribu,” Brian menoyor kepala Sena dan mengajaknya segera keluar. Kemudian, dua bocah itu akhirnya meninggalkan dapur dan terdengar berebut sandal jepit di depan sana, membuat gue menggeleng-gelengkan kepala.
“BANG YOGAAA!”
Sebuah teriakan muncul kembali. Ya ampun, ada apa lagi, sih.
“BANG IJUUUL!”
Mendengarnya Julian menatap gue dan bergegas bangkit dari tempat duduknya menuju sumber suara—Dennis yang sedang berteriak panik dari kamar Cakka. Gue dan Julian bergegas menuju lantai atas dan mendapati pintu kamar Cakka terbuka lebar dan Dennis dengan muka paniknya mengipas-ngipas Cakka.
“Kenapa?” Tanya Julian sama paniknya. Di samping Dennis, Cakka tampak memegangi perutnya dan menggigil. “Cakka lo kenapa?”
“Badan Cakka panas banget, Bang,” jawab Dennis.
Gue segera duduk di pinggiran tempat tidur Cakka dan memegangi bagian dahi serta lehernya, “Ambil obat coba, Den. Tuh biasanya Cakka mengoleksi obat di sudut meja belajarnya. Nah, iya-iya, coba buka kotaknya.”
“Di…klo..fenak?”
“Bukan-bukan, itu obat nyeri sendinya Babeh Rahmat,” jawab Cakka pelan. “Cari aja parasetamol di situ.” Ujarnya lagi.
Gue menatap muka adik gue yang kemerahan dan menahan rasa sakitnya. Gue jadi benar-benar berpikir untuk menuntut tukang nasi gorengnya, tapi gak tahu tukang nasi gorengnya di mana. Duh, kasihan banget adik gue. “Ya udah, udah lo minum obat, langsung tidur ya, Ka, semoga demamnya turun pas lo bangun.”
“Iya, Ka, jangan belajar mulu juga, jadi lo kayak gitu deh,” ujar Julian lagi. Sementara itu, Dennis segera memberikan obat pada Cakka dan Cakka segera meminumnya. Gue jadi merasa bersalah karena selama ini sering menyuruh Cakka untuk menunggu di fakultasnya sementara gue rapat. Ya, apa lagi yang bisa dia lakukan di sana selain belajar sambil menunggu gue?
“Gue yang masak deh, Ga. Lo mau jagain Cakka, kan?” Tanya Julian.
Gue mengangguk-angguk. “Oke, Jul,” jawab gue.
“Gue bantuin Bang Ijul aja deh, ya, Bang? Takut masakan Bang Ijul gak enak.”
“Yeuuu,” Julian menoyor Dennis.
Keduanya kemudian keluar dan berlari-larian rusuh menuju dapur sambil masih saling meledek. Gak si Sena, gak si Panjul sama aja sering bikin rusuh. Padahal tadi si Panjul ini masih badmood dan galau, tapi sekarang? Aneh banget emang tuh orang.
Pandangan gue beralih ke arah Cakka. “Lo kenapa sih, Ka? Kecapean? Atau gara-gara nasi goreng kemarin?”
“Dua-duanya kayanya, Bang,” jawabnya. “Gue tidur dulu, ya,” Cakka menarik selimutnya dan menghadap ke arah berlawanan. “Bang Yoga kan ada rapat, pergi aja, Cakka bisa sendiri.”
Gue menghela napas. Mau bagaimana pun sejak tadi gue sudah memutuskan untuk gak ikut rapat. Rapat kali ini akan membahas perwakilan lomba debat nanti. Kalau gue ikut, berarti gue akan menjadi perwakilan dari fakultas gue, dan kalau gue gak datang, gue gak akan jadi delegasi lomba tersebut. Tapi, it’s ok, masih ada ribuan lomba di luar sana. Lagipula, kalau gue gak menjaga Cakka, nanti gue takut dia kenapa-kenapa.
Handphone Cakka berdenting beberapa kali, membuat gue yang sudah terkantuk-kantuk—padahal masih pagi—berusaha untuk membuka mata kembali dan melihat ponsel Cakka. Handphone-nya gak menggunakan password, dan nama yang muncul di deretan notifikasi membuat jantung gue serasa berhenti berdetak.
[Kak Ditas]
Cakka, Abang lo dateng kan setengah jam lagi? Jangan lupa suruh mandi dan sarapan dulu.
Diam-diam gue tersenyum dan memikirkan kapan terakhir gue chat dengan Ditas, pacar gue sendiri. Mungkin satu minggu yang lalu? Atau lebih? Yang jelas, gue masih ingat isi chat terakhir kita. Ditas yang meminta pertemuan, tapi gue gak datang.
Alasannya cuma satu, ya, gue gak mau bertemu dengan dia.
Pernah gak sih lo ngerasa insecure akan diri lo sendiri? Gue sebenarnya bukan tipe orang yang rendah diri dan enggak bergaul dengan banyak orang karena gue merasa diri gue kurang, tapi, ketika gue melihat seorang Ditas, perasaan itu seringkali muncul dalam diri gue.
Ditas akan jadi satu-satunya orang yang menarik di tengah kerumunan orang-orang. Ditas akan selalu jadi pusat perhatian ketika dia berada di mana pun. Kalau gue berbicara tentang Ditas di mata orang-orang, mungkin gak ada habis-habisnya. Gue gak bisa menyangkal kalau di mana ada Ditas, di sana ada orang-orang yang mengerubunginya—entah mengajaknya makan, atau mungkin bertanya tentang pelajaran.
Gue akan selalu jadi orang yang memandang dia dari jauh dan menunggu dia selesai dengan urusan-urusannya bersama orang lain, tetapi yang gue dapat hanya kekosongan belaka. Ditas gak pernah ada waktu untuk berbicara dengan gue saking banyaknya orang yang membutuhkan dia.
Mungkin, kalau suatu saat gue tiba-tiba bicara bahwa gue adalah pacar Ditas dan gosip itu tersebar ke seluruh bagian fakultas, gak akan ada yang percaya. Mungkin reaksi pertama dari orang-orang adalah kaget dan gak menyangka, kemudian gosip itu akan menjadi gosip terpanas di sana.
Julian sering bilang sama gue, ‘lo bisa gak sih berhenti berasumsi kayak gitu? Belum tentu apa yang lo pikirin bakalan terjadi. Asumsi tuh bikin diri lo akhirnya gak melakukan sesuatu.’
Jawabannya adalah gak, gue gak bisa. Asumsi seperti itu memang terkadang membuat gue jadi berpikiran negatif terhadap lingkungan sekitar, membuat gue akhirnya mengurungkan niat awal gue. Tapi dengan asumsi itu setidaknya gue tahu respon-respon apa yang kira-kira akan terjadi dan gue bisa menghindarinya.
Kak Ditas is calling…
Mata gue terbelalak melihat nama itu muncul di handphone Cakka. Sambil berharap-harap kalau teleponnya mati sendiri, gue berpikir apa yang harus dilakukan. Apa gue bilang ala-ala operator gitu, ya? Nomor yang anda tuju sedang tidak aktif, jangan coba-coba telepon lagi.’
Tapi, rupanya jari gue mengkhianati otak gue. Karena, pada akhirnya jari gue memencet tombol hijau yang ada di sana dan membuat gue terdiam dalam beberapa saat ketika mendengar suaranya.
“Halo? Cakka, Abang lo ke mana? Dia dateng, kan?” Sempat ada jeda sebelum suaranya kembali mengisi pendengaran gue. “Cakka? Ini udah mau beres rapatnya, kalau Abang lo gak datang, dia gak bisa jadi delegasi lomba.”
Gue menarik napas dalam sebelum akhirnya berbicara. “Cakka lagi tidur, dia sakit.” Jawab gue pelan.
***
D i t a s
“Cakka lagi tidur, dia sakit.”
Baru saja gue akan membuka mulut untuk menjawab suara tersebut, gue langsung tersadar akan sesuatu. Ini… ini Yoga? “Oh…ehm… lo bakalan dateng kan, Yoga? Ini sepuluh menit lagi rapatnya bubar, nanti lo…”
“Lo kenapa masih peduli sama gue?” Tanya suara di seberang sana. Suara yang selama ini ingin gue dengar—dan akhirnya gue mendengarnya saat ini—dengan pertanyaan yang gak pernah gue kira akan dilontarkan.
Kenapa dia bertanya begitu ketika gue gak punya alasan untuk melakukannya?
“Ditas…,” panggilnya.
“Iya..”
“Kenapa lo gak putusin gue?” Tanya Yoga. “Gue udah jahat sama lo, gak pernah ngehubungin lo, tapi ternyata lo masih nanya-nanya tentang gue lewat Cakka.”
“….”
“Ditas, kalau lo cape sama gue, putusin gue.”
Gue terdiam. Bukan, bukan kalimat itu yang ingin gue dengar dari Yoga. Iya, gue memang kadang merasa lelah ketika gue harus seperti ini—dengan pacar gue sendiri. Gue harus sering merasa cemburu ketika dia dikerubungi banyak cewek—mau itu mengajak dia makan, mengajak dia foto, atau menanyainya pelajaran—tapi gue gak ingin putus.
Bagi gue, lebih baik masih bisa melihat dia sebagai seseorang milik gue walaupun dia sering mengacuhkan gue, dibandingkan harus melihat dia ketika dia bukan siapa-siapa bukan gue. Setidaknya, ya, setidaknya gue masih menyimpan nama di hati dia. Gak usah ditanya lagi, dia selalu menyimpan nama di hati gue.
Kadang gue ingin menuntut—kenapa dia mengacuhkan gue, kenapa dia gak pernah balas chat gue, kenapa gue seakan gak ada dalam kehidupan dia—tapi gue takut kalau itu justru akan menjauhkan gue dengan dia. Gue gak mau.
“Gue gak pernah cape, Ga…”
“Bohong kalau lo gak cape, Ditas,” jawabnya pelan. “Ditas, you can find a man, better than I am,” ujarnya pelan.
“Lo…kenapa ngomong kayak gitu, Ga?” Tanya gue. “Lo memang mau putus sama gue?”
“Iya.”
Jawaban singkatnya membuat jantung gue serasa turun menuju perut. Gue gak pernah mengerti isi pikiran seorang Yoga. Gue pikir, dia mengacuhkan gue karena memang dia sibuk dengan dunianya, dan gue bisa memaklumi hal itu. Tapi, tampaknya engga? “Kenapa?”
“Gue gak mau liat lo sedih gara-gara gue,” jawabnya. “Gue mungkin bukan orang yang tepat bagi lo dan lingkungan lo.”
Lingkungan lo.
“Yang bisa menilai tepat atau gak tepat, itu orang lain, bukan diri lo, Ga.”
“Terus, kalau orang lain yang bilang gue gak tepat buat lo?”
“Siapa? Siapa yang bilang, Ga?” Tanya gue cepat.
“Lo gak pernah malu punya pacar kaya gue?”
Gue ternganga, kenapa alasan dia…, “ Malu apa, sih, Ga?”
“Kalau orang-orang tau gue pacar lo, apa lo gak malu?”
Gue terdiam beberapa saat.
“Ditas….”
“…”
“Kenapa lo gak bilang kalau lo ada masalah sama papa lo?” Pertanyaan Yoga diujung sana membuat gue tersentak. “Dan kenapa lo gak bilang kalau masalah itu datang karena lo menolak menerima seseorang pilihan papa lo?”
Gue memejamkan mata dan perlahan air mata turun dari pelupuk mata gue. “Maaf, Ga…”
***
Y o g a
Lo pernah denger gak, kalau patah hati terbesar adalah ketika lo benar-benar kehilangan sesuatu? Kehilangan sesuatu yang mungkin gak bisa kembali. Gue sudah merasakan patah hati ini sejak beberapa bulan yang lalu, saat tanpa sengaja, gue mendengar percakapan Ditas dengan papanya.
Ditas terlahir dari keluarga yang kaya raya, keluarga yang memiliki perusahan dengan ratusan cabang dari Sabang sampai Merauke. Mungkin lo sering mendengar tradisi perjodohan di antara orang-orang kaya demi mempertahankan kejayaan perusahaan mereka, dan itu terjadi pada Ditas.
Gue tahu Ditas berkali-kali menolaknya, tapi itu justru membuat gue takut. Takut kalau seandainya di masa nanti, gue benar-benar gak akan bisa bersama dia.
“Maaf, Ga,” ujarnya sambil terisak. “Tapi gue bener-bener cuma memilih lo, gue udah menolak…”
“Gue ngerasa gak pantes aja buat lo, Tas,” gue tertawa parau. “Gue bukan apa-apa.”
“Lo kenapa gini sih, Ga?”
“Gue takut, Ditas,” jawab gue pelan. “Lo udah banyak berubah, sekarang lo udah menjadi Ditas yang berbeda. Gue sebenarnya takut bakalan kehilangan lo nanti, makanya…,” gue menarik napas panjang. “Makanya gue bersiap-siap untuk kehilangan lo sekarang.”
Ya, Ditas. Mungkin dulu gue dan lo masih berjalan menuju ke arah yang sama, karena itu satu-satunya jalan. Tapi, Ditas, ketika di depan lo banyak jalan yang bisa lo pilih, gue gak yakin kalau lo tetap akan berjalan bersama gue—di jalan yang sama.
***


 adillazulfana
adillazulfana