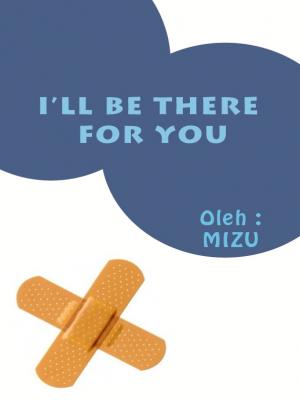Jangan
Jangan sengaja pergi agar dicari,
Jangan sengaja berlari agar dikejar,
Berjuang tak sebercanda itu.
Jangan baru mencari saat sudah terlanjur pergi,
Jangan baru mengejar saat sudah jauh berlari,
Menurutmu bagaimana?
Menurutku, menunggu tidak seasyik itu.
J h o r d a n
Bagi sebagian orang, rumah adalah tempat kembali. Orang-orang senang berjuang mati-matian, agar saat ia kembali, rumah akan menerimanya dengan senang hati. Mereka juga ingin segalanya cepat selesai dengan sempurna, agar mereka bisa kembali ke rumah secepat mungkin. Apa lo juga begitu? Gimana rasanya punya rumah untuk pulang?
Semenjak gue ditakdirkan untuk tinggal berdua dengan Bapak di rumah, rumah itu gak bisa lagi gue sebut rumah. Selama hampir delapan tahun gue tinggal di sana—berdua—Bapak gak pernah mengeluarkan satu kata pun setiap berhadapan dengan gue, pun begitu juga dengan gue. Ada sesuatu yang salah antara gue dan Bapak, tetapi itu hanya terkaan yang akhirnya menuju pada salah sangka.
Lalu, ketika gue merasa gak nyaman dengan itu semua, gue memilih untuk tinggal di luar rumah, berusaha mencari ‘rumah’ lain. Usia SMP, gue lebih sering tinggal di rumah nenek, kemudian pada usia SMA gue lebih sering tinggal di rumah bude. Tapi, selama itu pula, gue gak bisa menemukan rumah yang gue cari.
Sampai pada suatu saat, ketika gue—si anak nakal ini—berusaha untuk gak tinggal berdua dengan orang yang terus mendiamkan gue selama bertahun-tahun, gue menemukan sebuah rumah dengan cat warna biru yang saat itu baru ditinggali oleh tiga orang—Sena, Brian, dan Bang Ijul. Pada awalnya memang terasa aneh, tinggal di satu rumah dengan laki-laki seumuran gue yang berisik tiada tara, ketika biasanya di sekitar gue hanyalah keheningan.
Kemudian, satu per satu orang datang, mulai dari Bang Yoga, hingga adiknya yang baru masuk ke rumah ini beberapa bulan yang lalu. Sedikit demi sedikit, akhirnya gue tahu bagaimana karakter mereka. Walaupun pada dasarnya gue gak seperhatian Bang Yoga atau sepeduli Sana, gue sebenarnya tahu. Tahu apa yang mereka gak suka, tahu apa yang akan mereka lakukan ketika bosan, tahu apa yang ingin mereka capai di masa-masa ini, karena sebenarnya gue sangat peduli dengan mereka.
Gue peduli karena akhirnya gue menemukan sebuah keluarga di sini. Gue menemukan sebuah rumah di sini. Rumah yang benar-benar tempat gue kembali. Bukan berarti gue gak sayang Bapak, tapi buat apa gue terus berdiam di sana ketika tidak ada interaksi di antara kita berdua?
Gue senang ketika Brian berteriak, “Woy ini si Jhordan panas banget badannya gimana, dong?” Lalu kemudian Sena yang gak pernah naik motor gede terpaksa menggunakan motor itu untuk membeli obat di apotek. Lalu, Bang Yoga dengan kemampuan memasaknya berusaha untuk membuat bubur terenak buat gue. Dennis dan Cakka dengan telatennya selalu bergantian mengompres gue agar suhu badan gue turun. Dan terakhir, Bang Ijul yang dengan paniknya mondar-mandir di depan kamar gue hanya untuk melihat gue memakan bubur buatan Bang Yoga.
Rasanya geli banget kalau gue bilang gue sayang mereka, tapi memang begitu kenyataannya. Gue—yang sudah bepergian terlalu jauh untuk mencari sebuah rumah—akhirnya menemukan ‘rumah’ karena mereka.
“Katanya si Jhordan udah punya gebetan, emang iya?” Tanya Bang Ijul sambil menyalakan TV di ruang tengah. Matanya meyusuri satu per satu orang yang berada di sana.
Sontak semua mata mengarah pada gue yang membuat gue gelagapan, “Hah? Apa dah?”
Selanjutnya yang gue dengar adalah tawa menyebalkan keluar dari mulut seorang Sena, “Iya tuh ada. Kerjaannya diikutin aja terus setiap hari. Semoga deh cepet-cepet jadian,” ujarnya, kemudian tertawa lagi.
Bang Yoga menyahut, “Akhirnya anak mama udah gede sekarang.” Bang Yoga menepuk-nepuk puncak kepala gue. “Nanti kalau kamu nikah jangan lupain mama, ya.”
“Najis!”
“Heuu dia mah dari dulu juga udah playboy,” lah si bocah satu ini malah menoyor kepala gue. “Heh, lo tuh ya, udah makin tua, harus makin bener pilih pasangan. Jangan asal cantik terus lo embat, lo gak akan hidup dengan kecantikan itu.”
Halah, sok-sokan ni bocah. Sendirinya aja jomblo bertahun-tahun, “Heh, Yan. Lo kalau mau ngasih tau tuh ngaca, dong. Mirror, please! Lo apa kabar? Masih belum move-on dari pacar lo zaman SD?” Gue menyahut sebal.
“Hahaha, zaman SD anjir! Masih kecambah-kecambah udah punya pacar lo?” Tanya Bang Ijul, lalu menoyor Brian. Disusul oleh suara meringis yang keluar dari mulut Brian akibat perlakuan semena-mena Bang Ijul tersebut.
Helaan napas terdengar dari sudut sofa. “Kenapa ya, kadang gue mikir, sebenarnya apa yang harus gue lakukan biar gue gak dikecewain terus kayak gini,” ujar Bang Yoga pelan. Gue sangat yakin kalau sebenarnya dia hanya berbicara untuk dirinya sendiri, tapi sayangnya semua orang di sini mendengar dan berakhir bengong memperhatikan dia. “Rasanya susah untuk percaya sama seseorang, apalagi kalau kepercayaan lo pernah dihancurkan.”
Gak ada yang menyahut, tiba-tiba keadaan menjadi hening. Bang Yoga bukan tipe orang yang tiba-tiba curhat sana-sini tentang apa pun, tapi tadi gue baru saja mendengar dia mengatakan sesuatu tentang isi hatinya. Isi hati yang kita semua gak pernah tahu.
“Kok pada diem sih? Gue udah ngomong panjang-panjang anjir,” ujar Bang Yoga misuh-misuh.
“Hehehe,” Sena menyahut. “Habisnya aneh, Bang, lo tiba-tiba curhat kayak gitu gue jadi bingung nanggepinnya harus kayak gimana,” Sena menggaruk punuknya yang tidak gatal.
Gue gak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Bang Yoga dan pacarnya. Yang jelas, gue gak pernah melihat dia mengantar pacarnya pulang, atau membawanya ke sini. Berbeda dengan Brian yang selalu membawa Chila dan berakhir bilang kalau dia bukan siapa-siapa ketika gue tahu tatapan mata di antara mereka berbeda. Dunia ini aneh banget, ya, emang?
“Sebenernya gue mau bilang aja sama adek-adek gue,” kata Bang Yoga, kemudian bola matanya perlahan-lahan bergerak menyusuri semua orang satu per satu. “Kalau lo punya orang yang benar-benar lo sayang, jangan dikecewain. Karena balikin kepercayaan tuh susah banget. Jangan pas udah gak ada, lo baru nyari-nyari dia. Lo juga, Dan,” ujar Bang Yoga sambil menepuk bahu gue.
“Hah? Apaan nih, Bang?” Tanya gue bingung.
“Dan,” Bang Ijul melanjutkan. “Maksud Yoga, orang yang lo sayang gak cuma sebatas pacar atau perempuan. Selama hampir satu setengah tahun, lo belum pulang ke rumah, Dan. Gue tahu lo sekarang cuma tinggal sama bapak lo doang, that’s why gue kadang khawatir.” Bang Ijul menghela napas, “Khawatir kalau lo menyia-nyiakan kesempatan lo untuk kembali.”
“Kalian semua nyuruh gue pulang? Nyuruh gue gak tinggal di kosan ini lagi?”
Brian menghembuskan napas berkali-kali. “Lo ngerti gak sih, Dan, perasaan gue? Gue tuh kadang iri sama lo, lo bisa balik kapan aja lo mau—karena rumah lo deket—tapi lo gak pernah ambil kesempatan itu. Kalau gue jadi lo—“
“Lo bukan gue, Yan,” jawab gue pelan.
Gue merasa segala omongan teman-teman gue ini bercampur aduk di dalam pikiran gue. Sedikit banyak gue merasakan sesuatu mengganjal di dada gue, dan gue gak tahu apa maksud mereka tiba-tiba membahas ini sekarang. Ketika dulu mereka selalu berusaha diam dan gak mengata-ngatai tingkah gue, sekarang kenapa mereka semua tiba-tiba begini?
Dennis menghela napas sebelum akhirnya membuka mulutnya, “Jhordan. Waktu kemarin lo balik tengah malam, bude lo datang.”
Mendengar perkataan itu gue hanya terdiam, mencoba mencerna apa yang akan dia katakan selanjutnya. “Bude lo bilang, bapak lo pengen lo pulang,” lanjut Dennis.
“Gak usah bohong, anjir. Gak mungkin Bapak pengen gue pulang, buat apa? Dia mungkin lebih seneng gak ada gue di rumah,” jawab gue kesal.
“Dia bener-bener pengen lo—“
“Kenapa dia gak datang sendiri?” Tanya gue. “Kenapa dia gak ngomong sesuatu sama gue terus—“
“Bapak lo sakit, Dan!” Gue gak tahu apa yang menyebabkan suara Bang Ijul meninggi. Tapi mendengar kalimat yang dikatakannya membuat gue tersentak dan menatap matanya dalam. “Gue yakin lo gak tahu soal ini. Makanya gue kasih tahu, gue takut semuanya udah terlambat.”
“Jangan sampai lo bikin orang yang sayang banget sama lo—bapak lo sendiri—kecewa karena lo gak ada di sisi dia saat dia membutuhkan lo,” ujar Bang Yoga. “Itu yang gue maksud tadi.”
Sena menghampiri gue, kemudian duduk di sebelah gue. “Dan, kita semua gak tahu apa masalah lo, it’s ok kalau lo mau cerita atau engga, tapi gue saranin sama lo, kalau ada sesuatu antara lo dan bapak lo, gue harap lo segera membereskan itu semua.”
“Bukan cuma Bapak yang kecewa sama gue,” jawab gue pelan. “Gue juga kecewa sama Bapak. Lo semua berpikir kalau di sini gue yang salah? Kalian gak berpikir gimana perasaan gue yang sebenarnya? Gue bukan semata-mata orang yang membuat kecewa, gue juga dikecewakan. Menurut kalian ini gampang buat gue?”
“Then, talk to your father…”
“He doesn’t want to talk to me,”
“You do it first,” ujar Bang Ijul. “You’re a gentleman, so I think you can start it. Gue gak tahu apa masalah sebenarnya antara lo dan bapak lo, mau lo yang salah atau bukan, kalau gak ada yang mulai bicara, semuanya gak akan selesai. Jangan sampai semuanya terlambat, lo perlu alasan dari hal yang membuat lo kecewa, dan bapak lo juga butuh alasan kenapa dia dibenci oleh anaknya sendiri.”
“Bang Jhordan…,” ujar Cakka. “Lo mungkin gak percaya sama gue atau bilang kalau gue mengada-ngada, tapi ketika kemarin gue denger apa yang sebenarnya terjadi sama bapak lo, itu bukan sesuatu yang mudah untuk disembuhkan.”
Gue menghela napas panjang, mencoba berpikir jernih tentang apa yang sebenarnya harus gue lakukan. Mungkin iya, Bapak kecewa sama gue, tapi rasa kecewa gue lebih besar lagi. Terlalu banyak pertanyaan yang ingin gue lontarkan, tapi melihat Bapak hanya diam selama ini, gue ragu kalau pertanyaan itu akan terjawab. Dan walaupun pertanyaan itu akan terjawab nantinya, gue lebih takut lagi kalau akhirnya gue gak bisa memaafkan Bapak.
“Ibu gue meninggal delapan tahun lalu, saat gue masih sangat kecil untuk mengerti,” ujar gue. Membuat semua mata yang tadinya sangat emosi melihat kelakuan gue perlahan menatap gue dalam dan lembut. “Gue gak pernah tahu alasan kenapa itu terjadi, yang jelas kematian Ibu sangat gak wajar.”
“Dan…”
“Gue bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Karena, malam itu hanya ada Bapak dan Ibu di rumah. Gue ada di rumah nenek, makanya gue gak tahu apa-apa. Gue gak tahu apakah Bapak dan Ibu habis bertengkar atau enggak, karena selama hidupnya mereka selalu cekcok.”
“Gue seneng lo mau cerita, Dan,” Bang Yoga menyahut, menepuk-nepuk puncak kepala gue—lagi. Salah satu hal yang paling gue sukai dari Bang Yoga adalah sikapnya yang selalu seperti ini—lembut dan mengerti, seperti seorang ibu buat gue.
“Karena tiba-tiba Ibu ditemukan di lemari dengan bersimbah darah, banyak kecurigaan timbul dalam hati gue,” lanjut gue. “Tapi setiap gue ingin bertanya sesuatu, Bapak selalu menghindar. Dan selama ini pula, akhirnya gue dan Bapak gak pernah ngobrol, satu kata pun. Itu semua bikin gue muak.”
Mereka semua tidak menyahut. Beberapa dari mereka ada yang menatap gue pelan, beberapa lagi ada yang menatap langit-langit, mencoba untuk tidak terbawa suasana—tetapi gagal.
“Hal itu yang bikin gue kecewa sama Bapak, kenapa Bapak gak pernah cerita sama gue, dan kalau pun semua itu salah Bapak, lo pikir gue akan menjauhi Bapak? Enggak, justru dengan Bapak yang diem kayak gini buat gue makin curiga,” gue gak tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan ketika gue menceritakan semua ini, yang jelas perlahan beban di hati gue menghilang satu persatu. “Gue ingin Bapak yang bicara, bukan gue.”
“Jhordan…”
“Gue ingin Bapak yang cerita tanpa gue tanya,” ujar gue pelan. “Iya, mungkin Bapak kecewa sama gue karena gue gak ada di hari tuanya, mungkin Bapak kecewa gue gak bisa temenin dia, tapi apa Bapak gak pernah berpikir tentang gue? Gue ingin ada sesuatu yang dia katakan untuk gue, ” Gue beranjak dari tempat duduk gue. “Gue gak mau pulang, karena gue yakin, bukan Bapak yang ingin gue pulang.”
Langkah kaki gue membawa gue menuju pintu kos dan disusul dengan suara teriakan Sena. “Jhordan! Lo mau ke mana?” Tapi gue gak menjawab, karena gue sendiri gak tahu harus ke mana, yang jelas gue gak akan kembali ke rumah itu.
***
F a r h a n a
Jam yang melingkar di tangan gue sudah menunjukkan pukul delapan malam. Gue—orang yang sangat apatis dan gak ikut ekskul apa pun saat SMA dulu—akhirnya diharuskan mengikuti kegiatan yang memakan banyak waktu santai gue.
Bukan karena gue gak suka dengan orang-orang di sekitar gue, tapi bagi gue, lebih baik tidak usah berinteraksi banyak dengan mereka jika pada akhirnya gue harus menyusahkan dan merepotkan mereka. Dari sekian banyak orang yang berlalu lalang dalam hidup gue, Bening adalah satu-satunya orang yang gue izinkan untuk direpotkan oleh gue.
Entah mungkin karena terlalu banyak kesamaan di antara kita, atau karena memang hanya dia yang benar-benar peduli dengan gue, gue dan Bening menjadi dua orang yang sulit untuk terpisahkan. Lo akan menemukan gue dan dia di sudut kantin, di mall, di mana pun, yang jelas kita sering melakukannya berdua.
Tapi, akhir-akhir ini, Bening tampaknya punya masalah yang harus dia selesaikan. Karena, sudah seminggu ini dia tidak berada di samping gue. Di jam kosong, dia akan tiba-tiba menghilang—entah itu pergi ke perpustakaan, ke kantin, atau tempat mana pun yang menampilkan seorang Kak Sena di sana. Bening anak yang pintar, tapi dia gak suka perpustakaan. Makanya, aneh sekali bagi gue ketika dia tahan berjam-jam berdiam di perpustakaan hanya agar Kak Sena mau berbicara kepadanya.
Gak adanya Bening di sekitar gue membuat gue akhirnya kemana-mana sendirian—karena gue gak dekat dengan siapa pun—dan itu membuat gue agak….sedih? Berbeda seratus delapan puluh derajat rupanya—antara gue dan Bening. Bening adalah orang yang mudah bergaul bahkan kadang gak tahu malu, sementara gue, terkadang sulit untuk membuka percakapan kecil dengan orang lain.
Dan akibatnya, gue gak bisa nebeng siapa pun untuk keluar dari kampus yang sangat gelap ini, sementara fakultas gue sangat atas dan jauh. Gue gak mungkin menelepon Bening untuk menjemput gue, dan sialnya dari tadi gak ada yang menerima pesanan gojek gue—entah karena fakultas gue terlau jauh, atau mamang gojek yang takut kegelapan. Kalau sudah begini gak ada pilihan lain selain berjalan sendirian keluar dari kampus ini
Gue gak bisa bohong kalau gue takut, tapi gue gak mau diam sendiri di sini sampai pagi—apalagi mengharapkan ada teman gue yang menawarkan untuk pulang bareng.
“Farhana,” suara berat itu mampir ke telinga gue, membuat gue bergidik ngeri karena gue rasa gak ada siapa pun tadi. Tetapi, suara itu semakin jelas di telinga gue, “Hana.”
Gue berusaha untuk tidak mengangkat muka gue untuk menatap matanya. Tapi, gue berakhir melakukannya dan mendapati dia sangat kacau. Rambutnya acak-acakan, mukanya berkeringat, dua kancing bagian atas kemejanya—yang mungkin belum diganti sejak pulang kuliah tadi—terbuka, dan napasnya terdengar tidak beraturan.
“Kak Jhordan…”
“Hana, gue cari-cari ke kosan lo ternyata lo belum pulang, Bening bilang lo belum kelar rapat,” ujar Kak Jhordan, matanya dengan tajam menatap gue, membuat gue belum tahu apa yang harus gue katakan. “Kenapa—kenapa lo gak angkat telepon gue dan bales chat gue?”
Gue terdiam. Dia sekacau ini…apa cuma gara-gara gue? Gak mungkin, matanya berkata kalau ada sesuatu yang baru saja terjadi pada dia. Belakangan ini, Kak Jhordan adalah nama yang sering mampir di notifikasi line gue atau di riwayat telepon gue. Setelah insiden membantu-dia-mengerjakan-tugasnya, gak pernah satu hari pun dia absen untuk menghubungi gue mulai dari hal penting hingga hal-hal yang sama sekali gak penting.
Pun siang tadi yang terjadi seperti itu. Gue gak membalas pesan-pesan dia, gue gak mengangkat telepon dia, karena kalau dibilang risih, siapa sih yang gak risih dengan orang yang tiba-tiba muncul di hadapan lo setiap saat? Ditambah lagi, gue bukan orang yang mudah menerima kehadiran seseorang di dalam hidup gue. Apalagi menerima seseorang yang membuat sahabat gue menderita karena hukumannya.
“Hana, gue tanya—“
“Tadi gue di perpus, Kak,” jawab gue sekenanya. “Terus gue langsung rapat, dan Kak Jhordan juga tahu kalau gue gak boleh main handphone kalau rapat.”
“Kenapa lo gak bilang ke gue kalau lo pulang malem?” Tanyanya lagi.
“Emang gue harus bilang ke Kak Jhordan kalau—“
“Iya,” jawabnya cepat. Matanya menatap gue tajam, kemudian setelah beberapa kali menghela napas, dia akhirnya berbicara kembali. “Rapat apa sih yang bikin lo pulang malem kayak gini? Terus gak ada yang nganter lo pulang gitu?”
“Gue bisa sendiri, Kak.”
“Lo gak bisa sendiri,” jawab Kak Jhordan cepat. Kemudian, dengan cepat ia membuka jaket yang dikenakannya dan menyampirkannya di bahu gue. “Ayo pulang, Han.”
“Kak, lo gak perlu repot-repot melakukan ini untuk gue,” jawab gue lagi—dan lagi-lagi sekenanya. “Gue gak mau bikin repot orang, dan kalau pun ada yang mau gue bikin repot, bukan lo, Kak, orangnya.”
“Gue gak merasa dibikin repot sama lo..”
“Tapi gue ngerasa bikin Kakak repot,” jawab gue lagi. Rasa-rasanya, gue ingin berteriak dan berkata, “Kenapa sih, lo selalu gangguin gue?” Tapi, gue bukan seseorang seperti Bening yang akan mengatakan hal-hal seperti itu di hadapan orang yang gak dia sukai. Gue akan tetap diam, sampai akhirnya orang itu sadar bahwa gue gak suka.
Entah omongan gue bagian mana yang salah, tetapi tiba-tiba Kak Jhordan menatap gue nanar dan butiran-butiran bening keluar dari sudut matanya, membuat gue ternganga dan gak tahu harus melakukan apa. “Kalau gue yang bikin lo repot, lo mau?” Tanyanya dengan suara agak serak.
“Kak…”
“Gue butuh lo,” ujar Kak Jhordan cepat. “Tolong, jangan biarin gue pergi dari hidup lo.”
Seumur hidup gue, gue jarang melihat laki-laki menangis. Kalaupun iya, pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Dan seumur hidup gue, gue belum mendengar seseorang mengatakan kalau dia butuh gue—karena gue cenderung merepotkan orang-orang di sekitar gue.
Gue juga gak mengerti, kenapa orang yang baru beberapa bulan yang lalu mengenal gue tiba-tiba berkata dia membutuhkan gue di saat gue gak pernah melakukan apa pun yang membuatnya terkesan?
“Gue…gue harus gimana, Kak?” Tanya gue pasrah, karena gue gak tahu harus bagaimana ketika melihat dia menangis di depan gue.
Kak Jhordan masih terisak, kini matanya mencoba menatap langit untuk menahan lebih banyak lagi air mata yang keluar. “Seumur hidup, gue gak pernah nangis di hadapan orang, sebesar apa pun masalahnya, tapi sekarang gue gak tahan,” jawabnya. “Gue pengin lo jadi satu-satunya orang yang melihat gue nangis.”
“Kak…”
Tapi kenapa harus gue?
“Gue masih pengen nangis, Han,” jawabnya. “Tolong, jangan lari. Tolong, biarin gue menangis di hadapan lo.”
***
B r i a n
“Cilooook!”
Gue menggedor-gedor pintu kos Chila dan memastikan cewek berambut panjang itu belum tidur. Beberapa saat kemudian, pintu itu terbuka dan menampilkan sesosok cewek dengan kaos pendek yang sudah belel, celana panjang, dan rambut yang acak-acakan.
Chila menghela napas panjang. “Lo ngapain ke sini malem-malem? Ganggu gue tidur aja elah.” Mau bagaimana pun seorang Chila marah-marah ketika gue mengganggunya, dia akan tetap membukakan pintu dengan lebar untuk gue.
Gue sering datang ke tempat kos Chila, pun begitu dengan Chila yang sering datang dan seenaknya tidur di sofa maison de rêve. Gak sampai nginep sih kalau gue di kosan Chila, tar dikira kumpul kebo lagi.
“Napa sih, Bri?” Tanya Chila sambil membuka kulkasnya. Mencari-cari makanan yang kira-kira bisa dimakan oleh gue. Beberapa saat kemudian, dia menghampiri gue dengan sepiring biskuit dan segelas susu hangat. “Di luar dingin banget, gue bikini susu coklat kesukaan lo.”
“Lo kenapa, sih, jam segini udah tidur?” Tanya gue. “Gak ada tugas apa? Pantes chat gue dianggurin.”
“Yeuuu suka-suka gue, lah mau tidur apa mau bangun,” jawab Chila kesal.
Gue terkekeh. “Habisnya, gue tuh gak terbiasa liat orang-orang tidur masih jam setengah sembilan malem kayak gini. Orang-orang di kosan gue paling cepet tidur jam sepuluh malem, kayak si Dennis.”
“Ya, gue kan bukan orang-orang di kosan lo!” Ujar Chila sambil mendengus. “By the way, kayaknya raket nyamuk yang kita beli waktu itu sangat manjur. Buktinya, gak ada nyamuk di kosan gue sekarang.”
“Ya emang gak ada nyamuk, kan?” Tanya gue. “Modus lo, bilang aja pengen gue temenin jalan-jalan.”
Chila menoyor gue keras. “Gue emang butuh, lagian ngapain gue minta ditemenin jalan-jalan sama lo, bosen.”
“Ya udah cari yang lain!”
“Ya udah iya!”
“Tuh kan, lo udah punya pacar, ya?” Tanya gue sambil menunjuk Chila. Bertahun-tahun gue mengenal Chila, baru beberapa saat yang lalu tiba-tiba dia muncul di timeline dan menyukai status galau. “Sok-sok nge-like status-status galau gitu. Patah hati lo? Ditolak siapa?”
“Heh, Bri! Lo kalau mau ganggu gue tidur doang mending lo pulang aja deh sekarang!” Chila menyilangkan tangan di depan dadanya. “Bikin gue gak mood aja tau gak.”
Gue tertawa. “Hahaha, ngambek anjir!” Setelah meminggirkan piring biskuit—yang sudah gue makan beberapa—dan gelas yang sudah kosong, gue tidur-tiduran di atas karpet ruang tengah kosan Chila tersebut, sementara Chila tiduran di atas sofa.
“Kenapa sih, Bri?”
“Kenapa apanya?”
“Kok gak di kosan? Biasanya malam Kamis adalah malam produktif lo,” ujar Chila sambil memainkan handphone-nya, yaa ngapain lagi kalau gak melihat-lihat foto artis Korea yang sudah ia lihat berkali-kali. “Biasanya lo bikin lagu sama Sena atau ngapain gitu.”
“Suasana kosan lagi gak enak, Chil,” jawab gue pelan. Ya, itu lah salah satu alasan kenapa gue malam-malam ke kosan Chila, karena gue ingin keluar dari suasana aneh yang tiba-tiba tercipta di kosan semenjak Jhordan pergi tiba-tiba tadi.
Chila mengernyit. “Kalian berantem? Tumben.” Kemudian dia memperhatikan muka gue yang sedang merenung. “Terakhir kali kalian berantem cuma gara-gara lo gak kebagian bubur ayam yang dibeli Dennis, deh. Sesepele itu.”
Gue menghela napas lagi. “Ya, kali ini gak sepele, Chil. Tadi gue ngomong yang gak enak ke Jhordan,” gue memukul-mukul kepala gue pelan. “Ah anjir, bego banget sih gue, kenapa tadi gue ngomong kayak gitu tanpa mikir, sih? Sekarang gue gak bisa ngebayangin gimana canggungnya gue dan dia kalau nanti ketemu. Untung dia sibuk.”
Chila bangun dari posisi tidurnya dan kemudian duduk. Kakinya disilangkan di atas sofa. “Jhordan… dia kenapa emang, Bri?” Tanya dia memastikan. Mukanya yang penasaran membuat gue pengen nampol, tapi bukan saatnya gue menampol dia.
“Tadi kita sengaja bikin skenario gitu,” jawab gue. “Ya, kita pura-pura mau nonton pertandingan bola, ngajak semuanya buat ke ruang tengah. Sebenarnya kita mau ngasih tau kalau bapaknya Jhordan sakit. Lo tau lah, hubungan mereka gak begitu baik, ya bisa dibilang gak baik bahkan.”
“Terus terus?”
“Ya, kita semua nyuruh dia pulang, dan gue gak sengaja ngomong kalau gue iri sama dia karena dia bisa balik setiap saat,” jelas gue lagi. “Tanpa gue tahu kalau sebenarnya dia gak pulang karena suatu alasan yang….buat gue itu gak mudah diselesaikan.”
Chila mengangguk-angguk. “Lo tahu lah, Bri. Kadang-kadang, kita melihat sesuatu yang dimiliki orang lain itu mudah, sempurna, atau lebih baik dari kita. Kita gak pernah tahu kalau ternyata sempurnanya orang didapat dari kerja keras dia yang tiada henti, atau mungkin sebenarnya dia menutupi banyak hal dengan sikap tegarnya, kayak Jhordan.”
“Iya, Chil, lo bener,” ujar gue. “Tapi Chil, gue sekarang gak tahu Jhordan di mana, gue yakin, kata-kata gue bikin dia sakit hati banget.”
“Sejujurnya gue gak tahu kalau cowok bisa berantem soal masalah kayak gini?”
“Lebih dari cewek bahkan,” jelas gue. “Karena kita kayak gini berdasarkan logika, ketika ada perasaan yang ikut di dalamnya, semuanya tambah parah.”
“Gue yakin Jhordan pasti balik kok, Bri…”
“Semoga ya, Chil.”
Iya, semoga. Gue gak mau dengan kayak gini, tiba-tiba segalanya jadi canggung di antara kita bertujuh. Tadi saja, ketika Jhordan tiba-tiba pergi keluar dan mengendarai motornya dengan kencang, kita berenam hanya terdiam di posisi yang sama—mencoba mencerna apa yang terjadi, lalu berakhir menyalahkan diri sendiri. Gak ada satu pun dari kita yang bergerak dari ruang tengah, sebelum akhirnya gue pamit untuk pergi ke sini.
Gue harap Jhordan mau memaafkan gue, dan gue berharap juga kalau masalah dia cepat selesai.
“Gue salah gak ya, Chil?”
“Mungkin lo salah, tapi lo mengatakan itu juga karena suatu alasan, kan?” Tanya Chila lagi.
Gue mengangguk-angguk. Kini pandangan gue tertuju pada langit-langit kosan Chila yang bersih dan ada dua ekor cicak yang mengejar mangsa di sana. “Lo pernah berantem kayak gitu?”
“Cewek mah sering, marahnya bisa berminggu-minggu, Bri.”
“TUHKAN, TAR KALAU GUE DIEM-DIEMAN SAMA JHORDAN SELAMANYA GIMANA?”
“Yeuuu gak selamanya juga, lah,” jawab Chila. “Mending lo minta maaf bareng-bareng sama temen-temen lo ke Jhordan. Kayaknya, setelah kalian semua minta maaf, keadaannya bakal membaik, kok. Jhordan gak mungkin bisa marah lama-lama sama kalian.”
Gue mengangguk-angguk setuju. “Chil…”
“Apaan sih? Gue tuh dari tadi baru baca satu kata di timeline, terus lo ngomong lagi,” jawabnya kesal. “Gue gak jadi-jadi nih bacanya gara-gara lo!”
“Ih kan gue dateng ke sini mau ditemenin ngobrol,” ujar gue kesal. “Lo-nya malah fokus sama hape lagi. Tar gue bilangin ke nenek lo kalau lo di sini kerjaannya cuma menggunakan wifi gratis kosan untuk melihat-lihat artis Korea dan timeline yang isinya gak jelas itu!”
“Iya-iya, nih gue matiin hapenya.”
“Nah, gitu, dong, jadi kan enak ngobrolnya,” jawab gue, kemudian terkekeh.
Ya, habisnya orang-orang zaman sekarang kalau lagi ngumpul sama temennya lah, atau keluarganya lah, pasti fokusnya ke handphone masing-masing. Statusnya aja yang tulisan ‘Quality time w/ my family’, aslinya mah boro-boro quality time, ngobrol aja enggak.
Chila yang tadi sudah duduk kembali tiduran di atas sofanya.
“Chil, lo seumur hidup belum pernah punya pacar, kan?”
“Iya. Emang kenapa? Kan lo juga?”
“Yeuu, ya iya, biasa aja ngomongnya gak usah kayak gitu, seneng banget lo punya temen yang sama-sama jomblo dari lahir!” jawab gue.
“Kayaknya kutukan kejombloan gue ini karena terlalu sering bareng-bareng lo, deh!”
***
C h i l a
“Kayaknya kutukan kejombloan gue ini karena terlalu sering bareng-bareng lo, deh!” Gue mendengus kesal, ujung mata gue menangkap bahwa Brian sedang terkekeh. Dan yang membuat gue kaget adalah dia tiba-tiba duduk dan menghadap ke arah gue. “Lah, lah, lo kenapa?”
“Chil…”
“Hm?”
“Gue suka sama lo..”
Mata gue membelalak mendengar pengakuannya yang tiba-tiba, membuat gue gak tahu harus bengong atau harus menjawab. Pun jika harus menjawab, gue gak tahu harus menjawab dengan bercanda atau dengan serius.
“Bri, tapi gue… lo kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Bercanda ya lo?” Gue berusaha mengalihkan pandangan gue ke arah tempat lain. Dia harus bertanggung jawab karena selama hampir sembilan belas tahun gue hidup, gak cuma kali ini dia membuat jantung gue berdetak gak beraturan seperti ini.
“Gue serius, Chil…”
“Brian, kita kan temenan udah lama. Lo ngomong kayak gini tiba-tiba, bikin gue gak siap, dan gue gak tahu…”
“Gue serius kalau gue bercanda! HAHAHAHA!” Brian kemudian tertawa terbahak-bahak, membuat gue memukulnya tanpa henti.
“Ih, nyebelin ya lo!”
“Aw! Sakit-sakit, Chil. Gila, lo gede juga tenaganya,” ujar Brian, masih tertawa terbahak-bahak. “Muka lo merah banget anjir, gak pernah ditembak cowok ya lo? Hahahaha,” Ujarnya, kini berguling-guling di atas karpet.
Ya Allah, gue malu banget, deh. Tuh kan, gue gak bisa mengontrol perasaan gue, padahal gue harusnya tahu kalau dia sering bercanda kayak gini. Malu deh gue. Haduh, mau disimpen di mana muka gue?
“Atau jangan-jangan lo punya perasaan sama gue?”
Tiba-tiba mendengarnya gue terdiam. Otak gue tiba-tiba saja mencari-cari alasan kenapa gue gak pernah berpacaran seumur hidup gue. Yang jelas….gak, gak, gak. Gak mungkin gue gak pacaran karena gue suka sama si Brian ini. “Gak lah! Gila aja lo.”
“Chila, di antara kita berdua, siapa ya yang nanti punya pacar duluan?” Tanyanya.
Gue mengalihkan pandangan ke arah matanya yang kini sedang menerawang. Siapa ya, Bri? Siapa di antara kita yang bakal jatuh cinta lebih dulu sama orang lain?
***


 adillazulfana
adillazulfana