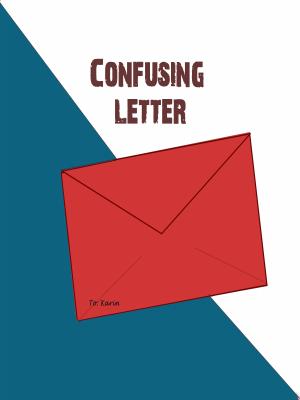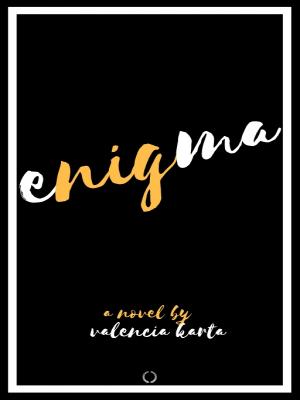Sudah seminggu sejak dada kirinya terasa nyeri kembali. Dan semenjak itu pula tidak ada kejadian di luar nalar yang menimpanya. Tapi, hanya tersisa dua puluh empat jam sebelum menghadapi puncak atau klimaks dari alur yang dijalaninya. Belum ada cabang yang ditemuinya, sepanjang memanjat pohon; hanya batang berkayu lurus menjulang ke atas.
Tinggal beberapa jengkal saja sudah sampai di puncak, namun ada sesuatu yang menghalangi; monster, benalu, atau burung pelatuk yang tengah membuat sarang. Bukan, hambatan itu berasal dari dirinya sendiri. Tercipta dari prinsip bodoh yang selalu digenggam. Terbentuk dari ketakutan akan kehilangan. Dimulai dari keraguan untuk memulai.
Memandangi layar ponsel yang tidak kunjung berubah; jari-jari tidak memainkannya. Berdiri tegap menghadap tembok yang senantiasa mendengar keluh kesahnya. Untung saja udaranya dingin, jika tidak, maka kamar tidurnya sudah berubah menjadi lautan keringat.
Urat saraf mengeras, seiring hati yang terus menahan. Ingin naluri bertindak lebih, tapi kesadaran menghalangi. Coretan merah pada setiap tanggal di kalender menjadi pengingat sekaligus cambuk baginya. Hanya tersisa satu angka berwarna hitam bersih di bulan ini.
Buku yang dipinjam di perpustakaan milik Prisna sudah habis dibaca hingga tak tersisa sekata pun. Senjata, bidikan, dan amunisi sudah siap. Sisanya, tinggal tugas dari jari telunjuk yang harus menekan pelatuk. Tapi, itu tidak mudah. Dirinya seperti prajurit yang terkena trauma perang. Mengerang ketika mimpi buruk menyerang.
“Betapa pengecut dan bodohnya diriku!” teriaknya, lalu diikuti tertawa jahat ala penjahat.
Untung saja di rumah ini ada orang, kakak perempuannya, tapi tengah terlelap dalam buaian mimpi semu. Jadi, tak payah risau jika berteriak layaknya pecandu. Deretan angka di kalender mengutuk dan memayahkan dirinya. Mereka seperti menertawai kekonyolan atau meludahi keraguannya. Dia sadar jika dirinya seorang laki-lai, setidaknya begitu jika melihat sisi biologis.
Pemancing tidak mendapat ikan, jika tidak melempar kailnya. Ikan tidak akan lompat atau masuk dengan sendirinya ke dalam sterofoam berisi es batu. Walaupun binatang, mereka masih mempunyai naluri, makan dan mencari makan.
Sosok yang dihadapinya mungkin manusia. Bukan itu masalahnya. Justru, dirinya sendiri yang membuat keadaan semakin sulit. Padahal hanya kurang lebih dua kata yang harus diucapkan olehnya. Tapi, kebekuan hati nampak begitu menghalangi.
Dia tidak ingin menjadi cacing yang hanya berkutat dengan tanah. Setidaknya, dia ingin jadi cacing yang dapat menjelajahi segala habitat, meski melawan kodrat. Kembali, menghembuskan napas dengan kasar, memukul kepala dengan pelan, dan mencubit dahinya.
“Baiklah,” gumamnya.
Ucapan spontannya barusan seperti dia telah menyetujui sebuah keputusan yang dihasilkan oleh kepalanya.
Sudah tidak perlu memedulikan prinsip konyol ini. Kehilangan? Itu merupakan sebuah hal wajar setelah pertemuan dan kebersamaan. Semua itu bagian dari siklus abadi. Daur ulang yang dilakukan secara alami. Mungkin kuasa bertindak seperti itu, agar manusia tidak bosan.
Entah dari mana asal ilham yang berbentuk tekad dan keyakinan itu. Hal terpenting, dia sudah lega karena mampu membuang benalu dari inangnya. Nampaknya, semakin waktu menghimpit, maka semakin mudah dirinya berbaur dengan pahit.
Jari-jarinya mulai mengetikkan sesuatu pada ponsel yang sedari tadi dibiarkan bisu.
Bisakah kamu datang ke bukit waktu kita melihat langit malam bersama?
Begitulah hasil dari perjuangan jarinya. Tapi, kemenangan masih belum dicapai oleh jarinya, setelah mengorbankan kalori. Tombol ‘kirim’ masih belum tersentuh sekalipun. Ini seperti seorang samurai yang ragu untuk melakukan seppuku, pasca gagal dalam perang.
Matanya membelalak ketika ponselnya berdering; ada pesan yang masuk. Dia sudah kalah, peluru terlebih dahulu menembus harga dirinya sebagai lelaki.
Apa kita bisa bertemu? Ada hal egois yang ingin kuucapkan padamu.
Langsung menuju pada inti, begitu berani. Kalimat tersebut seperti menggambarkan lelaki jantan, benar-benar jantan, seperti ayam jantan yang selalu berkokok setiap pagi. Tapi, si pengirim merupakan seorang betina; seharusnya menerima, bukan melontarkan.
Dia membuka sisa perjuangan jarinya yang sudah sekarat. Tanpa mengubah isi wasiatnya, dia mengirim kalimat tersebut secara utuh. Ini dilakukan sebagai penghormatan terakhir.
Dirinya tidak punya alasan khusus memilih tempat itu sebagai jengkal terakhir, melihat apakah ada cabang yang menunggunya di puncak pohon. Tempat yang cocok, itu anggapannya. Keadaan yang sepi; tanpa mahluk sejenis dengan dirinya. Jadi, tidak akan saksi mata berakal, kecuali dirinya dan si pengirim pesan.
Gusar menanti balasan, ragu tentang jawaban, dan bersiap untuk menghancurkan harga diri. Perkataan memalukan akan lepas landas, baginya. Mungkin bagi orang yang sudah terbiasa dengan itu¸bahkan sampai bermain itu. Label harga pada itu mereka sudah tidak ada. Jadi dapat diberi, dibagi, atau diminta secara cuma-cuma.
Ternyata benar apa yang dikatakannya.
Kini, dia sudah seperti orang tua yang akan mati. Dirinya tengah menenang kenangan yang tercipta. Memang betul, dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apapun tahapan berikut yang tertulis pada lembaran itu, dia akan mematuhi dan mewujudkannya.. Tekad sudah membulat seiring detik yang digunakan untuk menanti balasan dari pesannya.
“Akhirnya,” gumamnya kedua kali.
Tersenyum kecil di tengah membaca pesan tersebut. Dari raut wajah yang terlihat sumringah, isi pesan itu dapat tertebak dengan mudah.
Dia duduk di atas kasur untuk lebih membulatkan tekad. Menciptakan praduga setelah dia mengatakan itu. Tiba-tiba dia tersentak setelah sadar bahwa si pengirim juga akan mengatakan sesuatu. Dia terkekeh, ketika membayangkan dirinya akan menjadi pemancing yang tidak pernah menebar kail, tapi mendapat hasil. Tapi, dia tetap akan menjadi pemancing yang memakai kail dan tongkat pancing, bukan selembar uang.
Bangkit dari duduk, memakai pakaian khasnya: jaket jumper biru tua lengkap dengan jogger pants hitam. Mati gaya, begitu anggapan dirinya yang lain. Melintangkan senyuman sinis ketika melihat betapa buruk penampilannya. Bahkan cermin di kamarnya tidak sudi menampakkan wujudnya.
Mengambil selembar kertas yang dberikan olehnya waktu itu, lalu keluar dari kamar tidur. Menuruni anak tangga satu per satu dengan khidmat; merasakan sensasi ucapan selamat tinggal. Sedangkan kakak perempuannya tengah terlelap di atas sofa, sesuai dugaannya tadi. Jadi, dia tidak perlu risau tentang teriakanya tadi.
“Aku akan memertahankan dan menciptakan dunia untuk kita,” gumamnya sembari jongkok di depan kakak perempuannya yang tengah tidur dalam posisi terlentang.
Membelai rambutnya perlahan, mencium aroma alkohol kembali dari napas kakaknya, lalu berderu, “Dasar! Tapi, kakak sudah bekerja keras.”
Tanpa disadari, ada air yang tidak diinginkan mengalir melewati pipinya. Ini cuman air hujan, pikirnya. Bukan, aku sedang di dalam rumah.
Berdiri, berjalan menjauh dari kakak perempuannya, menuju ke pintu yang akan menjadi langkah pertama. Terasa berat, dirinya sudah seperti pengurung diri yang terjebak di dunia dalam; rumah. Bahkan, tangannya tak kuasa memutar gagang pintu.
Dia mulai memutar gagang pintu setelah mendapat cambukan. Himpitan waktu kembali menungganginya bagai keledai yang malas. Udara luar terasa begitu segar, bersyukur. Jika hari ini dirinya gagal, maka tidak ada esok. Semuanya akan berakhir. Alasann kakak perempuannya tidur; ingin terlelap dalam ladang bunganya, sehingga tidak perlu menyaksikam realita. Televisi pasti dipenuhi dengan acara berita yang memasang berbagai topik tentang kejadian pada esok hari. Manusia zaman sekarang memiliki bakat meramal.
Mengambil rute yang sama ketika sekolah, karena memang lokasi bukit itu berada setelahnya. Jadi, dia bisa melihat sekali lagi betapa mati sekolahnya pada akhir pekan, saat tidak ada penghuni sementara.
“Kasihan sekali, benar-benar kosong.”
Tiba di depan gerbang sekolah yang terkunci rapat; takut ada maling. Kedua mata mengamati detail setiap titik pada bangunan yang dinamakan sekolah itu. Ucapannya sejalan dengan fakta yang dipampangkan.
Kakinya mulai berjalan sendiri setelah puas mengasihani bangunan itu. Masih cukup banyak jengkal tanah yang harus ditapaki sebelum menuju bukit. Memang, dari kejauhan, matanya sudah melihat.
Tanpa sadar, matahari mulai memancarkan cahaya merah muda. Kelelawar keluar dari sarang, walet menyiapkan formasinya. Jalan beraspal telah berubah menjadi tanah cokelat yang dapat menjadi becek ketika hujan mengguyur. Untung saja tidak ada satu rintikan, jadi dia tidak perlu berkorban nyawa.
Untuk pertama kali dari tiga kali mereka saling bertemu di luar sekolah, gadis itu, Rafethea, berada terlebih dahulu di tempat perjanjian. Dia memakai gaun terusan berwarna putih. Cahaya merah muda membias di dalam pori-pori kain, memberi kesan bahwa dia mengenakan pakaian berwarna merah muda. Taka dapat melihatnya.
Taka menyaksikan punggung dengan rambut sampai tengkuk. Gadis itu menatap ke arah pepohonan yang berjejer rapi. Dia bahkan berdiri tepat di bawah pohon cemara waktu itu. Bukit ini satu-satunya lahan terbuka hijau di kotanya. Jadi, tidak perlu khawatir dengan kebisingan tengah kota.
“Maaf, apa kamu sudah menunggu lama?” teriak Taka sembari melambaikan tangan.
Dia terus berjalan dengan lambaian tangan; menanti gadis itu membalasnya, serupa. Tanpa menunggu detik berganti berkali-kali, gadis itu, sudah menjadi cermin yang memantulkan. Rafethea berjalan mendekati, dan berhenti di depannya sembari sedikit membungkuk.
“Justru kamu yang datang lebih cepat,” ucapnya, lalu diikuti senyum kecil. Selalu seperti itu.
Lelaki yang di depannya tersenyum balik, berjalan melewatinya tanpa membalas dengan ucapan. Gadis itu, Rafethea, merasa kesal, kemudian berjalan mengikuti agar sejajar dengannya. Di bawah pohon cemara, mereka saling menyelimuti diri dengan kebisuan. Taka berdiri di kanan Rafethea, begitu sebaliknya, seharusnya.
Mereka berdua menatap sisa pepohonan yang terlihat begitu renta untuk mencengkramkan akarnya di atas tanah. Taka melirik sedikit benda yang ada di belakangnya, lalu berkata, “Apa itu?”
Gadis itu mengikuti arah dari lirikannya, lalu tersenyum, selalu begitu. Dia memiliki kekuatan otot wajah yang luar biasa. Setiap kali pasti melintangkan senyum di muka. Taka yang melihatnya, hanya berdeham keren ala pria sejati.
“Lentera,” jawab Rafethea, singkat.
Taka memangutkan kepala; mengerti alasan di baliknya. Memang, langit sudah mulai gelap, jadi ini benda yang begitu tepat untuk dibawa.
“Apa yang ingin kamu katakan padaku?” tanya Taka. Rafethea sontak melebarkan kelopak mata, dan memberi tatapan padanya. Raut sedih muncul, hilang, muncul senyuman kembali.
Terlihat sekali dipaksa.
Rafethea mengambil lentera, lalu menyalakannya. Menaruhnya tepat di depan mereka. Cahaya yang dihasilkan cukup bagi mereka untuk saling melihat.
“Ini mungkin bukan hal yang wajar di dunia ini,” ujar Rafethea. Dia mulai menggeliat, entah kenapa. Tubuhnya bergemetar setelah menyelesaikan ucapannya. Taka berusaha menenangkannya; menggegam erat kedua tangannya. Dingin, itu yang dirasakan olehnya.
Taka mengangguk tanpa berusaha membalas ucapannya. Dia seolah mempersilahkan Rafethea untuk mendominasi, walau tahu akan diintimidasi. Puluhan praduga menggumpal di kepala seperti awan. Tinggal menunggu waktu hingga kristal es berubah menjadi bulir air; jatuh ke tanah.
Gadis itu, Rafethea, melepas genggaman Taka. Berjalan ke depan, berbalik badan, hingga mereka berdua dapat saling memandangi seutuhnya, walau bagian belakang tidak. Dia seperti menahan sesuatu di dalam tubuh agar tidak kelua. Urat leher yang menegang.
Bayangan Rafethea tiba-tiba menjadi begitu besar dan memiliki tinggi yang sama dengannya. Dia bergumam, “Aku harus segera mengatakannya.”
Taka menampilkan ekspresi yang seolah berkata, “Heh?” tapi dia menahannya. Ini demi terjaganya suasana yang sudah tidak bisa dibawa ke alur komedi. Serius, tegang, dan penuh tanya, itu yang ditangkap oleh jalanya.
Keringat keluar tanpa izin dari pori-pori kulit. Muka Taka dibasahi olehnya. Menanti perkataan yang tidak kunjung keluar memang menegangkan baginya. Seperti orang yang kesusahan berak, hingga membuang waktu di dalam toilet, tanpa hasil. Bahkan keringat dan kalori telah terbakar habis.
Rafethea mengepalkan kedua telapak tangan, perubahan itu kembali terjadi: bola mata memerah, kuku-kuku jari tangannya tumbuh memanjang. Taka ingin bertanya, “Apakah aku akan kamu bunuh?”
Ternyata menyaksikan langsung tidak semudah ketika dari kejauhan. Setiap senti meter pertambahan panjang kukunya terasa menegangkan. Pupil cokElat yang memudar, berubah merah, semakin mempercepat detak jantung, hingga hormon adrenalin diproduksi secara massal.
Gadis itu bergemataran, dan menundukan kepala. Taka sedikit berjalan mundur, lalu berhenti saat melihat hal yang normal dan seharusnya telah kembali. Rafethea mengangkat kepala: mata cokelat bersinar terkena cahaya lentera, kedua pipi merona seperti warna langit sebelum benar-benar gelap.
“Aku..”
Satu kata pembuka setelah ketegangan telah diluncurkan. Taka tidak menanggapi, lebih memilih menatap wajahnya dengan seksama. Dia sudah mampu menghubungkan akar pohon yang terpisah. Roda gigi sudah menemukan kesinambungannya.
Aku sudah tahu apa yang akan diucapkan olehnya. Apa aku harus mendahuluinya seperti yang kulakukan pada lelaki itu? Tidak-tidak, aku bukan pria sejati. Aku hanya pria pengecut yang menyengir ketika menelan buah masam. Biarkan saja dia yang mendominasi, begitu lebih baik.
Masih belum ada kata tambahan dari jeda yang diberikan. Kekosongan ruang itu masih dibiarkan tanpa penghuni. Taka sempat berpikir untuk mengisi agar tidak bernasib seperti bangunan sekolahnya, tapi tak kuasa. Sedangkan Rafethea, masih sibuk merangkai keberanian; mulutnya terus merapal sesuatu.
“Aku men-“
Tiba-tiba Rafethea jatuh tertunduk dalam posisi jongkok, seperti ada yang menduduki tubuhnya. Bayangan yang sejajar dengannya tadi, semakin bertumbuh besar dan memiliki wujud jelas. Sementara itu, api dari lentera mulai menyambar berontak. Dia tidak pada jalur bakarnya.
Taka terlihat panik, dan membantunya berdiri. Tapi, gadis itu mengangkat tangan kanan, seolah memberi sinyal untuknya, agar tidak bertindak, membantu. “Aku bisa,” gumamnya.
Iya kamu pasti bisa, walau aku tidak tahu apa yang kamu maksud, meski aku sudah tahu.
Rafethea berdiri setelah direndahkan, entah oleh apa, mungkin siapa. Dia memejamkan mata sejenak, lalu muncul keyakinan dan keberanian di pupilnya. Sudah tampak beda, Taka mampu merasakannya. Aura yang dipancarkan oleh Rafethea terlihat begitu silau, mungkin berwarna merah.
Dia menarik dan menghembuskan napas berkali-kali, lalu berteriak, “Arwantaka, aku, aku, aku mencintaimu!”
Ucapannya barusan menggaung ke seluruh penjuru bukit. Bahkan gendang telinga Taka mengulangi perkataan Rafethea berkali-kila, hingga menciptakan gema.
Ini benar-benar tidak adil bagi Taka, padahal dia sudah menyiapkan tekad beberapa hari terakhir. Kebulatan tekadnya seperti dibelah dua.
Api lentera mulai menyambar tak terkendali, tapi tidak membakar satu pun objek di sekitarnya. Tanpa disadari olehnya, Rafethea telah menghilang, hanya bayangan hitam yang tersisa di sebelah bekas posisinya. Bayangan itu dapat berjalan. Menapaki setiap jengkal ke arah Taka.
Semakin dekat, Taka melangkah mundur, perlahan. Api lentera yang menyambar seperti lidah ataupun ekor, bergerak menuju ke arah bayangan itu. Mereka seperti tengah bertarung. Api lentera seolah tengah melindungi Taka. Dia berinisiatif untuk menambah minyak pada lentera, dengan begitu akan semakin besar.
Ternyata Rafethea lebih siap dari dugaannya; sebotol minyak tanah terselip di belakang lentera. Taka menuangkan semua minyak tanah yang ada pada lentera. Benar saja, api semakin membesar. Tak butuh waktu lama, bayangan hitam itu menghilang seperti dilahap olehnya. Lalu, api dari lentera menuju ke arah Taka dan melahapnya juga.
Dunia putih ini, putih, aku pernah melihatnya. Kapan dan di mana? Ohh..Waktu itu, ketika pertama kali bertemu dengannya.
Taka mulai membuka mata dengan perlahan. Dia dalam posisi tidur terlentang di sebuah ruangan hampa berwarna putih. Tidak ada apapun atau siapapun di situ. Dia mendengar langkah kaki yang tengah berjalan ke arahnya. Segera bangkit menuju posisi duduk bersimpuh. Menyiapkan indera penglihatan dan pendengaran untuk menangkap.
“Kamu sepertinya berhasil.”
Sepatah kalimat yang dikenali dengan baik olehnya. Suara itu berasal dari belakang Taka yang tengah duduk bersimpuh. Dia membalikkan badan, dan melihat gadis itu berjalan ke arahnya. Gadis itu tetap mengenakan gaun terusan berwarna putih.
Taka meraba-raba tubuhnya sendiri, lalu mencopot pakaiannya. Dia tetap meraba, tapi lebih khusus ke dada kirinya. “Tidak ada,” gumamnya. Entah dia harus lega atau khawatir dengan peristiwa ini.
“Tanda itu sudah berubah menjadi ini,” ujar gadis itu sembari membawa dua bilah pedang pendek di kedua tangannya. Dia menyerahkannya pada Taka yang masih menganga.
“Apa yang harus kulakukan dengan ini?” tanya Taka yang masih sibuk memandangi dua pedang digenggaman tangannya. Begitu berat, itu yang dirasakan olehnya. Rasa penasarannya lah yang membuat pedang tersebut menjadi begitu berat.
Gadis itu membantunya berdiri dengan mengulurkan tangan. Halus dan lembut, itu yang dirasakan oleh telapak tangan Taka ketika menyentuhnya. Rasa-rasanya dia ingin terus berada di sini; menikmati.
“Jawabannya ada di lembaran yang aku berikan padamu.”
Taka menaruh dua pedang itu, dan segera mencari lembaran kertas yang dimaksud; di saku celana dan jaketnya. Cukup lama tangan mengobrak-abrik, akhirnya juga telapaknya menyentuh sesuatu seperti kertas. Dia menarik paksa agar keluar dari tempat persembunyian. Waktu hibernasinya sudah habis. Kini saatnya menjalankan tugas sebagai seorang informan.
Gadis itu tiba-tiba menggigit jempol kanannya; keluar darah. Dia meneteskannya di atas lembaran kertas yang akan dibuka oleh Taka.
“Untuk apa?” tanya Taka, kebingungan.
“Formalitas,” jawabnya singkat, lalu diikuti cekikikan kecil, seperti hantu.
Taka menggelengkan kepala; sebagai bentuk reaksinya. Responnya memang tepat untuk menanggapi alasan konyol gadis itu. bukan, jika dia salah, maka itu tidak benar dan gadis itu benar.
Mata Taka mulai mengejar setiap kata yang berbaris dan tidak pernah kabur ataupun berlari dari posisi.
Kamu yang bisa membaca ini, telah berhasil menciptakan momen tepat. Jadi, kuucapkan selamat atas keberhasilanmu. Berbahagialah, horeee… tapi, langkahmu masih belum berakhir. Ada klimaks yang harus kamu capai. Kamu bahkan belum mencapai puncak pohon. Masih ada cabang yang harus kamu lalui. Kamu harus bunuh aku! Kamu bunuh aku yang bersamamu itu ! Tidak usah kaget, aku tahu kamu pasti sedang membuka lebar-lebar kelopak matamu. Tapi tenang saja, aku tetap memberimu dua pilihan. Pertama, kamu tidak membunuhku, tapi duniamu hancur. Kedua, kamu bunuh aku dan duniamu baik-baik saja, entah sampai kapan. Bagaimana? Jika kamu memilih pilihan kedua, maka gunakanlah salah satu pedang itu untuk menusuk dada kiriku. Sedangkan pedang yang satunya, dapat kamu gunakan untuk mengakhiri hidupmu sendiri, jika tidak kuat. Mudah kan?
“Sialan!” umpat Taka dengan lantang.
Gadis itu tertawa begitu keras hingga susah bernapas. Air mata berlinang di tulang air matanya. Itu bukan kesedihan, melainkan kebahagiaan, karena juga ada senyum yang menghiasi, selalu begitu.
“Diriku yang itu memang cukup absurd kalau merangkai kata-kata, padahal tingga berkata bunuh diriku! Selesai sudah.”
Taka mengangkat salah satu alisnya, lalu berkata, “Kamu jangan memperumit ini.” Air mata yang berbeda dengan gadis itu mulai membasahi pipi Taka.
Gadis itu menepuk punggung Taka beberapa kali dengan pelan. Maksud hati untuk menenangkannya. Tapi, Taka malah semakin mencengkram kepalanya. Membenturkan kepala beberapa kali hingga keluar darah tepat pada dahinya. Gadis itu hanya tersenyum, selalu begitu.
Padahal aku mulai…
Dia menarik ingusnya dalam-dalam dan menghapus air mata, lalu bertanya, “Jika aku membunuh kamu yang ada di duniaku, apa kamu akan juga ikut hilang?”
Gadis itu sedikit memiringkan kepalanya ke kanan, dan menaruh jari telunjuk pada dagu; dia pernah melakukannya, sering sekali. Dia berlari-lari sembari melompat dan merentangkan kedua lengan, ibarat seekor burung.
“Aku ini burung yang bebas di duniaku sendiri. Jadi, kematian diriku yang itu, tidak akan menghapus keberadaanku di dunia ini.”
Taka mengangguk sembari mengepalkan tangan kanan. Mengambil kedua bilah pedang pendek yang sedari tadi dibiarkan tengkurap tanpa tugas. “Kembalikan aku!” perintah Taka padanya.
“Kamu sudah yakin?” tanya gadis itu. “Padahal kamu bisa hidup selamanya denganku di sini. Aku dan diriku yang itu kan sama saja.”
“Tidak! Tidak sama!” bentak Taka. Air mata kembali bermuara.
Gadis itu tersenyum, selalu begitu. Taka tersentak melihat responnya yang selalu berlawanan. Seharusnya dia menjadi cermin, begitu anggapannya.
“Tapi, aku bisa memakai ingatan diriku yang itu,” jelas gadis itu, tenang. Dia tampak begitu senang di sini. Padahal tidak ada apapun; hanya ruang kosong yang putih. Mungkin dengan begitu dia bisa menjadi apapun dan siapapun di sini.
“Sudah, cepat kembalikan aku,” ujar Taka yang menahan isak tangisnya. Dia mencengkram erat gagang dua pedang tanpa sarung itu.
“Oke, sampai bertemu kembali, Ar-wan-ta-ka.”
Taka tergidik dan tidak merespon. Pikirannya tengah sibuk menerima hal yang terjadi dan akan terjadi. Puncak dari perjuangannya akan segera dipampangkan dengan jelas.
“Kamu tidak apa-apa?”
Sebuah pertanyaan bersamaan dengan tubuhnya yang digoyang-goyangkan membuat dirinya tersadar. Dia tengah tertidur terlentang. Kepalanya mendapatkan sebuah bantal dari paha sebagai alas. Gadis itu, Rafethea, melihat tepat ke wajahnya ketika Taka membuka mata.
Taka bangkit, dan duduk bersimpuh, kedua kalinya. Dia segera memeluk Rafethea dengan erat. “Darah?” gumamnya. Dia mendapati tangannya penuh darah ketika menyentuh punggung Rafethea.
“Hehehehehe….Waktuku sudah tidak banyak, kamu harus segera menyelesaikannya,” ujar Rafethea, diikuti senyuman, selalu begitu.
Taka tak kuasa membendung aliran sungai di matanya. Terlalu deras dan banyak debit airnya.
“Tidak, aku tidak bisa!” teriak Taka. Padahal langit sudah gelap sekali, dia memang tidak punya malu pada tetangga.
“Kamu bisa Taka, tinggal tusukan saja salah satu pedang itu sesuai intruksi dari lembaran yang kamu baca. Atau diriku yang ada di dalam tubuhku akan menghancurkan duniamu. Kumohon, aku sudah tidak ingin menjadi monster, aku sudah lelah bertopeng, otot wajahku sudah keram melukis senyum ini, aku ingin menangis, mengerang sekencang mungkin, tapi itu tidak adil.”
Taka masih belum melepas pelukannya. Mungkin ini terakhir kalinya dia bisa melakukan itu. Tidak akan ada kesempatan kembali. “Baiklah, aku akan membantumu melepaskan semua bebanmu. Tapi, izinkan aku pergi bersamamu,” ucapnya.
“Tidak!” bentak Rafethea. “Kamu masih punya waktu untuk hidup di dunia ini. Jalanmu masih sangat panjang; tamat sekolah, bekerja, mencari pasangan hidup, berkeluarga, dan setelah itu kamu boleh pergi bersamaku. Tapi, jika aku menunggumu, duniamu akan hancur, hehehe…”
Taka tertegun sembari menciumi aroma wangi dari rambut Rafethea. Dia membelai dengan lembut setiap helainya. “Aku mencintaimu, sangat mencintaimu, terima kasih karena pernah hadir, kehadiranmu memberiku sebuah pandangan baru, terima kasih.”
Rafethea menganggukan kepalanya dengan dalam, lalu berkata, “Boleh aku meminta satu hal?”
“Apa itu?”
“Tolong panggil namaku. Sebelumnya kamu selalu memanggilku dengan kamu, dirimu, atau kau.”
“Aku akan memanggilmu sebanyak yang kamu mau,” jawab Taka dengan tegas. “Rafethea…Rafethea…Rafethea…Rafe-the-a.” Ingus dan air mata membuatnya tersendat dan tidak kuasa melanjutkan. Dia semakin menangis tersedu-sedu.
Rafethea tersenyum, tapi Taka tidak bisa melihatnya dengan jelas. “Terima kasih, Takoyaki.”
Taka melepas pelukan, dan mulai mengayunkan pedang yang ada di tangan kanannya; mengarah tepat pada dada kiri Rafethea. Dia memutar tiga ratus enam puluh derajat untuk mengoyak jantungnya. Rafethea bahkan tidak mengerang kesakitan sekalipun, walau darah memenuhi dada dan mulutnya. Menyemburat deras seperti pancuran. Darah itu menciprat ke wajah Taka yang berusaha memeluk Rafethea.
“Terima kasih Taka, karena telah membebaskanku,” bisik Rafethea sebelum kehilangan kesadaran dan menghilang dari pelukan Taka.
Bekas darah yang melumuri Taka telah menghilang sebelum dibilas dengan air. “Rafethea!” teriak Taka, hingga membuat hewan malam seolah mengikuti apa yang dilakukan olehnya.


 Ardhatn
Ardhatn