Setelah pertengkaran dengan Satria sore itu, di musala samping tempatku bekerja. Beberapa kali ia terus mencoba menghubungi lewat ponsel, tetapi aku selalu mengacuhkan. Rasanya enggan untuk membicarakan kembali, perihal yang sangat mengecewakanku itu.
Lukman rekan kerjaku, merasa ada perbedaan dengan tingkah lakuku saat bekerja akhir-akhir ini. Terkadang tanpa ia sengaja sering melihatku termenung, atau kadang memukul-mukul peralatan di dapur. Hingga akhirnya ia bertanya, “Kamu kenapa, beberapa hari ini sering ngelamun gitu, Bim? Ada masalah?”
Dengan acuh, aku menjawab, “Enggak ada apa-apa, Luk. Biasa sedikit masalah. Yah ... kamu tau sendirilah, antara aku ama Kartika kayaknya udah enggak bisa dipertahankan lagi.” Aku duduk di bangku dapur, yang biasa kujadikan alat untuk menjangkau barang di atas lemari.
“Kehidupan emang kadang enggak seperti yang kita bayangkan, Bim. Kayaknya, kamu butuh sesuatu buat naklukin Kartika, deh!” seru si mata belo, seraya duduk di sampingku setelah menyeduh kopi di dapur.
“Maksud kamu?”
“Aku perhatiin, kamu itu polos dan hidup lurus-lurus aja, Bim.” Si mata belo terlihat menyeruput kopi di tangannya, kemudian kembali berkata, “begini. Kadang kita mesti punya bekal, untuk dihargai oleh orang ataupun atasan, Bim. Hidup ini keras, segala hal kalau enggak punya bekal pasti dilecehin ama orang atau atasan. Makanya, kamu butuh suatu ilmu buat bekal dihargai oleh orang, Bim.”
“Maksud kamu, bekal apaan, Luk?”
“Ya bekal ... bekal ilmu gitu. Semacam ilmu pengasihan, pemikat atau kanuragan. Biar orang yang berhadapan sama kita, luluh dan enggak berani berbuat macam-macam. Aku aja pake yang gituan buat disukai atasan, dan kamu lihat? Karirku bagus di sini, bukan?” jelas si mata belo, membuatku bergidik.
Di zaman modern seperti ini, masih ada yang berpikiran primitif seperti Lukman ini. Terkadang lebih parah, mendewakan suatu barang yang diyakininya bisa memberikan kekayaan. Padahal, semua yang kita dapatkan di dunia ini, berasal dari Tuhan bukan semacam benda-benda keramat seperti yang diyakini Lukman itu.
Mendengar penuturan Lukman si mata belo, aku hanya bisa terdiam tanpa berani berkata apa-apa. Sementara ia sendiri, masih asyik dengan kopi di tangannya. “Begini, Bim. Kalau kamu mau, aku ada sebuah tempat di mana kamu bisa dapetin bekal yang tadi aku maksud. Yah seenggaknya, buat jaga-jaga dari marabahaya yang enggak tau datangnya kapan, kan?”
“Ah, kamu ini masih aja percaya hal mistis kayak gitu, Luk.”
“Eh, ini bener lho, Bim! Kalau kamu enggak percaya, entar sore aku ajak kamu ke sana. Biar liat langsung gimana saktinya guruku di sana ngasih ilmu itu. Aku juga mau minta pengasihan, buat naksir si Meti asistenku itu, hehehe.”
“Dasar buaya aja kamu mah, Luk. Udah si Lala yang dideketin, sekarang giliran si Meti buat jadi korban berikutnya. Huh ...!”
“Yah, cowok mah boleh milih yang terbaik kan, Bim? Wajar selama enggak ngerusak kehormatan cewek, sih. Asal tanggung jawab. Udah ... kalau kamu mau, entar sore ikut aku ke sana. Biar aku kenalin sama guruku di sana, dan kesulitan kamu bisa teratasi!”
Aku hanya terdiam, mendengar ajakan si mata belo Lukman tadi. Yah ... setidaknya sekedar ingin tahu seperti apa yang dijelaskan temanku tadi, mengenai ilmu semacam itu.
*****
Ponselku kembali berbunyi. Saat dalam perjalanan bersama Lukman menuju sebuah kampung yang bernama Kampung Keramat selepas pulang kerja, seperti yang diceritakan Lukman waktu di dapur. Di layar ponsel tertera nama Satria, tetapi kembali kuabaikan panggilan darinya. Sudah hampir dua hari ia menghubungi, entah apa yang diinginkannya tetapi hatiku sudah terlanjur kecewa.
Setengah jam perjalanan aku dan Lukman menuju Kampung Kramat, dengan menggunakan motor masing-masing. Membawaku ke sebuah desa terpencil dekat bukit Trengginas, yang terkesan angker menurut beberapa isu dari masyarakat sekitar. Aroma dupa tercium menyerbak, di sela-sela pepohonan tinggi yang rindang. Ukiran dengan tulisan kuno, tampak jelas di sebuah papan batas gerbang desa bertuliskan ‘Kampung Keramat’. Di sampingnya ada sebuah buntalan dari kain putih, yang ditengarai sebagai tolak bala menurut kepercayaan dari masyarakatnya.
Perlahan motor yang dikendarai Lukman, berhenti di sebuah rumah berdinding bambu kuno. Sedangkan aku yang mengikutinya dengan motor matik kesayangan berwarna hitam, ikut berhenti di samping motor milik Lukman. Tidak banyak yang kami bicarakan, setelah memarkir motor. Lalu Lukman berjalan memasuki rumah tadi.
“Selamat sore, Mbah. Saya Lukman, yang tempo hari ke sini ngasih mahar. Mbah ada di dalam?” sapa Lukman di depan pintu rumah, seraya mengetuknya. Aku yang berdiri di belakang, hanya melihat-lihat keadaan rumah yang sudah hampir roboh itu.
Aku pikir, kalau si Mbah ini emang sakti dan banyak didatangi orang buat minta ilmunya. Pasti banyak uang yang ia peroleh. Tetapi kenapa untuk membenahi rumah yang reot seperti ini, seakan-akan dibiarkan begitu saja. Lalu buat apa uang yang didapatkan dari segelintir orang, ia gunakan? Sungguh heran, dengan keyakinan orang-orang primitif ini.
Namun pikiranku segera membuyar, begitu pintu rumah dibuka seseorang dari dalamnya. Terlihat seorang laki-laki tua setengah baya, menyeringai dengan deretan gigi yang sudah jarang setengah ompong layaknya Kunto Ijo dalam seri pewayangan. Bertubuh gempal dengan perut yang hampir membuncah dari celana hitam, serta tatapan tajam layaknya makhluk astral dari negeri dongeng.
“Ouh kamu, Nak Lukman? Mari masuk. Sama siapa kamu ke sini sekarang? Ada pasien baru, ya?” tanya laki-laki setengah baya itu dengan suara seraknya, seraya melirik ke arahku. Matanya menatap tajam, layaknya binatang buas di hadapan mangsa yang sudah tidak berdaya.
“Ini teman kerja saya, Mbah. Dia penasaran, saat saya ceritakan ilmu yang pernah Mbah kasih tempo hari. Yah ... mudah-mudahan apa yang dia cari di sini, bisa Mbah beri buat pegangan dia juga, Mbah. Bim, kenalin nih guruku, namanya Mbah Suro,” jawab Lukman memperkenalkan sosok laki-laki setengah baya di hadapan kami, seraya menatap ke arahku yang masih termenung melihatnya.
“Ouh, begitu? Ya sudah, ayo kalian masuk. Entar Mbah kasih ilmu, yang bisa kalian pakai.” Laki-laki setengah baya, yang bernama Mbah Suro itu bergeser dari tempatnya berdiri mempersilakan Lukman dan aku untuk masuk ke dalam rumahnya itu.
Perlahan Lukman masuk, dikuti aku dari belakang. Sedangkan laki-laki setengah baya bernama Mbah Suro tadi, menutup kembali pintu rumahnya. Sungguh mencengangkan, saat mataku melihat keadaan di dalam rumah tersebut. Deretan kepala binatang, tampak menghias dinding rumah. Di tambah tulisan Arab setengah pudar, terpampang di beberapa sudut ruangan. Sedangkan di sebuah sudut lagi, terhampar sebuah meja setinggi badan jika duduk di lantai yang beralaskan tikar bambu. Di atasnya ada beberapa nampan, berisi kembang berwarna-warni. Juga tungku yang mengepulkan asap beraroma dupa, tercium jelas memenuhi seluruh ruangan.
‘Kayak Mbah Dukun aja nih, si Mbah Suro ini,’ pikirku, masih terpana melihat seiisi ruangan.
“Ayo silakan duduk, Nak Lukman. Baru pertama kali ke sini, temannya itu, ya?” tanya Mbah Suro, seraya duduk di depan meja pendek yang berada di hadapanku juga Lukman. Sedangkan mata tajamnya terus memandangiku dengan penuh selidik, seperti hendak menerkam mangsa buruan.
“Iya, Mbah. Dia baru dalam hal beginian, makanya pengen dapetin ilmu buat jaga-jaga,” jawab Lukman kemudian duduk diikuti aku di sampingnya, di hadapan meja tadi.
“Ada maksud apa, kalian datang ke sini?” tanya Mbah Suro, terlihat menabur sesutu di atas tungku yang mengepulkan asap.
“Begini, Mbah. Saya datang ke sini, mau minta ilmu pelet buat luluhin si Meti teman cewek sepekerjaan. Saya kesengsem ama dia, Mbah.” Lukman tiba-tiba menyebutkan nama rekan kerjanya, yang biasa bersama saat melayani tamu datang ke hotel. Hal itu membuatku terkejut. Tidak disangka, ia tega berbuat picik dengan cara kuno seperti ini. Ah ... suatu hal yang masih ia percayai. Padahal cukup gantenglah, untuk memikat wanita mana saja tanpa harus dengan pelet. Meski matanya belo, masih ada gurat kegantengan yang hampir mengalahkan Bang Mandra artis film Si Doel Anak Betawi.
“Gampang itu mah, Nak Lukman. Entar Mbah kasih jampe dari sini, dan ada bekel buat pegangannya. Cuma maharnya lumayan, Nak. Mau?” ungkap Mbah Suro, terlihat mengeluarkan sesuatu yang terbungkus kain hitam bertali dan diletakkannya di atas meja.
“Berapa kir-kira maharnya, Mbah? Jangan mahal-mahal ya, Mbah. Hehehe.”
“Murah kok, Nak Lukman. Cuma satu juta aja, udah bisa memikat hati cewek yang dipengen. Gimana? Kalau mau, nih pegang ini entar Mbah kasih jampenya. Bawa foto si ceweknya, kan?”
“Waduh! Jangan mahal-mahal, Mbah!,” Lukman tampak terkejut dengan ungkapan si Mbah tadi.
“Mau enggak? Segitu mah udah murah, Nak Luman! Dari pada kamu enggak dapetin tuh cewek, kan? Bawa enggak duitnya?”
“Bawa, Mbah. Bawa. Sebentar saya ambil dulu.”
“Sekalian mahar sama fotonya, ya? Biar Mbah sekalian kasih jampe juga.”
“Iya, Mbah.” Terlihat Lukman mengambil sesuatu, dari dalam tas selempang yang selalu ia bawa. Selembar foto wanita yang tidak asing buatku, juga amplop putih dan mungkin isinya uang sebagai mahar seperti disebutkan oleh si Mbah Suro tadi.
“Ini, Mbah. Foto juga uang maharnya. Ampuh kan ilmunya, Mbah?” tanya Lukman, seraya menyerahkan apa yang diminta si Mbah Suro.
“Tenang aja, Nak Lukman. Selama ini, ilmu dari Mbah enggak pernah gagal, kan?” balas Mbah Suro seraya menyeringai licik, kemudian menerima apa yang diserahkan Lukaman.
“Sip kalau gitu, Mbah. Saya udah enggak sabar, pengen deketin si Meti, Mbah.”
“Namanya siapa tadi?”
“Meti, Mbah. Meti Puspaningrum lengkapnya.”
“Ouh iya, Meti. Ya sudah, Mbah kasih jampe dulu, ya?”
Tidak berapa lama, setelah menerima apa yang diberikan Lukman kepada Mbah Suro. Tampak mulutnya komat-kamit, seakan-akan merapalkan sesuatu di depan sebuah foto yang dipegang tangan kirinya. Sementara tangan kanannya, dengan gerak cepat menabur sesuatu kembali ke atas tungku yang mengepulkan asap. Sontak si tungku, kembali mengeluarkan asap tebal yang membumbung mengisi seluruh ruangan. Aroma dupa yang menyengat dari asap tersebut, terasa begitu menyesakkan. Seolah-olah terbiasa dengan rutinitasnya melayani orang-orang, yang ia sebut sebagai pasien.
Cukup lama juga Mbah Suro merapalkan mantranya, di depan sebuah foto yang ia pegang. Sementara mataku melihat Lukman menyeringai senang, dengan apa yang dilakukan laki-laki setengah baya, yang ia panggil dengan sebutan guru itu. Selesai dengan apa yang dilakukan Mbah Suro. Ia menyerahkan kembali foto Meti kepada Lukman.
“Sudah Mbah kasih jampe, buat jabang bayinya si Meti ini, Nak Lukman. Kamu jangan khawatir, dalam beberapa hari ke depan akan ada perubahan dari si Meti ini kepadamu. Ini fotonya.”
“Terima kasih, Mbah. Saya percaya sama kesaktian Mbah ini. Sekarang giliran teman saya ini ya, Mbah?” ungkap Lukman, menerima foto dari tangan Mbah Suro seraya menatap ke arahku.
“Ouh iya, temanmu itu juga minta sesuatu dari Mbah, ya? Apa yang kau minta, Anak Muda? Entar Mbah kasih kayak temanmu ini.” Mbah Suro berganti menatap ke arahku, yang sedang termenung dengan apa yang baru saja terjadi.
Belum sempat aku berbicara. Tiba-tiba telinga ini, seakan-akan mendengar seseorang membisik dan memanggil namaku dari arah luar rumah. Sontak hal itu membuatku terkejut, dan mencari asal suara yang kudengar samar itu.
“Bimo ..., Bimo! Keluar dari tempat terkutuk itu, Bim!” Kembali terdengar suara samar memanggil namaku, dan membuatku kembali terkejut.
“Ada apa, Bim? Tuh, sekarang giliranmu minta ilmu ke si Mbah Suro.” Lukman yang sudah mendapatkan apa yang ia minta ke Mbah Suro, menatap ke arahku dengan terheran. Sebab tingkahku layaknya seroang yang hilang ingatan, akibat suatu bisikan yang sedari tadi terdengar memanggilku.
“Kamu denger seseorang manggil namaku enggak, Luk? Barusan kayak ada yang manggil namaku.”
“Enggak, Bim. Dari tadi, aku cuma lihat kamu kayak yang kebingungan. Ada apa?”
Belum aku jawab pertanyaan Lukman. Kakiku seakan-akan mengajak untuk keluar dari rumah itu, dan mencari-cari asal suara yang terus memanggil namaku. Sedikit berlari, aku keluar dari rumah Mbah Suro dan membuat Lukman juga si Mbah terheran.
“Temanmu kenapa, Nak Lukman? Tiba-tiba aja lari keluar rumah, enggak jadi minta ilmunya?” tanya Mbah Suro yang terheran juga dengan tingkahku.
“Enggak tau, Mbah. Sebentar, saya kejar dulu anaknya, ya?” Lukman kemudian beranjak dari hadapan Mbah Suro, mencari keberadaanku yang masih mengikuti arah suara yang terus memanggil-manggil namaku.
Aku masih kebingungan dengan arah suara yang terus menerus memanggil namaku, seraya keluar dari rumah si Mbah Suro itu. Dengan perasaan bimbang dan ragu, kudekati sebuah pohon besar yang tidak begitu jauh dari rumah Mbah Suro. Aku lihat si Kakek tua, yang pernah bertemu di teras musala tempo hari. Bergegas kakiku mendekatinya, yang sedang bersembunyi di balik pohon besar itu.
“Kakek?! Bukankah, Kakek ini yang ....”
“Iya. Kamu harus segera jauhi tempat terkutuk itu sebelum terlambat, Anak Muda! Tempat itu merupakan tempat musyrik, yang bisa membuatmu terkena azab dari Allah! Ingat! Hanya Allah tujuan hidupmu, bukan si Mbah terkutuk itu! Kalau kamu ingin selamat, bukan begini caranya, paham?!”
Belum sempat aku berkata, si kakek tua di hadapanku langsung memotong dan mengingatkan atas perbuatan yang tadi dilakukan oleh Lukman, dengan si Mbah Suro di dalam.
Belum sempat lagi aku berkata, terdengar suara Lukman memanggil namaku. Sontak aku berbalik ke arah Lukman memanggil, dan tiba-tiba ....
Wush ...! Bruk! Brak! Brayak!
Rumah Mbah Suro terlihat hancur diterjang angin yang datang tiba-tiba, dan meluluh lantakkan isinya termasuk si Mbah yang masih berada di dalamnya. Hal itu membuatku juga Lukman, terkejut melihatnya.
“Astagfirullah! Rumah si Mbah Suro, hancur!” teriakku, tercengang diikuti Lukman yang berada tidak jauh dari rumah yang tampak sudah rata dengan tanah itu.
Memiliki firasat kalau itu perbuatan si kakek tua, aku kembali berbalik ke arahnya yang sedang berada di balik pohon besar tadi. Namun apa yang kudapati. Sosoknya sudah menghilang dari balik pohon di hadapanku. Langsung kucari-cari keberadaannya, tetapi hasilnya nihil. Si kakek menghilang begitu saja, tanpa kuketahui ke mana ia pergi.
“Kamu kenapa lari tadi, Bim? Untung aku ngikutin kamu, kalau masih di dalam bisa ikutan hancur aku, nih!”
“Enggak, Luk. Tiba-tiba saja aku pengen keluar dari rumah itu. Enggak taunya malah begini kenyataannya.” Aku menutupi apa yang terjadi di hadapan temanku itu. Meski hati ini tahu kalau kejadian tadi pasti perbuatan si kakek tua, yang menyelamatkanku dari perbuatan syirik.
Tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, di hadapanku juga Lukman. Kami pun bergegas meninggalkan Kampung Kramat, yang menyisakan bermacam pertanyaan di dalam benak. Hal itu membuatku benar-benar terbuka kembali, dengan apa yang terjadi. Termasuk masalahku dengan Satria dan Kartika selama ini, yang sudah sedikit terlupakan.
*****


 Kang_Isa
Kang_Isa





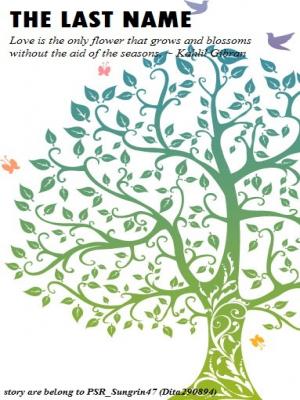

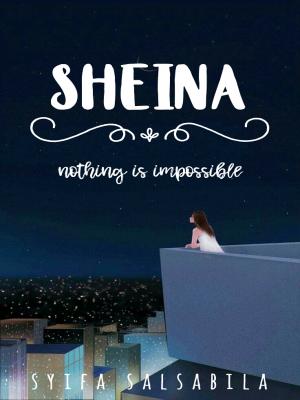


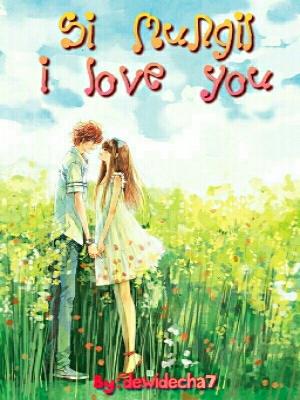


Amalaakk Satriaaa ... Kece ini mah ????
Comment on chapter Episode 1