Togar sudah menungguku lengkap dengan seragam putih-hitam mengaji. Hari ini jadwal masuk sore. Aku melupakan itu, sehingga tercengang mendapati Togar yang datang menjemputku lengkap dengan kopiah dan Al-Qur’annya. Sebelumnya aku sibuk mengobati lukaku dengan duduk di atas bangku. Togar melihat luka itu karena memang aku tak bisa menyembunyikannya. Bagaimana tidak, dari dulu aku sudah terbiasa mengenakan baju berlengan pendek, bahkan tanpa lengan jika sedang tak ingin ke mana-mana. Mengetahui kalau bekas luka itu sangatlah mengerikan, memar dan merah, membuat Togar teringat kembali dengan rasa bersalahnya. Ia berulang-ulang meminta maaf kepadaku, namun aku sudah lebih dulu memaafkannya, bahkan moodku sudah kembali membaik.
Terdengar nyanyian Batak, lama menungguku Togar pun melakukan hobinya. Bernyanyi dengan lagu favorite; lagu Batak. Aku hanya menggeleng dari dalam sambil berusaha memercepat gerakanku memakai seragam. Sementara itu, Amak sedang memasak tempe di dapur, dan Uda tidak di rumah. Sejenak aku bergeming, memandangi kopiah yang sesaat lagi akan menempel di kepalaku dengan gagah. Andai, mengenyam pendidikan di sekolah semudah mengaji. Selain dipersulit karena tempatnya yang jauh, biaya membeli buku pelajaran juga menjadi beban bagi keluarga-keluarga miskin di Manggopoh.
****
“Dia-lah yang Menjadikan bumi untuk kalian yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.QS.al-Mulk:15.”
Ust. Yusuf berhenti sejenak, memandangi wajah-wajah yang hadir memenuhi surau..
“Minang adalah suku terbesar yang memiliki tradisi merantau! Coba jelajahi bumi ini, maka kalian akan menemukan sedikitnya ada sepuluh kepala keluarga Minang di seluruh kota di Indonesia. Jangan bergantung pada takdir dalam keadaan diam.”
Sudah hampir setengah jam Ust. Yusuf berceramah. Begitu berambisi, bukan pemandangan langka—kami semua terpaku, tertegun, ternganga bagi sebagian anak. Aku mengangguk-angguk di setiap jeda ucapan Ustaz muda itu. Dia begitu ahli, namun selalu terlihat bersahaja.
“Orang-orang hebat adalah dia yang sudah berani menerima risiko terburuk. Dalam penghebatan diri, tidak ada proses instan. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Apa yang bisa dikejar, dikejar. Jendela harus dibuka untuk melihat pemandangan di luar sana. Jika aturan-aturan dan nasihat agama sudah tertancap di diri kalian, akan selalu ada kemudahan. Kita memang harus berserah diri kepada Allah, namun bukan berarti kita bisa diam atau mengurung diri di dalam kamar. Berserah yang dimaksud, membiarkan Allah menentukan hasil setelah kita berupaya. Anak-anak, jika yang terdekat memang tidak bisa membantu, merantaulah. Rasa malas tidak akan mendatangimu dalam keadaan yang serba sulit.
****
Pulang dari mengaji aku berpikir di sepanjang jalan. Menyaring dan mencerna ucapan Ust. Yusuf tentang perantauan. Gagasan itu benar-benar termakan olehku, sehingga mengabaikan Togar yang berceloteh membicarakan bumi dan seisinya. Bahkan aku masih ingat, rupa air mukaku yang terpekur mendengarkan ceramah ustaz muda tersebut. Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa minang adalah suku terbesar yang dikenal dengan budaya mereantau. Maka dari itu orang minang bisa ditemui di kota dan negara mana aja. Termasuk masakan khasnya, sehingga restoran padang kini telah tersebar diberbagai daerah. Aku bukan hanya sekadar memikirkan ucapan Ust. Yusuf, tapi, juga mulai menyusun rencana sematang-matang agar aku bisa merantau. Aku tahu kalau ini tidaklah mudah, karena terlebih dulu pastilah aku akan mendapatkan makian dari uda. Laki-laki pengaguran itu memang tidak pernah suka dan mendukung apa-apa yang kulakukan. Yang ia tahu hanyalah bagaimana aku bisa mendapatkan uang tanpa harus merugikannya.
“Pul.”
Togar menyempilkan suara cemprengnya di tengah-tengah pikiranku yang sedang bekerja keras. Sepertinya si anak batak yang tadi sukses menghanyutkan semua orang dengan bacaan murothalnya mulai merasa bosan untuk berceloteh panjang. Tubuh pendek itu dibawanya berdiri di hadapanku, seperti hadangan berandalan yang akan memalak.
“Ada apa, Gar? Kau bikin lama saja.”
Rambutnya yang gimbal didorongnya masuk ke dalam kopiah. Sementara itu, lengannya mengapit Al-Qur’an yang disimpan di dalam kantong plastik. Ya, orang-orang seperti kami menjadikan plastik yang didapat dari membeli baju sebagai alternatif tas mengaji.
“Pul, kau pasti memikirkan ceramah Ust. Yusuf tentang merantau, kan?”
“Tahu dari mana kau, Gar?”
Teman yang berjarak 2 bulan dariku itu, menepi. Memberi jalan, dan ia pun menarik napas panjang. Gaya itu memang sedikit pongah, namun seperti itulah cara Togar menyusun kata-kata yang akan diucapkannya.
“Bukan sehari dua hari aku kenal dengan kau, Pul.”
Tangan bantet itu diletakannya di pundakku, sisi cerdasnya perlahan mulai terlihat. Sayang, jika si jenius batak itu tak pernah ditakdirkan untuk mengennyam pendidikan.
“Iya, Gar. Aku ingin sekali pergi merantau.” Beban hidup mulai tersirat dinada bicaraku. Ini baru di hadapan Togar, belum di hadapan Amak dan Uda. Pastilah akan lebih sulit aku mengatakannya jika yang kuharapkan selancar seperti mengatakan kepada Togar.
Togar menepuk-nepuk pundak kurusku. Sifat yang selalu optimis berhasil membuatnya tampak dewasa seketika berbicara bijak. Wajar saja tak pernah terdengar keluhan darinya di saat terus-terusan memakan nasi yang dicampuri minyak kelapa.
“Kalau kau berhasil minta izin dengan keluargamu, aku akan ikut merantau dengan kau, Pul.”
Hampir-hampir aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Andai, semudah itu Uda mendukungku untuk melakukannya. Aku terkesiap, mataku membulat dengan sumringah menganga lebar di wajah.
“Kau serius, Gar?”
“Aku juga ingin jadi sukses, Pul. Bosan aku kalau setiap hari bolak-balik sana sini tak tentu arah. Aku mau jadi kayak orang-orang di tipi.”
“Aku tak punya TV, Gar,” ujarku memang mengatakannya apa adanya. Dan pemuda pendek itu langsung saja mendorong pelan tubuhku. Aku hampir terjengkang, mudah sekali tubuh kurusku ini hilang keseimbangan. Apalagi yang melakukannya adalah Togar yang berbadan besar walau pendek.
“Macam aku punya tipi aja. Ya tipi yang kita lihat di rumah orang-orang. Waktu itu aku nonton di rumah Pak RW, pilem tentang orang miskin yang jadi sukses, ke sana ke mari pakai mobil dan dikawal dengan 2 orang berbadan besar.”
“Bodyguard, Gar.”
“Ya itulah namanya, lupa aku.”
“Jadi kau serius ikut merantau denganku?” aku kembali meyakinkannya, takut-takut kalau Togar melupakan ucapannya karena terlalu bersemangat menceritakan sebuah film yang ditontonnya di rumah Pak RW.
“Aku serius, mana pernah aku bercanda dengan kau. Aku ini orang batak, Pul. Orang batak harus berbicara lantang dan benar.”
“Baiklah, nanti aku bicarakan dengan Amak. Kau doakan aku, ya....”
“Tenang, kawan!”
Hanya suara jangkrik dan berbagai hewan malam yang terdengar. Aku ikut terdiam saat Amak merenung usai mendengarkan ucapanku; tentang merantau. Rikuh, sungguh itulah yang kurasakan saat ini. Sebelumnya, memang aku dan Amak tak pernah berdiam lama, walau kutahu kalau Amak sedang berpikir. Aku tidak dengan gamblang mengatakan niatku kepada Amak, justru sangat perlahan dan berhati-hati. Memang selama ini Amak selalu mendukungku dalam melakukan berbagai macam hal untuk sukses, tapi untuk memainkan jarak, inilah yang pertamakalinya. Aku yakin, itulah yang memberatkan hati Amak ketika aku meminta restu padanya. Selain usiaku yang baru lima belas tahun, Amak juga tak bisa jauh dari anak-anaknya. Ya, sekalipun hidup dalam kedaan miskin. Dan jika Amak memberiku izin, pastilah tidak akan ada lagi yang menjajakan sala saluak buatan Amak. Karena Amak sendirilah yang akan menjajakan dagangannya dengan berbekalan meja yang diletakan di depan rumah. Ya, seperti waktu aku diserang demam yang cukup lama.
“Kalau anak Amak pandai menjago diri, Amak indak melarang. Amak hanyo takuik, beko kalau sakik, payah indak ado Amak.[1]”
Aku terkejut mendengarkan diam amak sudah usai. Akan tetapi, kesulitanku kali ini ialah untuk menjawab. “Ipul pai samo Togar, Mak[2],” jawabku takut-takut.
“Pailah, Amak agiah izin[3].”
“Uda ba a, Mak?[4]”
“Pai duo hari lai, inyo indak di rumah hari minggu[5].”
“Makasi, Mak. Ipul janji, Ipul akan jadi urang sukses.” Dialog yang tentunya terdengar berbahasa minang itu, kuakhiri dengan binar memenuhi wajah. Aku terpontang-panting memeluk amak yang duduk di tepi dipan. Dan besok, akan menjadi hari yang mendebarkan. Ya, karena aku dan Togar terlebih dulu harus membicarakan kota mana yang akan kami jejaki sebagai perantau.
Pagi-pagi sekali aku dikagetkan dengan kedatangan Togar dan Satria—salah satu teman kami di tempat mengaji. Berbeda dengan kami, dulu Satria pernah disekolahkan walau hanya sampai tamat SD. Pemuda asli jawa itu cukup dekat dengan kami berdua, namun seminggu belakangan batang hidungnya tak terlihat dikarenakan demam tinggi yang dideritanya. Togar menyampaikan maksudnya membawa Satria ke hadapanku. Ternyata dia yang memiliki kulit lebih bersih dan terang dari kami itu, juga berancana untuk pergi merantau. Bahkan dia menimpali Togar yang menceritakan kesamaan niatnya dengan mengatakan kalau sudah dari dulu kedua orangtuanya menginginkan anak semata-wayangnya itu pergi merantau. Dan ternyata niat itu juga didapatinya setelah mendengarkan ceramah dari Ust, Yusuf. Aku baru ingat, kalau kemarin sore si pemilik nama lengkap Satria Prabu itu sudah mulai kembali mengaji, dan duduk di susut sebelah kanan.
“Kita ke Jakarta dulu, kalau berjalan lancar, setelahnya barulah kita ke kota lain.”
“Macam kuntilanak aja berpindah-pindah tempat.”
“Itu yang dinamakan perantau sejati,” tukas Satria menyangkal timpalan Togar yang menurutnya sedikit aneh.
Aku membiarkan keduanya berdiskusi, karena merasa otak yang kumiliki tidaklah seencer cara mereka memikirkan rencana. Sementara itu, aku sibuk membayang-bayangkan seperti apa kehidupan kami di sana nanti. Disela-sela pikiranku aku tersentak, dan menyadari kalau hari ini aku harus kembali berjualan. Kulihat Togar dan Satria masih sibuk dengan berbagi pendapat yang keluar dari masing-masing mereka, bahkan kudengar Satria sudah mendapatkan titik temu. Untuk masalah itu, sepenuhnya kupercayakan pada pemuda yang usianya berjarak satu tahun dariku itu. Aku menyempil di antara percakapan mereka, mengatakan kalau aku harus pergi berjualan. Hari ini amak pagi-pagi sekali menyiapkan salanyanya, karena Amak harus pergi memasak ke rumah tetangga yang akan ada acara baralek; pernikahan.
“Semoga dagangan kau habis, Pul.”
“Kami akan menjaga rumahmu, dan turut mendoakan.” Mereka mengerti, bahkan memberi dukungan dengan dua logat yang terdengar berbeda.
"Sala, sala, sala lauak...." Kali ini semangatku berlebih. Aku sudah bertekat, kalau aku tidak akan pulang sebelum sala daganganku habis terjual. Mengingat ini hari terakhirku di Manggopoh, membuatku begitu haru memijaki tanah kelahiranku ini.
"Pul, sala ...!"
Aku menoleh ke belakang. Benar saja, ada pembeli yang mengharuskanku menghampirinya. Seorang janda berusia 71 tahun yang kami panggil dengan sebutan uwo, begitulah orang minang menyebut nenek.
“Bali bara, Wo?”[6]
“Tigo[7].” Wanita dari empat cucu itu mengambil sala daganganku lagsung menggunakan tangannya. Tentunya setelah lebih dulu mengambil uang receh sebanyak 1500 dari dompet beresleting miliknya, dan menyerahkannya kepadaku.
Tak lama setelah perniagaan itu seorang pemuda jangkung memanggilku dari arah belakang. Aku tidak mungkin lupa, dulu dia pernah tinggal bersebelahan denganku. Namun, keluarganya yang senang berpindah-pindah antara satu kontrakan ke kontrakan yang lebih murah, membuatnya seakan tampak menyerupai alchemist.
“Kecek si Togar ang nio marantau, yo[8]?”
“Iyo, Da.” Aku sedikit kaget mendengar pertanyaannya. Terang saja, karena pemuda caniago di hadapanku itu dikenal sebagai ahli pencemooh.
“Alah bosan ang menjua sala[9]? Haha ...” Tawa sumbang itu akhirnya kudengar kembali. Tawa cemooh yang sangat tidak disukai oleh semua orang. Termasuk Togar, uda, dan amak yang pernah menjadi korban cemoohannya.
“Indak. Awak menjua sala untuk mencari pitih, untuk itu pulo awak pai marantau. Awak nio jadi urang sukses[10].” Tak tanggung-tanggung aku memerlihatkan ketegasan di hadapannya, walau memang tak sehebat Togar yang begitu pandai menjawab dengan kembali mencemoohnya. “Biar dia tahu, kalau di atas langit masih ada langit,” begitulah yang sering diucapkan Togar usai membalasnya.
“Kecek urang, kesuksesan dibali dengan ijazah, Pul. Injankan ijazah, pakai saragam jo indak pernah.[11] Haha ...!”
“Urang yang ngecek macam itu, cuma urang-urang yang alah putuih asa bana dengan hiduiknyo, Da.”
“Ang kecek aden urang putuih asa, ha?” Dia berteriak, tentu karena tidak menyukai jawaban yang kuperdengarkan dengan kelakar padanya. Segera saja aku melengos meninggalkannya cepat-cepat. Orang seperti itu tidak baik jika kita terlalu menggubrisnya. Ada satu kalimat yang kutanamkan dalam hidupku; jika hidupmu hanya untuk memikirkan kata-kata orang lain, maka kau tidak akan memiliki waktu untuk memikirkan dirimu sendiri.
“Ampek baleh ribu, limo baleh ribu. Alhamdulillah....” Usai menghitung jumlah pendapatanku sementara, aku menyimpan uang itu di dalam bajuku karena memang tidak ada saku celana, dan kembali melanjutkan perjalananku. Aku baru menjejaki setengah dari kawasan Manggopoh Ujung, masih banyak jalan lagi yang belum kutempuh, dan masih ada sore sebelum aku pulang diwaktu senja. Di ujung sana ada pondok kecil, aku ingin beristirahat sejenak. Memanjakan perutku dengan bekal yang bila berjualan tak pernah lupa untuk selalu kubawa.
Ucapan syukur kepada Allah kembali terdengar dari bibirku. Aku berhasil menjual sala lauak buatan amak hingga tak bersisa. Beruntung aku mengistirahatkan diri di pondok kecil itu, karena banyak orang-orang yang pulang dari pematangan selalu melewati tempat itu, dan menyempatkan diri untuk membeli sala-salaku yang memang rasanya sudah dikenal oleh mereka. 2.8000 adalah jumlah terbanyak yang akan kubawa pulang. Di sepanjang perjalananku menuju rumah, aku memerhatikan orang-orang disekitarku. Kali ini dengan seksama aku melakukannya, seperti tak akan melihatnya lagi. Ada anak yang usianya jauh dibawahku pulang dari memancing, ada orangtua yang membawa jawi ternaknya pulang, dua pemuda yang bermain layangan dengan dada telanjang, dan induk ayam yang terseok-seok mengusir aaknya pulang ke kandang. Semua tak luput dari pandangan mata legamku. Pemandangan Manggopoh Ujung di waktu senja. unik dan beragam. Belum tentu di kota nanti aku bisa menemukan pemandangan seperti ini. Pastilah pemandangan di sana dipenuhi dengan gedung-gedung balok tinggi dan asap kendaraan; polusi. Dan senjanya, tentu tidak akan setenang berada di kampung-kampung Minang Kabau.
****
Adzan subuh mengalun tenang dari dalam Surau Ar-rahman, memenuhi Manggopoh hingga ke tetepian. Aku mengibaskan sarung yang baru saja kukeluarkan dari almari. Sudah lama sekali aku tak memakai sarung hasil memenangkan lomba panjat pinang tersebut. Warna dan teksturnya sudah sangat pudar dan kusam. Lusuh, juga mengumbar bau tak sedap dari telur-telur kecoa yang menempel di ujung-ujungnya. Aku sengaja memakainya, karena sarung-sarungku yang layak pakai sudah kukemaskan ke dalam tas; membawanya pergi merantau bersamaku.
Usai melaksanakan sholat pertama untuk hari ini, aku duduk di tepi pintu menyaksikan Amak yang sedang membersihkan halaman berukuran setengah meter itu dari genangan air hujan semalam. Amak juga menggunakan sapu lidi, sehingga halaman itu tampak seperti bekas sisir di rambut yang masih basah, bergaris-garis panjang.
"Mak, sabananyo Pul indak tega maninggaan Amak surang[12]."
Amak yang tadinya menunduk mencabuti rumput liar yang mulai tumbuh di sekat-sekat halaman, mendongak memandangku yang berada jauh di depannya. Amak mendekat. Sapu yang lidinya sudah banyak patah itu, disandarkannya ke dinding rumah. Kalau aku sudah di rantau, pemandangan pagi buta seperti ini tentu tak terlihat lagi mengawali hariku.
“Doakan sajo Amak di rumah. Kalau pai jo hati indak tanang, beko indak bajalan lancar.[13]” Amak menenagkanku dengan nada yang tak ubahnya alunan melodimerdu. Sangat menenangkan bila mendengarkannya pagi-pagi seperti ini. Kini amak telah berada di sampingku, ikut duduk di tepi pintu seperti yang kulakukan. Aku menatap mata yang kantungnya sudah mengendor itu. Ah, ternyata amak sudah semakin tua saja.
“Siap-siaplah, sabanta lai si Togar dan Satria datang menjapuik[14].”
“Iyo, Mak,” jawabku, semakin yakin dengan apa yang akan kulakukan nanti. Beruntung, uda sudah tak di rumah sejak semalam.
****
Berbeda dengan Satria yang membawa ransel, Togar justru menggunakan karung beras sebagai tempat untuk menyimpan baju-bajunya. Kami sudah sampai di terminal, sudah tak lagi berada di Manggopoh Ujung; Ulakan Tapakis. Untuk hal ini, aku sedikit lebih beruntung. Karena amak menghantarkanku hingga sejauh ini. Sementara Togar dan Satria, hanya berpamitan di depan pintu rumah saja dengan anggota keluarganya.
Sebelum berangkat, Satria berjingkat-jingkat kegirangan. Pemuda yang pandai berpuisi itu sudah sejak lama menunggu saat-saat seperti ini. Dan, anak jawa yang selalu berbicara fasih dengan menggunakan Bahasa Indonesia itu, juga tak lupa membawa buku catatan kesayangannya. Katanya ia akan selalu mengabadikan hari-hari yang dilewatinya selama di perantauan dalam sebuah tulisan. Harap-harap bukti nyata dari perjalanannya tersebut bisa menjadikannya seorang penulis, jika menarik.
Detik-detik keberangkatan, aku menepi di pinggir terminal bersama amak. Amak tak henti-hentinya menasehatiku tentang bagaimana caranya melewati hidup dengan baik di rantau. Sesekali mataku juga berusaha menjangkau keberadaan Togar. Si Gimbal itu begitu liar sedari tadi. Karena ini merupakan pengalaman pertamanya meninggalkan tanah kelahiran, dia terlihat begitu antusias dan bersemangat. Bis-bis yang sedang menunggu penumpang itu dimasukinya satu-persatu. Mendorong kepalanya ke dalam untuk mengintip, sekalipun itu bukanlah bis yang akan menemani perjalanan kami nanti.
“Woi, cepatlah kalian ke mari! Kita akan melaju!” Teriaknya dengan tubuh yang sedikit menggelayut di pintu bis. Kali ini Togar memang berada di bis yang tepat. Kami akan memulai perjalanan.
“Mak, Ipul pai dulu, yo?[15]”
“Elok-elok yo, Nak....[16]” Amak mengelus kepalaku.
Aku mengangguk penuh haru, dan setelah mengecup punggung tangan amak aku pun segera menghambur ke dalam bis—di tempat Togar terlihat sedang melambai-lambaikan tangannya.
“Rasanya seperti mimpi saja, Pul, kalau sekarang ini kita akan pergi merantau.”
“Semoga ini awal dari kesuksesan ya, Gar?”
“Aamiin, berdoa sajalah, kau.” Memang sambil berbicara, tapi, Togar benar-benar tak bisa diam dari semenjak mendudukan dirinya. Sedang asik-asiknya berbicara, kami menyadari akan sesuatu ...
“Satria!” Pekik kami berdua—yang langsung saja terpontang-panting ke arah jendela. Bis mulai berjalan. Dan benar saja, jauh di ujung sana Satria berteriak sambil berusaha mengejar bis—yang terancam melaju tanpa dirinya.
“Pak, Pak, berhenti dulu!”
“Sat, cepat lari ...!”
Kami berbagi tugas. Togar mencoba berbicara dengan Sopir, sementara aku, berteriak menyemangati satria agar lebih mempercepat dan memperlebar langkahnya.
“Pul, Gar, bantu aku ...!” Satria terus berlari, namun tetap saja kaki itu bukanlah kepunyaan kijang. Tangannya terulur-ulur, seperti halnya tangan kami berdua yang menantinya di pintu bis. Tak berhati, sopir tersebut tetap kekeuh tak ingin mengurangi kecepatannya, ia mempertahankan alasan bodoh yang tak kami mengerti dikarenakan gaya berbicaranya.
“Cepat, Sat ...!”
“Gapai tanganku, cepat ...!”
Sedikit lagi, jantung kami semakin berdebar cepat karenanya. Apalah arti perantau ini jika dia yang paling bersemangat tertinggal, dan kembali menyesap sepi di setiap hari.
“Woi, Pak, tolonglah kau kurangi kecepatannya!”
“Cepat, Sat, sedikit, lagi ...!” Teriakan kami berbentur, sama-sama terdengar lantang, bahkan memekakan. Jika semua yang berada di dalamnya tak ubahnya Si Sopir, kurasa menyebabkan mereka tuli pun tak apa.
“Tarik tanganku, Pul ...!”
“Iya, cepat!”
Beberapa langkah lagi, ternyata kaki kurus itu mendapatkan nilai bagus dalam latihan menjadi seorang pelari.
“Aaaaa ....!!!”
Kami berteriak, namun saat ini sudah kembali lengkap. Satria berhasil menggapai tanganku, walau karenanya kami bertiga hampir terjungkal demi menarik tangannya. Untunglah, ada kursi di sebelah sopir—yang menyangga tubuh kami.
“Jika satu pergi, maka semuanya harus pergi. Jika satu tinggal, semuanya juga akan tinggal. Mungkin kalau kau tadi gagal kami akan tetap pergi, tapi jiwa kami tertinggal bersamamu, kawan!” Si jenius Togar menyampaikan sepatah dua patah kata bijaknya sebelum kami kembali ke tempat duduk semula. Barulah perjalanan yang benar-benar perjalanan di mulai. Lampu merah sudah tergantikan menjadi hijau, saatnya kereta kencana bagi mimpi kami ini melaju melanjutkan perjalanan yang mungkin saja nanti akan lebih terjal.
Dua jam pelajaran, aku mulai menggusar. Perasaanku sangat-sangat tidak enak. Bodohnya aku, sebelum berangkat aku melupakan kalau aku tak pernah bisa naik bis terlalu lama. Jika itu terjadi, maka aku akan merasa mual, bahkan sampai muntah jika aku tak segera menanganinya. Ujung-ujung kaki dan tanganku dingin, terlebih-lebih di luar sana hujan turun menderas. Kulihat Satria tertidur, kami berbeda tempat duduk. Satria duduk bersebelahan dengan perempuan tua. Sementara aku berada di tempat yang sama dengan Togar, masih seperti pertamakali kami menaiki bis ini. Aku menyembunyikan apa yang kurasan. Dan buruknya lagi, kepalaku ikut-ikutan memperkeruh keadaan. Terasa berat, dan berputar-putar. Mataku liar, mencoba menjejah dari sudut ke sudut. namun, tak kutemui kantong plastik untukku melepaskan semua ini.
“Tangan kau dingin, Pul.”
“Gar ... aku mual.”
“Haaah ...?” Togar terbelalak. Aku tak dapat lagi menyembunyikannya dari Togar. Toh, dia mulai mengetahui keadaanku dikarenakan tangan kami yang sempat beradu. Togar ikutan panik, dia langsung saja terlihat mencari-cari sesuatu. Walau kutahu, tidak ada yang bisa ditemukannyauntuk membantuku.
“Sat, Satria ...”
“Dia lagi tidur, Gar,” ucapku sangat lirih. Entah kenapa, Togar bersaha membangunkan Satria—yang terlihat begitu menikmati tidurnya.
“Tadi kulihat dia banyak bawa obat, siapa tahu bisa membantu. Satria ...!” Togar kembali melakukannya, membangunkan pemuda jawa itu. Ya, suaranya terdengar dua kali lebih lantang. Namun tak sia-sia, Satria berhasil bangun karenanya walau terlebih dulu terlihat menggeliat-geliat. Ia masih harus melewati proses penyatuan jiwa.
“Woi, Sat, si Ipul dia mual-mual,” tukas Togar tak ingin berlama-lama.
Satria seperti menangkap dengan cepat maksud dari ucapan Togar, matanya menyipit ke arah kami, mendelik. “Mual?”
“Iya, mual.”
“Tunggu, aku carikan dulu obatnya.”
“Tuh, kan Pul, si Satria ini apotik berjalan.”
Aku hanya diam, tak sanggup lagi bila harus bergabung disela-sela percakapan mereka. Hanya berdoa agar tangan Satria segera menemukan obat—yang sepertinya sulit untuk dikeluarkannya dari dalam tas.
“Cepatlah, Sat. Udah pucat mukanya aku tengok.”
“Iya, sabar.”
Togar seakan mengetahui keadaanku yang semakin memburuk. Di keluarkannya baju lengan panjang dari dalam tasku, dan digunakannya untuk menyelimuti tubuhku yang kedinginan. Ia juga menjangkau botol minumanku, hanya menunggu obat yang masih belum jua diberikan Satria.
“Cepatlah!”
“Iya, iya. Nih.”
“Lama kalinya, kau!” Togar langsung menyambar obat yang diulurkan Satria dari seberang sana.
“Cepat minum, Pul.”
Aku mengamati benda yang akan mengobatiku tersebut. Ah, aku lagi-lagi mendapat kesulitan. Dari dulu hingga sekarang, aku tak pernah bisa untuk menelan obat. Setiap kali membutuhkan obat, amak biasanya menggerusnya terlebih dulu sebelum menyuapkan kepadaku. “Aku tak bisa menelan, Gar.”
“Ya salam. Macam mana kau ini, Pul. Kalau merantau, kau harus hidup layaknya penggembara.” Walau menceletuk, Togar tetap tak setengah-setengah membantuku. Ia mencari-cari sesuatu di dalam karungnya. Aku tahu, hanya menunggu apa yang akan dikeluarkannya dari dalam benda tersebut. sementara itu, dari seberang sana Satria masih antusias memerhatikan kami berdua. Sebelumnya pemuda yang sangat ingin menjadi sastrawan itu, menyampaikan ketidaksukaannya duduk dengan orang yang tidak dikenal olehnya.
“Nah, biar aku hancurkan obatnya.” Ternyata itu gagasannya. Walau jarak tempat duduk ke tempat duduk yang berada di depan sangat sempit, Togar berusaha menyelip di antaranya demi menghancurkan obat anti mual tersebut. Minyak rambut, itulah benda yang dikeluarkannya dari dalam karung. Dan dengan benda itulah ia akan menghacurkannya.
“Buruan, Gar. Jangan lama-lama!” satria sedikit bereriak dari tempatnya. Jika tadi Togar yang berteriak, maka saat ini Satria-lah yang mengambil alih tugas tersebut. Seperti sudah menyepakati untuk berganti giliran.
“Cerewet kau, Sat! Ha, Pul, udah hancur. Kau minumlah cepat.”
Tanpa sendok, begitulah kudapati obat tersebut masih di dalam bungkusnnya, namun sudah hancur dan terbuka. Togar bukan hanya menyodorkan obat, dia juga sudah memersiapkan air yang akan kutenggak cepat-cepat ketika obat pahit itu berhasil memasuki gua basahku; mulut. Aku tak membiarkan mereka berlama-lama menghawatirkanku. Segera saja obaat itu kubuat berpindah tangan, lalu kemudian memasukannya ke mulutku, walau takut-takut aku melakukannya. Namun, aku tak ingin kalah dengan keadaan!
“Makasih, Gar, Sat,” ucapku, berusaha merasa aman dan mulai menenangkan diri. Kuharap, perasaanku membaik, dan mengembalikan semangat yang sempat meninggalkanku.
“Sekarang kau tidurlah, bikin orang panik saja.”
Kedua temanku itu menarik napas lega, dan kulihat Satria kembali melanjutkannya tidurnya. Mungkin saja ada mimpi yang belum terselesaikan. Akan tetapi, tidak untuk Togar. Sedikit pun tak muncul guratan lelah atau pun mengantuk pada wajahnya. Si Gimbal itu masih terlihat segar bugar, terlebih-lebih bila mendengarkannya yang tak henti-hentinya mendendangkan lagu batak. Padahal, Sang Sopir punya lagu tersendiri yang dimainkannya lewat radio; menggunakan kaset.
****
Hampir dua hari perjalanan, kami masih saja melaju di dalam bis walau di jam-jam tertentu menyempatkan diri untuk berhenti. Seperti inilah orang yang tak punya uang lebih pergi ke suatu tempat. Membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan jika uang yang kami miliki digabung, pun belum bisa membeli satu tiket pesawat. Kendaraan yang melayang-layang di atas awan. Dulu, sewaktu umurku belum berkepala, kupikir siapa saja bisa menaiki pesawat dengan mudahnya, ternyata tidak. Ternyata kehebatan para penemu—hanya memudahkan mereka yang berdompet tebal saja. Aku tidak ingin seperti itu. Jika mereka memandangku sebagai orang hebat, maka aku akan menciptakan sesuatu yang bisa dinikmati oleh sesiapa.
“Pul, kau tak turun?”
Aku berpikir sejenak, kami sedang berhenti. Namun, aku sedikit ragu untuk mengkuti jejak Togar. Setiap pemberhentian, si gimbal itu tak pernah absen untuk turun. Akan tetapi, pikiranku berubah seketika perutku merasa dililit. “Iyalah, Gar.”
Ternyata waktu sudah menghantarkan malam hingga ke pertengahan. Langit hitam memekat, sepertinya akan turun hujan. Aku ingin sekali menanyakan tempat perhentian ini di mana, namun rasa di pertku sangat erat memerintakan kakiku untuk segera menuju toilet. Sementara itu, Togar dan Satria berpencar. Keinginan mereka selelu berbeda, tak pernah sama. Togar ingin melepaskan penat, kakinya sudah mulai tebal duduk berlama-lama, begitu katanya. Sedangkan Satria, melanglangbuana untuk beburu makanan ringan. Pemuda dengan rambut menyerupai tentara itu, begitu ketergantungan dengan makanan ringan bila sedang dalam perjalanan. Berbeda denganku—yang justru menghindari banyak makan. Takut-takut kalau aku akan merasa mual lagi, walau pun persediaan obat anti mual kepunyaan Satria masih banyak di dalam tasnya.
“Lama sekali kau, Pul, hampir kau ketinggalan.”
“Tadi perutku sakit sekali, Gar.”
“Mungkin masuk angin kau.” Setelah si gimbal itu menggak air mineralnya, tubuh pendek itu dibuatnya kembali dalam posisi nyaman di tempat duduk kami. Mungkin tak lebih dari satu menit lagi perjalanan kami dilanjutkan. Untung saja aku sudah melepaskan beban yang mengganjal di perut rataku.
Kurasakan bis itu kembali bergerak, perlahan. Diawali dengan gerakan mundur ke belakang, mengambil arah sebaik-baiknya. Dan tanganku pun mulai menyambar baju lengan panjang—yang dijadikan Togar sebagai pelindungku dari hawa dingin. Tampak di mataku Togar sedang mengangguk-angguk, seiring lanutunan musik yang diperdengarkan lagi oleh si sapur. Kami mulai larut dalam perjalan. Namun ...
“Satria ...!” Aku dan Togar seperti mengalami dejavu, kami kembali meneriaki nama Satria. Entah di mana letak kesalahannya, pemuda berbadan tegap itu untuk kedua kalinya tertinggal. Dan kami kembali terlihat sedang mengejar anak kelinci. Terpontang-panting. Akan tetapi, hujan yang sudah menderas dan hitamnya malam, membuatku tak dapat melihat dengan jelas apa-apa yang berada di luar jendela.
“Pak, kawan aku belum naik! Berhentilah dulu.” Togar tidak sabaran memenuhi pendengaran sapir yang hampir-hampir beruban itu dengan titahnya yang lantang.
“Apa kau tengok-tengok!” Bahkan kali ini keadaan hitam hampir berjelaga. Kami dipandang dengan tatapan tidak suka, penumpang lain yang melakukannya.
“Satria ...!” Aku hampir menangis, sungguh merasa begitu lemah, sehingga gagal melindungi Satria dalam perhatianku. Togar mengangkat dadanya, napas itu dihelanya dengan berat; dia menyerah!
“Satri—”
“Oh, kita sudah berangkat lagi, ya? Lho, ada apa dengan kalian?”
Togar terjingkat, mataku pun membulat. Satria menyembul dari belakang tempat duduk kami! Ah, tidak, wajahnya terlihat seperti ... baru bangun tidur?!
“Kubunuh kau, Sat!” Umpat Togar, mukanya berang, namun cemasnya hilang. “Kami susah payah mencari-carimu,” lanjutnya.
“Satria, apa yang kaulakukan di sana?” timpalku.
“Untuk apa mencariku? Aku tidur, ngantuk soalnya,” ucapnya tanpa rasa bersalah.
Aku dan Togar bersungut-sungut memandangnya. sesekali hampir menyamai wajah pemburu yang ingin membidik sasarannya. Pemuda jawa itu justru cekikikan melihat kami. Dia sukses membuat sinetron di telivisi berpindah ke dalam bis ini.
****
[1] Kalau anak Amak pandai menjaga diri, Amak tidak melarang. Amak hanya takut. Kalau sakit, susah tidak ada Amak.
[2] Ipul pergi dengan Togar, Mak.
[3] Pergilah, Amak izinkan.
[4] Uda bagaimana, Mak?
[5] Pergi dua hari lagi, dia tidak di rumah hari minggu.
[6] Beli berapa, Nek?
[7] Tiga.
[8] Kata Togar kamu mau merantau, ya?
[9] Sudah bosan kamu menjual sala?
[10] Tidak. Aku menjual sala untuk mencari uang, untuk itu juga aku pergi merantau. Aku mau jadi orang sukses.
[11] Kata orang, kesuksesan dibeli dengan ijazah, Pul. Jangankan ijazah, pakai seragam saja tidak pernah.
[12] Mak, sebenarnya Pul tidak tega meninggalkan Amak sendiri.
[13] Doakan saja Amak di rumah. Kalau pergi dengan hati tidak tenang, nanti tidak berjalan lancar.
[14] Siap-siaplah, sebentar lagi Togar dan Satria datang menjemput.
[15] Mak, Ipul pergi dulu, ya?
[16] Baik-baik ya, Nak.
____________________
Harusnya bab ini diupdate bulan lalu, tapi karena aku memiliki sedikit kendala--dimana aku berada dalam situasi yag tidak memungkinkan untuk memegang laptop--ceritanya jadi sangat terlambat diupdate. Di sisa kesempatan ini, aku akan mengupdate beberapa bab sekaligus.
Terima kasih untuk dukungannya!


 Ladysun
Ladysun








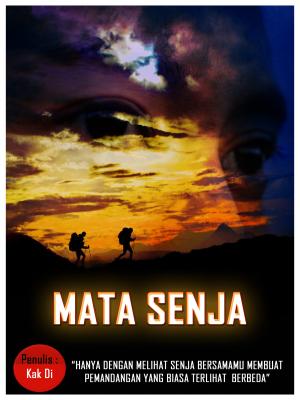

Alaaamaakkk keren kali ni cerita.
Comment on chapter Bab. 1 (Manggopoh Ujung)