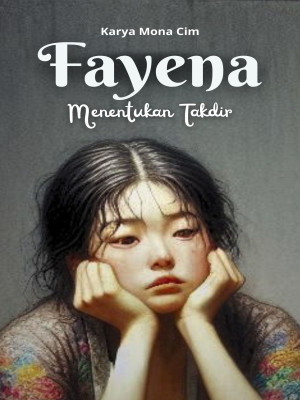PRANG!
Ibu Emilia bergegas ke dapur saat terdengar barang jatuh itu. Ia menemukan putrinya berjongkok dengan tubuh gemetar, menatap pecahan gelas dan berupaya menggapainya dengan tangan pucat.
“Maaf, Ma. Peganganku kurang kuat tadi, makanya gelasnya jatuh,” ujar Emilia tanpa berani menatap ibunya. “Aku langsung beresin.” Emilia berdiri demi meraih sapu dan merapikan kekacauan di lantai. Ia sadar ibunya yang berdiri di dekatnya menyimak gelagat Emilia sedari tadi, untuk itulah Emilia merasa gugup. Ia khawatir tindak-tanduknya terbaca mencurigakan.
“Sini, biar Mama yang buang ke tong sampah.” Ibu Emilia menawarkan diri. “Kamu ambil minum aja, gih.”
Emilia mengangguk tanpa bantahan. Saat ibunya mengambil alih pengki dan beringsut ke arah tempat sampah, Emilia berbalik demi mengambil gelas lain. Kali ini ia memilih gelas plastik, khawatir menjatuhkannya kembali meski ia memegangi benda itu lebih erat dan fokus. Setelah air terisi penuh, Emilia pamit ke kamar, mengabaikan tatapan lekat ibunya.
Pintu kamar Emilia tidak dibiarkan bercelah. Ia duduk di depan meja belajar dan meneguk air minumnya hingga separuh, lalu meletakkan gelas di samping buku Biologi yang tengah dipelajarinya. Mata hitamnya yang menyiratkan riak lelah memaku pada rangkaian teori pelajaran, yang belum mampu mendobrak masuk ke ingatan Emilia. Ia tidak bisa berkonsentrasi. Halaman yang dibacanya tidak berpindah sedari tadi.
“Mi?”
Ketukan pintu di kamar diikuti sahutan ibunya. Emilia praktis menegap.
“I-iya, Ma. Masuk aja.” Emilia mengurai rambutnya ke sisi wajah dan menyambar pena sementara matanya tertuju ke buku. Ia harus benar-benar terlihat sedang belajar.
Pintu didorong membuka dan ibunya berjalan masuk, lantas duduk di tepi ranjang yang berada di sisi meja belajar.
“Lagi belajar apa?”
“Biologi, Ma. Persiapan UTS,” jawab Emilia tanpa menatap ibunya. Tangannya bergerak kaku ke sebaris kalimat tanpa benar-benar menyelaminya.
“Mi...”
“Hm?”
Ibu Emilia berdeham. “Sini dulu. Mama mau ngomong.”
Saat itulah Emilia tahu ia tidak lagi bisa berpura-pura. Emilia melepas pena dengan lesu. Ia mengarahkan posisi duduknya ke hadapan sang ibu. Tak bisa benar-benar menatap wanita itu, Emilia hanya mengangkat sedikit wajahnya.
“Kamu pucat.”
Komentar pertama ibunya yang membuat Emilia tanpa sadar menahan napas. Ia mengembuskannya saat tangan ibunya menangkup wajah Emilia, mengarahkannya hingga arah tatap mereka sejajar. Tangan itu hangat dan menghanyutkan, meski suhu wajah Emilia seolah kembali membeku begitu sentuhan itu berakhir.
“Kepikiran soal Al?”
Pandangan Emilia bergerak turun. Keningnya mengernyit samar menanggapi tanya itu, sementara kedua tangan yang berada di pangkuannya saling bertautan, bagai ingin berbagi kegelisahan. Emilia tidak akan bertanya-tanya maksud ucapan ibunya. Perihal video Alvaro sudah beliau ketahui. Perubahan sikap Emilia pun sudah pasti mengusik ketenangan ibunya karena Emilia kerap melamun juga tak fokus selama di rumah. Terlebih, saat Emilia pulang dengan kondisi mata sembab setelah berbicara dengan Alvaro.
Pembahasan tentang Alvaro selalu berhasil menyeruakkan memori pahit ucapan cowok itu, dan Emilia acap kali kewalahan menata emosi karena ia akan berakhir pada dorongan kuat untuk menangis. Sungguh, ia tidak ingin secengeng ini. Namun, perkataan Alvaro teramat menyakitinya.
“Emi...”
Teguran ibu Emilia menyadarkannya bahwa setetes air mata baru saja melesak keluar. Ia lekas menghapus kedua matanya.
“Maaf, Ma...” Emilia menunduk.
“Al masih nggak ngomong apa-apa sama kamu?”
Emilia menggigit bibir. Tak ia curahkan fakta sikap Alvaro padanya. Informasi yang ia bagi pada ibunya hanya terkait video Alvaro yang memang sudah beliau tahu dari liputan berita di stasiun TV lokal, dan bahwa cowok itu belum bercerita apa pun pada Emilia. Emilia tidak sanggup berterus-terang. Ia tidak ingin membeberkan rasa sakitnya. Atau barangkali, ia tidak sudi pendapat ibunya pada Alvaro berubah terlalu banyak. Ia masih ingin ‘melindunginya’. Salahkah jika hingga detik ini, Emilia masih menganggap Alvaro berharga untuknya?
“Mama ngerti kamu kepikiran Al. Tapi, Mi, jangan sampai kayak gini. Kamu susah makan, nggak fokus, sering ngelamun. Awalnya Mama mikir Al butuh waktu buat ngomong sama kamu, dan walau Mama kecewa lihat berita soal pergaulan Al, Mama masih yakin Al anak yang baik. Dia nggak akan kayak gitu lagi. Tapi, ngelihat kamu sekarang, Mama nggak rela, Mi. Kamu harus tegas sama diri kamu sendiri.”
Emilia tertegun. Ia menatap ibunya penuh tanda tanya. Belaian hangat mendarat di lengannya.
“Kalau Al nggak mau ngomong apa-apa sama kamu padahal udah lama video itu kesebar, artinya Al nggak cukup sayang sama kamu buat ngasih penjelasan, Mi. Mama rasa dia sadar hal itu nyiksa kamu, tapi dia nggak berbuat apa pun.”
Emilia menelan ludah karena tidak sanggup berkata bahwa sebenarnya Alvaro sudah sangat berterus-terang padanya, termasuk soal Casi. Namun, tampaknya hal itu tidak bisa ia sembunyikan lagi lebih lama. Sekejap saja mata Emilia menghangat dan basah. Ia menunduk dalam.
“Apa yang kamu simpan, Sayang? Cerita sama Mama.”
“Ma...”
“Emi.” Ibu Emilia merangkul pundak putrinya, mengelusnya lembut. “Mama dengerin.”
Semula Emilia meragu, sebelum kisah itu bergulir dari mulutnya dengan tersendat dan diiringi tangis yang mengusik kejelasannya berucap. Tak sekali pun ibunya menyela. Tiba di pengakhiran cerita, Emilia menyeka wajahnya yang basah. Mulutnya membuka karena berupaya meraih udara. Sesak sekali rasanya.
Ibu Emilia mendekap putrinya hangat. Terdengar desahan napas beliau.
“Kamu nyimpen semua ini sendiri, Mi.”
Emilia menyembunyikan wajahnya di dada sang ibu, membuat pakaian wanita itu basah oleh air mata. Di sela tangisnya, ia berbisik maaf.
“Mama tahu kamu sayang Al. Tapi kamu juga harus sayang dirimu sendiri.” Ibu Emilia membelai rambut putrinya penuh sayang. “Al perlu menata hati dan hidupnya kembali.”
“Aku...pengin...bantuin...”
Ibu Emilia menarik napas pelan. “Mama tahu. Kamu pengin bantuin dia dan ada di sisi Al. Mama ngerti, Mi. Tapi, pengorbananmu udah cukup. Kamu harus berhenti biar Al bisa berkaca sama kehidupannya sendiri. Kalau dia belum bisa ngehargain perjuangan kamu, maka kamu harus menjauh. Kamu harus ngasih kesempatan buat kalian berdua. Kesempatan buat Al bangkit dengan usahanya sendiri. Kesempatan buat kamu bahagia.”
Kalimat itu seolah mencekik napas Emilia. Ibunya menangkup wajah Emilia dan tersenyum lembut serta pilu padanya.
“Kasih dirimu sendiri kesempatan buat jalanin hidup tanpa Al, Mi.”
“Ma...”
“Kesempatan buat kamu hidup bahagia, dengan atau tanpa Alvaro. Jangan nyiksa diri kamu sendiri begini. Mama ikut sakit, Mi. Kamu ngerti maksud Mama, kan?”
Air mata Emilia kembali tumpah. Ia menunduk dan mengangguk kaku. Sungguh ia memahami maksud ucapan ibunya. Persoalannya hanya satu. Sulit baginya melepaskan Alvaro. Cowok itu segalanya bagi Emilia. Alvaro selalu ada untuknya, menemaninya. Namun, perkataan ibunya mau tak mau menyeret Emilia pada renungan. Dirinya yang menjaga Alvaro sedemikian besar, layakkah menunda bahagia karena terus-menerus menahan luka? Karena secara tanpa Emilia sadari, ia telah menyiksa dirinya sendiri, menelantarkan kehidupannya demi seseorang yang telah secara gamblang menyia-nyiakannya. Sepadankah? Masihkah harus Emilia bertahan, atau seperti pesan ibunya, memberi diri mereka kesempatan untuk melangkah di jalan yang berbeda? Apakah sungguh hal itu bisa membuat Emilia bahagia?


 zazahra
zazahra