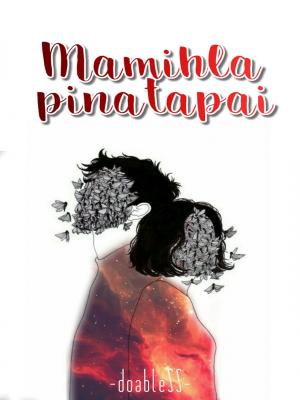ALVARO menatap kepergian Emilia dengan sorot kosong. Sesuatu dalam dirinya merutuki ucapannya dan mendesaknya untuk menyusul Emilia, memohon maaf. Namun, sesuatu yang lain membuang jauh-jauh semua rasa dan kehendak itu, hingga menahannya beberapa saat. Begitu Emilia tidak lagi berada dalam pandangan, Alvaro mengepal erat dan mengumpat. Ia melihat kotak bekal yang tergeletak dengan nanar, lalu meraihnya. Dipandanginya barang itu entah berapa lama. Alvaro meletakkan bekal itu di bangku yang ada di koridor, dan mulai beranjak. Baru beberapa langkah terukir, Alvaro berbalik dan mengambil bekal itu kembali.
“Kamu kok udah pulang—kamu kenapa nggak les lagi, Al?”
Teguran ibunya muncul saat Alvaro baru tiba di rumah. Ia melihat wanita itu sekilas, lalu mulai menapaki tangga.
“Alvaro!”
Pekik tak tertahan yang Alvaro abaikan. Ia mengunci pintu kamarnya dan memasang headphone dengan lantunan musik keras-keras dari pemutar MP3 di ranjang yang menampung tubuhnya. Samar Alvaro bisa mendengar ketukan pintu, tapi ia tidak berniat membukanya. Tak berapa lama, ketukan itu hilang. Alvaro masih bertahan dengan entakan keras musik meski membuat telinganya berdenging nyeri karena suara yang terlampau tinggi.
Di saku celananya, Alvaro merasakan getaran ponsel. Ia meraih benda itu. Raka menghubunginya.
“Lo apain Emi, Al?”
Pertanyaan itu segera menyambut Alvaro begitu ia menerima panggilan Raka. Mulut Alvaro bungkam.
“Gue lihat dia nangis di jalan tadi.”
“Terus lo nuduh gue yang bikin dia nangis?” Alvaro mengecap pahit di lidah. Isi kepala dan hatinya kusut sekali.
“Lo bener-bener tega sama dia, Al.”
Alvaro mengusap wajahnya dan mendengus. “Lo perhatian banget sama Emi. Kenapa? Lo demen sama dia? Ya udah pacarin aja sana.”
Raka mengumpat pelan, lalu panggilan itu diakhirinya sepihak. Alvaro melempar ponselnya sembarang ke ranjang, lantas melepas seragamnya dan berganti pakaian. Diraihnya jaket di tepi tempat tidur yang dilepasnya tadi. Setelah mengenakannya, ia mengantongi ponsel dan dompet, bergegas keluar kamar.
“Mau ke mana?” tanya ibunya tajam.
“Keluar.”
“Alvaro! Demi Tuhan, berhenti jadi anak berandalan!”
Alvaro menghentikan langkahnya dan berbalik. Ia menatap ibunya datar, bertolak belakang dengan sorot sengit di mata beliau.
“Emang kenapa kalau aku jadi berandalan, Ma? Bahaya ke reputasi Papa, atau bahaya ke image Mama?”
“Alvaro!”
Alvaro memunggungi ibunya lagi dan pergi. Sikapnya selalu seperti ini setiap kali berhadapan dengan orangtuanya. Ia tak lagi peduli dengan bentakan atau pukulan yang menunggunya nanti. Alvaro akan menjalani hidupnya sesuai yang ia ingini.
Alvaro menenggak gelas berisi alkohol hingga tandas. Ia menerima sorak sorai penuh sanjungan kawan-kawannya. Alvaro terkekeh, mengusap mulutnya. Ia bangkit dan menarik tangan Casi, lalu menggiringnya ke lantai dansa. Mereka menari berhadapan, menggoyangkan tubuh dan anggukan kepala yang mengentak sesuai irama musik.
Saat DJ mengubah iringan lagu menjadi lebih bertenaga, Alvaro mengangkat kedua tangannya ke udara, bersorak gembira. Bibirnya melengkung penuh bahagia. Pikiran dan hatinya adalah ruang lengang. Ketika tubuhnya terhuyung ke belakang, tarikan tangan Casi membuatnya terkekeh riang. Ia menatap wajah cantik itu dengan gairah, dan ditariknya sosok semampai itu ke dekapan. Pertemuan kulit bibir mereka menari lincah.
“Aku sayang kamu, Al...”
Suara itu menghentikan pagutan Alvaro. Ia memandangi roman Casi yang selalu berhasil membuainya. Musik kian mengentak, tapi ucapan Emilia merenggut seluruh suara itu di pikiran Alvaro.
“...Aku nggak mau putus... Aku pengin ada buat kamu... Aku pengin kamu kayak dulu lagi... Aku bakal nemenin kamu...ngadepin semua...”
Emi...
Alvaro menggeram. Ia merasakan tubuh dan kepalanya kian melayang. Tautan bibirnya di bibir Casi kembali terulang. Hanya beberapa detik, karena sebuah dorongan di perutnya membuat Alvaro melepas diri.
“Beb? Kenapa?” Casi mencoba mengimbangi suara musik dengan percuma.
Alvaro tak menggubris. Ia menatap sekeliling dengan linglung. Kakinya menarik langkah menjauh. Ia keluar dari kerumunan dengan susah payah. Alvaro berjalan ke toilet. Baru tiba di sana, isi perutnya mendesak keluar di salah satu wastafel yang disediakan.
“Aku lebih butuh cewek kayak Casi, Mi.”
Perut Alvaro menegang sementara mulutnya terus memuntahkan seluruh makanan dan minuman yang ia konsumsi. Rasa pedih menggaruk tenggorokan, membuatnya terbatuk-batuk kering. Napasnya terengah saat ia melihat kekacauan di wastafel. Alvaro menyalakan keran, membiarkan air membasuh kekotoran itu. Ia membasahi wajahnya dan mengusapnya kasar, lalu menatap cermin.
Alvaro terpaku. Di hadapannya, wajah asing itu terpampang. Mata merahnya dinaungi kantung mata hitam dan cekung. Pipinya tirus dengan bibir kering yang pucat. Tidak ada sinar di mata itu, pun cahaya di romannya. Alvaro tidak mengenali wajahnya sendiri. Ia tampak begitu berbeda.
Dan Emi masih bilang sayang sama orang ini?
Alvaro tersentak saat ponselnya bergetar kuat. Ia meraihnya di saku celana, melihat nama yang menari di sana. Raka. Ingatan akan perbincangannya dengan cowok itu membuat Alvaro meletakkan ponsel di sisi wastafel, membiarkannya berdering tanpa jawaban. Alvaro membasuh wajah sekali lagi. Kepalanya luar biasa pening, namun pengaruh alkohol bagai ikut terbuang karena Alvaro sepenuhnya sadar.
Panggilan itu berhenti. Alvaro hendak memasukkannya kembali ke saku celana saat Raka mengirimnya WhatsApp. Alvaro terpaku membaca isinya.
Raka Manggala
Toni OD. Gue di Harapan Kasih.
Alvaro memelesat keluar toilet dan memberitahu Bara juga Gagah. Sialnya, pengaruh alkohol membuat Alvaro sulit menembus kesadaran mereka. Ia akhirnya berangkat ke RS Harapan Kasih sendiri. Begitu tiba, Alvaro memarkir motornya asal-asalan dan berlari menuju UGD. Ia menemukan Raka di depan ruangan itu.
“Udah ditanganin?” tanya Alvaro dengan nada panik dan napas memburu.
Raka mengangguk. “Ibu Wahyu nemenin di dalam.”
Selepas mendengar itu, Alvaro melangkahkan kakinya memasuki UGD dan mencari Toni. Ia mendapati Ibu Wahyu di salah satu balik tirai, menangis tertahan.
“Den Toni nggak keluar-keluar kamar, Dok. Tadi siang sempat minum. Bir. Terus masuk lagi. Nggak makan dan nggak mau diganggu. Sampai malam Den Toni nggak keluar. Tadi saya minta Den Raka nubruk pintunya, soalnya saya takut Den Toni kenapa-napa. Saya gedor-gedor pintu tapi nggak dibuka-buka. Den Toni udah di karpet, berbusa banyak banget, Dok.” Ibu Wahyu terisak. Ia mengusap air matanya. “Den Toni bakal sembuh kan, Dok?”
Energi Alvaro bagai diserap paksa mendengar penuturan itu, dan keterangan dokter tentang kondisi Toni. Sahabatnya itu sedang kritis karena mengonsumsi narkoba bersamaan dengan alkohol dalam kadar tak wajar. Alvaro mengepal, merutuki diri kenapa ia tidak berkunjung ke rumah Toni. Alvaro menghabiskan waktu bersama Casi sebelum pergi ke kelab. Saat Gagah menghubungi Toni, panggilannya dijawab dengan satu kata; malas.
“Den Al...” Ibu Wahyu mengadukan hal yang sama pada Alvaro setelah dokter pergi dan wanita itu menyadari kehadiran Alvaro.
“Ibu udah hubungin keluarganya?”
“Udah, Den. Tapi tadi Ibu nggak bisa dihubungi. Nelepon Bapak cuma kesambung sama asistennya, tapi saya udah nyampein kondisi Den Toni. Den Bagas baru dapat penerbangan besok subuh dari Surabaya. Den Yagi bakal usahain cepat pulang katanya.”
Alvaro menelan ludah pahit mendengar itu. Ia menatap Toni yang terbaring tanpa daya di ranjang. Tubuh itu semula begitu kuat dan penuh percaya diri. Kini, sosoknya tampak menyedihkan.
Alvaro meminta Ibu Wahyu yang tampak begitu letih dan sedih untuk pulang, tapi wanita itu menolak. Ia bersikeras akan menemani Toni. Alvaro pun membiarkannya dan meninggalkan UGD. Raka masih berada di sana, duduk di salah satu deretan kursi yang disediakan. Malam sudah sangat larut, dan ruang tunggu itu begitu lengang. Tidak ada percakapan bising pengunjung atau kelincahan petugas medis yang berlari dari satu ruang ke ruang lain. Ada ketenangan yang menyiksa dan terasa mencekam.
“Lo nungguin gue lagi?” tanya Alvaro begitu ia duduk di sebelah Raka. Selama beberapa hari ini Raka selalu didapatinya di rumah Toni, menunggu. Pernah di satu kesempatan saat Alvaro dan kawan-kawannya larut pada minuman keras dan Raka datang. Cowok itu sempat melarang Alvaro minum, tapi nasihatnya ditertawakan semua orang. Alih-alih pergi, Raka bertahan di sana, tidak terusik dengan bujukan atau perintah Alvaro agar Raka pulang. Di tengah pengaruh alkohol yang mengikat kuat kewarasannya, Alvaro bisa mendengar ucapan Raka.
“Setidaknya gue bisa mastiin lo nggak ngelakuin hal lain selain minum.”
“Gue datang jam sembilan. Ibu Wahyu bilang lo nggak ke rumah Toni. Tadinya gue mau nyamperin lo ke rumah, tapi gue yakin lo nggak di sana. Gue tahu lo bakal ke rumah Toni kalau udah mabuk, makanya gue tungguin. Terus Ibu Wahyu tiba-tiba panik, minta gue ngedobrak pintu kamar Toni.” Raka mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ada gurat lelah di sana. “Lo udah tahu Toni ngedrugs?”
Alvaro bergeming. Di sisinya, Raka berdecak sambil menggeleng.
“Al, lo ngaku sahabatnya Toni, tapi lo biarin dia make.”
Ucapan itu terdengar serupa penghakiman yang membuat Alvaro mengernyit tak suka ke arah Raka.
“Justru karena gue sahabatnya gue nggak bisa ngelarang dia mau ngapain. Itu haknya dia.”
“Hak dia mati karena ngobat maksud lo?” Raka menegap, nada suaranya meninggi. “Dia sekarat, Al! Denyut nadinya hampir nggak kerasa! Kalau gue telat, Toni nggak bakal di sini tapi di ruang mayat!”
Alvaro bangkit dengan erangan keras. Dadanya menggelegak.
“Lo pikir gue pengin Toni OD dan jadi kayak gini? Nggak! Tapi gue nggak bisa minta dia berhenti karena gue tahu itu cara dia nenangin pikiran!”
Raka tersentak. Ia turut berdiri. Bibirnya tersenyum pahit.
“Pikiran lo udah tenang sama alkohol?” sindir Raka.
Tangan Alvaro mengepal erat. “Maksud lo apaan?!”
“Kalau lo emang peduli sama Toni dan nggak mau dia kayak gini, lo bakal larang Toni ngedrugs! Tapi lo biarin dia atas nama persahabatan. Dangkal banget, Al.”
Alvaro mendengus kasar. “Lo nggak bakal ngerti!”
“Kenapa? Karena menurut lo keluarga gue harmonis?” Raka menimpali sama kerasnya. “Menurut lo, gue nggak bakal paham sakit hatinya lo direndahin orangtua atau dibikin bonyok! Menurut lo, gue juga nggak bakal ngerti gimana rasanya jadi Toni yang nemuin nyokapnya main sama selingkuhannya!”
Alvaro terkesiap. Ia tidak tahu bagaimana Raka terpapar informasi itu, karena Alvaro tidak pernah memberitahunya. Apakah Ibu Wahyu?
“Lo ngerasa lo yang paling menderita di dunia ini. Lo marah sama satu-dua orang, tapi itu bikin lo marah satu dunia! Gue, Emi, semua lo salahin! Lo cuma mikirin diri lo sendiri! Lo ngancurin hidup lo sendiri!”
“Lo—“
“Lo pikir gimana perasaan gue sama Emi ngeliat lo kayak gini? Lo pikir kami bisa hidup tenang?!”
Raka menghujani Alvaro dengan tatapan sengit yang mengandung kepedulian, dan hal itu membuat Alvaro sesak. Ia mengerang, pergi dari sana.
“Mau ke mana lo?”
“Ngerokok!”
Alvaro meninggalkan area rumah sakit dan menepi ke sebuah warung yang berada tidak jauh dari sana. Ia membeli sebungkus rokok, lalu menyingkir ke dekat pohon dan mulai menyalakan batangan yang terapit di bibirnya. Sebuah isapan membuat napas Alvaro terasa berangsur lengang, meski tercekat kemudian saat ia teringat ucapan Raka.
“Lo ngerasa lo yang paling menderita di dunia ini. Lo marah sama satu-dua orang, tapi itu bikin lo marah satu dunia! Gue, Emi, semua lo salahin! Lo cuma mikirin diri lo sendiri! Lo ngancurin hidup lo sendiri!”
Kemarahan Alvaro membumbung. Ia menghabiskan rokoknya separuh.
“Hak dia mati karena ngobat maksud lo? Dia sekarat, Al! Denyut nadinya hampir nggak kerasa! Kalau gue telat, Toni nggak bakal di sini tapi di ruang mayat!”
“Lo pikir gimana perasaan gue sama Emi ngeliat lo kayak gini? Lo pikir kami bisa hidup tenang?!”
Alvaro tertegun. Matanya menatap rokok di tangannya dengan nanar. Pandangannya memburam sementara tubuhnya menggigil hebat. Ia jatuh berjongkok dengan kepala menunduk, membiarkan rokoknya terabaikan.
Luka hatinya terasa kembali basah. Kewarasannya seolah bangun lagi. Apa sebenarnya yang sedang ia lakukan ini? Mengonsumsi alkohol, mengisap rokok, mengabiskan waktu di kelab. Apa seperti ucapan Raka, Alvaro tengah menghancurkan dirinya sendiri? Kenapa? Karena ia marah pada ayah dan ibunya? Karena ia merasa tidak lagi ada gunanya mengharap pengertian dan belas kasihan? Karena ia tidak lagi peduli pada semua hal? Jika memang begitu, kenapa batinnya terasa sakit sekali saat ini? Kenapa ia berharap kembali, bahwa kejadian ini tidak pernah ada, dan bahwa ia adalah putra seorang walikota yang disayang ayahnya, dibanggakan ibunya, dan sanggup mengukir prestasi akademik yang jujur?
Alvaro mengangkat wajahnya yang dingin diterpa angin, memandangi rokok itu dengan mata berkabut. Ia mencari ketenangan dengan berbatang-batang rokok dan berbotol-botol alkohol. Toni mengeruk kedamaian dengan mengonsumi narkoba. Sedangkal itukah definisi persahabatan bagi mereka hingga saling membiarkan? Alvaro selalu merasa bahwa pemahaman tertinggi di hubungannya dengan Toni adalah tidak mencampuri urusan masing-masing, tidak peduli apa pun yang mereka ingin lakukan. Tapi, ucapan Raka seolah menyadarkan Alvaro bahwa ia telah keliru. Keberadaan Toni di ranjang rumah sakit detik ini menggenapkan hal itu. Jika Alvaro bisa menghentikan Toni, barangkali cowok itu masih tertawa dan penuh canda di dekatnya saat ini.
Getaran di ponselnya membuat Alvaro membuang napas kasar dan berdiri.
“Halo?” sapa Alvaro lemah.
“Beb, kamu di mana? Kok tiba-tiba nggak ada?”
Casi. Suaranya antara sadar dan tidak. Cewek itu sepertinya belum sepenuhnya mabuk.
“Mau pulang?” Alvaro menimpali lesu. Saat Casi mengamini, Alvaro berkata, “Aku nggak bisa nganterin. Minta yang lain, ya. Besok kutelepon.”
“Ya udah. Aku minta Bara anterin pulang, deh.”
Alvaro mengiyakan. Ia lantas mematikan sambungan. Pikiran dan tubuhnya letih sekali hingga ia malas bicara panjang lebar.
Alvaro sempat memandangi rokoknya sebelum mengisapnya lagi. Ia membutuhkannya.
Begitu batangan ketiga habis, Alvaro memasukkan kotak rokoknya ke jaket dan kembali ke rumah sakit setelah membeli biskuit dan empat botol air mineral. Keheningan menyambutnya saat ia tiba di ruang tunggu depan UGD, dan melihat Raka masih di sana. Cowok itu sedang tidur dengan posisi duduk dan kedua tangan terlipat di dada. Kepalanya sesekali terantuk-antuk.
Alvaro sempat melihat kondisi Toni yang belum sadarkan diri. Ibu Wahyu tertidur di sisi ranjang dengan kepala terantuk ke tempat tidur. Alvaro meletakkan biskuit dan dua botol air mineral di meja, lantas kembali duduk di sebelah Raka. Kriet kursi saat didudukinya membuat sahabatnya terjaga. Raka mengerjap beberapa kali, seolah mengumpulkan kesadaran dan menatap Alvaro dan sodoran botol minum bergantian.
“Thanks.” Raka menerima uluran itu dan meneguk isinya hingga setengah.
Kesunyian mengikat kebersamaan Alvaro dan Raka, sebelum Alvaro buka suara.
“Lo tahu dari mana soal Toni?”
“Ibu Wahyu.” Raka meletakkan botol minum di sisinya. “Waktu gue nungguin lo tadi, gue nanya kenapa rumah Toni sunyi terus. Ibu Wahyu cerita. Nggak ngerti juga kenapa Ibu Wahyu cerita itu sama gue.”
“Mungkin karena dia pengin lo bisa ajakin Toni jadi anak bener.” Alvaro mengambil kesimpulan. Ia menyadari Raka sempat menatapnya. “Ibu Wahyu naruh harapan yang sama ke gue. Tapi...” Alvaro terkekeh. “Gue sama aja kayak Toni.”
“Dan gue beda?”
Alvaro mengangkat bahu. “Mungkin karena lo kuat iman walau udah ditawarin bir.”
Keduanya kembali terdiam. Setelah diingat-ingat, ini perbincangan pertama mereka sejak yang terakhir.
“Lo dapat SP2?” tanya Raka akhirnya. “Wali kelas manggil lo lagi, kan?”
Alvaro menyeringai.
“Anak walikota dikasih SP2. Headlinenya ngejual, tuh,” guraunya diikuti tawa kering.
“Mau sampai kapan lo kayak gini, Al?”
Alvaro tidak menjawab. Mulutnya bungkam bahkan hingga belasan menit berlalu dan ia melihat Raka membaringkan tubuhnya di kursi, tidur di sana. Alvaro menyandarkan punggungnya yang seketika membuatnya meringis, lupa area itu teramat peka. Ia akhirnya beranjak dari sana dan berdiri di taman rumah sakit yang sunyi.
Malam kian larut dan angin menerpa tubuhnya tiada ampun. Alvaro tampak tak terusik. Jika serangan angin bisa membekukannya, barangkali itu lebih baik.
Alvaro mengeluarkan kotak rokok yang dibelinya tadi dan menjepit sebatang di jarinya. Ia menyalakan batangan itu dan mengisapnya teramat domestik. Alvaro mendongak ke arah langit tanpa butiran cahaya bintang, pun sapaan pendar bulan. Hanya kelam yang menaungi.
Alvaro menghabiskan berjam-jam di sana, sebelum kembali ke ruang tunggu dan duduk lesu dengan mata terpejam. Ia terjaga saat Raka membangunkannya, menyodorkan kantung plastik berisi roti dan susu kotak yang menurut Raka, pemberian Ibu Wahyu.
Langit mulai terang saat itu. Alvaro beranjak ke toilet untuk membasuh wajahnya dan masuk ke UGD. Toni masih belum sadarkan diri, sementara Ibu Wahyu masih setia menemaninya.
Alvaro dan Raka sedang melahap roti saat Bagas tiba. Ia lekas melipat bungkusan roti yang isinya masih separuh, lantas berdiri menyambut kehadiran cowok itu. Alvaro mengantar Bagas ke bilik ranjang Toni. Cowok berperawakan tinggi besar dengan rambut acak-acakan itu meneliti kondisi adiknya, lalu menyambar tatapan tajam pada Ibu Wahyu.
“Ini kenapa jadi gini, Bu? Kenapa Toni bisa OD? Ibu kenapa nggak bilang Toni ngobat?”
Alvaro bisa mencium aroma kemarahan di tubuh Bagas, dan hal itu menciutkan nyali Ibu Wahyu.
“Ma-maaf, Den. Saya—“
“Udah lama dia kayak gini?” sela Bagas dengan nada frustrasi.
Ibu Wahyu mengangguk lesu. “Den Toni ngelarang saya buat bilang, Den. Saya bingung juga.”
“Harusnya walau dia ngelarang, Ibu bilang sama saya! Masa mesti nunggu kejadian kayak gini baru ngomong!”
Rasa bersalah Ibu Wahyu begitu kentara, dan hal itu membuat Alvaro tidak tega. Ia tahu posisi Ibu Wahyu sulit. Alvaro ingin berkata sesuatu untuk mencairkan suasana, tapi ketika ia melihat Bagas menyugar rambutnya dibarengi desahan napas keras, ia terdiam. Raut wajah Bagas kusut dan tak terbaca.
“Maaf, Bu, saya jadi melampiaskan ke Ibu. Saya cuma...” Bagas mengusap wajahnya. Alvaro mendengarnya mengumpat pelan dan berbisik lirih, “Abang macam apa gue.”
Bagas meminta Ibu Wahyu untuk pulang demi beristirahat dan membawakan Toni pakaian ganti. Raka berinisiatif menemani. Tertinggal Alvaro dan Bagas di sana. Bagas sempat menghubungi istri dan orangtuanya sebelum duduk di sisi ranjang Toni, menatap adiknya tanpa berkedip. Bagas lantas membuang napas keras dan mengusap wajah. Tangannya bertumpu pada tempat tidur.
“Kamu tahu soal ini juga, Al?”
Alvaro yang berdiri di ujung tempat tidur, mengangguk. “Belum lama ini, Bang.”
Seulas senyum getir hinggap di bibir Bagas. “Dan sebagai Abang, gue nggak tahu apa pun,” gumamnya samar.
Barangkali penyesalan terbesar bukanlah dirasakan Ibu Wahyu, melainkan Bagas. Detik ini, Alvaro bisa melihat bagaimana sosok tegas itu terpukul dengan kondisi adik yang jarang ia temui. Alvaro tidak tahu bagaimana Toni berhasil menipu keluarganya, hingga Bagas mengira Toni baik-baik saja. Kemampuan Toni dalam bersandiwara pastilah terlampau hebat. Atau terbatasnya interaksi pertemuan antar anggota keluarga itu memberi peranan yang lebih besar.
“Kamu juga?”
Pertanyaan itu bisa diartikan berbeda oleh orang lain, tapi Alvaro tahu yang Bagas maksudkan adalah apakah Alvaro pun mengonsumsi narkoba. Alvaro menggeleng. Detik itu Bagas membuang napas. Ada kelegaan di wajahnya.
“Jangan sampai, Al. Jangan coba-coba.”
Pesan itu singkat dan tegas. Alvaro hanya mengangguk kaku. Bagas lalu berterima kasih karena Alvaro sudah turut menemani Toni dan mempersilakannya beristirahat di rumah. Alvaro tidak ingin pulang. Ia lebih memilih ke rumah Toni. Namun, hal itu jelas mesti ia hindari karena Bagas kemungkinan pulang ke sana. Alhasil, setelah pamit Alvaro melajukan motornya ke rumah. Ia bersyukur ayahnya tengah mengisi jadwal kegiatan hari Sabtu ini, jadi ia tidak perlu bertemu dengannya. Meski teguran keras ibunya tetap menyambut Alvaro yang berjalan lunglai ke kamar, berbaring di ranjang setelah mengunci pintunya. Seluruh tubuhnya letih. Kepalanya berkunang-kunang. Matanya pedih dan berat.
Alvaro baru hendak tidur saat ia teringat akan menghubungi Casi. Alvaro meraih ponselnya dan membiarkan nada tunggu memenuhi indera pendengaran. Panggilan itu tidak diterima. Waktu menunjuk pukul delapan pagi. Ia yakin Casi masih tidur, efek mabuk semalam. Apa Casi pulang ke rumahnya? Siapa yang mengantarnya?
“Halo?”
Sapaan Bara serak dan tak bertenaga. Alvaro memutuskan menghubungi cowok itu.
“Bar, udah baca WA gue? Toni OD. Sekarang lagi di Harapan Kasih.” Semalam Alvaro memang mengirim WhatsApp pada Bara dan Gagah, memberitahu mereka terkait kondisi Toni karena ia yakin kedua cowok itu tidak mendengarnya di kelab.
“Hah?” Suara Bara menyentak. “Serius? Ah, gila! Bentar, Al. Sial. Bentar, kepala gue berat banget.”
Terdengar bunyi grasak-grusuk di ujung sana. Sepertinya Bara baru bangkit dari tempat tidur dan melewati pintu, karena Alvaro mendengar suara pintu yang ditutup.
“Lo di RS?” Suara Bara kembali.
“Udah di rumah. Ada Bang Bagas di sana. Tapi Toni masih belum sadar.”
Bara mengumpat keras. “Tuh anak makin banyak makenya pas tahu bokapnya mau kawin lagi.”
Pernyataan itu mengejutkan Alvaro hingga kantuk yang sempat membuai kelopak matanya, terusir paksa. Ia bangkit dan duduk di tempat tidur. Terdengar bunyi kucuran air.
“Bokapnya mau kawin lagi?”
Bara menggumam. Kucuran air tidak lagi terdengar. “Pas gue lagi make bareng dia, dia bilang gitu.”
Alvaro tidak tahu soal itu. Apa karena ia tidak turut mengonsumsi narkoba hingga Toni tidak bercerita? Atau karena persahabatan mereka memang sedangkal yang Raka pikir, hingga kebersamaan keduanya hanya sebatas rokok dan bir?
“Bar! Buka ih pintunya! Kebelet nih!”
Alvaro tersentak. Ia mengenali suara yang muncul di balik teleponnya.
“Lo bareng Casi? Di mana?”
Terdengar Bara mengumpat samar. “Bentar, Al.”
Saat tidak lagi ada suara, Alvaro tanpa sadar menguatkan cengkeraman di ponselnya. “Bar, lo di mana?!”
Sambungan terputus. Alvaro membeliak menatap ponselnya. Jantungnya berdentum-dentum gusar. Kepalanya berdenyut memikirkan Casi bersama Bara. Ia melakukan panggilan kembali pada Bara, tapi cowok itu tidak menerima. Alvaro mengerang, bangkit dari ranjang. Tangannya bergerak cepat dan tegang menghubungi Gagah. Tidak tersambung. Baru saat ia menelepon Darka, cowok itu mengangkatnya.
“Sialan, Al. Jam berapa, nih? Kepala gue—“
“Di mana lo?” Alvaro mengabaikan gerutuan Darka.
“Hah?”
“Lo di mana?!”
“Jir, apaan lo, Al, nelepon tiba-tiba langsung marah-marah!” Darka menggeram keras di ujung sana. “Gue di rumah! Ada apaan?!”
“Lo nggak bareng Bara?”
“Lah, ngapain! Dia cabut sama Casi—“ Darka diam sejenak. Ia tiba-tiba terkekeh, membuat Alvaro mengernyit dalam. “Lo nyariin Casi? Bareng Bara dia. Nggak tahu deh ke mana. Hotel kali.”
Mulut Alvaro melontarkan sumpah serapah. Ia mematikan panggilan dan menyambar kunci motornya di meja, berderap keluar. Alvaro mengabaikan panggilan ibunya, dan memelesat menuju rumah Casi. Rasanya ia ingin memukuli pintu rumah Casi saat ART menyebut putri majikannya tidak pulang semalam. Alvaro kembali ke motornya yang terparkir di depan rumah Casi, menghubungi cewek itu.
Kepalanya seolah akan meledak karena panggilannya tidak diterima. Ia mengirim WhatsApp pada Casi, meminta cewek itu mengangkat teleponnya. Tubuhnya kaku dan jemarinya gemetar menahan emosi. Pikirannya semrawut dan napasnya memburu. Baru pada percobaan panggilan entah yang ke berapa, Casi menerimanya.
“Di mana?”
“Di rumah, Beb. Masih ngantuk banget.”
Cengkeraman Alvaro mengerat. “Cas, aku di depan rumah kamu!” sergahnya tak sabar. “Kamu di mana?! Bareng Bara? Kalian check in?!”
Hening.
“Casi!”
“Duuh, bisa nggak sih nggak teriak-teriak, Al? Sakit telingaku!” Casi menggerutu keras di seberang. “Iya, aku bareng Bara! Kamu nggak bisa nganterin aku pulang kan tadi malam? Bara yang nganterin aku!”
“Nganterin kamu pulang! Sekarang kamu di mana?” Alvaro membuang napas sesak. Dadanya sakit sekali, seolah akan meledak. Ia tidak bisa berpikir jernih detik ini. “Casi—“
“Al, nggak usah ribut lo!” Suara Bara menggantikan Casi, membuat Alvaro tercekat. “Gue sama Casi lagi di hotel. Udahlah, kayak yang nggak tahu aja lo, cowok sama cewek lagi mabok bareng, ya ujungnya ke hotel! Kayak lo sama Casi nggak pernah aja.”
Apa? APA?!
“Lo ngapain Casi?”
“Ck!”
“Lo ngapain Casi?!”
“Mulut lo, Al, kayak banci! Lo cuma selingkuhan Casi, nggak usah sok gitulah. Casi juga mau sama gue. Udahlah. Gue masih ngantuk! Ribut lo!”
Tidak lagi terdengar suara apa pun. Alvaro terpaku di tempatnya, berdiri tegang di samping motor, hingga ia sadar bahwa panggilan telah berakhir. Alvaro menatap ponselnya nanar. Ucapan Bara terngiang. Detik itu, seluruh kewarasan Alvaro bagai mengambang, karena ia memukulkan ponselnya ke jok motor keras-keras hingga menimbulkan denyut nyeri di telapak.
Apa kata Bara tadi? Ia dan Casi sedang di hotel, dan Casi juga menginginkannya? Alvaro menggeram jengah. Ia mengusap wajahnya keras. Gelegak emosi yang dirasakannya saat ini sama persis saat ia menahan amarah karena perlakuan ayahnya. Sesak. Nyeri. pedih. Casi, perempuan yang ia percayai yang akan selalu ada untuknya, berani bersama lelaki lain di kamar hotel! Bukankah Casi menyukainya? Menyayanginya? Apa cewek itu berdusta? Apa bagi Casi, Alvaro sebatas selingkuhan yang bisa sewaktu-waktu diabaikan? Apakah serendah itu arti Alvaro bagi Casi, hingga ia bisa bersama cowok lain di tempat yang tidak pernah Alvaro berani datangi dengan cewek mana pun? Semudah itukah Casi dan Bara melakukannya?
Alvaro tidak pernah merasa dikhianati sedemikian besar, dan rasanya teramat menyakitkan.


 zazahra
zazahra