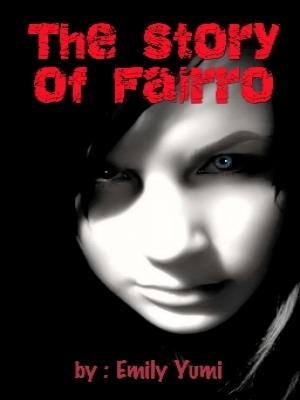ALVARO mengembuskan asap rokok yang membumbung di langit malam. Pencahayaan yang memadai di teras belakang rumah Toni membentuknya menjadi berkas-berkas wajah yang hilang begitu melerai bersama angin. Seketika saja hati Alvaro bagai dicubit, yang lekas ia hempaskan dengan satu isapan kuat di gulungan tembakaunya.
Getaran ponsel menyentak Alvaro. Ia meraih benda itu di sisinya. Pesan dari Kevan.
Kevan Prasaja W
Abang nggak sekolah?
Papa tahu.
Alvaro mengabaikan pesan itu dengan perasaan campur aduk. Ia memang tidak berniat sekolah hari ini. Atau barangkali sejak seminggu lalu. Tak sedikit pun motivasinya untuk datang ke tempat yang selalu mengingatkannya akan kepayahannya mengasah otak dan menata emosi. Nilai-nilainya merosot drastis dalam seminggu. Ulangan harian matematika yang ia tempuh tiga hari lalu, mendapat nilai 61. Kemarahan ayahnya tak terelakkan. Alvaro dengan cantiknya menjadi samsak beliau.
Dan hatinya...
Sebuah pesan WhatsApp lain tiba.
Casi Fortuna
Beb, aku udah siap, nih.
Jemput, ya.
Alvaro bangkit dari duduknya. Ia memadamkan sisa rokok dan membuangnya, lalu melangkah lebar ke kamar tamu di lantai dua demi meraih jaketnya. Seragamnya telah teronggok tanpa daya di kursi.
“Ton,” panggil Alvaro sambil membuka pintu kamar Toni yang seketika membuatnya mengumpat pelan. Toni tengah melakukan rutinitasnya di sofa, tampak tak terusik dengan suara Alvaro. Dadanya berdentum keras menyaksikan Toni menikmati barang terlarang yang tak pernah ia duga dikonsumsi Toni. “Gue cabut.”
Tidak ada jawaban. Alvaro menutup pintu dengan risau, lalu turun ke lantai satu dan berpapasan dengan Ibu Wahyu.
“Aku keluar dulu, Bu. Nanti balik lagi.” Alvaro diam sejenak saat melihat bola mata Ibu Wahyu beriak gelisah ke arah tangga. Apa ART itu tahu yang majikannya lakukan?
“Den?”
Alvaro yang baru hendak beranjak, menoleh pada Ibu Wahyu yang menatapnya lamat.
“Kenapa, Bu?” Alvaro berbalik menghadap wanita itu.
“Den Al mau ke kelab lagi? Sekarang Del Al ngerokok sama minum-minum.”
Pertanyaan sederhana yang menyentak Alvaro. Ia menangkap raut cemas di wajah Ibu Wahyu. Barangkali karena wanita itu sudah cukup mengenal Alvaro, begitu pun sebaliknya. Meski ada keengganan di suara wanita itu, yang Alvaro pahami sebagai bentuk keraguan untuk bertanya, tapi terlalu ingin tahu untuk mengabaikannya.
Alvaro tersenyum miring. “Bir enak lho, Bu. Bikin hati sama pikiran plong,” katanya sambil lalu, mengadopsi ucapan Toni. Alvaro meraih sepatunya dan mengenakannya dengan tubuh membungkuk yang memunggungi Ibu Wahyu.
“Jangan menipu diri sendiri, Den. Pasti cuma sesaat aja kerasa enaknya. Den Toni suka banget ngerokok sama minum. Dulu nggak begitu. Tapi waktu tahu Ibu...” Ibu Wahyu berhenti sejenak.
Alvaro baru mengenakan sebelah sepatunya. Ia menatap Ibu Wahyu. “Selingkuh?” tembak Alvaro tenang. Ia tahu ‘Ibu’ yang Ibu Wahyu maksud adalah mantan nyonya rumah ini.
Gelagat Ibu Wahyu kian tak nyaman. “Kasihan Den Toni. Den Toni dekat banget sama Ibu. Makanya waktu tahu, Den Toni sedih banget. Saya tahu Den Toni pasti sedih, walau kelihatannya Den Toni tegar. Cuma, tiba-tiba Den Toni jadi suka minum-minum, yang awalnya minum bir simpanan Bapak. Saya kaget banget, Den. Waktu Ibu tahu, Den Toni dimarahi. Biasanya Den Toni nurut sama Ibu, tapi setelah tahu Ibu punya...” Ibu Wahyu berdeham. “Den Toni jadi nggak nurut lagi. Sering membangkang. Den Toni jarang pulang. Tahu-tahu, saya nemuin puntung rokok di kamar Den Toni, sama ada kaleng bir. Waktu Ibu sama Bapak pisah, kelakuan Den Toni makin bebas. Apalagi rumah ini selalu kosong. Den Bagas jarang banget jenguk Den Toni. Den Yagi juga lagi kuliah di luar negeri. Kalau Den Toni udah bawa temen-temennya ke sini buat minum-minum, bingung saya, Den. Dinasihatin, Den Toni malah nyuruh saya pulang.”
Tak ada suara yang keluar dari mulut Alvaro selama Ibu Wahyu bicara. Ia mendengarkan dengan saksama, karena penuturan itu berupa kisah Toni yang tak diceritakan sahabatnya. Padanya, Toni pun bercerita tentang penemuannya pada adegan berani sang ibu dengan selingkuhan, menggunakan nada ceria seolah hal itu bukan persoalan serius. Namun, Alvaro tahu Toni menyimpan sedemikian besar rasa sakit dan kecewa, karena ia pun tahu kedekatan Toni dengan ibunya.
“Makanya saya senang waktu ada Den Al.”
Alvaro mengernyit. Senang?
“Saya ngarep Den Al bisa bantuin Den Toni biar nggak ngerokok sama mabuk-mabukkan lagi. Kasihan. Tapi...”
Alvaro tertegun. Ia tidak pernah tahu Ibu Wahyu menyimpan harap sederhana itu padanya.
Alvaro terkekeh muram. Ia mengenakan sepatu yang masih bebas. “Sekarang aku kayak Toni juga, Bu,” akunya dengan nada dibuat ceria. Tangannya mengikat tali sepatu, tapi pikirannya tidak sedang pada benda itu.
Saat Alvaro kembali tegap dan melihat Ibu Wahyu, wanita itu tersenyum sendu. Alvaro tidak tahu apa yang Ibu Wahyu pikirkan sekarang tentangnya. Barangkali ia mencap Alvaro tak jauh beda dengan Toni. Remaja bermasalah dengan pergaulan sebebas ini.
“Den Al belum sejauh Den Toni. Ibu percaya, Den. Den Al anak baik. Ajakin Den Toni berubah juga.”
Alvaro meneguk ludah. Tenggorokannya terasa kesat. Tanpa sadar ia mengepal.
“Buat apa jadi anak baik kalau nggak bisa jadi anak pintar, Bu,” gumam Alvaro muram. Ucapan itu meluncur lancar bersama bayangan wajah ibu dan ayahnya. Benar. Apa gunanya menjadi anak baik jika kemampuan otaknya tak memadai? Sedari awal, ia sepatutnya lahir sebagai anak cerdas, bukan anak yang berperilaku baik. Orangtuanya tak memedulikan hal lain, kecuali prestasi akademik.
“Den Al emang harus pintar.” Ibu Wahyu kembali bicara. “Pintar memilih mana yang bagus dan mana yang nggak, buat hidup Den Al.”
Pernyataan itu membungkam Alvaro seutuhnya. Ia menatap Ibu Wahyu dengan mulut membuka tanpa suara. Alvaro menelan ludah, merunduk sejenak. Napasnya mulai sulit.
“Dulu, waktu Den Toni masih pulang ke rumah, saya sering nemuin Den Toni ngelamun. Waktu ditanya, Den Toni cuma ketawa, terus minta makan. Setelahnya, Den Toni jarang pulang. Nggak tahu tidur di mana. Sekarang Den Toni kayak gini. Saya suka nyesel, Den. Coba waktu itu saya lebih dekat sama Den Toni, mungkin Den Toni nggak bakal kayak sekarang. Makanya, walau saya sempat diajakin Ibu ikut pindah karena katanya Ibu udah nyaman banget sama saya, saya nggak mau pergi, Den. Saya maunya terus di sini, jagain Den Toni. Bapak udah jarang pulang. Den Bagas sama Den Yagi juga jarang kelihatan. Cuma saya muka lama yang Den Toni kenal di rumah ini. Saya mikirnya, mungkin aja Den Toni bisa nganggap saya keluarga. Saya sendiri udah sayang sama Den Toni. Udah ngurus dari kecil.”
Ah, Alvaro lupa. ART di rumahnya dengan Ibu Wahyu teramat berbeda. Ada kesenjangan yang begitu kentara bersama sang asisten rumah tangganya. Namun, Ibu Wahyu terasa bagai seorang ibu. Kehangatan dan kelembutannya terasa familiar. Maka, tak heran jika Ibu Wahyu bertahan mengurus Toni hingga sekarang, di saat ART lain memilih berganti majikan. Ibu Wahyu bukan sekadar pegawai.
Alvaro tersenyum samar.
“Aku pamit, Bu.”
Alvaro melajukan motornya dengan kecepatan tinggi menuju rumah Casi. Ia tiba lima belas menit kemudian. Tanpa menemui orangtua Casi, Alvaro menunggu di depan gerbang. Tak berapa lama cewek itu muncul, memamerkan senyumnya yang memesona. Bibir Alvaro turut merekah. Casi adalah moodboosternya.
Mereka pergi ke kelab berbeda yang pertama kali Alvaro datangi, tapi sudah ia kunjungi beberapa kali hingga hari ini. Kelab itu lebih berkelas dan tertutup. Lokasi yang Bara anjurkan setelah menyebarnya video Alvaro.
Tiba di sana, teman-teman Alvaro sudah berkumpul. Bara sempat menanyakan keberadaan Toni yang dijawab Alvaro ala kadarnya. Bara mengangguk paham, lalu mereka pun masuk. Bangunan kelab itu jauh lebih megah. Di salah satu meja VIP, belasan remaja itu menghabiskan bergelas-gelas alkohol, rokok dan tawa.
Kepala Alvaro mulai terasa melayang saat ia memandangi Casi di lantai dansa, tengah menari lincah bersama teman ceweknya. Alvaro mengalihkan pandangannya pada botol bir di tangan.
“Jangan menipu diri sendiri, Den. Pasti cuma sesaat aja kerasa enaknya.”
“Den Al emang harus pintar. Pintar memilih mana yang bagus dan mana yang nggak, buat hidup Den Al.”
“Beb.”
Alvaro mendongak. Casi datang menghampirinya. Tanpa bersuara, Alvaro meraih pergelangan tangan Casi dan menariknya hingga jatuh di atas tubuhnya, dan ia cumbu cewek itu tanpa aba-aba.
“Tapi dia nggak bener-bener peduli sama lo! Emi yang peduli! Dia nyariin lo dan pengin lo baikan sama keluarga lo! Casi nganjurin apa? Ke kelab buat mabuk-mabukan?! Hidup lo makin kacau dekat sama dia!”
Alvaro menggeram begitu teringat ucapan Raka. Ia memperdalam serangannya pada Casi, tak peduli cewek itu sempat mengaduh yang akhirnya pasrah berada di bawah kendali Alvaro.
“Aku emang nggak bisa nepatin janjiku ke kamu. Kalau kamu mau putus, nggak masalah.”
“Lo serius bilang putus sama Emi?”
Alvaro mendorong tubuh Casi menjauh darinya secara tiba-tiba saat wajah Emilia membayang kuat di kepala dan menyentaknya. Pengaruh alkohol seolah tersamarkan oleh keterkejutan itu, membuat jantungnya mengentak-entak dan peluh membayang di keningnya.
“Beb?” Casi membelai wajah Alvaro. “Kenapa?”
Alvaro menelan ludah yang terasa amat pahit. Ia menggeleng, membuang sosok Emilia jauh-jauh dari benaknya. Tak peduli ia serius atau tidak. Ia tidak ingin memedulikan apa pun lagi karena hanya membuatnya kian lelah. Jika ucapannya waktu itu dianggap Emilia sebagai pengakhir hubungan mereka, maka biar itulah yang terjadi. Tidak masalah bagi Alvaro. Setidaknya Casi selalu ada untuknya.
Sebelah tangan Alvaro yang bebas merangkul Casi, memeluknya erat.
“Beb?”
“I love you,” bisik Alvaro serak.
“I love you too, Beb.”
Apa sesungguhnya yang Alvaro butuhkan? Ia tidak tahu. Setidaknya jawaban Casi membuatnya agak lega, meski barangkali ia telah secara tanpa sadar mengabaikan nyeri yang kian menganga atas kekosongan di hatinya.


 zazahra
zazahra