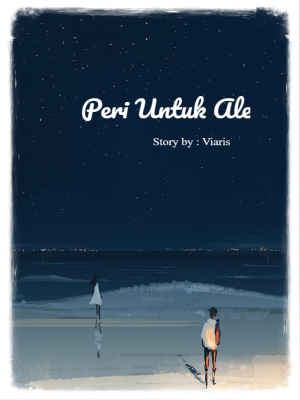ALVARO W
Emi.
Emilia baru saja hendak mematikan lampu kamarnya untuk beranjak tidur saat denting ponsel muncul, dan mendapati sebuah pesan singkat dari Alvaro. Isinya tak mengandung lebih dari satu kata. Alvaro hanya mengirim namanya, seolah tengah memanggilnya.
Emilia menegakkan tubuh untuk menarik napas panjang agar degupnya sedikit lebih tenang, karena menerima pesan dari Alvaro selalu sanggup membuatnya berdebar-debar. Terlebih, di waktu yang tak ia duga seperti sekarang; pukul sebelas malam. Ada apa, ya? Emilia bertanya-tanya. Ia meregangkan otot-otot jemarinya agar lebih rileks.
Emilia S
Alvaro.
Emilia bingung harus membalas apa. Sungguh. Duduknya sudah gelisah memikirkan balasan seperti apa yang tepat diberinya. Alhasil, Emilia hanya mampu mengulang apa yang Alvaro lakukan.
Alvaro W
Wkwkwk. Belum tidur, Mi? Nggak nyangka SMS-ku dibalas.
Emilia mengembuskan napas panjang kuat-kuat. Dadanya sesak karena kian berdetak liar. Ia menarik tubuhnya mendekat ke ranjang, menumpuk bantal dan bersandar di sana. Bantal yang empuk tidak membuatnya merasa lebih baik. Ia tetap saja gugup. Akhirnya Emilia menegak kembali. Ia menggigit bibir mencari balasan yang tepat.
Emilia S
Baru mau tidur.
Emilia menghapusnya. Ia tidak ingin kesempatan ini berakhir.
Emilia S
Belum ngantuk. Hehe.
Setelah mengirimnya, Emilia menunggu balasan. Namun, hingga sepuluh menit berlalu, ponselnya tak juga berdenting. Emilia menghela napas kecewa karena mulai meyakini Alvaro sudah tidur. Ia pun meletakkan ponselnya di nakas. Saat itulah benda itu berdering. Bukan denting pendek menandakan SMS masuk, melainkan nyanyian panjang dari ponsel karena panggilan. Emilia membeliak saat melihat nama Alvaro di layar. Ia praktis mulai panik. Tubuh yang awalnya mulai tenang, kini tegang kembali. Ia duduk tegap, menarik napas panjang, lantas menerima telepon Alvaro.
“Halo?” Emilia menyapa pelan. Ia menggigit bibir karena suaranya tadi terdengar begitu gagap.
“Nggak apa-apa kan kalau aku telepon?” sahut Alvaro di ujung sana. Nada bicaranya terdengar riang, meski Emilia menangkap sesuatu yang berbeda. Suara Alvaro tertangkap agak parau dan sedikit tak bertenaga.
“Nggak apa-apa, kok.” Emilia berujar cepat. Ia mengusapi siku tangannya yang memegang ponsel dengan gugup. “Kamu belum tidur?”
Tawa Alvaro menyambut. “Udah, Mi. Ini roh aku yang lagi telepon kamu.”
Emilia praktis tersenyum, merasa konyol.
“Lagi ngapain, Mi?”
Emilia melirik buku-buku di meja belajarnya. “Ngulang-ngulang pelajaran aja.”
“Ya ampun. Kamu nggak capek belajar, Mi?” Kekehan riang menyusul tanya Alvaro.
“Biar nggak lupa.” Emilia mendorong tubuhnya hingga menempel ke tumpukan bantal, mencari kenyamanan. “Kalau kamu?”
“Mikirin kamu.”
Emilia tertegun. Jantungnya bagai berhenti berfungsi. Keterkejutan membungkusnya hingga membuat sekitar terasa hening, lantas telinganya mendengar dadanya yang menderu-deru, juga entakan yang terasa menyesakkan.
“E-eh?”
Alvaro tertawa. “Mikirin kamu,” ulangnya. “Mikir, kenapa kamu kok bisa pintar banget ya, Mi?”
Pernyataan susulan itu menyabit sayap-sayap pengharapan yang tadi sempat berembus terbang di dadanya. Bahu Emilia seketika melesak. Ia menghela napas kecewa.
“Transfer otakmu sedikit sama aku dong, Mi.”
“Otakku biasa aja, Al.” Emilia mencoba tetap tenang agar kekecewaannya tak kentara.
“Seriusan, Mi. Aku iri sama kamu. Di kelas, kayaknya cuma kamu yang selalu dapat nilai sempurna. Jauh banget levelnya kita.”
Emilia mengernyit karena suara Alvaro memelan, dan caranya bicara memberi kesan muram. Ia tidak pernah mendengar Alvaro berbicara seperti ini. Di sekolah, Alvaro selalu terlihat riang dan senang bergurau. Sosok di ujung telepon sana, terasa agak berbeda. Apakah Alvaro tengah menghadapi sesuatu? Soal apa? Sekolah? Padahal, mereka bersekolah di tempat yang sama. Mereka lolos seleksi ketat yang sama. Mereka bahkan berada di satu kelas. Tidak ada yang berbeda bagi Emilia. Tapi perkataan Alvaro memberi kesan sebaliknya.
“Ada yang mau diceritain, Al?” Tanya itu terlontar begitu saja. Alvaro tak segera menyahut, dan hal itu membuat Emilia menggigit bibir penuh penyesalan. Duh. Kenapa aku nanya gitu? Kesannya sok tahu banget. Kalau dia nutup teleponnya gimana? Minta maaf, Mi. Ayo cepat minta maaf. “Ma—“
“Mamaku dosen, Mi.”
Mulut Emilia membuka karena ucapannya disela. Ia terdiam, bingung dengan arah pembicaraan.
“Dan papaku walikota.”
Emilia tahu itu.
“Mereka cerdas-cerdas, Mi. Adik-adikku juga. Kevan sama Ana juara kelas mulu. Hebatlah pokoknya mereka. Beda sama aku.” Alvaro tertawa hambar. Ia mengembuskan napas cukup panjang. “Orangtuaku peduli banget soal nilai, Mi. Mereka mau anak-anak ikutan jejak mereka. Jadi dosen atau pejabat. Kadang mereka berantem gara-gara debat aku harus ngikutin mama atau papa. Konyol banget nggak tuh, Mi?” Alvaro tergelak sejenak. Emilia hanya tersenyum samar, mulai memahami keluh-kesah Alvaro. “Kalau Kevan sama Ana sih udah pasti bisa tinggal milih. Mereka beneran encer banget otaknya, Mi. Persis kayak kamu. Kalau aku...” Alvaro mendesah. “Faktor keberuntungan aja sih, Mi, aku bisa masuk Bina Pekerti.”
Hening. Emilia menunggu Alvaro bicara lagi, tapi yang ia dengar hanya helaan napas berat cowok itu. Emilia merunduk, menatap tangannya yang tak lagi mengusapi siku. Kebiasaan yang selalu dilakukan saat gugup. Kini, yang dirasakannya adalah kegelisahan. Ia bisa menyerap keresahan di suara Alvaro, dan apa yang tengah bergumul di hati cowok itu. Hal itu ikut membuat Emilia muram. Ia ingin melakukan sesuatu, mengatakan apa pun. Tapi apa? Apa yang bisa membuat Alvaro sedikit lebih baik?
“Menurutku, nggak ada yang namanya keberuntungan, Al. Aku percaya, apa pun yang kita dapatkan adalah hasil kerja keras kita. Keberuntungan itu kesannya apa, ya? Kayak nggak yakin sama diri sendiri, nggak yakin sama Tuhan.” Emilia melipat bibir. “Maksudku, kita pasti usaha keras buat dapatin apa yang kita mau, kan? Tuhan lihat itu. Jadi kalau kita berhasil, bukan karena keberuntungan, tapi ya karena kita sendiri dan izin Tuhan.”
Lengang kembali. Emilia berdeham, jemarinya mulai mengusap siku lagi.
“Ma-maaf. Omonganku ngaco banget, ya?”
Di ujung sana, Alvaro terkekeh. “Nggak, Mi. Kamu benar. Nggak ada faktor keberuntungan. Apa yang kita dapatin ya...emang udah kita usahain. Bagus atau nggaknya tindakan kita.”
Emilia mengernyit. Bagus atau tidaknya?
“Percaya nggak, Mi, kalau kubilang aku beli tes seleksi tertulis Bina Pekerti?”
Mata Emilia membulat sempurna. Mulutnya membuka tanpa suara. Emilia kian gusar. Ada apa dengan Alvaro?
“Asli harganya mahal banget, Mi. Tapi aku butuh. Aku mau coba ngerjain tesnya sebelum ikut seleksi. Dan, Mi, aku nggak lulus. Soalnya susah gila! Aku sampai harus beli jasa orang buat mecahin jawabannya. Jadi emang bukan keberuntungan sih yang bikin aku bisa lolos Bina Pekerti. Usaha curang aku yang bikin aku berhasil, Mi. Kalau aku nggak ngelakuin itu, aku nggak bisa masuk Bina Pekerti. Orangtuaku bakal marah besar. Mereka nyeramahin aku yang nggak ikut seleksi SMA terbaik di sini. Karena aku tahu aku nggak bakal bisa. Makanya aku pilih Bina Pekerti. Dasar sial, Bina Pekerti aja tesnya bikin pengin bakar sesuatu.”
“Al-Alvaro?” Emilia tercekat. Ia hanya sanggup mengucap satu kata itu. Tangannya kian kuat menggenggam ponsel. Apa Alvaro sedang bercanda? Apa ia tengah berbohong? Atau, cowok itu sedang berkata yang sesungguhnya?
Panggilan Emilia tak ditanggapi selama beberapa saat, sebelum akhirnya tawa Alvaro pecah. Keras dan bertenaga.
“Kamu percaya, Mi?” sahut Alvaro. “Bercanda lagi.”
Emilia mengerjap. Isi kepala dan hatinya semrawut. Ia tidak berhadapan dengan Alvaro secara langsung detik ini, tapi berbicara dengannya lewat telepon sudah sanggup membuatnya kehabisan kata-kata.
“Eh, udah malam banget, Mi. Lupa waktu aku. Sori. Tidur, gih. Makasih ya udah ngeladenin omong kosongku. Bye, Mi.”
Sebelum Emilia sempat menanggapi, panggilan itu sudah keburu Alvaro akhiri. Tak lagi terdengar suara Alvaro beserta desahan berat napasnya. Emilia termenung, menurunkan tangannya dan menatap ponsel dengan bingung. Ia mencoba mencerna peristiwa ini.
Ini adalah pertama kalinya Alvaro menghubunginya larut malam. Kali pertama juga Alvaro berbicara tak seperti dirinya yang biasa. Apa memang segalanya seperti yang Alvaro katakan, bahwa ia sedang bercanda? Emilia melirik waktu. Nyaris pukul dua belas malam. Mungkinkah seseorang repot-repot terjaga hingga sekarang demi membohongi orang lain? Atau Alvaro melakukannya karena ia berada di ujung tebing dan membutuhkan seseorang?
Emilia menghirup udara kuat-kuat. Ia menyalakan ponselnya dengan tangan gemetar dan pucat, membuka kolom pesan singkat dengan Alvaro. Emilia terpaku. Apa yang harus dikirimnya? Isi kepalanya begitu penuh, dan dadanya sesak oleh desakan untuk menumpahkan segala yang ingin dikatakannya. Ia tahu Alvaro tidak berbohong. Ia memercayai ucapan Alvaro, juga suara hati Emilia yang berkata bahwa batin Alvaro sedang sengsara. Emilia ingin ada untuknya.
Emilia S
Al, kamu ingat nggak barang yang harus kita bawa pas hari terakhir MOS? Bunga mawar. Aku telat bangun, dan Mamaku ngebut banget nganterin aku ke sekolah. Tapi, waktu aku turun dari motor, bunga mawar yang kupegangi gundul. Kelopaknya habis kebawa angin. Aku langsung panik. Beneran panik. Mamaku juga ikutan bingung. Waktu itu masih jam setengah enam, nggak ada toko bunga yang buka. Aku udah pengin nangis, ngebayangin dihukum panitia yang ngeri-ngeri itu. Tapi aku nggak bisa ngelakuin apa-apa. Terus, kamu muncul, Al. Kamu nyamperin dan ngasihin bunga kamu ke aku. Aku bengong waktu itu. Kaget. Aku nggak mau bikin kamu dihukum gara-gara ngasihin bunga kamu ke aku. Tapi kamu santai banget. Nggak kelihatan panik. Kamu bilang, ‘Pakai aja. Tugas bawa bunga buat dikasihin ke orang. Aku udah ngasihin bunganya ke kamu.’ Aku masih ingat banget omongan kamu waktu itu, Al. Aku langsung mikir, kenapa kamu berani ngelakuin itu, padahal waktu sampai sekolah, kamu dimarahin habis-habisan sama panitia sampai nyuruh kamu squat jump dan keliling lapangan. Aku ngerasa bersalah banget. Tapi kamu malah senyum santai sama aku.
Mungkin kamu bingung. Tapi aku cuma pengin bilang. Menurutku, kualitas seseorang nggak ditentuin dari kepintarannya memecahkan soal, atau berapa kali dia dapat nilai sempurna. Tapi dari gimana dia hidup. Dan kamu hidup dengan bantuin orang lain, ngorbanin diri kamu sendiri padahal waktu itu kita belum saling kenal. Kamu udah jadi orang yang berkualitas tanpa harus dapat nilai 100.
Makasih udah bantuin aku. Makasih udah mau cerita sama aku. Maaf SMS-ku sepanjang ini sampai kebagi beberapa SMS. Met tidur.
Emilia membuang napas panjang. Ia meletakkan ponselnya di ranjang, mengusap wajah dengan kedua tangan yang masih gemetar. Emilia memejam. Matanya terasa panas. Desakan tangis membuatnya kewalahan, hingga pipinya sempat basah.
Selama ini, Alvaro tidak tahu bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan dulu pada Emilia telah menjadikan cowok itu seseorang yang selalu Emilia ingat. Emilia hanya sanggup berterima kasih, tak berani berujar atau berbuat lebih. Kini, kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya terpampang, membuatnya mengirim pesan sedemikian panjang agar Alvaro paham, bahwa dirinya berharga untuk seseorang tanpa embel-embel nilai sempurna.
Saat pemberitahuan bahwa semua pesan Emilia telah terkirim, ia berebah di ranjang, menggenggam ponselnya demi menunggu jawaban. Emilia gelisah dalam keheningan. Ponselnya lantas berdenting. Emilia terperanjat, membuka cepat.
Alvaro W
Emi... Kamu bikin perasaanku lebih baik. Thanks.
Sleep tight.
***
Ingatan itu membayangi benak Emilia sementara ia menyiapkan bekal untuk Alvaro. Ia sulit tidur semalam karena memikirkan cowok itu, menunggu balasan WAnya, menahan kantuk dengan belajar. Namun, Emilia tetap jatuh tertidur. Ia tersentak saat tiba-tiba terbangun dan melihat WA dari Alvaro. Pesan itu hanya berisi satu kata, yang sanggup mengembalikan Emilia pada ingatan masa lalu. Detik itu ia tahu ada yang tidak beres. Emilia mengirim balasan, meminta maaf karena terlambat membaca. Sayangnya, Alvaro tak lagi membalas WA Emilia. Ia bahkan tidak membacanya.
Setelah siap dengan bekalnya, Emilia membawa kedua kotak itu ke kamar, hendak mandi. Namun, dering ponselnya menahan langkah Emilia. Ia terperanjat dan menyambar ponsel di nakas. Jantungnya bertalu-talu memikirkan Alvaro menghubunginya. Tapi yang tertera di layar adalah nomor asing. Masih pukul lima subuh. Siapa yang menghubungi sepagi ini?
“Ha-halo?” Emilia menerima panggilan berbalut ragu.
“Emilia?”
Emilia mengerjap. Suara di ujung sana terdengar tak asing. Hal itu membuat Emilia kian gusar.
“Ya-ya?”
“Ini Mama Alvaro.”
Emilia menelan ludah dan menegang, tanpa sadar menahan napas. Ia pernah beberapa kali bertemu beliau saat Alvaro mengajaknya berkunjung ke rumah.
“O-oh, iya, Tante. Ada yang bisa saya bantu?”
“Alvaro ada di sana?”
“Eh?”
“Alvaro ada di sana?” Ibu Alvaro mengulang dengan nada tak sabar. “Suruh dia pulang. Punya masalah, keterlaluan kalau sampai nggak pulang, nggak ada kabar pula. Kamu juga seharusnya nggak nampung dia kalau kabur-kaburan dari rumah begini. Apalagi kamu perempuan. Gimana pandangan orang kalau membiarkan lawan jenis menginap di rumah. Suruh dia pulang. Bilang, orangtuanya mau bicara. Atau kamu berikan HP-nya ke Alvaro sekarang. Saya mau bicara langsung.”
Alih-alih melakukan hal yang diminta ibu Alvaro, Emilia tercenung dengan mulut menganga. Matanya mengerjap, tatapannya nanar. Alvaro nggak pulang? Emilia mencengkeram ponselnya, merasakan sergapan sesak di dadanya.
“Halo?”
Emilia tersentak. “I-iya, Tante. Maaf.”
“Kasihkan HP-nya ke Alvaro sekarang.”
Tangan Emilia gemetar. Punggungnya menghangat oleh kegamangan. Ia menelan ludah, merundukkan kepala. “Maaf, Tante. Tapi Al nggak ada di sini.”
“Nggak ada?”
“Al nggak datang ke rumah saya. Sa-saya pun nggak dapat kabar dia.” Begitu pengakuan itu terlontar, batin Emilia terasa semakin perih. Fakta bahwa Alvaro tidak pulang semalam dan tidak mengabari siapa pun termasuk orangtuanya dan Emilia, membuat Emilia panik. Al tidur di mana? Apa dia baik-baik aja?
“Saya sudah menghubungi semua kontak teman-temannya, dan nggak satu pun mengaku Alvaro di sana. Kamu pacarnya. Dia pasti lari ke kamu.”
Nyatanya, tidak. Bahkan, sekadar membalas WA Emilia pun, Alvaro tidak melakukannya. Cowok itu menghilang bagai tak membutuhkannya. Padahal, Emilia adalah kekasihnya, bukan? Kenapa Alvaro tak mengadu padanya? Kenapa Alvaro tidak bercerita padanya? Apa Emilia masih bisa menganggap dirinya pacar Alvaro?
“Maaf, Tante. Tapi, Alvaro nggak kemari.” Emilia berucap lirih. Ia mencengkeram sikunya kuat-kuat.
Terdengar desahan keras penuh jengah. “Kalau dia datang ke rumah kamu, langsung suruh pulang!”
“I-iya, Tante.”
Panggilan itu pun diakhiri sepihak oleh ibu Alvaro, menyisakan Emilia bersama ketakutan yang menguasainya. Selama mengenal Alvaro, tidak pernah ia dihubungi ibu cowok itu, terlebih dalam situasi seperti ini. Wanita yang telah melahirkan Alvaro itu sampai hati meyakini Emilia menampung Alvaro, artinya masalahnya tidak main-main.
Emilia kian menggigil. Ia sudah tak peduli waktu, tak berniat membasuh tubuh. Ia masih berdiri kaku di tempatnya, mencari kontak Alvaro untuk ia hubungi. Dalam keadaan normal, Emilia kerap dilanda gugup setiap kali berinisiatif menghubungi Alvaro lebih dulu. Namun, kuatnya desakan untuk bicara pada cowok itu berhasil membuat Emilia menekan call di nomor Alvaro. Ia menunggu dengan jantung berdentum keras. Panggilannya terhubung, tapi hingga nada tunggu berakhir, Alvaro tak menerimanya.
Al, kamu kenapa? Kamu di mana? Emilia mengusap wajahnya yang tegang dan dingin. Ia yakin warnanya hilang sempurna, karena kini ia bahkan merasakan bibirnya bergetar dan luar biasa kelu. Emilia mencoba menghubungi Alvaro sekali lagi. Hasilnya tetap sama. Jari Emilia lari ke WhatsApp, melihat last seen Alvaro. Masih pukul 23.15 sejak terakhir kali Emilia mengeceknya. Entah Alvaro yang tidak membuka wadah chat itu atau ia tidak memegang ponsel sama sekali.
Emilia S
Yang, di mana?
Melihat sejenak tanya itu, Emilia menyanggah kalimatnya sendiri. Jika ia menggelontarkan pertanyaan demikian, Alvaro akan langsung sadar Emilia tahu cowok itu tidak pulang. Yang Emilia inginkan adalah Alvaro bercerita padanya, bukan membuatnya kian menjaga jarak. Akan sulit bagi Emilia untuk membantu Alvaro jika kondisinya sudah seperti itu.
Emilia pun menghapus isi chat itu dan menggantinya dengan yang baru.
Emilia S
Yang, mau jemput?
Aku baru bangun. Hehe. Kalau pakai angkot pasti telat.
Sent. Meski kalimat itu tampak biasa, tapi jemari Emilia masih gemetar hebat. Ia berharap Alvaro lekas membacanya, dan mau bercerita pada Emilia. Jika tidak demikian, Emilia tidak tahu apa lagi yang mesti ia lakukan.
Sayangnya, hingga Emilia usai mandi dan bersiap berangkat, WA itu tak kunjung dibaca. Emilia mencengkeram tali paper bag dan memutuskan pergi. Posisi duduknya di dalam angkutan umum tak nyaman sama sekali. Ia ingin segera tiba di sekolah dan menemui Alvaro.
Begitu sampai, Emilia bergegas masuk ke area sekolah. Tempat yang ditujunya bukanlah kelasnya, melainkan kelas Alvaro. Namun, cowok itu rupanya belum datang.
Tidak biasanya Alvaro terlambat. Saat bel berbunyi, Emilia lekas ke lantai satu. Sepanjang pelajaran, ia tidak bisa berkonsentrasi, gelisah memikirkan Alvaro. Pesannya belum dibaca hingga sekarang. Seharusnya aku nggak ketiduran. Seandainya aku masih bangun, aku bisa ada buat Al.
Emilia mengulang penyesalan itu di benak hingga waktu istirahat tiba. Pamit pada Puspa, ia buru-buru keluar kelas sambil menenteng bekalnya. Tiba di depan kelas Alvaro, Emilia harus mendesah kecewa.
“Al nggak masuk?”
Raka yang semula menginformasikan hal itu, mengangguk lesu. “Nggak ada keterangan, Mi. Aku udah WA dia, tapi belum dibalas.”
Emillia mengernyit dalam. Ia serta-merta meraih ponselnya dari kantung rok, melihat Alvaro masih belum menghubunginya. Tangannya mulai gemetar. Ia memegangnya kuat-kuat, termasuk tali paper bag di tangan kirinya.
“Mi?”
Emilia tersentak. Ia mendongak menatap Raka. “Mama Al...nelepon kamu?”
Raka membenarkan. “Tapi dia nggak ke rumahku, Mi.”
Emilia tak henti-hentinya memikirkan keberadaan Alvaro sekarang. Rasa cemasnya begitu kuat hingga ia mulai merunut tempat-tempat yang kemungkinan akan Alvaro datangi. Jika tidak pada Raka, di rumah siapa cowok itu bertandang? Apakah salah satu teman lesnya? Tapi, bagaimana Emilia bisa mencari tahu? Ia bahkan tidak mengenal satu pun teman les Alvaro.
“Aku mau coba ke rumah dia sepulang sekolah nanti. Siapa tahu dia udah pulang.”
Gagasan itu membuat Emilia berharap. “Kabarin aku kalau kamu ketemu dia ya, Ka.”
Raka mengangguk seraya tersenyum menenangkan. “Kamu mau titip itu buat Al? Itu bekal, kan?”
“Eh? I-iya.” Emilia menyerahkan paper bag pada Raka. “Tolong, ya, Ka. Makasih sebelumnya.”
“Santai, Mi. Mudah-mudahan Al beneran ada di rumah. Atau setidaknya, dia bisa dihubungi. Aku kabari kamu nanti.”
Rencana itu terdengar mudah. Meski Emilia tidak tahu, hasil seperti apa yang akan Raka dan dirinya dapatkan nanti.


 zazahra
zazahra