19 September kamu datang bersama kejujuran mengatakan hal yang selama ini ternyata terpendam. Namun apalah yang bisa kita lakukan lagi setelah nasi sudah menjadi bubur, nyatanya perpisahan tetap berada di depan mata.
***
“LIKA!! ASTAGA SAYANG... UDAH JAM SETENGAH TUJUH DAN KAMU MASIH AJA TIDUR?! SEKOLAH LIKA ANDREA HIRATA!!”
Teriakan itu memaksaku membuka mata dengan berat, aku mengerjap menyesuaikan penglihatan ku dengan cahaya yang merambat masuk dari jendela. Hari sudah tampak terang sekali. Jam berapa sekarang?
“Enghh...” aku melenguh panjang, merenggangkan otot-ototku yang terasa kaku. Sementara Mama menarik jauh selimutku yang tadinya menutupi tubuh, tangan Mama bergerak menarik-narik kakiku. “Aduh, Ma, jangan usil dong, masih pagi ini Mama. Emang udah jam berapa sih sampai Mama ribut kayak gini?
Aku mengucek mata, masih mengantuk. Tadi malam aku tidur pukul setengah dua karena mengerjakan tugas yang sudah mepet dikumpulkan hari ini.
“Setengah tujuh, Lika!” seru Mama.
Mataku membelalak kaget, lalu meraih jam beker yang ada di nakas. Mataku semakin membulat saat melihat jam sudah menunjukan pukul 07.45, secepat kilat aku berlari masuk di kamar mandi. Memandikan tubuh ala mandi bebek, aku tidak punya banyak waktu untuk berleha-leha di kamar mandi.
Tak butuh waktu lama akhirnya aku sudah sampai di meja makan, menemukan seluruh anggota keluargaku tengah duduk menikmati sarapan mereka masing-masing. Aku melirik Kak Rigel yang bergerak meminum segelas susunya.
“Iya, kamu diantar sama Kakak. Tenang aja sih, emang udah gitu kan aturan mainnya,” kata Kak Rigel yang bangkit berdiri seraya merapikan bajunya.
Aku tersenyum dan mengangguk setuju, delapan bulan belakangan ini kehidupanku tak ada kemajuan. Tetap seperti itu dan monoton, diantar dan dijemput oleh Kak Rigel atau Kak Handi ke sekolah ataupun jalan-jalan ke mall dan semacamnya, kecuali aku berangkat dengan Retna dan teman-temanku yang lain. Juga, tetap dengan perasaan yang sama kepada orang yang sama dan setia memberi luka. Ah, sudahlah, tak ada gunanya aku mengungkit-ungkit hal yang sudah lewat.
“Kabar Tata gimana, Li?”
Gerakanku mengacak dashboard mobil Kak Rigel terhenti dan beralih menatapnya. “Kakak mau pindah ke Tata lagi? Udah bosen sama Retna? Iya? Tega banget sih kalo beneran Kakak kayak begitu,” semburku langsung terpancing karena pertanyaan Kak Rigel barusan.
“Ck,” decakan Kak Rigel tetap membuatku setia menatapnya. “nanya aja gak boleh. Posesif banget sih kamu, pantes Gilang gak mau. Tata kan pindah beberapa bulan lalu, masa kalian gak saling ngabarin, sih?”
Helaan napas kasar membuat tangan Kak Rigel terangkat mengusap rambutku. Aku menyergah, “Jangan bahas-bahas Gilang lagi. Aku capek mikirin dia, udahlah. Tata baik-baik aja, dia juga dapet kasih sayang cukup walau sama keluarga tirinya.”
Kak Rigel ber-oh ria, setelah itu tak ada lagi pembicaraan diantara kami hingga mobil Kak Rigel berhenti di depan pintu gerbang sekolahku. Setelah aku pamit masuk dan mencium punggung tangan Kak Rigel aku lalu masuk, berjalan dengan santai di koridor sekolah. Senyumku berubah getir, dari arah yang berlawanan aku melihat sepasang manusia tengah tertawa bahagia. Mereka tampak begitu serasi.
Gilang dan Seli yang berjalan bergandengan semakin mendekat dengan posisiku berdiri sekarang, aku memutar langkah berbalik berjalan di koridor menuju ke arah ruangan teater yang bisa membuatku terhindar dari pemandangan menyakitkan itu. Tidak menyakitkan, hanya saja sedikit sesak. Hari ini 19 September, ulang tahun Gilang yang ke 18. Tahun yang berbeda dari sebelumnya dimana dulu aku merayakannya bersama Gilang, mengatakan aku menyayanginya lalu membuat Gilang bergerak menjauh hingga kami berakhir sejauh bulan dengan bintang. Terlalu banyak perbedaan diantara kami sehingga kemungkinan bahagia bersamanya tidak akan pernah bisa aku cicipi.
Akhirnya aku sampai di kelas XI IPS-2 walaupun memakan banyak waktu karena harus memutar arah dan menunggu Gilang dan Seli berlalu dan menghilang dari pandangan baru aku bisa ke kelas. Di kelas, aku bertemu dengan Retna dan Dhanu lalu bergabung duduk diantara keduanya. Dhanu yang kocak mulai melempar leluconnya dan Retna ikut menimpali, sementara aku setia menertawakan kekonyolan keduanya.
Sekarang, setelah kepindahan Tata ke sekolah yang lain persahabatan kami menjadi berjarak. Sehingga entah seperti apa prosesnya aku dan Retna bisa bersahabat dan akrab dengan Dhanu.
Mereka yang berperan besar dalam kehidupanku belakangan ini, sedikit demi sedikit mereka bisa membuat aku benar-benar mengikhlaskan sesuatu yang memang bukan milikku.
***
Malam sudah menjelang namun mataku belum mengantuk dan tidak berniat tidur, aku masih setia berbaring di sofa-bed sambil menonton televisi yang menayangkan film horror. Entah kenapa aku tak merasa ketakutan dengan hantu yang wajahnya berdarah dan hancur tak beraturan itu.
Sekarang sudah pukul sebelas malam, berulang kali Kak Rigel masuk ke kamarku memeriksa apakah aku sudah tidur. Nyatanya aku tidak juga tertidur, akhirnya Kak Rigel menyerah dan kembali lagi ke kamarnya setelah gagal menyuruhku tidur.
Ponsel di samping kepalaku berbunyi tanda notifikasi pesan masuk, keningku berkerut dalam saat membaca pesan dari nomor tidak dikenal itu.
+6281317599001
Udah tidur?
Aku tak membalas pesannya, ponselku aku letakkan lagi di samping kepala dan aku kembali mengarahkan pandangan ke arah televisi. Ponselku kembali berbunyi, nomornya yang sama mengirimiku pesan lagi.
+6281317599001
Ini Gilang
Gue ada di balkon kamar lo, tolong buka pintunya dan temui gue.
Napasku tertahan, persendian di seluruh tubuhku terasa kaku, detak jantungku terlalu cepat memompa bahkan kepala sampai terasa pening setelah membaca dua pesan itu. Secara tidak sadar kepalaku menoleh ke arah pintu yang menghubungkan ruangan kamar dengan balkon, entah hal apa yang membuatku tiba-tiba kehilangan kendali sehingga sekarang sudah berdiri kaku membuka pintu balkon dan bersitatap dengan mata hitam yang sorotnya terasa sama dengan delapan bulan yang lalu.
“Hai, apa kabar?”
Air mataku tak mampu jatuh walau aku ingin membebaskannya, perasaan terkejut bercampur heran dan tak bisa dibohongi bahwa aku senang bisa menatap wajah Gilang secara dekat seperti ini. Rasanya ada bagian di dalam dadaku yang kembali terisi saat melihat sorot hangat dan senyum tulus Gilang yang mengembang di bibirnya.
Dengan susah payah aku menarik napas dalam, berusaha bernapas seperti baisa saja saat bertemu lagi dengan Gilang tengah malam seperti ini. Jujur dari hatiku yang paling dalam, aku merindukan sosoknya yang dulu hangat dan membuatku cinta hingga jatuh sampai detik ini.
“Baik,” jawabku akhirnya setelah sadar aku sudah cukup lama mendiamkan sapaan pertama Gilang untuk pertemuan kami.
Air mata yang tadinya tak bisa jatuh akhirnya luruh juga dengan begitu derasnya, ingin sekali aku melangkah maju memeluk dan mendekap Gilang menyalurkan seluruh kerinduan yang selama ini aku pendam. Namun aku menahan semuanya, banyangan wajah Seli teringat di benakku.
“A—ada apa datang ke sini?” tanyaku terbata, perasaanku benar-benar kacau sekarang ini.
“Gue kangen lo,” jawabnya enteng.
Aku menggigit bibirku dengan kuat tak perduli mau dia berdarah atau pecah sekalipun.
“Sudah? Kalo sudah gue tinggal masuk,” pungkasku cepat. Masuk lebih baik daripada aku tetap menyiksa hatiku dengan berdiri berhadapan cintaku di sini.
“Jangan menghindar kalo emang itu bikin lo sakit,”
Kalimat Gilang dan kedua tangannya yang memegang bahuku membuatku menegang bingung, selama ini apa ada yang menghindar? Bukannya Gilang sendiri yang memutuskan pergi? Baiklah, aku saja yang dalam posisi menghindar di sini. Mungkin Gilang sedang tidak ingin disalahkan.
“Gue mau ngomong semuanya sama lo, tolong dengerin sampai akhir,” sambung Gilang membuatku tak berkutik.
Aku hanya diam saat tangan Gilang bergerak turun mengusap punggung tanganku lalu perlahan jarinya yang besar mengisi sela-sela jariku. Dengan susah payah aku mengangkat kepala menatapnya beserta dengan mata yang sembab, tangan Gilang terangkat mengusap pipiku. Menghapus jejak air mata di sana.
Gilang menarikku untuk duduk dilantai dengan tangan yang masih menggenggam tanganku, senyum getir terukir pasrah dibibirku yang terasa kelu. Genggaman tangan Gilang masih hangat, hanya saja menjadi percuma karena dia berada pada pilihan yang berbeda dengan yang aku inginkan.
Aku membalas tatapan Gilang yang entah kenapa berubah sayu, entah kenapa aku melihat ada luka di sana.
“Hari ini lo harus tahu. 19 September di ulang tahun gue, gue akan jujur dengan semuanya. Bahwa gue...” Gilang menarik napasnya dalam. “sayang banget sama lo. Cinta banget sama lo. Kehilangan lo adalah kenyataan terakhir yang ingin gue terima di hidup gue. Jatuh cinta sama lo mudah, itu yang gue tahu.”
Tatapanku terarah ke depan dengan kosong, ada getaran luar biasa yang mengusai dadaku saat mendengar pernyataan Gilang barusan. Semua terdengar aneh bersamaan dengan kenyataan yang tersedia di depan mataku sekarang.
“Jangan pernah berpikir gue bahagia dengan jarak yang tercipta diantara kita selama lebih dari sembilan bulan ini, Li. Gue terlihat baik dihadapan semua orang, tapi gue mati dan merasa kosong dibalik semuanya. Lo alasan gue masih di sini, Lika,” lirihnya dengan suara teramat pelan. Nyaris menjadi bisikan.
Aku membekap mulut, menahan isakan yang mendesak keluar atas pernyataan yang baru lagi dari Gilang. Genggaman tangannya tak lepas dari tanganku, malah semakin mengerat.
“Jangan nangis. Gue udah cukup sakit melihat luka yang tercipta dari sorot mata lo. Tolong, untuk kali ini berhenti menyiksa gue dengan luka itu. Gue mau lo bahagia, Lika. Dengan atau tanpa gue.”
Deg! Seakan ada godam besar menimpa kepalaku sehingga membuatnya pening, ucapan Gilang kali ini mengejutkan. Siapa yang sebenarnya terluka di sini?
Pundak kiriku terasa berat, ternyata kepala Gilang bertumpu di sana. Entah sejak kapan kami mulai duduk berhadapan seperti ini dengan kedua tanganku yang digenggam erat oleh Gilang.
“Selama ini, gue sakit melihat keadaan lo gak sebaik yang dulu gue tahu. Gue gak baik-baik aja saat ngelihat lo jalan sama Felix malam tahun baru dan pelukan dibawah pesta kembang api, terlalu banyak waktu yang terbuang sia-sia di hidup gue pas lo pergi. Gue kacau, Li,” lirihnya. Aku menggigit bibir bawah menahan agar tanganku tidak bergerak memeluk Gilang.
“Apa maksud dari semua yang lo ucapakan ini? Siapa Seli?” tanyaku.
“Seli ... masa depan yang sudah ditakdirkan bersama gue,” jawabnya berat.


 yourex
yourex









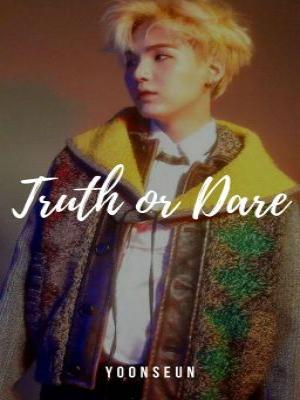

@penakertas_ paham kok wehehe
Comment on chapter Prolog