Ditemani gedung-gedung pencakar langit di sekelilingnya, Isabel berjalan pelan sambil mengecek e-mail di ponselnya. Sekelebat perasaan, mendadak saja ia merasa ada seseorang yang membuntutinya; nyatanya memang ada seorang pria bersetelan kantor berjalan tepat di belakangnya, terlihat begitu tergesa-gesa padahal saat itu hari masih terlalu dini dan gelap.
Isabel memang sering lupa, di mana ia menjejakkan kakinya sekarang. Di Manhattan, New York City, pergerakan manusia bisa dikatakan mengalahkan kecepatan waktu, dan ajaibnya bisa secara fisik ditukarkan dengan gulungan materi yang tak mengenal kata sejati. Begitulah penilaian Isabel yang sudah lima bulan lebih lamanya tinggal di kota itu, magang sebagai asisten penata gaya untuk Pinklist Magazine, majalah remaja yang baru empat tahun belakangan berdiri tapi cukup digandrungi. Yang didirikan secara mandiri oleh suami sahabat Mummy-nya.
Isabel sadar betul, bahwa pekerjaannya ia dapatkan bukan karena murni usahanya, tapi lebih pada koneksi. Maka, meski perannya yang melelahkan itu hanya digaji kecil, Isabel menjalani setiap harinya di tempat kerjanya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Bukan hanya untuk membuktikan bahwa ia memang layak dipekerjakan, tapi lebih pada dorongan dalam dirinya untuk memaknai titik balik kehidupannya.
Dan seperti biasa, jika ia pulang lembur pada dini hari atau jika ia sedang di luar rumah terlalu pagi, ia akan menyempatkan diri untuk mampir membeli sepotong croissant dan segelas kopi di Machbet & Moneta, toko roti langganannya. Setelah itu, bak sebuah ritual suci, ia akan mengarungi trotoar, berjalan satu blok dari toko roti itu supaya ia bisa memandangi etalase mungil toko perhiasan favoritnya, The Swannies.
Seperti Holly Golighly dengan Tiffany's-nya, Isabel telah menemukan kuil agungnya sendiri di trotoar halaman The Swannies. Meski toko itu tidak semewah Tiffany's dan hanya menjual perhiasan antik dari perak, tapi menurut Isabel tempat itu amatlah spesial. Terutama karena lambang angsa raksasa yang terpatri di pintu masuk toko itu mengingatkannya pada dirinya. Seekor angsa, julukan yang diberikan seseorang padanya.
Sambil melahap sarapan dan meneguk kopinya, Isabel memandangi bayangannya yang tipis terpantul di permukaan kaca jendela. Bukan salahnya kalau ia masih mengenakan T-Shirt bertuliskan Metallica, kardigan kebesaran, dan celana jins biru pudar. Setelannya yang kemarin. Ia tidak tahu kalau semalam akan jadi sesibuk itu sehingga ia dan timnya mendadak harus melemburkan diri.
Di tikungan blok, ia mencegat taksi guna pulang ke apartemennya di West 45th Street. Kini, ia tinggal di unit studio lantai tiga gedung kelabu di kawasan tersebut, berhadap-hadapan dengan unit milik sepasang suami-istri baik hati asal Fort Collins yang kerap membantunya, Ben dan Anna Cunning.
Usai membersihkan diri di kamar mandi, Isabel bermaksud untuk istirahat. Saat itulah pintunya diiketuk. Anna yang datang. Singkat cerita Anna memberitahu bahwa barusan ada seseorang yang menitipkan surat untuk Isabel padanya ketika Anna hendak masuk ke dalam gedung.
Setelah berterima kasih pada Anna dan menutup kembali pintu apartemennya, Isabel membuka lipatan kertas itu. Ia perlu mengucek matanya berkali-kali untuk meyakinkan diri bahwa memang benar itulah yang tertulis di sana.
Tanpa berpikir untuk mengganti pakaiannya, Isabel segera bergegas meninggalkan gedung apartemennya. Ia punya tempat mendesak untuk dituju.
Beberapa waktu kemudian, ia sudah sampai di lokasi yang dimaksud, sebuah taman umum di West 48th Street, terletak beberapa blok dari apartemennya. Namun, sejauh mata memandang, hanya orang-orang yang asing baginyalah yang berseliweran di sana. Saat itulah, mendadak saja, Isabel merasakan ada seseorang yang menyentuh pundaknya.
"Hey, are you Isabel?" sahut wanita berambut ikal padanya.
"Um, yes."
Wanita itu menyerahkan sepotong kertas yang terlipat pada Isabel. "Some guy just left this for you. He gave me twenty bucks just to wait for you here."
Isabel buru-buru membaca kertas itu. Sekali lagi, ia menarik napas sebelum kembali berjalan cepat. Kali ini, ia berhenti di depan sebuah kafe mungil bercat merah di 10th Ave, tak terlalu jauh dari taman sebelumnya, tempat yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Ketika ia masuk, pintu tersebut mendentingkan bel.
Pramusaji kafe itu menghampiri Isabel, memastikan hal yang sama dengan orang-orang sebelumnya, "Excuse me, are you Isabel?"
Isabel mengangguk. "Yeah."
"Please, have a seat," katanya dengan ramah. "And please wait here ten minutes."
Isabel merasa tak punya pilihan, meski hatinya dipenuhi perasaan meluap-luap.
Ketika Isabel sedang membaca ulang surat kedua yang ada di tangannya, alih-alih memberikan surat pramusaji tersebut malah menghidangkan seporsi Spaghetti Carbonara dan segelas es limun untuk Isabel.
Isabel yang merasa tidak memesan makanan itu langsung memprotes, "But I didn't order any of these."
" It's good. The guy suggested you should enjoy the food; everything has been paid and I have something for you when you finish," jawab pramusaji itu.
Isabel tidak lapar, tapi toh semua makanan itu ia habiskan dengan cepat. Tanpa menunggu makanan itu turun, Isabel segera memanggil pramusaji tersebut dan meminta haknya.
Di depan kafe itu, Isabel kembali membaca surat yang baru diterimanya. Lokasi berikutnya yang harus ia datangi, tertera di dalam lipatan kertas itu. Alasan Isabel memercayai isinya berasal dari Abriel adalah karena lambang angsa yang digambar cowok itu, angsa yang sama yang menjadi lambang di sampul komiknya. Buku yang tak pernah lepas dibaca Isabel setiap hari, sebelum ia terlelap, ketika ia gelisah, atau merindukannya. Buku itu, bukan hanya sekadar komik mengenai petualangan fantasi yang tercipta dari khayalan liar penciptanya saja, tapi juga terasa seperti bagian dari dirinya. Ia sadar, dengan sungguh-sungguh Abriel menciptakan Mazzy melewati jiwa dan pikirannya.
Bunyi klakson taksi yang marah karena sebuah mobil van berhenti mendadak di depannya membuyarkan lamunan Isabel. Tanpa menunggu lagi, Isabel kembali memacu langkahnya.
Dan, di sanalah ia sekarang. Di 9th Ave. Di depan toko besar yang terbagi menjadi beberapa area, menjual berbagai macam kostum hingga DVD film. Sesaat Isabel sempat meragu, sebelum ia mendorong pintunya yang terbuat dari kaca tebal dan berat.
Seperti si pramusaji, seorang karyawan otomatis menghampirnya dan tanpa banyak kata memberikan sepucuk surat dan sebuah buku.
Hati Isabel terasa dicubit. Ia mengenali buku itu. Itu adalah buku sketsa yang pernah dilihatnya dibawa cowok itu. Isabel mendahulikan membuka surat itu, hanya tertulis:
Hai, Angsa.
Kamu sudah hampir sampai di akhir. Barusan aku ajak kamu jalan-jalan sebentar. Maaf bikin kamu capek... dan mungkin kesal?
Dulu, untuk makan mie aja kita susah banget. Barusan, anggap aja aku duduk di sebelah kamu saat kamu makan spaghetti kamu. Kamu juga sempat jalan-jalan di taman, kan? Bayangin juga itulah first date kita. Dan kita ngobrol banyak di sana.
Untuk acara nonton kita yang sempat batal, boleh nggak kamu pilih satu DVD di toko itu. Dan setelahnya, kalau kamu nggak keberatan, saat nanti kamu nonton film itu, bayangin aku duduk di sebelah kamu.Tangan kita pegangan sampai akhir film, kepala kamu nyender di bahu aku kayak waktu perjalanan kita menuju Subang.
Tujuan terakhir, kamu mungkin harus naik taksi yang udah nunggu kamu di depan toko. Nama sopirnya, Abe. Sempurna, ya. Aku, Abriel. Kamu, Abel. Dan sopir yang akan nganterin kamu namanya Abe. Semoga hadiah terakhirnya, kamu suka.
Isabel pun memilih satu film dengan cepat: Fight Club. Saat ia sudah di luar toko, seorang pria tua yang mengaku bernama Abe langsung mempersilakannya masuk ke dalam taksinya. Perjalanan terasa menegangkan, karena Isabel tidak tahu kemana tujuannya. Ternyata hanya sedikit saja taksi itu melaju, Abe kembali membukakan pintu penumpang untuknya di depan bangunan ANHM yang megah dan mewah.
"What am I supposed to do here?" Isabel bertanya pada pria tua itu.
Pria itu mengangkat bahu. " The kid only told me to take you to this address. Try to wait and see, maybe he's somewhere waiting for you."
Isabel mengangguk sebelum berjalan menaiki satu demi satu hamparan tangga di sana. Tapi, tak ada tanda-tanda akan orang yang mengantarkan petunjuk lainnya. Ketika Isabel akan mencari tempat yang lebih teduh, seorang musisi jalanan yang dilihatnya duduk di dekat tangga terbawah menghampirinya.
"Isabel...?"
Isabel mengangguk. "You have a letter for me?"
Pria itu menggeleng. "I only got this." Pria itu mengulurkan beberapa tangkai bunga daisy yang beberapa kelopaknya terlihat sudah sedikit layu.
Isabel menerimanya, jantungnya berdegup lebih cepat.
"Did he tell you he's meeting me here?" tanya Isabel penuh harap.
Kali ini pria itu hanya memandanginya. Lalu tangannya sudah siap di atas gitarnya. "One song to cheer you up. Before he left, he asked me to tell you this: I hope you won't get mad because I'm not seeing you today."
* * *
Abriel menggeletakkan tas ranselnya di bawah meja belajarnya. Ia harus mandi setelah menempuh perjalanan selama seharian, pikirnya. Setelah mandi, seolah tidak lelah sama sekali, Abriel pun sudah duduk di meja belajarnya, mulai mengerjakan proyek komik lanjutan dari buku pertamanya yang sukses di pasaran.
Pada jam makan malam, sepenggal wajah adiknya muncul di ambang pintu yang sedikit terbuka.
"Kak, kata Mama makan, tuh," Jensen memberitahu.
Abriel menoleh. "Kakak makannya nyusul, ya. Perut Kakak masih kerasa nggak enak."
"Masih jet lag ya, Kak?" Jensen pun masuk menghampiri kakaknya itu. "Kakak seriusan ke New York, kok cuma tiga hari doang? Waktu Papa ke New York, lama banget... Kakak nginapnya di mana?"
"Di Manhattan, motel murah gitu," jawab Abriel. "Buat backpacker."
"Kakak jadi ketemu sama Kak Isabel?"
Abriel menggeleng. "Kakak nggak ketemu dia, Sen."
Jensen mengerutkan keningnya. "Bukannya Kakak ke sana mau ketemu dia?"
Abriel mengacak puncak kepala adiknya. "Penginnya sih gitu. Tapi kadang, untuk meraih sesuatu yang sangat berharga, kita harus sangat amat bersabar. Isabel bukan tipe yang akan happy dan terharu dengan surprise. Kalau Kakak tahu-tahu muncul di sana, mungkin yang ada dia cuma bakal kaget. Nggak akan ada maknanya."
"Lah, terus Kakak ngapain aja dong di sana?"
"Kasih kenangan. Dulu, waktu Isabel di sini, Kakak nggak sempat bikin hal-hal manis sama dia. Kakak sekarang berharapnya, dia senang sama hal-hal yang coba Kakak persiapkan buat dia, dan bukannya malah ngambek."
"Kalau Kakak nggak ketemu, Kakak nggak nyium dia dong."
Sebelum Abriel menjawab, mamanya menyela, "Apa sih kamu, Sen, anak kecil omongannya cium-cium."
"Eh, Mama..." Jensen menyeringai malu kepada mamanya sebelum ngacir karena malas dinasihati.
"Nanti El makannya nyusul aja ya, Ma. Lagi nanggung," pinta Abriel kepada mamanya.
Mamanya mengangguk. "Nggak apa-apa. Kamu pasti capek banget. Istirahat, ya. Papa baru pulang besok dari Cianjur, jadi makan malamnya nggak perlu di meja makan segala. Mama bilang Mbak ya biar bawain nasi ke sini."
"Makasih ya, Ma," ucap Abriel.
Pintu kamarnya kembali ditutup. Abriel melenguhkan napas panjang. Meski ia tampak tenang, sebetulnya hatinya berbebar-debar tak menentu.
Hari-harinya setelah itu, dilaluinya sambil menunggu harap-harap cemas kabar dari gadis itu. Tapi yang ditunggu tetap tidak muncul. Bahkan selang satu minggu kepulangannya dari New York, Abriel belum juga menerima kabar dari Isabel. Abriel jadi terus bertanya-tanya, apakah Isabel marah padanya karena Abriel tidak menemuinya di sana alih-alih merencanakan sesuatu yang awalnya terasa romantis dan genius namun setelah dipikirkan lagi terasa amat konyol?
Entahlah.
Hanya Isabel yang bisa menjelaskan...
* * *
"Gue udah bilang seratus kali, Dit, meski lo tajir, masih pedekate nggak perlu ngasih yang mahal-mahal gitu," Abriel mengingatkan sahabatnya itu dengan nada bosan. Sore itu, secara khusus Adit datang menjemput Abriel dengan satu misi penting: membantunya memilihkan hadiah yang sesuai untuk Ratih, gadis yang sedang dekat dengan Adit. Menurut Adit, kali ini ia menemukan gadis yang sangat mendekati kriteria gadis impiannya: cerdas, manis dan sama-sama mencintai dunia otomotif.
Adit tidak menggubris ucapan sahabatnya, dengan mata berbinar ia menatap jam tangan mahal yang sedang digenggamnya di sebuah konter di PVJ. "Yang ini cakep. Cocok banget buat dia," ujarnya mantap.
Abriel tak dapat mencegah lagi ketika Adit sudah membayar benda itu. Setelah nongkrong sebentar di sebuah kafe di sekitaran Ciburial, mereka pun memutuskan untuk pulang.
Jam menunjukkan pukul sembilan lewat beberapa menit ketika mobil Adit sampai di depan rumah Abriel. Adit langsung pamit. Mulanya, Abriel tidak melihat sesuatu yang berbeda. Tapi ketika ia akan masuk ke dalam rumahnya usai mobil Adit memutar dan menghilang, Abriel menyadari sesuatu: salah satu lampu menyala di rumah tetangga depannya itu.
Sesaat, hatinya terasa berhenti berdetak. Seperti aki yang kehilangan daya dan diisi kembali, segalanya lalu tiba-tiba menjelas, mengikuti koordinasi syaraf-syaraf otaknya yang kembali terhubung.
Abriel segera kembali ke luar halaman rumahnya, mengamati lekat-lekat cahaya itu, seleret cahaya dari celah gorden yang tidak menutup sempurna. Sebelum ia akan menyeberangi jalan, jendela itu terbuka, memunculkan satu sosok.
Gadis ramping berambut sebahu itu memandangi Abriel dari ambang jendela kamarnya.
"Bel?" panggil Abriel, suaranya masih tercekat. Sosok itu tidak mungkin mendengar panggilannya.
Bulan tampak menggantung rendah bagai permata di atasnya, Abriel maju satu langkah lagi.
Sosok itu membuat isyarat agar Abriel mengangkat teleponnya. Dengan kikuk, Abriel segera mengangkat panggilan itu. Panggilan dari nomor yang tidak tercatat di contact-nya.
"Halo?"
Abriel bisa melihat di atas sana, gadis itu juga meletakkan ponselnya di telinga.
"Hebat ya, kamu. Ke New York tanpa nemuin saya," protes suara itu langsung.
"Jadi aku nggak berfatamorgana," desah Abriel, lega. "Kamu di Bandung..."
"And, seriously, Elvis Presley?" tambah gadis itu sambil terkekeh.
Abriel menghela napas, lega. Itu benar-benar Isabel. "Can’t Help Falling in Love-nya Elvis adalah lagu legendaris, musisi itu nggak mungkin nggak hafal chord-nya, aku rasa."
"Oke," ujarnya setuju. "Well, walaupun nggak ketemu kamu, dengan semua itu, rasanya juga berkesan. Saya belum pernah dibuat penasaran kayak gitu. Dan ngos-ngosan."
Abriel menghela napas. "Bel, kamu turun, ya," pintanya. "Di sini. Dari tempat aku berdiri, kamu terlalu menyilaukan. Udah cukup aku disilaukan, nggak perlu bikin situasinya lebih dramatis lagi. Aku nyerah."
"El," panggil Isabel. "Waktu musisi itu mainin lagunya, sebenarnya saya nangis. Kemudian saya sadar, air mata hanyalah kata-kata yang tidak bisa diungkapkan hati. Seharusnya saya paham lebih awal. Idealisme itu nggak nyambung kalau disangkutin sama perasaan."
"Selama kamu nggak ada, aku pernah kepikiran buat nyerah melanjutkan komik. Tapi, aku sadar kalau aku berhenti itu bakal jadi akhir segalanya. Karena dengan Mazzy aku bisa tetap yakin, bahwa kamu itu nyata dan pernah ada. Bukan cuma khayalanku yang ketinggian."
"Bukan saya, tapi kamu sendiri yang mengenggam keyakinan itu sampai akhir. El, isi kepala kamu bisa stagnan, diam di tempat, seperti roda yang diberi rantai. Tapi tidak dengan setitik cahaya dalam diri kamu yang selalu meraba-raba rasa; biar di dalam penjara atau kotak besi, dia akan selalu bergerak, melayang atau melonjak. Hanya kamu yang bisa menyuruhmya diam. Tapi diamnya pun bisa kamu rasakan. Karena kamu itu tangguh. Dan saya bangga bisa jadi bagian semua itu." Isabel kemudian memutus sambungan teleponnya. Juga mematikan lampu di kamarnya. Tak lama, pintu depan rumahnya membuka.
Isabel berdiri di depan ambang pintu yang membuka itu, sendu ditatapnya Abriel, dan hangat Abriel balas tersenyum padanya;
Abriel, belum pernah melihat makhluk seindah itu. Dengan tatapan, yang lebih menyentuh dan sejati dari apa saja. Termasuk titik yang paling sentimentil dan dramatis, ketika membuat satu tokoh bernama Mazzy. Yang hidup di tangannya, di pikiran, pada setiap mata serta hati;
Isabel, belum pernah merasakan dadanya sekecut dan sepedih itu, menyesal membuang waktu terlalu lama untuk memahami perasaannya, menyingkirkan ego dan prasangka, mencoba untuk hanya jujur dan berdamai dengan ketakutannya.
Malam itu keduanya, kuat, saling menyatukan gelombang, dengan seiring, di permukaan; tak lagi ada pikiran-pikiran menggantung dan kata-kata mengambang. Tatapan itu akhirnya mengunci alam pikir dan bibir mereka.
TAMAT


 Andrafedya
Andrafedya











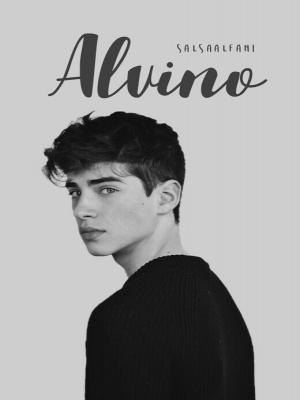



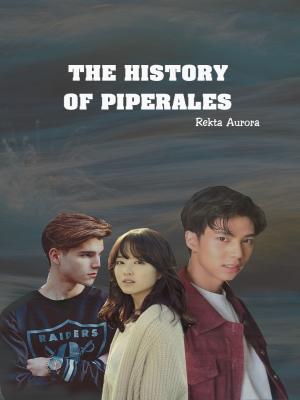
Teenlit namun lbh matang. Metropop namun tidak ngepop amat. Kadarnya pas, bakal lanjut membaca cerita cantik ini. Trims Author untuk cerita ini
Comment on chapter 1. Makhluk MalangKalau suda beres saya akan kasih review.