Di sekolah, selama lima hari berikutnya, Abriel duduk sendirian di kelas. Hingga lusa mendatang, Adit barulah diperbolehkan kembali menginjak sekolah. Itu termasuk keberuntungan yang patut disyukuri Adit, sebab ia urung dikeluarkan mengingat kesalahannya termasuk fatal.
Meski begitu, Abriel tidak mengetahui berita itu dari Adit langsung. Tomi-lah yang tahu-tahu menyampaikannya seolah ia berkewajiban menjadi penengah komunikasi kedua temannya yang tengah memanas dan merenggang. Dengan sungkan dan tak enak, Tomi pun menambahkan bahwa Adit memintanya secara khusus bertukar tempat duduk dengannya. Abriel langsung menerima usul itu. Ia tahu itulah yang terbaik dan diinginkan baik ia maupun Adit.
Abriel juga yakin, sedikit-banyak Adit telah bercerita pada Tomi mengenai masalah mereka.
Ingatannya masih jelas, ketegangan hari itu masih bisa dirasakannya. Lobi The Palm adalah tempat terakhir ia berbicara dengan sahabatnya itu. Sejak itu, komunikasi mereka seratus persen terputus.
Meski banyak hal buruk yang terjadi belakangan, Abriel tidak dapat berlama-lama larut dalam masalahnya. Karena try out terakhir untuk Ujian Nasional sudah hampir di depan mata. Hari-hari Abriel kini disibukkan dengan soal-soal latihan dan proyek komiknya yang perlahan namun pasti terus dikerjakannya. Ketika ia sedang jengah dengan soal-soal, proyeknya seolah menjadi oase yang kembali membuatnya bersemangat.
Alih-alih mengurung diri di kamarnya, kini Abriel lebih sering melakukan aktivitasnya di balkon lantai dua rumahnya. Duduk dengan kopi dan camilan buatan si Mbak tersaji di meja. Dan saat hujan turun mengguyur bumi, ia merasa idenya ikut menghujam kepalanya lebih deras bersama instrumen kedamaian yang diciptakan rintikan hujan.
Dari balkon itu jugalah, ia bisa memandangi jendela lantai atas rumah itu. Yang kadang terbuka, membiarkan segelintir hembusan angin menyusup masuk.
Pemuja senja itu masih sering dilihat Abriel, pergi dan pulang bersama pengantar-jemputnya yang setia: Adit.
Tak lagi Isabel datang dan pergi dengan orang asing. Sedikit, kenyataan itu membuatnya lega. Secuil yang lain, ia merasa sedih untuk dirinya. Ia cemburu, tentu saja. Tapi ia bisa apa? Isabel pantas didampingi seseorang yang lebih baik darinya.
* * *
Pada minggu berikutnya, Abriel sampai harus mengerutkan dahinya dalam-dalam ketika menatap layar ponselnya. Ketika itu ia baru saja pulang pelajaran tambahan dan hendak menggelar buku sketsanya di atas meja belajarnya.
"Halo," ragu-ragu ia menjawab panggilan itu.
"El!" sahut suara riang itu. Suara Irena. "Kamu lagi ngapain?"
"Mmm... Ini baru balik...," ujarnya setelah terdiam beberapa detik.
"El! Aku punya kabar penting nih buat kamu. Kemarin kan aku dateng ke acara syukuran tujuh bulanan tetehnya Sasa, di sana aku ketemu sama tantenya, kita nggak sengaja ngobrol-ngobrol gitu. Eh, nggak tahunya tantenya itu editor di Fixmedia, lho!"
"Maksud kamu Fixmedia penerbitan itu, Na?"
"Iya! Yang kantornya di Jakarta Pusat."
Abriel mendadak bersemangat, tertarik. "Terus, terus?"
"Terus aku ceritain tentang kamu. Yah, awalnya kayak nggak tertarik gitu soalnya komik memang bukan bagiannya Tante Asri. Tapi aku terus yakinin. Dapat deh kartu namanya," Irena meneruskan. "Tante Asri bersedia antar naskah komik kamu ke temennya yang memang bagiannya buku bergambar, termasuk komik. Kamu tahu komik Blink, kan? Nah itu juga terbitan Fixmedia."
"Serius kamu, Na?"
"Seriuslah."
Abriel tidak tahu harus berkata apa lagi.
"Terus, apa yang perlu aku siapin?"
"Gimana kalau aku main ke rumah kamu aja sekarang? Mumpung aku lagi nggak ada latihan."
Abriel menimang-nimang sebentar. Ada sesuatu yang berkecamuk di dadanya.
"Kamu mau aku jemput?"
"Nggak usah. Aku bakal diantar Andre. Tadi dia yang nawarin diri. Sebenarnya aku mau ngasih surprise, tapi rasanya nggak enak juga kalau tiba-tiba aku nongol di rumah kamu."
Napas lega terembus tanpa disengaja. "Lega kamu bisa baikan sama Andre, Na. Eh, jam berapa kamu mau ke sini?"
"Nih, aku lagi nunggu Andre jemput. Sekarang aku lagi di Pizza Country. Nanti aku take away meat addict-nya ya, buat ngerayain berita besar ini."
"Na, makasih banyak, ya... Makasih. Buat kabar baik ini dan pizza-nya," Abriel berkata sungguh-sungguh dari dalam hatinya yang paling dalam.
* * *
Isabel yang petang itu mengenakan gaun hitam panjang berkerah rendah dengan tiga lilitan choker menghias lehernya tampak sedang mengecek isi tasnya di halaman depan rumahnya, ketika ia menengadah, tepat saat pintu rumah tetangganya itu membuka.
Ia mengerjap. Dan mata itu balas menatapnya dari kejauhan. Awalnya hanya sepasang mata, lalu sepasang lagi, yang asing, muncul belakangan.
Mata asing itu milik gadis itu. Gadis dengan perawakan mungil, ramping, dengan rambut panjang yang dikucir tinggi dan kencang. Sosok manis yang memberi kesan dreamy. Menyusul, barulah Isabel sadar, itulah gadis yang datang bersama Abriel di resto tempo hari itu. Dan ia amat yakin bahwa gadis itu juga yang hari itu dibonceng Abriel.
Isabel tidak berniat untuk bereaksi, tapi entah mengapa kedua tangannya bergerak ke pinggang dan berkacak.
Setengah mati ia berusaha untuk menahan diri, tapi akhirnya gumpalan di tenggorokannya itu semakin menekannya.
"Hai, berduaan aja," Isabel menyapa dua sosok itu. Halus, suaranya sok-sokan direndahkan, berusaha terdengar kasual sekaligus ramah. Jelas sekali ia gagal mengupayakan imej santainya karena ekspresinya terlihat kaku dan kejam.
"Hei," balas Abriel, sungkan.
Gadis itu maju selangkah, wajahnya tampak polos berseri-seri. "Sorry, sorry, kalau kayak sok kenal, kamu Isabel, kan?" ia memastikan dengan ramah.
Isabel mengangkat alisnya, terkejut. "Iya. Kok tahu?"
Irena baru akan menjawab sebelum Abriel memotong ucapannya. "Kita duluan, ya."
"Okeee," balas Isabel, agak terlalu dipaksakan keceriaannya.
Isabel pun lalu hanya menjadi penonton ketika Abriel sibuk membukakan pintu mobilnya untuk gadis itu. Sebelum mereka benar-benar meninggalkannya dalam keadaan sangat menyedihkan seperti itu, Isabel melihat dari arah yang berlawanan mobil Adit sedang menuju ke arahnya.
Ia menarik napas lega. Kali ini Adit menyelamatkan wajahnya. Serta hatinya.
Dua mobil itu pun lalu saling berpapasan, tapi tak satupun kaca jendela yang turun untuk saling menyapa. Terbebat ego masing-masing, menyulap akrab jadi asing.
Ketika sudah di mobil Adit, Isabel langsung menanyakan hal yang mengganggunya pada Adit. "Saya nggak tahu hubungan kalian jadi kayak gitu. Kenapa kamu nggak pernah cerita sih, Dit?"
Adit mengangkat bahu. "See, kamu pun akhirnya harus menyerah sama ketololan dan keegoisan dia," desahnya dengan ekspresi serius.
Isabel menghela napas, memutuskan tidak lagi ingin mengatakan apa-apa lagi soal Abriel kepada Adit.
"Kamu mau dijemput jam berapa?" tanya Adit ketika membukakan pintu penumpang untuk Isabel di lahan parkir restoran bintang lima yang begitu ternama di Bandung.
"Dua jam lagi, gimana?" ujar Isabel. "Kamu nongkrong di mana aja dulu, okay?"
"Gampang." Adit melebarkan bibirnya meski hatinya kembali diliputi perasaan khawatir. "Kamu yakin kan setelah semuanya beres, kamu bakal berhenti?"
"Positive. Saya udah pikirin masak-masak, dan sepertinya memang sudah sampai target. Lagian, ada hal lain yang mau saya lakuin."
Adit menghela napas. "Kalau soal uang..."
"Duuh. Nggak, Dit. Kita kan udah sering bahas ini. Saya nggak bisa terima uang kamu. Lagian, ini bukan soal nominalnya, tapi maknanya," jelas Isabel.
"Besok, terakhir. Betul, kan?" Adit memastikan sekali lagi.
Isabel mengangguk. "Yang terakhir."
Adit pun meninggalkan tempat itu setelah Isabel masuk ke dalam. Ia sudah memutuskan untuk menunggu Isabel di bengkel yang jadi markasnya.
Meski dengan genggaman dalam kemudi, dan tatapan yang lurus ke depan. Otaknya tetap sibuk berpikir. Berputar dan berputar, seperti gasing. Sepanjang perjalanan ia mengatur rencana baru. Ia tidak menduga akan memakai kesempatan ini untuknya, karena sebelumnya ia nyaris tidak melihat ada kesempatannya. Tapi, hari ini membalikkan segalanya.
* * *
Waktu Yang Sama di Ibu Kota,
Empat orang gadis muda itu sedang asyik berbincang-bincang di sebuah kafe mewah di dalam salah satu mall ternama di Jakarta Selatan. Satu orang yang berambut panjang dan ikal yang sedang menyesap kopinya, yang sejak tadi tampak dominan di antara yang lain, merogoh ponsel yang terselip di antara dompet dan bedak padat dalam tasnya.
"Hold on," kata perempuan itu, meminta temannya yang baru akan mengomentari ceritanya untuk berhenti. "Fiz, gimana? Besok udah fix?" ujarnya ke ponselnya. Ia kemudian tampak mendengarkan dengan serius. "Beneran? Oke, oke. Gue sama yang lain abis ini langsung balik, kok. Kita ngopi bentaran doang. Udahnya, langsung siap-siap."
Setelah berbicara sebentar lagi, ia menutup sambungan telepon itu.
Temannya yang bernama Anna bertanya, "Afiz, ya? Gimana besok pasti, kan, Nes?"
"Iyalah," ujarnya seraya menyereput kembali minumannya. "Gue penasaran kemana dia ngilang selama ini. Gara-gara dia kan, kita dapat masalah..."
Temannya yang lain yang duduk berseberangan dengannya terkikik. "Gue memang nggak sekesal lo sama dia, tapi seru aja kali lihat dia lo balas."
"Dua minggu ngatur rencana ini, gue harap kali ini gue ancurin dia sampai ke tulang-tulangnya. Untung banget si Afiz nggak sengaja ketemu dia di Bandung, jadinya bisa kita lacak kan dia."
"Lo sama Jef niat banget sih sampe bisa ketemu gitu," komentar satu yang berambut pendek dan memakai jepit rambut mengilat.
"Waktu di Jakarta kan dia udah jadi pecun, terus dia ngilang, ya nggak susah setelah tahu dia di mana, lacak satu-satu situs yang mengarah ke dia. Cewek gila. Jual diri dia lewat Internet. Temennya Jef sama Afiz kan banyak yang bisa bantu," ujarnya. "Dampaknya kan bagus, girls. Kita jadi kumpul lagi, itung-itung reuni."
"Oke, gue akuin lo memang hebat," puji yang bernama Mariska. "Queen Bee always be queen bee."
"Pokoknya, kalian fix ya, ikut ke Bandung bareng gue," ujarnya, memandangi wajah teman-temannya satu per satu. "Kita kumpul di rumah gue jam sepuluh, biar nyampe hotel tengah malam, bisa seru-seruan bentaran."
"Satu pertanyaan," tambah yang bernama Anna. "Gimana andaikan gosip yang beredar itu bener. Kalau dia itu sempat depresi setelah malam itu..."
"Kalau dia memang depresi, ya dia nggak akan nerusin jual dirinya, dong. Yang ada dia tuh udah iris nadinya sendiri. Mati," potongnya lagi.
Refleks Anna dan Mariska saling melayangkan pandangan.
"Ngeri ah, ngomongin begituan. Serem. Gosipnya kan dia emang sempat nyoba ngiris tangan gitu. Katanya, sih... nggak tahu benar apa enggak," desah Anna.
"Alah." Dengan jengkel Nessa mengibaskan jemarinya. "Memang dia dari dulu udah aneh, stres, nggak jelas. Udah, ah—eh, gue minta bill, ya. Biar kita cepet cabut. Pokoknya, gue jamin besok bakalan seru."
Anna menghela napas. Entah mengapa ia merasa kali ini Nessa sedikit berlebihan. Meski begitu, Anna tidak bisa melewatkan keseruan yang dijanjikan Nessa padanya dan teman-temannya. Mungkin hanya sekali ini saja ia kembali menjadi domba pengikut Nessa, seperti ketika mereka satu sekolah dulu. Mungkin semuanya akan baik-baik saja... Sejak dulu Nessa selalu tahu caranya bersenang-senang, bukankah begitu?
Jauh, tak dapat dicegah pikiran terdalam Anna melengsak mundur ke masa lalu. Saat malam prom itu, saat Nessa menarik paksa gadis itu masuk ke dalam mobilnya. Membawanya dari hotel nan megah tempat anak-anak sekolah mereka menggelar acara prom night, ke sekolahnya. Gaun indah gadis itu tercabik-cabit oleh cuter, ponselnya tercerai-berai-segalanya tampak kacau dan menyedihkan. Kemudian, ketika Nessa merasa cukup puas, mereka meninggalkan gadis itu sendirian di sana.
Anna meringis dalam hatinya. Wajah gadis itu terbayang kembali di kepalanya. Sekilat, ketika Nessa menutup pintu hendak meninggalkan gadis itu, dari seleret cahaya yang masuk, Anna bisa melihat bahwa bibir gadis itu tertarik menyunggingkan senyuman. Senyumankah? Atau itu adalah kefrustasian dan keputusasaan yang membumbung melampaui batas sehingga membingungkannya?
Kali ini, bahunya bergidik sendiri. Meski udara di dalam kafe itu terasa hangat.
* * *
Adit mendadak mengubah tujuannya, ia membelokkan mobilnya di percabangan jalan, dan berbalik arah menuju Ciwalk, pusat perbelanjaan terdekat dari tempatnya. Setelah memarkirkan mobilnya secara valet, ia bergegas menyambangi toko perhiasan nan mewah di lantai satu.
Begitu ia mendapatkan apa yang diinginkan, ia kembali ke restoran tempat Isabel menemui kliennya. Meski ia datang beberapa waktu terlalu cepat, Adit tampak tidak keberatan sama sekali. Dengan setia ia menunggu di dalam mobilnya dengan stereo yang menyala.
Sebuah kalung cantik yang disangkutkan di dalam kotak beledu diangkatnya dengan perlahan. Dalam kepalanya, ia membayangkan kalung itu melingkar sempurna di leher jenjang Isabel yang cantik. Leher yang seindah milik angsa...
Anak itu tidak keliru menilai, Isabel memang menyerupai angsa, batinnya.
Ia mendadak memikirkan kembali rencananya ketika teringat eskpresi terakhir sahabatnya di The Palm saat itu. Haruskah ia memberikan anak itu satu lagi kesempatan?


 Andrafedya
Andrafedya













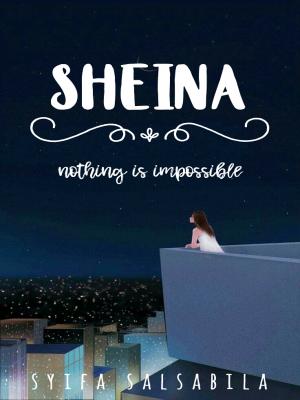
@shalsabillaa semoga ga mengecewakan ya, terima kasih banyak buat apresiasinya
Comment on chapter 1. Makhluk Malang