Abriel menghela napas sambil menatap kertas putih kosong melompong di meja belajarnya. Di samping kotak pensilnya, tergeletak sekotak bento yang belum dihabiskan, menyisakan dua ebi goreng yang tampak berminyak namun lezat.
Sudah empat jam ia memaksa kepalanya berimajinasi, tapi tak satupun ide yang sesuai dengan keinginannya muncul di sana. Abriel sadar, sejak ia menjalani harinya tanpa Irena, sulit baginya untuk melanjutkan komiknya. Ide-idenya hanya bertahan sekejap di kepalanya sebelum ia menepis ide-ide tersebut karena menurutnya dangkal dan kusut.
Dulu, ia berbagi semuanya dengan Irena. Jika ada bagian yang dirasa kurang sreg, Irena akan memberikan sentuhan untuk menghidupkan ceritanya hingga tak lagi kehilangan nyawa. Abriel selalu memercayai kritik dan pendapat Irena.
Denyut cerita, guratan halus pensilnya, dan napas tokoh-tokohnya, mereka berbagi segalanya...
Kini, tak ada lagi Irena yang memberinya jutaan inspirasi dan arahan. Tokoh-tokoh komiknya seperti hilang arah. Ceritanya tak jelas juntrungannya. Abriel bahkan lupa ke mana sebetulnya ia akan membawa "anak-anaknya" itu kelak. Irena membuatnya hilang panduan.
Namun, Abriel yang memiliki harga diri tinggi tak ingin mengakui bahwa semenjak hari itu ia tersesat. Jadi, meskipun sangat sulit, ia tetap meneruskan komiknya dengan merayap-rayap.
Ketika Abriel memutuskan untuk tidur dan berusaha memejamkan mata, untuk pertama kalinya Abriel kembali merasakan kehampaan panjang di ulu hatinya. Perasaan familier seperti yang dirasakannya berbulan-bulan lalu, perasaan yang membuatnya merasa bernapas di ruang angkasa, tanpa pakaian antariksa.
Abriel menduga-duga dalam benaknya, apakah ia akan sekarat karena kehabisan oksigen atau karena rasa kalut kronis yang melanda dadanya. Abriel mengambil gulingnya kemudian menutup kepalanya, seolah dengan begitu ia bisa berhenti memikirkan kejadian di lapangan tempo hari itu, saat ia melihat air mata Irena menggenangi dagunya...
Abriel tiba-tiba merasa sangat kehausan, tapi enggan untuk bangkit menelan seteguk air, padahal gelasnya begitu dekat dari tempat tidurnya. Begitulah Abriel, terkadang ia senang membuat perasaan seolah dirinya orang paling menderita di dunia ini. Terkadang, Irena juga berpendapat seperti itu tentang Abriel.
* * *
Di sekolah, orang-orang yang bertemu dengannya menyelamatinya karena ia berhasil melalui waktu skors yang diberikan kepala sekolah. Abriel hanya nyengir kepada mereka semua, berharap ia tidak menjadi pusat perhatian karena hal yang memalukan. Ia sudah berjanji kepada orangtuanya untuk tidak mengulangi perbuatannya, meskipun diam-diam dalam hatinya ia menambahkan kalaupun ia bolos sekolah lagi ia akan memastikan bahwa ia tidak akan terlibat masalah serius.
Pada jam istirahat, Abriel dan Febby sudah memisahkan diri dari murid-murid lain ke tempat Abriel biasa mengasingkan diri ketika ia ingin. Ruangan kosong itu dulunya adalah ruang sekretariat OSIS sebelum dipindahkan ke tempat yang lebih besar. Berhadapan dengan gudang tempat petugas kebersihan menyusun bangku-bangku yang akan diperbaiki. Ruang itu memiliki gang sempit dan buntu di belakangnya, yang kadang digunakan murid-murid yang senang melanggar peraturan untuk merokok atau membolos pelajaran. Namun, berkat kerjasama yang solid, ketika guru-guru datang menggerebek, tidak pernah berhasil menemukan seorang pun di sana.
Abriel menarikkan sebuah kursi dari dalam ruang penyimpanan keluar supaya Febby bisa duduk di sana. Menyedihkan memang, pikir Abriel, demi mendapatkan privasi dan menghindari mata-mata penasaran ia harus membawa Febby ke tempat yang selain agak kumuh tapi juga banyak nyamuknya. Tapi, apa boleh buat. Febby sepertinya sudah akan meledak sejak ia melihat Abriel di kelas tadi.
"Feb," Abriel memulai, sedari tadi mereka belum bicara apa-apa, Abriel bahkan belum menatap langsung ke mata Febby, "aku tahu kamu marah banget. Harusnya aku ngejar kamu hari itu, tapi entah kenapa aku nggak lakuin. Kalau kamu tanya kenapa, aku benar-benar nggak bisa jawab. Aku malu sama diri aku yang banyak salahnya sama kamu. Cuma, kamu harus percaya, aku beneran nggak aneh-aneh kayak apa yang Jensen bilang."
Febby melipat tangannya di dada. "Kita pacaran udah lima bulan tapi nggak tahu kenapa kayaknya kita nggak pernah bener-bener saling memahami, ya? Seolah kita berada di gelombang radio yang beda. Aku FM kamu di AM mana gitu. Kadang kita nyambung, tapi itu momen langka nyaris kayak keajaiban."
"Aku nggak bisa bilang apa-apa lagi sama kamu selain maaf, maafin sikap aku yang mengecewakan kamu terus. Sekarang semua keputusan ada di tangan kamu..."
"El, asal kamu tahu aja, aku suka sama kamu sejak kita kelas sepuluh. Mau seratus cowok yang nyatain sama aku, aku tetep tertariknya sama kamu. Muamar aja udah bilang rela lakuin apa aja yang aku minta, tapi aku cuma kegugah sama semua yang kamu lakuin. Awalnya, aku bahagia banget kita jadian. Tapi sekarang, kita malah kacau kayak gini..."
Abriel kehabisan kata-kata. Tapi anehnya, ia merasakan perasaan lain menyusul, menggelombang di dadanya melewati rasa bersalahnya. Lega. Abriel merasakan perasaan lega menjalari tubuhnya sekarang. Ia tahu kemana Febby akan membawa perkataannya.
"Masalahnya, walau kamu nyakitin aku, aku tetap nggak rela kita putus! El, ingat waktu aku ke rumah kamu lusa kemarin? Waktu kamu masih tidur, aku sengaja lihat-lihat buku gambar kamu, di sana ternyata nyelip fotonya Irena. Harusnya aku nggak kaget kamu masih nyimpan foto dia. Kamu bohong sama aku. Kamu belum bisa lupain dia."
Jadi, kemarahan Febby selama ini bukan gara-gara ucapan Jensen tempo hari itu.
Abriel menelan ludah, mengutuki kebodohannya. Ia ingat saat itu lagi-lagi imajinasinya tersumbat. Ia sengaja membongkar dus sepatu di mana ia meletakkan semua hal-hal yang berkaitan dengan Irena di sana. Dalam pikiran yang buntu, ia memungut sepotong foto dirinya sedang memeluk Irena. Mereka berdua tampak bahagia, dagu Abriel mendarat di puncak kepala Irena, sedangkan jemari Irena menggenggam jemarinya. Adit yang mengambil foto itu ketika mereka liburan ke Taman Safari dulu.
"Feb, dengar, aku nggak mungkin jadian sama kamu kalau aku belum—"
"Aku ngerasa goblok banget," potong Febby. "Harusnya aku nangis aja, biar lega and puas sekalian hari itu. Tapi masih aja aku pura-pura tegar. Itu yang malah bikin aku kelihatan menyedihkan banget."
Abriel merasakan bahunya merosot turun. Idiot macam apa dirinya yang tega menyakiti hati orang yang menyayanginya seperti itu. Selama ini ia selalu berpikir kalau Febby yang selalu memaksakan keinginannya, selalu egois dan keras hati. Tapi nyatanya, Febby-lah yang paling menderita dan tertekan dalam hubungan mereka.
Sudah saatnya ia berhenti menyakiti perasaan Febby. Sudah saatnya...
"Setelah aku pikirin, sebaiknya... kita putus aja, Feb," kata-kata itu keluar dari mulut Abriel seperti serbuan peluru.
"What?" Suara Febby terdengar tercekat. Ia bangkit berdiri.
Abriel menatap mata Febby, ia tidak akan mundur. Febby berhak mendapat kebahagiaannya.
"Hari ini aku sadar, sesadar-sadarnya kalau aku itu jahat sama kamu. Dan kamu pantas dapatin seseorang yang bisa memuliakan hati kamu." Sekilas terbayang Muamar di kepala Abriel.
Febby masih tampak tak percaya. Matanya membelalak, bukan karena marah, tapi karena frustasi. "Kemarin kamu hancurin hati aku, sebelum kamu betulin, malah mau kamu remukin sampai nggak bersisa? Apa kamu nggak punya sedikit aja nurani?"
Abriel mengangguk pelan. "Kalau aku berusaha pertahanin kamu, hanya kamu korbannya, karena hati aku nggak peka buat kamu. Aku minta maaf banget."
Air mata Febby akhirnya jatuh, bahunya bergetar, giginya terkunci rapat menahan isakan tangis. Abriel memalingkan wajahnya dari Febby. Deja vu. Ia ingat persis ketika ia mengatakan kalimat itu kepada Irena, Irena juga menangis sejadi-jadinya.
Bedanya, Irena menangis karena hatinya hancur, sedangkan Febby menangis karena harga dirinya yang hancur.
"Oke, aku ngerti," isak Febby. "Kamu balik gih sana sama dia. Nggak usah jadiin aku alibi buat memantapkan hati kamu untuk dia!"
Febby pun menghambur dan meninggalkan Abriel, tapi sebelum Febby jauh, Abriel mengejar dan menarik tangan Febby agar ia berhenti. Beberapa pasang mata mengamati mereka dari jendela ruang OSIS yang lebar dan tanpa gorden.
"Apa hebatnya sih dia sampai bikin kamu kayak gini?" bentak Febby.
Sekarang semakin banyak orang yang tertarik mendengar keributan mereka. Febby pergi sekali lagi meninggalkan Abriel.
"Kamu salah paham, ini murni tentang aku sama kamu. Aku cuma pengin kamu lebih bahagia. Sejak kita jadian, kamu jadi lebih pemarah. Kamu juga sadar sama hal itu, kan?"
"Bullshit! Kalau kamu emang pengin aku bahagia, tinggal kamu aja yang berubah buat aku. Tapi, emang kamu nggak niat sama hubungan ini." Febby masih terus berjalan cepat. "Selama lima bulan, bisa diitung pakai jari kamu ngeromantisin aku. Kissing sering, tapi selalu kamu duluan yang nyudahin. Aku sampai nanya-nanya sama diri aku, apa sebegitu mengecewakannya ciumanku? Tanda-tandanya memang udah ada dari dulu. Aku doang yang buta!"
Abriel berhasil menghentikan langkah Febby di pinggir lapangan basket yang ramai. Kali ini, ia pun tidak lagi menghiraukan tatapan-tatapan penasaran semua orang.
"Cukup, Feb. Aku yakin kamu sendiri sadar. Hampir tiap hari kita berantem. Pacaran itu seharusnya bikin kamu bahagia, bukannya bikin kamu jadi terus berharap untuk bisa ngubah aku jadi cowok perfect yang sesuai ekspektasi kamu."
Febby tidak mendengarkan perkataan Abriel, pikirannya sibuk menyatukan kepingan puzzle. "Aku tahu kamu putus sama Irena dipaksa bapaknya dia. Adit pernah kelepasan ngomong sama aku. Kamu jadian sama aku karena kamu nggak bisa sendiri aja, kan? Soalnya kalau kamu sendirian, kamu bakal terus kepikiran dia!" Febby kembali terisak-isak. "Lihat semua orang di sini. Ngelihat aku nangis kayak gini, pasti tahu kalau aku baru aja dicampakin sama kamu. Makasih buat kamu yang udah ngancurin aku sepenuhnya."
Abriel menyadari maksud Febby. Permainan basket di lapangan sudah resmi berhenti. Murid-murid yang tadinya nongkrong-nongkrong di depan kelas mereka dan duduk-duduk di taman mulai tertarik memerhatikan drama yang diciptakan dari isakan tangis Febby. Abriel merasa harus melakukan sesuatu demi menyelamatkan harga diri Febby.
"Tampar aku sekarang," perintah Abriel pada Febby.
"Apa maksud kamu?" Febby memelototi Abriel.
"Terus, kalau ada yang nanya, bilang kamu yang ambil keputusannya," tambah Abriel tanpa menggubris reaksi Febby lagi. "Karena aku ketahuan selingkuh."
"What—Oh, bagus, kamu sekarang bertingkah jadi pahlawan—klise, tahu!"
"Kalau kamu sayang sama diri kamu. Kalau kamu nggak mau harga diri kamu jatuh, tampar aku sekarang."
Sebagian murid mulai bersorak, berspekulasi mengenai pertengkaran Abriel dan Febby, pasangan yang paling serasi menurut pendapat mereka. Sisanya hanya menonton, berharap terjadi sesuatu yang menarik dan mengejutkan. Tentu saja pertengkaran mereka akan menjadi perhatian: yang cewek adalah gadis yang digadang-gadang paling ideal di sekolah; cantik, cerdas dan sulit dijangkau; cowoknya sepadan mendapatkan gadis selevel itu.
"Kalau kamu nggak lakuin, kamu bakal nyesel setelah semuanya nyebar nanti," Abriel mengingatkan Febby sekali lagi. "Feb—"
Alih-alih sebuah tamparan, tendangan yang dilayangkan Febby ke tulang kering kaki kanan Abriel begitu bernafsu. Seolah Febby melakukannya dari hati yang terdalam, mengeluarkan rasa sakit, frustasi, marah dan kecewa. Dan malu. Jadi satu tendangan yang begitu kuat. Abriel tidak menduga bahwa Febby akan menendangnya dengan sekeras itu. Tetapi, setidaknya sakit yang dirasakannya, pastilah tidak sesakit yang dialami hati Febby saat ini, batinnya. Abriel tahu ia layak mendapatkannya.


 Andrafedya
Andrafedya












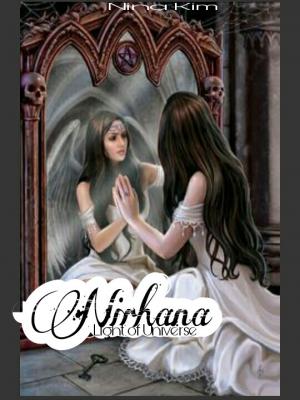



Teenlit namun lbh matang. Metropop namun tidak ngepop amat. Kadarnya pas, bakal lanjut membaca cerita cantik ini. Trims Author untuk cerita ini
Comment on chapter 1. Makhluk MalangKalau suda beres saya akan kasih review.