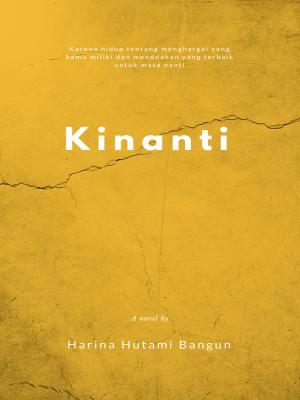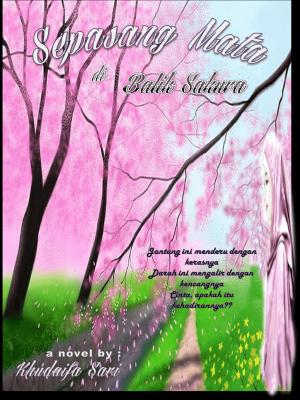Keesokan harinya, Amherst diselimuti kabut tebal. Jarak pandang hanya beberapa ratus meter, dan itu normal. Banyak orang yang masih tertidur pulas. Orang Amerika biasanya memang baru memulai aktivitas mereka pukul sembilan. Sekarang masih pukul enam kurang sedikit. Masih terlalu pagi untuk bangun. Andai pun sudah terbangun, mereka pasti memilih untuk tetap di rumah atau asrama mereka. Terlebih, di luar angin berembus cukup kencang. Pohon-pohon bergoyang ke kanan dan ke kiri, mengikuti sang bayu yang menerpanya. Suhu udara tercatat sekitar dua belas derajat Celcius. Tupai-tupai pun masih di sarang mereka untuk mencari kehangatan.
Andai perutnya tak keroncongan, Bara mungkin lebih memilih untuk berdiam diri di kamar, bersembunyi di bawah selimut tebal yang nyaman. Chai pun masih tidur pulas di kasur sebelah. Namun, jeritan lambungnya sudah tak dapat ditoleransi. Bara menyesal mengapa di acara penyambutan kemarin tidak mengambil makanan barang sedikit. Ia hanya makan dua buah kue kering ringan di meja resepsionis sepulang dari bistro. Sama sekali tak mengenyangkan. Bara pun memilih untuk turun ke lobi dan mencari makanan di sana.
Hotel UMass memang tak memiliki restoran sendiri. Tapi setiap pagi, sarapan sederhana—roti-rotian, bubur, dan telur—selalu tersedia di lobi. Jangan bayangkan sarapan di Amerika serupa dengan di Indonesia yang cenderung berat. Di sana, sepotong roti dengan secangkir kopi saja sudah cukup untuk jadi bahan bakar bekerja sampai siang. Namun, karena perut Bara made in Indonesia, ia menambah porsinya jadi lebih banyak. Dua potong roti bakar dengan selai blueberry, dua butir telur rebus, dan segelas susu. Kalau masih lapar, ia berencana mengambil bagel—roti berbentuk cincin yang sangat mirip dengan donat, meskipun bahan adonan, teknik pembuatan, dan cara penyajiannya sama sekali berbeda.
Bara menikmati sarapannya sambil menonton saluran berita CNN. Isi beritanya tentang badai Harvey, Irma, dan Maria yang melanda Florida, Puerto Riko, dan kawasan sekitarnya. Tiba-tiba, seseorang menyapanya.
“Hai, Tirta.”
Bara langsung menoleh. Ternyata itu Grace yang memakai kaos olah raga dengan bawahan celana training.
“Oh... hai, Grace,” Bara balas menyapa.
“Ternyata sepagi ini kamu sudah bangun, ya.”
“Iya nih. Kemarin malam aku nggak makan, makanya laper. Kamu mau ke mana, kok sporty banget?”
“Mau ke gym. Rugi banget kalau dapat fasilitas nge-gym gratis tapi nggak dimanfaatkan.”
UMass memang memiliki fasilitas olah raga yang sangat lengkap di Campus Recreation Center. Ada biaya bulanan jika ingin menjadi anggota. Namun, pengunjung hotel—termasuk para fellow—dapat menggunakannya secara gratis hanya dengan membawa selembar surat dari resepsionis.
“Kamu sendirian aja ke sana?”
“Nggak. Sama Raymond. Sambil nunggu anaknya turun, aku mau sarapan dulu.”
“Oh, begitu. Oke deh. Aku makan dulu ya.”
“Sip. Aku juga mau ambil bubur sama kopi dulu.”
Begitu Grace pergi untuk mengambil makanan, Bara buru-buru menyelesaikan sarapannya.
“By the way, kamu dapat salam dari Ignas,” tiba-tiba Grace sudah berada di sampingnya. Meletakkan mangkuk berisi bubur gandum yang dicampur walnut alias kenari dan kismis. Juga tak ketinggalan secangkir kopi hitam pekat tanpa gula.
Bara terkejut. “Hah? Ignas?”
“Iya. Ignas Jaya Marpaung. Berapa orang sih yang namanya Ignas?”
“...”
Bara pura-pura mengingat-ingat, walaupun sebenarnya ia tidak tahu siapa itu Ignas. Yang jelas, pasti anak itu kenalan Tirta.
“Duh, masak baru beberapa bulan udah lupa. Itu lho, delegasi UI di Pilmapres kemarin. Anaknya juara dua, tepat di bawahmu.”
“Oalaaah! ya...ya...ya, si Ignas itu ya, aku ingat sekarang. Titip salam buatnya ya.”
Titip salam adalah cara paling mudah untuk membuat kesan bahwa dirinya kenal dengan orang yang Grace maksud.
“Dia masih kerabat jauhku. Dia Marpaung, aku Napitupulu. You know lah, orang Batak punya marga-marga begitu. Aku kenalnya di perkumpulan anak Batak se-UI.”
“Ooo...”
“Kamu keren banget bisa ngalahin si Ignas. Dia itu orangnya outstanding lho. IPK 4,00, juara lomba di mana-mana, ke luar negeri udah kayak pergi ke pasar, dan rencananya dia nanti bakal ditarik jadi dosen di kampusnya kalo udah lulus. Pokoknya perfect deh! Makanya, dia biasa dipanggil Prof alias profesor. Kalau Ignas aja profesor, kamu pasti profesor kuadrat, ya? Hahaha...”
“Hahaha...”
Bara hanya bisa tertawa. Ia bingung harus ngomong apa. Ingin rasanya ia segera pergi demi menghindari obrolan-obrolan dengan Grace yang membuatnya tampak seperti orang bodoh—padahal ekspektasinya serupa dengan seorang profesor.
Sejurus kemudian Raymond datang dengan memakai outfit yang serupa dengan Grace.
“Hai, Grace!” sapa Raymond.
“Hai!” balas Grace.
Bara pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melahap roti bakarnya dalam satu suapan dan menghabiskan susunya dalam satu teguk.
“Ehm, Grace, Raymond... aku duluan ya.”
“Mau ke mana, Tirta? Kok buru-buru?” Raymond yang belum sempat menyapanya heran.
“Emm... si Chai minta dibangunkan jam setengah tujuh,” Bara berbohong. “See you!”
Bara langsung pergi mengabaikan segala prasangka yang mungkin ada di benak Grace dan Raymond. Ia tidak jadi mengambil bagel meskipun perutnya masih lapar. Ia memilih bersabar sampai jam 8 nanti, ketika The Lincolns janjian bertemu untuk sarapan bareng di kantin Worcester. Yang terpenting sekarang, dirinya bisa menghindar dari kedua anak itu—Grace yang tahu tentang Tirta dan Raymond yang bisa membuatnya minder.
Karena hari masih terlalu pagi untuk jalan-jalan, Bara kembali ke kamar. Ia ingin melengkapi catatan hariannya yang kemarin malam belum sempat ia selesaikan. Usai pesta penyambutan, Bara terlalu lelah untuk sekedar menggoreskan pena. Ia pun memutuskan untuk langsung tidur setelah mengganjal perutnya dengan dua keping kue kering.
Pukul delapan kurang lima menit, Bara turun ke lobi. Keempat anggota The Lincolns yang lain—Dev, Mai, Vin, dan Cheryl—sudah ada di sana. Mereka berlima langsung berangkat ke kantin Worcester dengan berjalan kaki sekitar tiga ratus meter ke arah timur laut.
Kabut tebal yang tadi pagi menyelimuti Amherst sudah hilang. Udara di luar mulai menghangat. Sang bayu memang masih mampu menggoyangkan ranting dan dahan, tapi ia sudah tak sanggup untuk menggugurkan dedaunan. Jalanan mulai ramai dengan mahasiswa yang melintas dari dan ke berbagai arah. Ada yang jalan kaki, ada yang memakai skateboard, ada juga yang naik skuter manual. Bahkan, tupai-tupai pun mulai keluar untuk mencari penghidupan.
Kantin Worcester punya dua pintu. Pintu barat adalah akses masuk ke bagian masakan Asia, sementara pintu timur adalah akses masuk ke bagian masakan Barat. Kedua bagian itu tersambung oleh sebuah lorong pendek berdinding kaca tebal. Dari lorong itu, para pengunjung bisa berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain tanpa harus menggesek meal card mereka lagi.
The Lincolns masuk lewat sayap barat, bagian masakan Asia. Hari itu, menu utamanya adalah pho, makanan khas Vietnam mirip bihun rebus isi tahu putih tetapi dengan rasa jahe yang lebih kuat di kuahnya. Mai yang sudah rindu masakan dari kampung halamannya langsung ikut mengantre di soup station. Sementara itu, Bara malah pergi ke sayap timur kantin untuk mengambil pasta dengan saus daging. Ia masih penasaran dengan makanan Barat dan belum tertarik makan masakan Asia. Ketiga teman mereka berpencar untuk mengambil makanan yang mereka inginkan. Setelah mendapatkannya, mereka semua berkumpul di sebuah meja yang tak jauh dari halal station di sudut ruangan.
“Jadi, apa rencana kita?” tanya Cheryl tiba-tiba saat yang lain sedang menikmati santapan mereka.
“Rencana apa?” tanya Dev sambil menyendok nasi karinya.
“Bukankah kita berkumpul untuk membicarakan tugas pertama?”
“Ya. Tapi, tak bisakah kau menunggu sampai kita selesai makan?”
“Astaga, Dev, aku sudah menunggu semalaman. Kau tahu, begitu ada email masuk dari Leia, Jessica teman sekamarku langsung mengajak seluruh anggota Jefferson berkumpul.”
“Jessica dari Malaysia?”
“Siapa lagi kalau bukan dia?”
“Jefferson, ya? Pantas Fee kemarin malam keluar kamar,” celetuk Mai. Fee adalah teman sekamarnya.
“Nah, kau juga tahu kan, Mai.”
“Jika kau bisa menunggu semalaman, kenapa sekarang tak bisa menunggu beberapa menit?” ujar Dev tidak mau kalah. Ia terus menikmati makanannya.
Cheryl geram melihat Dev. Apa salahnya sih diskusi sambil makan? Begitu pikirnya. Ia berharap seseorang membelanya.
“Bagaimana menurutmu.... Tirta?” tanya Cheryl.
Bara tak mendengar pertanyaan itu. Ia sibuk melahap sepiring besar pasta di hadapannya.
“Tirta?!”
Bara baru mendengar panggilan itu.
“Ah, ya?” Bara yang terkejut tak jadi memasukkan pasta ke mulutnya.
“Lihatlah. Tirta pun perlu menghabiskan makanannya terlebih dulu,” ujar Dev.
“Sorry, aku sangat lapar. Kemarin malam tidak sempat makan.”
“Ah, sudahlah. Kalian sama saja!” Cheryl merasa diabaikan.
“Mmm... Cheryl, aku sudah selesai,” kata Mai setelah meletakkan sendoknya di mangkuk yang sudah kosong. “Kau ingin memulainya dari mana?”
“Thanks, Mai. Kau memang pengertian,” ucap Cheryl.
Cheryl lalu membuka ponselnya. Ia membaca ulang email dari Leia yang dikirim ke semua fellow kemarin malam. Para fellow diinstruksikan untuk segera login ke Blackboard, sebuah media pembelajaran daring yang digunakan di UMass, menggunakan akun dan kata sandi yang telah dikirim ke email masing-masing. Di Blackboard, pengguna bisa mengunduh materi, mengunggah penugasan, menonton video, melihat jadwal, dan menulis di blog yang bisa tersambung dengan media sosial masing-masing. Setelah login, instruksi berikutnya adalah membentuk grup belajar sesuai kelompok. Lewat grup itulah tugas pertama harus diunggah.
Di antara lima anggota The Lincolns, hanya Cheryl yang memiliki dokumen penugasan itu di ponselnya. Ia sudah mengunduh dokumen itu langsung setelah masuk ke inbox-nya kemarin malam memakai Wi-Fi hotel, lalu membaca dan memahaminya, sampai berinisiatif membuat grup The Lincolns dan mengundang teman-temannya sarapan bersama pagi ini sebagai tindak lanjut. Cheryl bukan tipe orang yang suka menunda pekerjaan.
“Dan, tugas pertamanya adalah.....?” tanya Vin setelah dua gulung sushinya habis.
“Membuat proposal social project berdasarkan masalah di sekitar kita. Pertama, masalah di Asia Tenggara. Kedua, masalah di Amerika. Jadi ada dua dokumen yang harus dikumpulkan.”
“Kapan batas waktunya?” tanya Mai.
“Malam ini pukul sembilan tepat.”
“Whatt??!” Dev, yang sejak tadi santai, terkejut mendengar berita itu.
“Itulah mengapa aku mengajak kalian segera membahasnya!”
“Apakah grup belajar di Blackboard harus dibuat dulu?” tanya Vin.
“Tidak,” jawab Cheryl. “Itu terakhir saja. Lagi pula, kita tidak punya akses internet sekarang.”
“Jadi, selanjutnya bagaimana?”
“Kita bicarakan project apa yang akan kita kerjakan. Lalu, setelah kembali ke hotel, kita langsung buat grup. Bagaimana?”
“Aku sepakat,” kata Mai.
“Oke kalau begitu,” ujar Vin.
“Dev?”
“Agar lebih efektif, bagaimana kalau kita bagi tugas?”
“Bisa dipertimbangkan. Tirta?”
“Aku ikut saja.”
“Kau tak ingin memberi pendapat?”
“Untuk saat ini, tidak. Terima kasih.”
“Serius?”
“Ya.”
“Mmmm... Baiklah. Jadi, begini...”
Cheryl langsung mengambil alih forum. Ia paparkan ide-ide yang sejak semalam sudah bersemayam di benaknya. Meskipun selama ini ia kurang disukai orang karena sikapnya yang kurang ramah dan sedikit cerewet, ia menutupi semua itu dengan kinerjanya yang menjanjikan.
Seperti usulan Dev, Cheryl membagi The Lincolns menjadi dua kelompok sesuai preferensi masing-masing. Mai, Dev, dan Vin mengurus proposal untuk masalah Asia Tenggara, sementara dirinya dan ‘Tirta’ mengurus masalah Amerika.
Kedua kelompok langsung melakukan brainstorming ide. Kira-kira masalah apa yang cukup penting untuk diselesaikan, dan apa solusi yang bisa ditawarkan? Sekitar tiga puluh menit berdiskusi, mereka sudah mendapatkan beberapa alternatif. Namun, karena Worcester semakin ramai, dan banyak pengunjung yang mencari kursi kosong, mereka memutuskan untuk melanjutkan diskusi di hotel. Mereka pun langsung membawa piring dan gelas mereka ke bagian dish return.
Saat hendak keluar, tiba-tiba Cheryl memanggil Bara yang sudah beberapa langkah di depan bersama ketiga temannya yang lain.
“Tirta!”
Bara berhenti di tangga turun tepat sebelum pintu. Mai, Dev, dan Vin sudah keluar.
“Ya?”
“Tunggu aku!” teriak Cheryl sambil bergegas menyusul Bara.
Bara menunggunya tanpa prasangka. Mereka berdua lalu berjalan berdampingan menuju hotel.
“Bagaimana kabarmu?” tanya Cheryl.
Pertanyaan yang aneh untuk dilontarkan setelah sekitar satu jam mereka bersama.
“Seperti yang kau lihat. Aku baik-baik saja.”
“Baguslah.”
“Ada apa, Cheryl?” tanya Bara polos.
Langkah Cheryl berhenti mendadak. Tentu Bara terkejut. Apalagi setelah melihat ekspresi wajah Cheryl yang berubah.
“Ada yang salah?” Bara sedikit bingung.
Cheryl kembali berjalan dengan langkah yang lebih cepat. Bara agak kesulitan untuk mengimbangi langkahnya.
“Cheryl, ada yang salah?” Bara mengulang pertanyaannya.
“Tidak,” jawabnya dengan senyum sedikit dipaksakan. Ia sama sekali tak menoleh ke Bara dan terus menatap ke depan.
Pertanyaan itu membuat langkah Cheryl semakin cepat. Bahkan, di depan gedung UMass Press, ia bisa menyalip Dev, Mai, dan Vin tanpa sekalipun menoleh. Mereka bertiga pun heran dengan tingkah Cheryl.
“Ada apa?” tanya Mai ke Bara yang datang dari belakang.
Bara menggeleng. “Aku tidak tahu.”
“Mau menstruasi mungkin,” celetuk Dev.
“Mungkin,” Vin ikut-ikutan.
Mereka berdua langsung mendapatkan timbukan pelan di lengan dari Mai.
Buk!!
“Aww!!”
Mai dan Bara langsung mengejar Cheryl, meninggalkan Dev dan Vin yang masih kebingungan. Sayangnya, langkah Cheryl terlalu cepat untuk dikejar Mai dan Bara. Begitu masuk Campus Center, dirinya menghilang entah ke mana. Anak itu pasti sembunyi di suatu tempat.
“Apa yang sebenarnya terjadi?” tanya Mai penasaran.
“Aku benar-benar tidak tahu,” jawab Bara yang masih ngos-ngosan. “Dia bertanya kepadaku, ‘apa kabar?’, lalu saat kujawab ekspresinya sudah berubah.”
“Aneh.”
“Ya, sangat aneh.”
Setelah dialog singkat itu, Dev dan Vin menyusul mereka masuk ke Campus Center yang cukup ramai.
“Di mana Cheryl?” tanya Dev.
“Kalau kami tahu di mana dia, kami takkan berdiri di sini, Dev,” jawab Mai.
“Oh, oke. Jadi, bagaimana kelanjutan diskusinya?”
“Kalian pergi ke lobi saja,” kata Bara, “aku akan mencoba mencari di kamarnya. Aku menduga dia lewat tangga darurat untuk pergi ke lantai tujuh.”
“Biar aku saja, Tirta,” Mai menawarkan. “Mungkin ada sesuatu yang membuatnya kurang nyaman. Kau dan Dev dan Vin, pergi saja ke lobi.”
Sesuatu yang membuatnya kurang nyaman? Bara berpikir keras.
“Itu terdengar lebih realistis,” ujar Dev. “Ayo, jangan buang waktu.”
Mereka berempat pun langsung naik lift. Bara, Dev, dan Vin turun di lantai tiga untuk ke lobi hotel, sementara Mai bablas ke lantai tujuh menuju kamar Cheryl. Sebenarnya, Mai tidak tahu kamar Cheryl nomor berapa. Tapi, karena tadi dia bilang sekamar dengan Jessica, Mai menduga mungkin nomor 701. Semalam, ia pulang bersama delegasi Malaysia itu dan melihatnya masuk ke kamar tersebut.
Saat mengetuknya, ada seseorang menjawab dari dalam. Suara laki-laki. Ternyata yang keluar Lee, delegasi Singapura.
“Oh, kau, Mai. Ada apa?”
“Maaf, Lee. Aku mencari Cheryl. Kukira ini kamarnya dan Jessica.”
“Kamarnya nomor 703. Ini adalah kamarku dan Thu.”
“Oke. Thanks.”
Setelah Lee menutup pintunya, Mai langsung beralih ke kamar nomor 703 dan mengetuknya. Tidak ada jawaban. Kalaupun Cheryl ada di dalam, mungkin ia sedang tidak mau ditemui siapapun. Mai kembali ke lobi dan bergabung dengan anggota The Lincolns yang lain. Ia terlebih dulu pergi ke kamarnya untuk mengambil laptop yang barangkali dibutuhkan.
“Bagaimana?” tanya Bara begitu melihat Mai datang.
“Dia tidak ada di kamarnya,” jawab Mai.
“Jadi, bagaimana dengan proposalnya?” Dev tidak begitu peduli dengan Cheryl. Ia lebih peduli pada deadline tugas mereka yang mepet.
“Aku bawa laptop. Kita bisa langsung mengerjakannya.”
“Oke.”
Mereka berempat kembali berdiskusi soal proposal yang harus mereka selesaikan malam ini. Kini dengan formasi yang sedikit berubah. Mai membantu Bara setelah Cheryl tak lagi bersama mereka. Dev dan Vin meneruskan diskusi mereka sebelumnya.
“Menurutmu, ada apa dengan Cheryl?” tanya Bara sedikit khawatir.
“Aku juga tidak tahu. Tapi untuk sementara ini sebaiknya kita fokus pada tugas dulu,” jawab Mai. “Kau tak perlu khawatir, Tirta. Aku yakin Cheryl akan baik-baik saja.”
Bara tersenyum. “Terima kasih, Mai.” []


 gadingaurizki
gadingaurizki