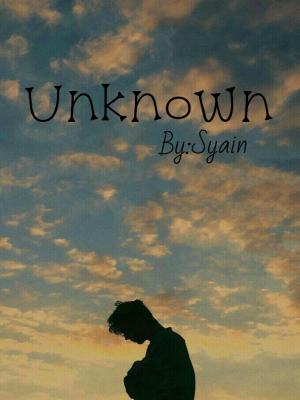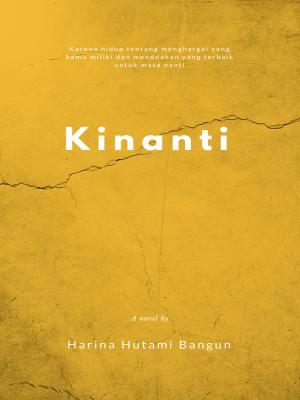Bara mendengarkan sambutan Bill dengan dada bergemuruh. Ia akhirnya sadar kalau program ini bukanlah ajang main-main. Ia kembali bertanya dalam hati, sebenarnya apa tujuannya berangkat ke Amerika? Apakah hanya untuk membuktikan diri? Kalau iya, pembuktian diri macam apa itu? Alih-alih menunjukkan kalau ia berprestasi, justru akan terlihat kalau dia orang yang oportunis. Sampai tega memanfaatkan musibah yang menimpa saudaranya hanya demi memenuhi ambisinya semata.
Namun, ia juga sadar kalau pemikiran seperti itu tidak ada gunanya. Ia sudah terlanjur berada di Amerika. Tidak mungkin dia kembali ke Indonesia tanpa membawa apa-apa. Satu-satunya jalan adalah terus maju dan meraih sesuatu.
Bara kembali terngiang kalimat sambutan Bill. “Setiap prestasi akan diapresiasi. Setiap pencapaian akan diberi penghargaan. Di farewell party nanti, kita akan tahu apa yang telah kalian raih dan dapatkan.”
“Aku harus meraih sesuatu!” gumam Bara penuh tekad. “Tapi apa?” Disusul keraguan yang masih menyelimuti pikirannya.
Pertentangan antara tekad dan keraguan itu membuat perasaannya campur aduk. Tangannya menjadi sedingin es. Jantungnya berdetak cepat. Hembusan nafasnya mulai tak teratur. Lagi-lagi, ia perlu waktu untuk menenangkan diri. Ketika yang lain sudah pergi mengambil makanan, ia masih tetap duduk di kursi. Ia merasa belum siap untuk berinteraksi dengan siapapun.
“Kau tak mengambil makanan?” tanya Chai yang datang membawa sepiring spageti dan segelas jus apel.
“Antrean masih panjang,” Bara beralasan.
“Oh, oke. Kalau begitu aku makan duluan.”
“Enjoy your meal, Chai.”
Chai langsung menyantap spagetinya. Tak lama setelah itu, beberapa fellow berdatangan ke meja mereka membawa makanan masing-masing. Meja pun menjadi ramai. Saat itulah Bara memutuskan untuk pergi.
Bara mengambil segelas jus jeruk dan membawanya ke sofa di sudut ruangan. Di sana, ia duduk santai sembari mengamati seisi aula. Ia mencari sosok Mai. Gadis itu sedang berswafoto dengan beberapa fellow, termasuk Brian teman senegaranya. Mai tampak begitu anggun. Ia memakai baju panjang berbahan sutra khas Tiongkok dengan warna peach motif bunga sakura. Rambutnya digelung. Wajahnya diberi riasan tipis, mulai lipstik hingga blush on kemerahan. Penampilannya berbeda seratus delapan puluh derajat dengan kesehariannya yang sporty.
Tengah asyik memandang Mai dari jauh, seseorang menegur Bara.
“Sepertinya kau enggan berbaur?”
Ternyata itu Bill. Dari tadi ia memang berpindah-pindah dari satu sudut ke sudut lain agar bisa berinteraksi dengan seluruh fellow tanpa terkecuali.
Bara terperanjat. Ia tidak menyadari keberadaan pria itu.
“Ah, tidak. Aku baik-baik saja, Bill,” Bara berkilah. Ia tidak mau siapapun tahu apa yang sedang dipikirkannya.
“Apakah kau keberatan jika aku duduk di sini?”
“Tentu saja tidak.” Mustahil Bara menolak permintaan duduk bersama dari seorang direktur program.
“Apakah kau menyadari kalau gaya hidup anak-anak Filipina sudah seperti orang Amerika kebanyakan? Setidaknya itu yang kusimpulkan dari beberapa kali perjumpaanku dengan mereka.”
Bara tak tahu mengapa Bill menyampaikan hal itu. Mungkin ia sedang berbasa-basi untuk memulai pembicaraan.
“Ya, sepertinya begitu,” jawab Bara.
“Kau pernah bertemu orang Filipina sebelumnya?”
Bara terdiam sejenak. Ia berpikir keras, apakah akan menggunakan sudut pandangnya sendiri atau sudut pandang Tirta? Dalam obrolan seperti ini, ia harus pandai memposisikan diri. Kalau tidak, orang-orang bisa curiga.
“Pernah,” jawab Bara. Ia ingat, Tirta pernah bercerita tentang teman-teman Filipino-nya yang suka berpesta pora dan hobi ke bar. Itu yang ia jadikan bahan jawaban. “Aku punya beberapa teman orang Filipina, dan mereka sangat suka berpesta dan minum.”
“Di mana kau bertemu mereka?”
“Err... Aku pernah mengikuti Harvard MUN[1].”
“Wow...great! Itu adalah ajang yang sangat bergengsi. Bagai...”
“Apa pendapatmu tentang delegasi Indonesia, Bill?” Sebelum Bill menyelesaikan kalimatnya, Bara langsung memotong. Ia tidak ingin obrolan tentang HMUN berlanjut.
“Ah, delegasi Indonesia selalu membuatku terkesan,” jawab Bill. “Lebih dari dua puluh tahun, aku telah berkecimpung di dunia politik. Sepuluh tahun terakhir kudedikasikan untuk mengajar. Selama itu, aku banyak menemui mereka yang memiliki talenta, tapi passion mereka lemah. Mereka menikmati permainan, bukan hasil akhir. Alhasil, mereka tak memberikan perubahan apa-apa bagi masyarakat. Ada juga yang punya passion, tetapi tak memiliki talenta. Mereka cenderung frustasi karena ketidakmampuan mengeksekusi rencana besar yang mereka canangkan. Anak-anak Indonesia yang kutemui selalu memiliki keduanya—baik passion maupun talenta. Itulah mengapa, sepulang mereka dari Amerika, aku selalu mendengar mereka melakukan hal-hal yang besar.”
“Menarik....” lirih Bara.
“Ya. Tidak ada hal menarik daripada bertemu dengan orang-orang luar biasa seperti kalian.”
“Emm, Bill... Bagaimana kalau ternyata aku tidak seluar biasa yang kau kira? Tak seperti anak Indonesia lain di dalam ceritamu?”
Pertanyaan itu muncul begitu saja dari mulut Bara. Ia merasa Bill adalah orang yang bisa diajak bicara dan berbagi.
“Maksudmu?”
“Ada kalanya aku merasa orang-orang berekspektasi terlalu tinggi terhadapku. Terkadang itu menjadi beban tersendiri.”
Bill terdiam sejenak. Ia tahu, ada nada kekhawatiran dalam kalimat tersebut. Bill pun memandang lekat pemuda yang duduk di sebelahnya itu. Ia belum pernah menerima pernyataan pesimistik seperti ini dari seorang fellow. Mereka adalah orang-orang terpilih, seharusnya sudah tuntas dengan diri mereka sendiri. Namun, ketika ada pemuda di hadapannya yang sepertinya mengalami masalah kepercayaan diri, tugasnya adalah membantu sebisanya.
“Aku punya buku favorit,” kata Bill, “judulnya Man’s Search for Meaning karya Viktor E. Frankl, seorang dokter Yahudi Austria yang lolos dari kamp konsentrasi Auschwitz Nazi di Perang Dunia ke-2. Frankl menulis kalau manusia memang tidak bisa mengendalikan apa yang bakal menimpa dirinya, termasuk ekspektasi maupun prasangka dari orang lain seperti katamu. Tapi manusia memiliki kebebasan untuk memilih cara meresponsnya. Orang boleh berkata apapun, tapi yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya adalah bagaimana kita menyikapi perkataan tersebut. Jika aku jadi kau, ekspektasi tersebut akan kujadikan pelecut agar aku bisa setara atau bahkan melebihi ekspektasi mereka.”
Bara menyerap kalimat itu perlahan, sampai akhirnya Bill beranjak dari sofa.
“Ah, sepertinya aku harus menyapa fellow lain. Semoga jawabanku tadi memberikan pencerahan. Aku tak sabar melihat kiprahmu di sini, Tirta,” kata Bill sambil tersenyum, lalu pergi.
“Thank you, Bill!” teriak Bara sambil beranjak dari sofa setelah Bill berjalan agak jauh.
Bill hanya memberi tanda jempol dengan tangan kanannya. Bara berdiri mematung di sana sambil menatap Bill yang menghilang di tengah keramaian. Beberapa detik kemudian, bibirnya menyungging senyum. []
[1] Harvard Model of United Nations (HMUN), simulasi sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa paling bergengsi di dunia.


 gadingaurizki
gadingaurizki