Tepat pukul enam sore, kereta Gajayana membawa mereka berenam menuju sebuah petualangan. Situasi kereta yang tidak terlalu ramai, membuat suhu AC yang semula dingin, makin dingin saja.
Tadinya, Boy duduk dengan Maya, dan Juang dengan Caca. Tapi kemudian, Juang minta tukar, dengan alasan, ia masih sedikit awkward jika harus duduk bersebelahan dengan Caca, yang notabene mantannya.
Akhirnya, Boy duduk dengan Caca, lalu Maya dengan Juang, dan Sherin dengan Angga.
Berpasang-pasangan, layaknya tripple date, tapi sebenarnya bukan. Karena mereka hanyalah enam kepala yang sudah dipersatukan, meski tetap saja ada cela diantaranya. Tapi tak apa, intinya, keenamnya sudah ada dalam satu payung yang sama.
Maya sudah asik dengan buku sketsa di tangannya, serta pensil di genggamannya, dan tak lupa earphone yang sudah terpasang mesra di telinganya--seolah dunia adalah miliknya sendiri, dan tiada orang lain di sekitarnya. Hidup Maya, mudah, sesederhana itu.
"May, May.. Lo bener-bener typical cewek yang beda," kata Juang, membuka topik.
Mendengar Juang mengajaknya bicara, akhirnya Maya melepas earphone di telinganya. "Apa? Sorry gue nggak begitu denger kata-kata lo tadi."
"Lo tipe cewek yang beda dari yang lain," kata Juang, mengulang perkataanya.
"Beda gimana?"
Juang menunjuk Maya. "Lihat aja gaya lo."
"Kenapa? Ada yang salah?"
"Gaya lo cuek, tapi asik. Lihat, deh, semua orang mengakui kalau lo cantik, meskipun lo bareface tanpa polesan make-up." Juang berimajinasi sejenak tentang sosok Maya di pikirannya. "Dan pembawaan lo super santai, nggak pernah gugup. Ibarat, lo bisa hidup hanya dengan earphone, dan buku sketsa lo. Hidup lo simple, nggak ribet.
Ah, dan satu lagi... Lo nggak pernah takut sendiri. Ibarat, lo nggak takut punya musuh, dan lo malah segan cari musuh andai lo nggak suka sama orang itu. Lo apa adanya, nggak pernah pencitraan."
"Aneh, ya, cewek kayak gue?"
Dengan cepat, Juang menggeleng, "Bukan aneh. Malah, sama sekali nggak aneh, menurut gue."
"Kan menurut lo. Kalau kata orang-orang, gue aneh," ungkap Maya, dengan tawa palsunya.
"Pandangan orang beda-beda, sih. Tapi bagi gue, lo nggak aneh."
"Emang pandangan lo ke gue, gimana?"
"Lo itu unik." Juang melanjutkan lagi, "Apalagi ada satu hal yang benar-benar menonjol dari lo."
"Apa?"
"Cara lo mengintimidasi orang lain, pakai tatapan ataupun kata-kata. Misalnya, kalau lo nggak setuju sama pendapat seseorang, atau bahkan kalau lo mengibarkan bendera permusuhan ke orang lain.. Ah, banyak, lo pasti paham sama apa yang gue maksud." Juang kehabisan kalimat, tuk mendeskripsikan tentang sikap Maya.
Dan Maya paham, maksud Juang adalah tentang dirinya dan Caca.
Maya mengendikkan bahu. “Kayaknya itu ciri khas gue, ya.”
“Jangan terlalu jutek, May. Suatu saat, lo pasti butuh orang lain.”
Maya tersenyum kecut. “Mungkin itu salah satu hal yang bikin gue jomblo kelamaan."
*
Daritadi, Sherin sudah memejamkan matanya. Tidak, tidak, Sherin tidak tidur. Ia hanya berusaha memejamkan mata, agar makhluk di sebelahnya tak banyak bertanya mengenai apa yang terjadi.
“Sher, gue tau lo belum tidur,” kata Angga. “Mata lo lebam, pasti habis nangis, kan? Pipi lo juga biru, pasti lo habis dipukulin lagi, kan?”
Tanpa sengaja, Sherin menggeleng.
“Tuh, lo aja bisa geleng-geleng. Gue udah feeling, lo pasti belum tidur. Lo nggak bisa menghindar dari pertanyaan gue, karena gue akan selalu bawel sebelum lo jawab.”
Akhirnya, Sherin membuka matanya. Mata yang menurut Angga, adalah mata paling cantik; sayangnya, seringkali sendu dan kelam.
“Tapi gue males bahas, Ngga… Gue capek, gue sedih…”
“Lo boleh bersandar di pundak gue, kalau lo bener-bener capek,” kata Angga. “Kalau sebuah peluk bisa bikin lo tenang, gue mau kasih satu pelukan. Tapi gue sadar, lo masih punya orang.”
Miris.
Dengan perlahan, Sherin meletakkan kepalanya di bahu kiri Angga. “Angga?”
“Apa?”
“Thanks, buat segala yang udah lo lakuin. Tapi lo bisa dapat perempuan yang lebih dari gue, yang bisa hargai semua kebaikan lo…” ucap Sherin pilu. “Gue nggak bisa berbuat apa-apa.. Kalau lo nunggu gue terus, lo malah jalan di tempat, Ngga.”
Angga menggeleng. “Gue nggak pernah merasa jalan di tempat. Gue yakin, Tuhan denger doa gue, supaya gue makin didekatkan sama lo. Toh kalau ternyata kita bukan jodoh, ya nggak masalah, setidaknya, gue pernah berarti buat lo, meski hanya sebagai sahabat.”
Air mata Sherin tak bisa ditahan lagi. “Gue capek dipukul terus, Ngga.”
“Putus, kalau begitu.”
“Nggak semudah itu. Ada sesuatu yang lo nggak tau, yang bikin gue selama ini selalu bertahan sama Marcell. Kalau bisa, sih, gue lebih baik single seumur hidup, daripada harus menghabiskan sisa hidup dengan siksaan Marcell. Gue capek. Gue manusia, bukan objek siksaan…” Bahu Sherin bergetar hebat.
Angga menghela nafas. “Gue nggak tau kita jodoh atau bukan. Tapi sebelum Tuhan menjawab jawaban tentang hal tersebut, tolong izinin gue untuk selalu jagain lo.”
Sherin mengangguk dalam tangisnya. “Thank you, Angga. Semoga Tuhan kasih jawaban terbaik untuk kita..”
Karena sebenarnya, baik Angga maupun Sherin, mereka mengharapkan hal yang sama. Karena sebenarnya, baik Angga maupun Sherin, sama-sama sedang berusaha dalam diam dan doa. Karena sebenarnya, mereka sama-sama terlanjur nyaman.
*
"AC-nya dingin banget, ya," kata Boy, pelan.
Caca yang bisa mendengar gumaman pelan Boy, tertawa kecil. "Lo kan laki-laki, anak gunung pula. Masa kalah sama AC?"
"Kan dingin gunung sama dingin AC beda kali, Ca.."
“Bedanya?”
“Ya beda pokoknya,” jawab Boy, asal. “Gimana, udah siap naik gunung, kan?”
“Udah. Kan udah jogging beberapa hari ini sama lo. Gue siap, kok. Cuma, ya, rasa takut tetap ada.” Caca begidik ngeri, membayangkan hal-hal mengerikan yang terjadi pada pendaki, yang gagal, ataupun pulang dengan tak bernyawa. Mengenaskan.
“Tenang aja, yang penting berdoa dulu. Dan, jaga sopan santun di sana,” kata Boy.
Benar. Sopan santun adalah kunci terpenting. Dengan bersikap sopan dan sewajarnya, hal aman pasti akan mengikuti. Termasuk untuk hal mendaki gunung.
“Intinya, jangan remehkan alam sekitar. Misalnya, lo buang sampah sembarangan selama pendakian. Oke, mungkin nggak ada orang yang lihat. Tapi gunung adalah wilayah sakral. Banyak makhluk yang nggak kelihatan, yang bisa lihat apa saja yang kita lakukan. Jadi, sopan santunlah, bukan hanya pada manusia, tapi juga pada hal-hal yang tidak bisa dilihat manusia.
Caca menelan ludahnya sendiri. “Kok horor, ya?”
“Memang, sedikit.”
“Lo pernah ngalamin hal horor gitu nggak selama pendakian?”
Boy mengangguk. “Pernah. Ya, bukan cuma gue, sih. Tapi gue dan rombongan gue.”
“Kenapa?”
Boy menarik nafas panjang, mulai bercerita. “Jadi waktu itu, kita mendaki ramai-ramai. Terus rutenya tuh kayak itu-itu aja, kayak nggak maju-maju, padahal sudah berjalan tiga jam. Dan seharusnya, dalam tiga jam, kita sudah sampai puncak.”
Caca mengerutkan kening. Penasaran. “Kok bisa?”
“Ternyata, ada salah satu perempuan di rombongan gue, yang pada saat mendaki lagi haid. Padahal perempuan haid kan nggak boleh mendaki. Rawan.” Boy menatap Caca. “Lo nggak haid, kan?”
Caca menggeleng. “Udah dua minggu lalu.”
“Jadi lo aman,” sahut Boy, lega.
Mereka terdiam lagi. Sebenarnya, banyak hal yang ingin mereka ungkapkan, agar suasana menjadi lebih hidup. Tapi entah mengapa, mereka memilih diam kali ini.
Apalagi Boy. Sejujurnya, ia ingin bertanya pada Caca, mengenai masa SMA, yang tadi diceritakan oleh Juang. Tapi, Boy pikir, ini bukan waktunya. Karena kali ini, fokus utama mereka adalah pendakian, bukan masalah pribadi yang didasari rasa penasaran.
“Kenapa lo suka naik gunung?” tanya Caca.
Boy tersenyum. “Nggak tau. Gue cinta aja. Cinta nggak butuh alasan, kan?”
“Klasik banget lo,” ejek Caca. Nggak, nggak. Nggak mungkin tanpa alasan. Ini kan masalah hobi, bukan cinta manusia pada manusia lain. Jadi pasti ada sesuatu yang mendasari, kenapa lo bisa suka mendaki.”
“Mungkin passion kali, ya. Gue merasa lebih hidup. Gue merasa lebih bahagia ketika bisa sampai puncak. Beban gue hilang. Rasa syukur gue makin tumbuh. Di atas gunung, gue bisa tau, kalau Tuhan menciptakan segalanya begitu baik dan rupawan, seperti pada alam. Tuhan saja mengatur alam sedemikian indah, dan gue yakin, Tuhan pasti mengatur hidup kita juga nggak kalah indah,” balas Boy, panjang lebar.
“Duh, lo cocok jadi anak filsafat, deh,” kata Caca, sembari tertawa.
“Coba aja, deh. Ketika nanti lo sampai puncak, pasti lo bakal terharu,” ucap Boy. “Dan lo akan sadar, kalau masalah-masalah yang terjadi pada hidup lo, nggak lebih besar daripada masalah yang menimpa alam kita.”
Caca tertegun. “Gue kagum sama lo.”
“Cuma kagum? Nggak cinta?” ledek Boy.
“Apaan sih!”
“Bercanda, bercanda.”
Cinta?
Caca sudah pernah merasakan hal itu pada Boy. Ketika ia begitu menyukai lelaki itu, namun ternyata dunia memilihkan seorang perempuan lain untuk bersanding dengan Boy kala itu; dan perempuan itu bukanlah Caca.
Jujur, bagi Caca, Boy adalah sosok pemimpin yang baik. Dia baik kepada semua orang, dia bisa mengayomi orang yang butuh tuntunan. Boy, sosok lelaki istimewa.
Tapi justru karena kebaikan Boy, Caca takut. Takut jatuh lagi kepada lubang bernama ‘nyaman’ yang berakhir pada rasa ‘sayang’ dan ‘takut kehilangan’; sementara sosok lelaki sebenarnya tak memiliki rasa yang sama, karena memang lelaki tersebut selalu memperlakukan semua makhluk wanita dengan istimewa.
“Tidur, Ca. Bangun-bangun udah sampai Malang, kan seger,” ucap Boy, membuyarkan lamunan Caca.
“Bentar lagi, Boy. Lo duluan aja.”
Boy membenarkan posisi jaketnya, kemudian mengangguk. “Gue duluan, ya. Night, Ca.”
Caca tersenyum, “Good night, Boy.”
Tanpa keduanya sadari, bahwa ucapan selamat malam yang baru saja mereka berdua ucapkan, membuat mereka sama-sama berharap akan ucapan selamat malam di malam-malam selanjutnya.
*
*


 Ervinadyp
Ervinadyp












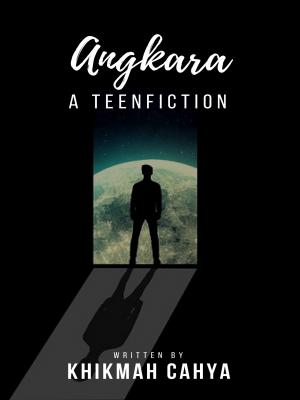



Lucu juga baca ini. Aku suka kok. Tapi, aku saranin untuk kata seperti lipbalm dan fix, sepertinya harus di italic. Over all ceritanya bagus. 🙏❤❤
Comment on chapter Rencana Mereka