Perjalanan mereka lanjutkan lagi dengan jalan yang terus menanjak. Disisi kiri dan kanan tak jarang terlihat ladang-ladang penduduk lokal di lereng bukit yang seolah tertata sedemikian rupa sehingga terlihat amat cantik. Seperti lukisan yang hidup saja.
"Kapan sampainya?" Maya mulai gelisah.
Juang memandang ke luar jendela sekilas. "Sebentar lagi, kita sampai Pos Ranupani."
"Lo kenapa, May?" tanya Boy, tampak mengerti akan kegelisahan yang Maya utarakan melalui raut wajahnya.
"Nggak apa-apa," jawab Maya.
Juang terkekeh. "Cewek, kalau bilang nggak apa-apa, pasti aslinya ada apa-apa."
"Nggak usah sok tau lo!" timpal Maya.
Caca tersenyum tipis. Ia tau benar arti ekspresi Maya. Jalanan yang naik turun dan udara dingin menusuk tulang sudah pasti membuat seorang Maya masuk angin.
"May," panggil Caca.
Maya hanya menjawab dengan tolehan, tanpa suara. Bagi seorang Maya, bicara pada seorang Caca adalah hal tak penting, yang tak seharusnya dilakukan.
Berbeda dengan Caca. Meski selalu sakit hati dengan perilaku Maya, namun itu tak membuat Caca ingin menghentikan niat baiknya pada Maya. Karena bagaimanapun juga, Maya adalah sahabat baiknya, hingga sekarang, meski Maya tak menganggapnya sama.
"Lo mual?" Dan dengan segera, Caca merogoh minyak kayu putih dan tolak angin dari dalam tasnya, kemudian menjulurkannya kearah Maya.
"Nggak perlu. Gue bisa tanganin sendiri," balas Maya, tetap cuek, bahkan hanya melirik sekilas kearah obat-obatan--yang sebenarnya ingin Maya terima, tetapi gengsinya super duper tinggi--kemudian, membuang wajahnya lagi membelakangi Caca.
"Maya... Perjalanan kita masih jauh, loh." Caca mencoba membujuk. Tapi bujukan ini ada maksudnya, yaitu agar Maya selalu sehat dan bisa menikmati segala proses perjalanan.
"Ya gue tau. Emangnya, siapa yang bilang perjalanan tinggal satu kilo?!" tandas Maya.
Caca diam. Nada tinggi Maya, selalu berhasil menggores hatinya.
Juang melerai kedua gadis itu. "Apa-apaan sih kalian?!" Namun Juang menolehkan kepalanya kearah Maya. "Caca tuh berniat baik ke lo, May. Hargain, kek."
"Pertama, gue nggak sudi terima barang apapun dari dia!" tegas Maya, sambil menunjuk Caca dengan jari telunjuknya. "Kedua... Gue nggak selemah itu! Gue belum butuh obat-obatan itu. Karena apa? Karena gue tau kapasitas gue sendiri!"
Boy menatap kearah Caca, memastikan gadisnya baik-baik saja.
Juang menggeleng. "May, jangan teriak-teriak.. Nggak enak sama penumpang yang lainnya."
Benar. Rupanya perdebatan singkat itu mengundang para penumpang lain. Dan dalam hitungan detik, Maya menghembuskan nafas, dan menundukkan kepalanya.
Boy mendekat ke telinga Caca, dan berbisik, "Lo nggak apa-apa?"
Dan tanpa suara, Caca menjawab dengan sebuah anggukan penuh makna.
**
Sekitar pukul 12 siang, rombongan mereka tiba di Pos Ranupani, pos pertama dalam rangkaian pendakian Gunung Semeru. Pos Ranupani berada diketinggian 2100 mdpl. Udara dingin mulai begitu terasa, kabut tipis menutup beberapa bagian.
"Dingin, asli," ucap Juang, memeluk tubuhnya sendiri.
Boy mengangguk setuju. "Gimana di atas, ya?" Atas yang Boy maksud adalah 'puncak'.
"Nggak tau, deh. Perasaan, dulu, nggak sedingin ini."
Maya melipat tangannya, sama, mengalami nasib kedinginan yang serupa. "Kita ngapain nih?"
"Pertama, kita harus daftar dan lengkapin dokumen-dokumen perjalanan kita," kata Boy, menjelaskan. "Ayo."
Keempat manusia itu berjalan menuju tempat pendaftaran. Karena kebetulan pendakian ini mereka lakukan bukan di libur panjang--dengan curi-curi waktu kuliah--maka pendakian kali ini nampaknya tak terlalu ramai, seperti jika di hari-hari libur panjang.
Di pos ini, setiap pendaki, harus mendaftar dulu dan melengkapi dokumen-dokumen persetujuan, fotokopi identitas, check list peralatan rombongan. Proses tersebut dinamakan Simaksi.
Proses tersebut berjalan dengan lancar untuk empat kepala manusia ini. Dan setelah Simaksi, mereka di briefing oleh petugas tentang aturan-aturan dan larangan selama pendakian Gunung Semeru. Dan petugas sedikit membagikan tentang hal-hal yang pernah terjadi di Semeru. Salah satunya cerita tentang temen pendaki yang meninggal di atas.
"Ya rata-rata gitu.. Saking ngototnya mereka ingin sampai puncak, saking ambisiusnya, nggak jarang mereka memaksakan diri. Efeknya ya mereka nggak peduli sama keselamatan mereka," kata Boy, setelah petugas memberi briefing singkat.
Boy menegaskan lagi. "Kita harus utuh. Berangkat empat orang, pulang empat orang."
Ketiga teman di sekeliling sama-sama meng-amin-kan ucapan Boy.
"Kok gue takut, ya," ucap Maya.
Boy menggeleng, mencoba menguatkan. "Wajar takut. Tapi anggap aja ini pengingat untuk kita, agar tetap berhati-hati dan tetap dalam rule."
Juang menambahkan. "Dan kalau nggak kuat, mundur, jangan ragu-ragu, jangan dipaksakan."
Maya melirik Caca. "Tuh, Ca. Dengerin."
Caca hanya menanggapinya dengan seulas senyum. Malas berdebat dengan Maya dan malas menyimpan rasa sedih karena nada tinggi Maya, karena kali ini ia harus menyimpan energi.
"Jadi, mendaki jam tiga?" tanya Juang.
"Boleh deh. Kita istirahat dulu di sini." Boy menjawab.
"Ngerokok dulu, yuk," Juang menjulurkan sebatang rokok ke arah Boy.
"Djarum Super?" tanya Boy.
"Iya. Suka, kan?"
"Sebenernya gue lebih suka Dji Sam Soe, sih. Tapi okelah, karena rokok gue di dalem tas dan gue males buka tas, jadi rokok lo tue terima," kata Boy, sambil menerima rokok yang Juang julurkan.
Juang terkekeh. "Nih korek."
"Thanks, bro!"
Caca mengibaskan tangannya. "Kalian mau pada ngerokok, ya?"
"Keberatan, Ca?" Boy menatap Caca tak enak.
Maya memutar bola matanya. "Ya kalau lo nggak suka asap, minggir lah! Masa mereka kudu pergi hanya karena satu orang kayak lo?!" Maya meluapkan emosinya. Sebenarnya, Maya tidak emosi. Hanya saja rasa sebalnya pada Caca, membuatnya bahagia jika ia berhasil berbicara dengan nada tinggi--atau membentak--pada Caca.
Juang yang memang sudah pernah menjalin hubungan dengan Caca, dan paham betul sifat Caca, mengalah. "Sorry, Ca. Gue sama Boy pergi bentar deh. Cari tempat ngerokok."
"Jangan, jangan!" sahut Caca cepat.
"Kenapa?"
Maya melirik sinis. "Lo aja yang pergi, Ca."
"Iya, gue mau ke mushola." Caca menunjuk satu mushola di dekat pos tersebut. "Mau sholat dhuhur."
Dan tanpa basa-basi, Caca langsung pergi meninggalkan ketiga temannya yang ternganga.
Bagi Caca, kewajiban ibadah adalah segalanya. Jantung dari hidupnya. Tak peduli bagaimana pendapat orang lain tentangnya--yang katanya banyak mantan, suka make up, dan lain-lainnya--ia tetap mengutamakan ibadahnya.
**
Usai shalat dhuhur, Caca melipat mukena yang ia bawa. Dan setelahnya, Caca melangkahkan kaki keluar dari bangunan yang selalu berhasil membuatnya tenang, yaitu masjid ataupun musholla.
"Caca?"
Caca menoleh, tepat saat Caca akan mengenakan sepatunya. "Loh, Boy? Sejak kapan disitu?"
"Daritadi. Gue barusan sholat juga."
Caca tersenyum. Ada rasa bahagia membuncah di hatinya. "Alhamdulillah.."
"Gue kok seneng ya, lihat lo sholat," kata Boy.
"Gue juga seneng lihat lo sholat. Gue kira, lo tadi ngerokok sama Juang."
"Nggak jadi. Mendingan sholat, lah. Ngerokoknya nanti-nanti aja, masih banyak waktu." Boy menghela nafas. "Gue sadar, ibadah gue masih payah. Gue perlu banyak perbaiki hal itu. Apalagi gue suka berpetualang, kebayang nggak sih, kalau gue meninggal pas petualangan?"
"Ssst! Jangan bilang gitu, ah."
"Ya kan siapa yang tau, Ca..."
Caca menghela nafas. "Ya makanya, dimanapun, harus ibadah dan hati-hati. Setidaknya kalau meninggal, kita punya bekal."
Keduanya hening sejenak. Mereka memikirkan sesuatu di benak mereka masing-masing, tanpa bicara.
Hingga salah satu dari mereka, memulai lagi.
"Gue kangen ibu," kata Caca.
Disitulah, Boy paham, bahwa sorot sedih yang selalu tampak dari wajah Caca, adalah bentuk kerinduannya pada Ibunya.
"Ibu gimana sekarang?" tanya Boy, penasaran.
Caca menghela nafas berat. "Udah tinggalin gue dan Ayah.. Dan udah menikah sama laki-laki lain."
"Astaga.. Sorry, Cha.."
"Nggak apa-apa.."
Boy bertanya lagi, kali ini dengan wajah lebih serius. "Terus.. Lo nggak apa-apa? Ayah lo, gimana?"
"Ayah gue kena stroke ringan. Tapi sekarang udah pulih lagi, alhamdulillah.. Tapi, ya, gue harus pastikan Ayah selalu senang, supaya nggak kumat lagi."
Boy diam. Kehidupan Caca tak seperti yang orang-orang bilang. Hidup Caca, sejujurnya miris, tak seperti penampilan Caca yang terlihat selalu cantik dan menarik.
"Makanya gue pengen cepet-cepet lulus. Biar bisa kerja, banggain Ayah.. Bentar lagi Ayah pensiun. Biar gantian gue yang cari uang.." Caca menggigit bibirnya. Tiap kali mengingat Ayahnya, selalu sedih dan rindu yang ia rasa.
Boy menepuk pundak Caca. "Gue akan ada buat lo, Ca."
Caca menggeleng, "Jangan janji, kalau nggak bisa buktiin.."
"Gue bisa, Ca.."
Gadis itu diam lagi. Kemudian, terlintas sesuatu di pikiran Caca. "Boy?"
"Kenapa, Ca?"
Caca merogoh saku tasnya, mengambil beberapa bungkus tolak angin dan minyak kayu putih, lalu menyerahkannya kearah Boy. "Ini... Tolong kasihin Maya. Dia nggak akan mau menerima kalau gue yang kasih."
Boy menerima obat-obatan tersebut. "Maya sebenarnya butuh. Tapi dia gengsi."
Keduanya tertawa. Tawa pilu, tepatnya, bagi seorang Caca yang menginginkan persahabatannya dengan Maya kembali.
"Lo baik banget sama Maya, deh.."
Caca tersenyum tulus. "Kan dia sahabat gue.."
"Ya udah, yuk balik. Bentar lagi briefing sama petugas, nih," ajak Boy.
"Ayo."
Dan Boy mengulurkan tangannya kearah Caca, tuk membantunya berdiri. Namun saat Caca sudah berdiri sempurna, Boy belum juga melepas tangannya dari tangan Caca. Yang terjadi justru Boy tetap membawa tangan Caca terkait dengan tangannya--mereka bergandengan--tanpa peduli bahwa karena hal sepele seperti itu, perasaan mereka bisa tumbuh tak terkendali.
*bersambung*


 Ervinadyp
Ervinadyp









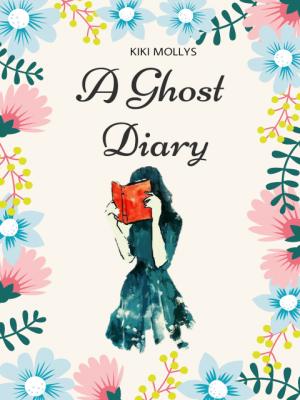







Penasaran sama lanjutannya
Comment on chapter Chit Chat