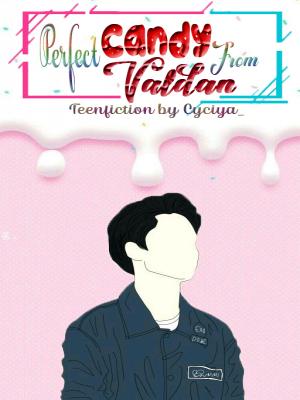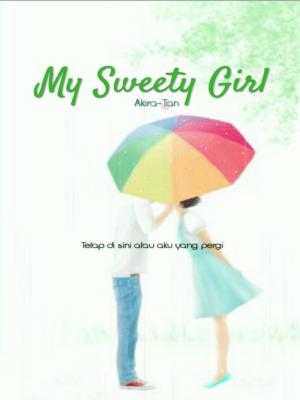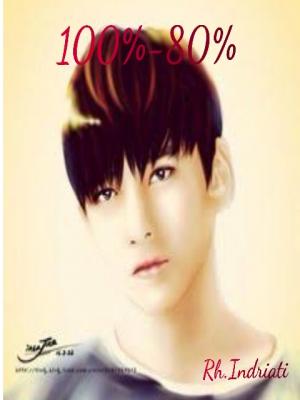Dia, Gue Maunya Lo
Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisi-Nya lah terdapat Umulkitab (Lohmahfudz) (QS. Ar-Ra’du, 13:39)
Abu mengakhiri bacaannya di ayat itu. Sejenak ia mencoba mencari arti dari ayat yang baru saja ia baca. Hanya Allah lah yang berhak menetapkan segalanya, termasuk tentang Zahra. “Semoga Allah menghendaki lo hanya untuk gue, Ra.” Abu bergumam lirih sambil menutup Al-Qur’an kecil di tangannya.
Tak beberapa lama, Abu melangkah mendekat jendela kamar yang masih terbuka. Senja mulai menyapa. Warna jingganya mulai ikut masuk ke kamar Abu. Hangatnya menyentuh kulit yang sedari pagi terasa dingin. Hujan dari pagi sudah reda sempurna. Matahari baru menebar hangat saat senja. Hari ini, matahari cukup malas rupanya. Sejak pagi, ia hanya sembunyi di balik awan.
Abu tersenyum menatap langit senja dari balik jendela. Mengagumi karya Allah ini memang tiada habisnya, apalagi mengagumi karya secantik dan sesempurna Zahra. Ah, hayalan Abu terhenti karena suara notifikasi yang terdengar dari ponsel Abu. Ia pun mengusap layar ponsel dan membaca sebuah pesan, dari Ali.
“Abu, lo ada waktu nggak? Kalau lo lagi nggak ada acara, kita konkow yak, di café biasa.” (Ali)
“Siap! insyaAllah, tigapuluh menit lagi gue nyampek ya, bray.” (Abu)
“Okay. On time ya, bray. Gue butuh lo, nih.” (Ali)
“Ada apaan sih, bray. Lo bikin gue penarasan.” (Abu)
“Ntar aja ceritanya. Gue tungguin lo, ya.” (Ali)
Tanpa membalas lagi pesan singkat dari sahabatnya itu, Abu segera mempersiapkan diri dan melangkah menuju mobilnya.
“Ma, Abu keluar bentar, ya.”
“Abu! Hujan baru aja reda. Mau kemana kamu?”
“Mau ketemu Ali, Ma. Sepertinya, dia lagi ada masalah tuh. Assalamualaikum.” Abu membuka pintu mobil dan segera duduk di balik kemudi.
“Oh, Ali. Iya deh. Salam ya buat Ali.”
“InsyaAllah, Ma.”
“Kamu hati-hati, ya, sayang. Waalaikumsalam.”
Abu melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju café yang ditunjuk Ali dalam pesannya. Café yang biasa mereka gunakan untuk melewatkan senja.
Tak butuh waktu lama untuk Abu sampai di café itu. Waktu tiga puluh menit yang dijanjikannya, masih tersisa banyak. Ia pun memarkir mobil dan segera masuk ke dalam café.
Mata Abu langsung mengarah ke bangku sudut café, tempat yang biasa mereka bertiga gunakan untuk bertemu. Sudah ada Ali di sana. Menunggu dengan secangkir cappuccino di depannya.
Ali. Lelaki yang lupa cara serius. Menjalani semua dengan santai dan tanpa beban adalah kebiasaan Ali. Tapi kali ini, guratan keseriusan tergambar dari wajah Ali. Ada kegelisahan yang sedang melingkupi dirinya. Abu mudah saja melihat kegundahan itu. Kali ini, Ali terlihat serius membaca sebuah buku setebal bantal. Ali membaca buku artinya ia sedang berusaha keras menenangkan diri.
“Assalamualaikum. Udah dari tadi, bray?” Abu duduk di bangku depan Ali.
“Waalaikumsalam. Cepet banget, ngebut lo, bray?”
“Iya lah. Takut lo kenapa-napa. Kusut gitu muka, lo.” Tanpa permisi, Abu pun menyesapi cappuccino Ali yang terlihat belum tersentuh sejak tadi. Sudah cukup menghangat.
“Gue pesenin, ya.” Ali memanggil waiter dan memesan secangkir cappuccino lagi untuk Abu.
“Ada apaain sih? Harusnya lo seneng, study lo bentar lagi kelar.” Abu menghentikan kalimatnya. Ingin ia menanyakan tentang rencana Ali dan Zahra selanjutnya. Tapi, Abu tidak ingin merusak suasana hati Ali yang sudah terlihat kacau sore itu.
“Bray, nyokap gue, pengen gue segera menikah.”
Deg!
Andai jantung tak terhalang rusuk dan daging, mungkin sudah melompat saja ke luar meninggalkan tubuh Abu saat itu juga.
“Menikah?” Abu kembali menghentikan pertanyaannya. Padahal, ingin sekali ia memastikan, apakah dengan Zahra, Ali akan menikah.
Kembali Abu mengatur raut wajahnya. Berusaha ia sembunyikan lagi guratan kecemburuan yang mungkin saja tergambar di sana. Ali masih sibuk dengan bukunya. Sesekali, ia melirik ponsel yang terbaring bisu di atas meja. Sepertinya, ia sedang menunggu dering ponsel itu.
“Lo nggak ngajak Zahra juga, bray?” Abu mencoba membuka percakapan.
“Nggak lah.”
“Kenapa?”
“Nggak pa pa. Gue hanya mau ngobrolnya sama lo.” Ali menatap dalam mata Abu. “Lo nggak keberatan, kan?”
“Ya nggak lah.” Abu menyandarkan punggungnya pada sandaran bangku café. Seperti ada sesuatu yang berat menggantung di punggungnya sore itu. “Setelah sekian lama nggak ketemu, ternyata lo masih mau bicara tentang hal pribadi lo sama gue. Thanks ya, bray.”
Ali tersenyum mendengar ucapan Abu. “Gue yang terimakasih. Lo sahabat terbaik buat gue, bray. Banyak hal yang lo lewatkan tentang gue selama ini.”
Hening.
Tidak terdengar lagi percakapan antara Ali dan Abu. Mereka sibuk dengan cangkir cappuccino masing-masing. Abu ingin segera membuka saja segalanya. Menanyakan sejuta tanya yang menjejal di kepala. Namun, bibir Abu seakan kelu. Banyak hal apa yang telah ia lewatkan itu? Apakah tentang Zahra?
“Oya, bray. Gue suka tulisan-tulisan lo. Selama ini, lo banyak banget berkarya, ya. Nggak nyangka gue. Ternyata, kesukaan lo nulis berlanjut sampai sekarang.” Kali ini Ali membuka percakapan walau terdengar sedikit garing.
“Ah, biasa aja. Gue hanya menuliskan yang ada di kepala aja. Belum bisa disebut berkarya.”
“Kok gitu?”
“Menurut gue, tulisan-tulisan gue masih biasa aja. Belum bisa bermanfaat buat orang lain.”
“Nah lo. Bukannya pembaca buku-buku lo udah bejibun, bray. Udah pada dipajang aja tuh di toko buku superior. Lo bilang biasa?”
“Lebay lo.” Abu tertawa ringan mendengar pujian Ali. Sesaat, wajah Ali pun terlihat lebih segar dari beberapa menit lalu. Ia sudah mulai bercanda seperti biasa dan bicara sedikit ringan.
“Gue juga pengen berkarya seperti lo. Punya sesuatu yang fenomenal.”
“Heleh. Bukannya modifikasi motor lo itu lebih dari fenomenal?”
“Itu dulu, bray. Sekarang gue hampir nggak ada waktu untuk hal sekecil itu.”
Dan kembali hening.
Beberapa menit berlalu tanpa obrolan apapun. Abu dan Ali sibuk menata hati mereka masing-masing. Hingga dering ponsel Ali pun terdengar. Ali hanya memandangi layar ponsel yang menampakkan wajah seorang perempuan berhijab. Sayangnya, wajah itu tidak dapat terlihat jelas oleh Abu. Lagi-lagi, ia mengira itu Zahra. Namun, setelah dua kali ponsel itu berdering, tangan Ali tidak bergeming untuk menyentuhnya.
“Kok nggak lo angkat?” Abu bertanya lirih. Ali hanya membalasnya dengan senyum. Penasaran makin menyeruak di dada Abu, “Siapa yang telepon, bray?”
“Mama.”
“Angkat lah, bray. Siapa tahu penting.”
“Ah, paling juga nanyain tentang rencana entar malem.”
“Rencana? Entar malem?”
“Iya. Mama mau ngundang keluarga calon istri gue dinner.”
Pyar!
Hati Abu pecah berkeping-keping rasanya. Calon istri Ali? Tapi, mengapa ia tidak menyebut saja namanya, Zahra! Mungkin Ali hanya ingin menjaga perasaan Abu saja. Saat ini, perasaan yang seperti apa lagi yang harus dijaga. Sedang semua rasa yang Abu miliki terasa sudah pergi meninggalkan tubuh Abu yang membeku di bangku sudut café.
Ponsel Ali kembali berdering.
“Lo angkat deh, bray. Kali aja nyokap lo butuh sesuatu atau … .” Abu menghentikan kalimatnya. Gesture tangannya menunjuk pada ponsel yang sedang meraung-raung di atas meja, sudah cukup untuk memaksa Ali mengangkat telepon dari mama.
“Iya deh. Lo tunggu bentar, ya.” Ali meninggalkan Abu sendiri. Ia sedikit menjauh dari bangku sudut café. Abu hanya mampu tersenyum.
Percakapan antara Ali dan mama memang tidak seharusnya Abu dengar. Abu sadar, ini adalah masa-masa sulit untuk Ali. Jika benar ia akan menikah dengan Zahra, tentu ia harus menata segalanya untuk menyampaikan pada Abu, agar ia tidak terluka.
“Sorry ya. Lo jadi nugguin gue.” Ali kembali setelah beberapa menit.
“Nyantai aja. Oya, jadi, lo sebenarnya mau ngomong apa?”
Ali tersenyum dan menyesapi cappuccino di cangkir yang terlihat tinggal setengah. “Alhamdulilah, bray. Acara entar malem pending.” Wajah Ali terlihat sumringah. Seperti ada beban berat yang tetiba lenyap.
“Pending? Kok lo malah seneng gitu?”
“Iya, paling nggak ada waktu untuk gue … .”
“Untuk apa?” Abu makin tidak sabar mendengar cerita Ali yang terlihat terputus-putus itu.
“Hhhhggghhh. Karena gue juga belum tahu siapa anak teman mama itu. Dan gue … .” Kembali Ali terhenti. Wajah Abu makin terlihat penasaran. “Gue mencintai orang lain, bray.”
“Ya, Allah, apa lagi ini?” Abu berkata dalam hati.
“Tapi gue nggak berani bilang itu ke dia. Karena gue juga nggak tahu, siapa yang dicintainya.”
“Dia? Siapa?” Abu berada di puncak keingintahuannya kali ini. “Gue kenal?”
Kali ini, Ali yang terkesiap. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Selama ini ia tahu bahwa Abu juga mencintai Zahra. Bahkan sejak SMA. Jadi, tidak mungkin jika ia menyebut nama Zahra.
“Ah, sudahlah. Lupakan, bray. Oya, gue dengar, besok lo ada meet and greet lagi di café ini? Jangan lupa undangan gue, ya. VVIP” Ali menyenggol lengan Abu yang masih lemas di atas meja. Abu hanya tersenyum. Abu benar-benar lupa jadwalnya besok.
Bertemu dan berbincang dengan para pembaca serta berbagi tanda tangan adalah hal yang luar biasa bagi Abu. Seorang penulis baru yang tanpa ia sangka,buku-buku yang ditulisnya banyak diminati, terutama remaja.
Obrolan dua orang sahabat itu pun mengalir begitu saja. Ali sejenak melupakan rencana perjodohannya. Sedang Abu telah sedikit lega karena untuk sementara, ternyata bukan Zahra yang akan menikah dengan Ali. Tapi, hanya Allah yang tahu. Siapa jodoh Ali dan Abu sebenarnya.


 FaAli
FaAli