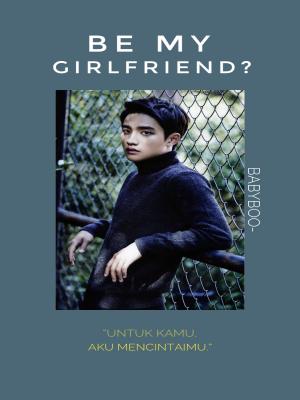Siapa lagi, Selain Kamu?
“Kamu,
Kamu yang memaksaku menggoreskan tinta
Menggambarkan isi hati seadanya
Menceritakan yang tersembunyi sebenarnya,
tanpa jeda
Kamu,
Apa lagi yang terlewat dari kepalaku?
Semua seakan tersurat lengkap di situ
Bahkan,
Tak mampu lagi kutemukan apa pun,
Selain, kamu!”
Kepulan asap cappuccino di meja Abu masih tampak membumbung tinggi, menyapa langit-langit café yang terdiam mengamatinya sedari tadi. Abu masih sibuk dengan tulisannya sore ini. Buku kesekian yang sedang ia selesaikan, rasanya akan lebih cepat finish kali ini. Tidak seperti buku-buku sebelumnya, ia hanya butuh waktu tidak lebih dari satu bulan. Subjek di buku ini, lebih menginspirasi Abu untuk lebih cepat menyelesaikan tulisannya. Siapa lagi, selain Zahra.
Abu terlihat menyesapi cappuccino-nya. Sebuah desahan dalam, mengikuti Abu merebahkan punggungnya di sandaran bangku café. Seakan menerjemahkan kegelisahan di dadanya. Sekali lagi Abu mengusap layar ponsel. Dibacanya kembali pesan singkat yang dikirim Zahra beberapa jam lalu.
“Abu, temui gue di café biasa sore ini, ya. Ada yang mau gue ketemuin sama lo.”
Pesan singkat yang benar-benar singkat bagi Abu. Tanpa memberi penjalasan lebih, bahkan Zahra tidak menjawab balasan yang dikirimkan Abu. Siapa yang akan Zahra ketemukan dengannya sore ini? Mengapa Zahra ingin Abu bertemu dengan orang itu? Pesan singkat itu sungguh menjadi virus di kepala dan hati Abu.
Ia memandang lepas ke luar café. Jendela kaca di sudut café tepat menghadap ke jalan raya. Abu memandang beberapa orang yang berlalu lalang, namun pikirannya tetap mencari jawaban atas segala keresahannya.
“Ya Allah, tenangkanlah hatiku. Jauhkanlah dari pikiran yang tidak karuan ini.” Abu berbisik pada senja yang mulai mengintip hari. “Allahuma inni as aluka nafsaan bika muthma-innah, tu’minu biliqaa-ika wa tardhaa bi qadhaa-ika wa taqna’u bi’athaa-ika.” Kali ini, hanya Allah lah yang mampu menenangkan Abu, siapa lagi? Ia mengusap wajah dengan kedua tangannya.
Gerimis tiba-tiba hadir. Biasan air langit itu terlihat lembut merapat. Tempiasnya mulai menyapa kaca jendela café. Langit sore ini seakan ikut merasakan gelisah yang menghinggapi Abu sejak tadi. Dingin di luar café pun ikut memaksa masuk ke dalam. Meski tertutup, ruang café itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Entah karena hujan di luar yang semakin menderas, atau resah hati Abu yang semakin menjadi.
Sudah cukup lama Abu menunggu Zahra datang bersama orang yang dimaksud dalam pesan singkatnya. Duduk sendiri di bangku sudut café ini sungguh tidak nyaman bagi Abu sore ini. Cangkir cappuccino yang sedari tadi menemani Abu menunggu, sudah mendingin. Namun, masih belum ada bayang Zahra mendekat café itu.
Abu meraih kitab suci Al-qur’an yang terdiam di samping laptopnya. “Bismilahirahmanirahim. Hanya ini yang mampu menenangkanku kali ini.” Gumamnya dalam desah yang makin gelisah. “Ya Allah, sungguh, siapa lagi selain Engkau yang mampu menolongku sekarang.”
Selama ini, selain menulis, Abu banyak menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu Islam. Baginya, kitab suci Al-qur’an yang seakan tidak pernah dikenalnya semasa remaja, sekarang menjadi pegangan paling kuat untuknya. Semakin ia mempelajari isinya, semakin ia memahami mengapa Zahra menolak tawaran cintanya kala itu.
Abu meninggalkan kota kelahirannya saat itu, bukan untuk melupakan Zahra. Balasan surat Zahra memang membuat Abu jatuh. Abu tetap mencari tahu, siapa yang dimaksud “Dia” dalam surat itu. Kegalauan menyergap erat hati Abu, bahkan hingga kini. Yang ia yakini adalah janji Allah dalam salah satu firman-Nya dalam kitab suci Al-qur’an yang menyebutkan bahwa wanita baik hanya untuk lelaki baik. Sejak itu, Abu hanya mempercayakan semua pada Allah dan terus berusaha memperbaiki diri untuk Zahra yang menurutnya sempurna baik.
Kali ini, gelisah Abu sudah benar-benar menjadi. Beberapa ayat yang sempat ia baca dari kitab suci itu pun tak mampu menenangkan hatinya. Sejenak melupakan Zahra dengan mengingat Allah sore ini, rasanya tak semudah biasanya.
Abu mengambil pena, dan menuliskan sesuatu di selembar tissue meja.
“Banyak kata yang berkeliaran bebas di kepalaku. Namun, tak ada satu pun yang mampu kususun untuk menjadi alasan sebab apa aku mencintaimu. Lalu, siapa lagi, selain kamu?”
***
Abu yang sibuk dengan tulisannya pagi itu, terkesiap dengan suara pintu yang terketuk dari luar.
“Abu!” Wajah mama tampak berbinar muncul dari balik pintu. “Sedang apa kamu?”
“Ah, mama. Lagi nyelesein naskah, nih. Biasa. Mumpung nggak ada tugas sekolah.” Abu menjawab sambil memutar posisi duduknya. “Ada apa, Ma?”
“Ada Zahra.” Mama terdengar sedikit berbisik.
“Zahra?” Abu menjawab dengan wajah tanya yang tersirat.
“Iya. Udah sana, temui. Sudah ngobrol sama mama dari tadi.” Mama mengelus rambut Abu dan meninggalkannya dengan keterkejutan yang tak juga habis. “Abu, kok malah bengong. Ayo, cepet. Zahra udah dari tadi di sini.” Mama tersenyum dan menghilang di balik pintu.
Abu memandang lagi tulisannya. Mana mungkin sesuatu yang baru saja ia tuliskan, seketika menjadi nyata. Beberapa menit lalu, Abu sedang menyelesaikan cerpen yang akan ia kirim ke redaksi majalah sekolah. Cerita tentang seorang gadis muslimah yang berpendirian. Gambaran gadis itu persis dengan Zahra, gadis yang tak pernah bisa pergi dari kepala Abu.
Liburan sekolah akhir semester kali ini memang terasa lebih lama dari liburan biasanya. Zahra harus ke luar kota, mengunjungi saudara yang tinggal di sana. Jadi, tentu saja, hampir liburan berlalu, Abu tidak pernah bertemu Zahra. Hanya Ali yang sesekali mengajaknya bertemu, bahkan menginap di rumah Abu, seperti biasa.
Selama liburan, Abu mengawali paginya dengan sebuah kehilangan. Rindu yang makin bertumpuk membuatnya lebih produktif menulis. Beberapa tulisan memang dibiarkannya tidak selesai. Karena kegalauan akan rindunya, banyak ide berbeda yang bercarut-marut menindas tulisannya.
“Abu! Cepetan, nih ditungguin Zahra.” Suara mama menyeruak masuk ke gendang telinga Abu.
***
“Hey, Abu, assalamualaikum.” Zahra menyapa Abu yang masih termangu menatap kosong ke luar jendela café yang makin membasah. “Terlalu lama nunggu, ya? Sampai bengong gitu. Maaf banget.”
“Waalaikumsalam. Ali?” Abu melihat ke arah seseorang yang datang bersama Zahra. Tanpa menunggu jawaban dari keduanya, Abu pun memeluk sahabat yang entah telah sekian lama tak dijumpainya. “Lo beneran Ali, kan?” Abu menepuk punggung Ali.
“Hey, bray. Alhamdulilah lo masih kenali gue.”
“Ah, masih mulut sambel lo ternyata.” Abu kembali memeluk Ali. Seakang sejenak melupakan Zahra yang telah duduk di bangku sudut café itu. Ia memandang kedua sahabat itu berpelukan dan saling menyapa.
“Gue dengar lo kuliah di Ausie?”
Ali hanya tersenyum mendengar pertanyaan Abu. “Karena lo juga, kan?”
“Akhirnya, lo jadi mahasiswa juga ya, bray.” Abu kembali menepuk pundak Ali.
“Eh, ngeremehin gue, lo.” Tanpa menghiraukan Abu yang masih berdiri, Ali pun duduk di bangku sebelah Zahra. “Begini-begini nih, gue udah insaf.”
Tawa pun pecah di antara ketiga sahabat yang telah sekian lama terpisah. Hujan di luar café tak mampu menandingi riuh bahagia mereka. Pertemuan mereka senja itu selaksa hujan yang tiba-tiba menderas di pertengahan kemarau.
“Oya, bray? Kapan lo datang?” Abu mengalihkan pembicaraan.
“Barusan, baru saja. Zahra jemput gue tadi di bandara.” Ali menoleh ke arah Zahra yang masih menikmati hangat cangkir cappuccino yang baru saja ia pesan.
“Oya? Zahra jemput lo?”
“Iya. Biasanya juga gitu. Iya kan, Ra?”
“Masa sih? Gue nggak nyadar deh.” Zahra masih sibuk dengan usahanya menghangatkan diri.
Drama kecemburuan di hati Abu mulai diputar. Ternyata, selama ini, Ali dan Zahra masih sering bertemu dan mereka terlihat begitu dekat.
“Kenapa, bray? Cemburu lo?” Ali bertanya dengan mengurangi volume suaranya.
“Ah, nggak. Nggak mungkin, kan gue cemburu sama lo.” Abu berusaha menutupi kecemburuan yang mulai terbaca Ali dengan mengalihkan topik, “Gimana kuliah lo di sana? Kapan kelar? Gue nggak bisa bayangin deh, mahasiswa macam apa lo disana.”
“MasyaAllah, masih hafal juga lo dengan kebiasaan gue.” Ali menjawab setelah menyesapi kopi hitam pesanannya. “Gue udah berubah, bray. Lebih tepatnya, berusaha berubah.”
“Alhamdulilah. Insaf beneran, lo?”
“Eh, jangan salah. Gue mahasiswa teladan di sana. Lo ingat nggak, sehari sebelum gue berangkat, lo bilang apa ke gue?”
“Waduh. Pikun mendadak nih gue. Apaan?”
“Aamiin.”
“Maksud, lo?”
“Biar pikun beneran, lo.”
“Naudzubilahimindalik. Sekali-kali doa yang bener kenapa?” Ali dan Abu masih sama seperti dulu. Meski telah lama berpisah, tapi kedekatan mereka masih tetap sama. “Emang pesen apaan gue?”
“Lo bilang, kalau gue bakal jadi mahasiswa terkeren di sana. Management bisnis yang gue pelajari hanya penguat doang. Otomotif tetap jadi dasar gue.” Ali memandang Abu yang menatapnya dengan senyum. Mengingat semua yang pernah ia katakan pada sahabatnya itu. “Jadi, di sana, gue memang mahasiswa management bisnis. Tapi, gue juga dosen otomotif. Keren kan sahabat lo ini?”
“Subhanalah. Ajib lo, bray.”
“By the way, kayaknya kalian udah nggak butuh gue, deh.” Zahra memecah nostalgia Ali dan Abu. “Gue pulang aja deh.”
“Eh, eh, tumben lo bisa ngambek, Ra.” Ali menahan Zahra untuk pergi.
“Maaf, Ra. Bukannya mengabaikan lo, gue hanya nggak percaya aja, si tukang tidur ini bisa jadi mahasiswa sekaligus dosen di Ausie.” Sekali lagi, celoteh Abu memecah tawa di antara mereka.


 FaAli
FaAli